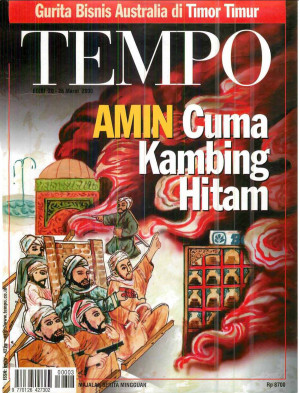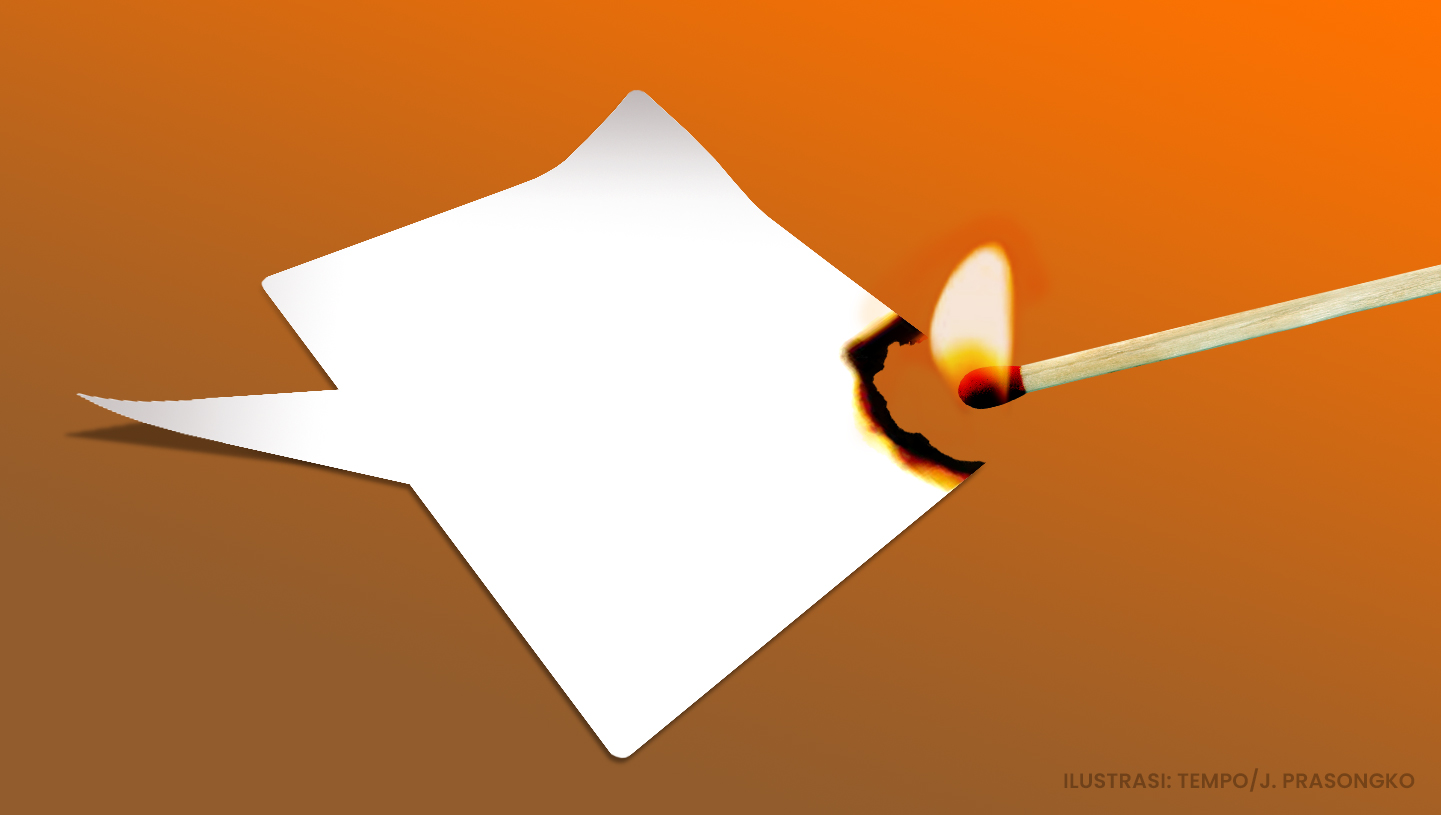MEREKA yang menjagokan Megawati Sukarnoputri untuk tampil lagi sebagai ketua umum PDI Perjuangan—yang berkongres di Semarang mulai 27 Maret 2000—tentu punya banyak alasan. Prestasi PDI-P, yang dipimpin Mega, dalam memenangi pemilu lalu sekaligus menamatkan kekuasaan rezim Orde Baru adalah alasan utama. Mereka yang kritis boleh saja mengatakan bahwa dukungan rakyat banyak itu lebih karena Mega dan PDI-P selama ini diperlakukan semena-mena oleh penguasa, ketimbang karena kecanggihan programnya. Lainnya bisa saja berpendapat bahwa Mega didukung lebih karena sentimen masyarakat yang masih memuja karisma Bung Karno, sang bapak, ketimbang kemampuannya mengartikulasikan gagasan. Yang lain mengatakan, PDI-P yang nasionalis itu menang karena banyak masyarakat khawatir ihwal bermunculannya partai-partai berlandaskan agama. Semua "gugatan" untuk Mega itu sah-sah saja, tapi faktanya Megalah yang membawa PDI-P mencatat sejarah terbesar sepanjang kelahirannya.
Kelompok yang menolak Mega tampil lagi di Semarang juga bukan tanpa argumen jelas. Soal etika politik, misalnya. Sebagai wakil presiden, Mega memang harus berdiri di atas semua golongan, dan tetap menjadi ketua umum PDI-P hanya membuka celah baginya untuk bertindak tidak adil. Yang lain mempersoalkan kemandirian partai. Jika PDI-P terus-menerus mengandalkan dinasti Sukarno, kaderisasi partai yang sudah tak jalan di masa rezim Orde Baru terus akan macet di zaman reformasi ini. Lalu, mengapa PDI-P tidak diubah namanya menjadi Partai Barisan Pendukung Sukarno saja, misalnya?
Pilihan memang ada di tangan rakyat pemilih PDI-P, walau ada beberapa catatan yang layak dikemukakan. Rasanya jelas, tidak satu figur pun yang cukup kuat menantang Mega di Semarang nanti. Dengan kata lain, Megalah yang menentukan ia maju atau tidak. Tapi, apakah naiknya kembali Mega akan menjadikan PDI-P partai terbuka yang menarik untuk dipilih dalam Pemilu 2004 nanti? Belum tentu. Sebab, selama ini daya tarik PDI-P dan Mega adalah bahwa mereka merupakan korban otoriterisme Orde Baru—salah satu bagian pentingnya adalah Peristiwa 27 Juli. Kini Mega berkuasa, dan seketika itulah simbol sebagai korban lenyap. Lalu, apa lagi daya tarik yang masih melekat padanya?
Masih ada. Umpamanya citra diri Mega sebagai seorang ibu yang tulus dan membuat "adem" rakyat. Namun, di masa depan, daya tarik sentimental begini akan dinomorsekiankan oleh tuntutan akan mutu kepemimpinan dan kemampuan merangkul semua komponen bangsa. Kepemimpinan yang efektif dan luwes, yang sedikit banyak telah diperagakan oleh Gus Dur—dan membuat orang tak lagi alergi dengan partai-partai agama—akan semakin diperlukan. Kemampuan bekerja dalam tim akan memegang peranan sentral. Justru di titik itulah Mega mengalami kesulitan. Ketika PDI-P memenangi suara terbanyak dalam pemilu lalu, dan ia cukup rendah hati merangkul dua atau tiga partai lain, tak akan ada yang mampu menahannya meraih kursi presiden. Toh, itu luput dilakukannya. Walau begitu, rasanya tak bisa dimungkiri, Gus Dur memang lebih hafal lika-liku politik dan karenanya ia lebih pantas memimpin.
Jika PDI-P menyebut diri partai masa depan, dalam hal memilih pemimpin, ia seharusnya mulai memikirkan "investasi" untuk menyongsong masa depan yang mungkin lebih pelik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini