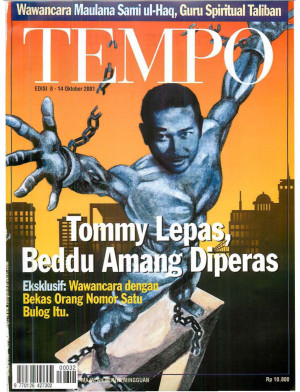SEBUAH pepatah yang dipelesetkan mungkin layak dikirim ke Presiden Bush. Kata bijak itu berbunyi, "Siapa menabur bom akan menuai teror, siapa menebar harapan akan memanen kejayaan." Siapa tahu, andai kata nasihat ini sampai ke Gedung Putih, perintah penghentian aksi pengeboman ke Afganistan lantas dikeluarkan. Jutaan rakyat negeri miskin itu pun boleh berhenti takut, kemudian kembali ke rumah untuk bersiap-siap menghadapi bulan puasa. Sementara itu, ajakan dialog di bulan suci barangkali dapat membuat para pemimpin Afganistan duduk bersama menikmati santapan berbuka dan mencari kesepakatan untuk membawa bangsa ke masa depan yang lebih aman serta sejahtera. Jika ini terjadi, benih harapan berkesempatan untuk tumbuh di negeri yang tak henti dirundung malang itu.
Perang berkepanjangan memang telah membuat harapan menjadi langka di Afganistan. Setidaknya bagi sebagian besar rakyat negeri berpenduduk 25 juta ini, yang seperempatnya berdesakan di berbagai kampung kumuh pengungsi di perbatasan. Sebagian lagi, yang masih punya ongkos, berupaya hijrah ke negeri yang lebih aman seperti Australia tapi mendapatkan pintu-pintu perbatasan yang tertutup rapat. Sedangkan sisanya, yang mencoba bertahan di dalam negeri kendati ditindas oleh pemerintahan yang bengis, kini dilanda waswas hujan bom Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi mereka, syair mendiang Chairil Anwar—bahwa hidup hanyalah menunda kekalahan—seperti sebuah keniscayaan.
Kita semua tentu tak boleh membiarkan rakyat Afganistan kehilangan harapan. Bangsa ini punya banyak modal untuk bangkit dan berdiri sama tinggi dengan warga dunia yang lain. Wilayah Afganistan yang cantik mempunyai potensi besar untuk menarik wisatawan dari berbagai pelosok bumi, seperti pernah terbukti sebelum berbagai perang berkecamuk di wilayah ini. Bagaimana tidak. Kota-kota bersejarahnya, yang telah menjadi saksi ribuan tahun peradaban manusia, adalah cagar budaya yang harus dilestarikan. Bahkan diduga, oleh sejumlah pakar, terdapat timbunan deposit minyak dan gas dalam jumlah besar di bawah kawasan tua ini. Kalaupun jumlahnya tidak istimewa, Afganistan punya peluang memberikan jasa pemipaan minyak dan gas dari dan ke negara-negara tetangganya.
Semua potensi yang menjanjikan itu cuma menunggu kehadiran tangan-tangan piawai untuk merealisasikannya. Tangan pertama yang ditunggu adalah yang mampu membawa perdamaian dan stabilitas. Rasanya tak berlebihan untuk menganggap Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang paling cocok untuk diminta turun tangan. Pengalaman PBB mengubah perang saudara di Kamboja menjadi perebutan suara pemilih akan sangat bermanfaat di Afganistan. Sementara itu, pengalaman di Yugoslavia menunjukkan pemenang pemilihan umum yang demokratis cenderung akan menyerahkan pelaku teroris ke mahkamah internasional. Ini sebuah alasan kuat untuk menekan Presiden Bush dan rakyat Amerika Serikat agar mendukung PBB masuk Afganistan bukan dengan bom dan peluru, melainkan dengan program dan dana untuk mengadakan pemilihan umum. Percayalah, pemenang pemilu pasti akan terdorong untuk menyerahkan para pelaku teror di wilayahnya ke mahkamah internasional.
Pemilihan umum saja tentu tidak cukup. Masyarakat internasional juga harus menjinjingkan tangannya untuk menjalankan pembangunan ekonomi Afganistan. Ini bukan soal baru. Amerika Serikat telah membuktikan kemampuannya membangkitkan bangsa Jerman dan Jepang dari puing-puing kehancuran Perang Dunia Kedua menjadi negara yang sangat sejahtera. Biayanya pun tak akan mahal, hanya sebagian kecil dari US$ 40 miliar yang disediakan Kongres AS untuk perang Afgan pun sudah memadai. Maka, persoalan yang penting adalah apakah Amerika Serikat mau melakukan semua ini.
Jawabannya tentu berpulang pada rakyat Amerika Serikat. Hanya, seandainya para pemimpin AS mau berpikir dingin, sebetulnya mereka tak punya pilihan lain. Mengebom Afganistan hingga luluh-lantak hanya akan menghasilkan jutaan pengungsi yang—sebagian di antaranya—di kemudian hari akan menjadi kader teroris berani mati. Sebaliknya, menabur harapan kepada bangsa Afganistan akan berdampak seperti sinar matahari yang cerah, yang akan membangunkan rakyat biasa untuk berani hidup dan sekaligus mengerdilkan para kader terorisnya. Bagaimana tidak, harapan adalah pemusnah kebencian seperti sinar matahari melenyapkan makhluk vampire.
Dampak harapan tak hanya efektif di Afganistan, tapi juga di Amerika Serikat. Bagi bangsa terkaya di dunia ini sekarang terdapat dua pilihan: mencoba memusnahkan terorisme melalui kekerasan atau dengan kesabaran dan kecerdikan. Kedua pilihan ini punya konsekuensi yang berbeda. Bila jalan kekerasan yang dipilih, masyarakat Amerika Serikat harus siap menanggung ongkosnya, terutama kehilangan berbagai hak kebebasan sipil yang selama ini dinikmati. Simaklah apa yang kini ditanggung rakyat Israel, yang setiap saat harus waspada terhadap kemungkinan diserang teroris dan semua warga dewasanya harus menyumbangkan waktu untuk menjalankan masa wajib militer yang berisiko tinggi.
Sebaliknya, bila jalan kesabaran dan kecerdikan yang dipilih, Amerika Serikat akan menuai kekaguman dan rasa sayang masyarakat dunia. Kenikmatan berbagai hak kebebasan sipil juga dapat tetap berlangsung dengan risiko serangan teroris yang sangat rendah. Sebuah kenyataan yang kini sudah dinikmati rakyat negara-negara Skandinavia, yang dikenal paling rajin menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk memerangi kemiskinan di negara-negara yang kurang beruntung.
Dalam kerangka pemikiran ini, pemerintah Indonesia sepatutnya segera mengambil inisiatif. Bila di Kamboja kita dapat memainkan peran penting, tak ada alasan untuk tidak mengulanginya di Afganistan.
Paling tidak, mengupayakannya adalah sebuah tugas konstitusional: menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini