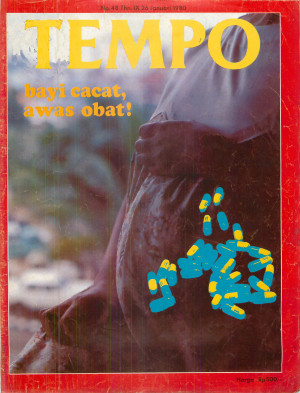ADA satu kasus. Seorang kepala daerah mengeluh. "Saya sudah
membangun jambanjamban untuk rakyat, tapi rakyat ternyata tak
mempergunakannya," begitu ia berkata.
Apa yang salah?, tanyanya kemudian, pelan-pelan.
Yang salah jelas Bapak, jawab analisa A. Bapak membangun untuk
rakyat, tapi berdasarkan konsepsi yang asing bagi rakyat. Bapak
tidak menanyai terlebih dahulu benarkah rakyat memerlukan jamban
itu. Bapak, dengan kesigapan seorang mertua yang mau menolong
menantunya dari bahaya lontang-lantung, segera ambil keputusan
untuk bangun ini dan bangun itu. Terang saja rakyat akhirnya
bingung: buat siapa sih proyek ini? Buat kami atau buat ambisi
pak kepala daerah? Atau malah buat pemborong?
Ah, nanti dulu, jawab analisa B. Analisa anda kedengarannya
populis, atau demokratis, tapi tunggu. Untuk terlebih dahulu
menanyai rakyat tentang perkara jamban itu, kita harus ada cukup
pegangan bahwa rakyat sendiri memang tahu betul yang mereka
butuhkan. Coba. Apa gerangan jadinya bila setelah ditawari
ternyata mereka minta gedung bioskop -- tempat nanti mereka
menonton film-film tak bermutu? Rakyat tidak selamanya benar.
Jangan terlalu romantis. Kita harus ikut mendidik.
Di tahun 1921, Dr. W. Huender membuat satu survei tentang
keadaan ekonomi rakyat Jawa dan Madura.
Huender nampaknya tak cuma ingin berbicara tentang statistik. Ia
menyalahkan anggapan -- yang berlaku selama 50 tahun sebelumnya
-- bahwa pemerintah kolonial akan berhasil memperbaiki keadaan
rakyat jajahan hanya lewat jalan perekonomian. Bagi Huender,
dorongan utama orang Indonesia bukanlah motif ekonomi. Tugas
pemerintah-lah "untuk mencoba mengubah mentalitas orang Timur
itu."
Salahkah Huender? Yang jelas, pendirian semacam itu biasanya
tidak mengenakkan orang Timur. Ketika dalam Polemik Kebudaaan
yang termashur di tahun 30-an S. Takdir Alisyahbana berseru agar
kita menengok ke Barat (yang "materialistis" itu), reaksi pun
menggeletar seperti geludug vulkanis. Tapi toh hampir separuh
abad kemudian ada Dr. Kuntjaraningrat. Ia berbicara tentang
rintangan mental dalam pembangunan. Ada Dr. Suparman. Ia tak
putus-putusnya menyebarkan ajaran entrepeneurship -- dengan
kisahkisah sukses mirip Horatio Alger di negeri sana.
Tapi benarkah Huender?
Ia memang tidak menganjurkan perubahan "mentalitas orang Timur"
melalui paksa. Namun tidakkah ia sebenarnya sama saja dengan
orang Barat lain -- yang punya semangat missioner yang mirip,
dan tak jarang menimbulkan korban? Di Colombo, Sri Lanka, 15
Agustus 1979, Ivan Illich berbicara tentang The New Frontier
for Arrogance Pastor ini mencatat, bahwa sejak berdirinya
institusi Gereja sampai dengan kolonialisme, sejak kolonialisme
sampai dengan masa modernisasi atau development, kini, Dunia
Barat menganggap 'orang luar" sebagai "seseorang yang harus
ditolong".
Dengan kata lain, keunggulan Barat selalu dicoba dipertegas
kembali. Di luar Gereja, orang bersifat "kafir". Di luar
kekuasaan kolonial, orang adalah "inlander". Di luar negeri
"maju", yang terhampar ialah masyarakat "terkebelakang". Tiap
kali mereka harus diselamatkan.
*****
Modernisasi memang menimbulkan banyak dilema, dan pengertian
"rakyat" terkadang menyesatkan. Bahkan bagi partai semacam PKI.
Partai ini memasang bendera populisnya antara lain dalam bentuk
menulis "rakyat" dengan "R" tapi ia juga bicara soal
modernisasi. "Kami adalah orang-orang yang memodernisasikan
kehidupan di desa-desa," begitulah ucap Njoto di tahun 1965
kepada wartawan Trouw (Belanda) Huib Hendrikse. "Kamilah
orang-orang yang memperkenalkan abad keduapuluh."
Namun tak mudah untuk mewakili rakyat dan sekaligus untuk
memodernisirnya. Kegagalan itukah agaknya yang menyebabkan
akhirnya PKI tak bisa meniti buih di lautan dahsyat 1965?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini