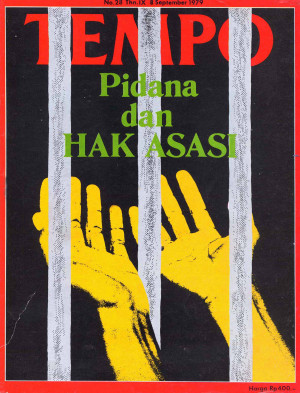SEORANG dokter muda berjalan di pedalaman yang jauh. Di sebuah
teratak di ujung jalan ia merunduk masuk. Pasiennya seorang anak
berumur 12 tahun yang bermata besar berkulit hitam dan berkata
tiap kali demamnya membaik: "Pak dokter, terimakasih."
Dokter itu cepat-cepat keluar, menahan sesuatu di hatinya
seperti ia kemarin dulu menahan airmatanya. Ia tahu anak itu tak
punya harapan sembuh. Ia tahu anak itu tahu.
Tapi dokter itu tak tahu bahwa tiap kali ia melewati jalan di
pulau yang sangat jauh itu ia sebenarnya memberikan harapan yang
lain. Tidak lebih kuat daripada Maut, barangkali, tapi lebih
tinggi. Sesuatu yang timbul karena persintuhan kebaikan. Sebuah
harapan yang kuno sekali. Sebuah harapan ketika seorang manusia
bilang "terimakasih " kepada kehadiran seorang manusia
lain--biar pun dalam situasi yang paling mustahil.
TAPI pesimisme tetap saja terasa lebih beralasan, bukan?
Sebab besok mungkin kita ketabrak truk. Besok mungkin seorang
yang paling kita cintai hilang. Tahun depan mungkin pekerjaan
yang kita senangi lepas. Di tahun 2000 mungkin anak-anak kita
akan jadi garong atau gelandangan.
Pesimisme memang sering lebih mudah ketimbang optimisme, seperti
halnya kemungkinan kita untuk menemui nasib buruk lebih besar
daripada menemukan durian runtuh. Lebih banyak orang tewas dalam
kecelakaan lalulintas ketimbang jumlah pemenang Undian Harapan.
Lebih banyak orang jadi korban kebakaran ketimbang para pemenang
Hadiah Nobel.
Tetapi kenapa kita toh berjalan terus, sering dengan muka riang
Seorang anthropolog suatu kali bermain-main dengan sebuah
gagasan, dan menulis Optimism, The Biology of Hope untuk
mengatakan: barangkali, dalam zat-zat terdasar kesadaran kita,
sejak nenek moyang, harapan sudah diikatkan. Untuk survival.
Mereka yang pernah menderita memang tahu. Siapa yang hanya hidup
dengan fikiran "aku-akan-ketabrak-truk" sudah akan roboh
pagi-pagi di tengah sarapan.
***
Konon jika lebih banyak lagi orarg baik di kota Sodom dan
Gomorah, azab tidak akan turun. Tapi lihatlah baik-baik. Setiap
kali kita mengatakan bahwa kian bertambah jumlah pencuri di
antara tetangga kita, setiap kali kita menambah jumlah itu
dengan satu orang perampok di hati kita.
Kita memang dengar orang berbisikbisik tentang garong dan
maling, mafia dan bajingan --berjajar dari Barat sampai ke
Timur. Tapi ingatkah anda seorang dokter muda berjalan di
pedalaman yang jauh, dan seorang anak hampir mati yang berbisik
"terimakasih"?
Khotbah memang bicara tentang kebejatan akhlak --dan itu memang
ada. Tapi adakah kita telah sepakat bahwa bangsa ini bangsa
terkutuk? Percakapan intelektuil memang berbicara tentang
kebobrokan --itu memang nyata. Tapi benarkah kita tidak punya
apapun untuk mengatasinya?
**
DI sebuah bioskop kecil di sebuah kota kecil, orang menonton
November 1828. Film tentang suatu episoda Perang Diponegoro iN
sebenarnya nyaris tanpa suspens. Tapi toh di bioskop kecil di
kota kecil itu, penonton bertepuk riuh ketika adegan pendek ini
terjadi seorang pemuda pemberani menaiki tiang bendera, merobek
Merah-Putih-Biru dari tempatnya, ketika pertempuran sengit
terjadi ....
Pemuda itu tewas. Tapi ada yang lebih besar ketimbang mati.
Bahkan ada yang lebih besar dari kekalahan yang panjang. Dan
para penonton di bioskop kecil di kota kecil itu tahu: manusia
lebih baik dari yang diteriakkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini