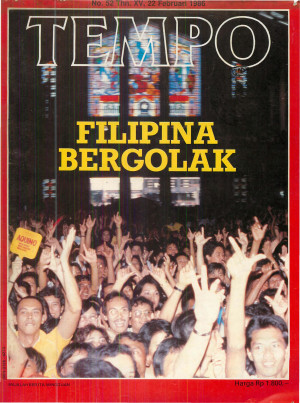SEJAUH manakah kita memerlukan orang swasta? Seorang teman baru-baru ini mengirimi saya sebuah tulisan pendek tentang Aceh antara 1550 dan 1700. Penulisnya Anthony Reid, seorang ahli sejarah dari Australia. Judulnya Trade and the Problems of Royal Power in Aceh. Di abad ke-16, demikianlah kisah Reid, Aceh dibangun jadi sebuah negara yang kukuh oleh Ala'ad-din Ri'ayat Syah al-Kahar. Aceh menguasai perdagangan antara bandarnya dan Laut Merah. Di tahun 1567 al-Kahar mengadakan aliansi dengan Turki. Tak diketahui persis bagaimana perdagangan yang sibuk itu diorganisasikan: seberapa besar kekuasaan dan bagian Sultan, sejauh mana pula hak-hak para saudagar. Tapi tampaknya, tanpa pedagang-pedagang yang aktif di seantero Selat Malaka, yang kemudian berdiam di Aceh, proses ekspor dan impor abad ke-15 itu tak akan sedemikian mengesankan. Dan mungkin cuma bakal sebentar. Agaknya, dari kalangan saudagar yang masuk ke dalam sistem kenegaraan Aceh itulah kemudian muncul satu kelas atas tersendiri: kelas "orang kaya". Apa pun artinya, pelbagai catatan Barat melukiskan betapa istimewanya lapisan sosial ini. Mereka umumnya membiarkan kuku ibu jari dan kelingking jadi panjang -- suatu tanda bahwa mereka tak pernah melakukan pekerjaan tangan. Dan Augustin de Beaulieu bercerita bagaimana para orangkaya itu hidup: dalam kemewahan, di rumah-rumah besar yang memasang meriam di depan pintu, mereka memelihara sejumlah besar pelayan dan penjaga. Yang lebih menakjubkan ialah kekuasaan mereka, terutama sebelum akhir abad ke-16. "Para orangkaya utama memiliki kekuatan yang sedemikian besar, hingga apabila mereka capek dengan pemerintahan seorang raja, mereka pun membunuhnya untuk segera menobatkan seorang raja lain." Beruntunglah, tulis Beaulieu seraya melebih-lebihkan lukisannya di sana-sini, "jika seorang raja dapat tetap bertahta untuk dua tahun." Perimbangan kekuasaan yang sedemikian itu bisa siapa tahu bermanfaat. Seorang Sultan dengan begitu tak akan punya kekuasaan mutlak. Sumber-sumber wewenang dan ekonomi bisa lebih tersebar. Orang kebanyakan bisa mendapatkan alternatif-alternatif lain untuk memperoleh perlindungan. Tapi ternyata kekuasaan besar para orang kaya di masa itu tidak berhasil melembagakan suatu perimbangan kekuatan yang bisa jadi basis pemerintahan yang mantap. Aceh terguncang-guncang terus. Kemudian tibalah raja baru, al-Mukammil, pada 1589. Bandul jam pun berbalik. Sang raja inilah yang dengan cepat ganti membasmi orangkaya dari sekitarnya. Beaulieu mengutip al-Mukammil yang menjelaskan kenapa ia berbuat begitu drastis: ia tak mau rakyat menderita karena pertikaian yang terus-menerus di kalangan atas. Demikianlah, seorang raja yang absolut telah tampil. Dan puncaknya terjadi ketika seorang Sultan muda yang cemerlang naik tahta antara 1607 -- dan 1636: Iskandar Muda. Ia menaklukkan Sumatera Timur dan Malaya, guna menguasai hasil bumi untuk ekspor. Ia memaksa pedagang asing harus lebih dulu berurusan dengannya sebelum menawar di tempat lain. Dan ia, yang memegang sejumlah besar penjualan lada, mendesak mereka untuk membeli dagangannya dengan harga tinggi. Para penulis sejarah Aceh tentu saja melukiskan Iskandar Muda sebagai penguasa yang agung. Sultan ini memang berhasil membuat Aceh sebuah negeri yang kuat dan rapi. Ia mengontrol tiap gerak para bangsawannya, seperti yang dilakukan Shogun Tokugawa waktu berkuasa di Jepang. Anthony Reid bahkan membandingkan Aceh di bawah Iskandar Muda dengan bangkitnya negara "modern" Eropa setelah feodalisme runtuh. Tapi Reid juga mencatat: kekuasaan mutlak Iskandar Muda ternyata tak mendapatkan padanan dengan usaha perdagangan swasta. Orang-orang asing, yang lebih banyak bergaul dengan mereka yang di luar istana, yakni para saudagar setempat dan para pejabat, mencatat betapa penuh ketakutannya orang-orang ini. Para saudagar Aceh sendiri bahkan lebih buruk nasibnya dibanding dengan saudagar pendatang. Dalam catatan Beaulieu, Iskandar Muda "memperoleh laba besar dengan menyita barang-barang orang yang ia bunuh tiap hari ...." Sejarah Aceh, tentu saja, tak berhenti pada Iskandar Muda. Tapi raja ini konon membinasakan para calon penggantinya sebelum ia sendiri mangkat. Tak ayal, ia meninggalkan Aceh yang semakin lemah. Seorang otokrat yang tak mau disaingi siapa pun, memang pada akhirnya tak menyiapkan Aceh yang lebih Jaya. Dan sementara di atas tahta penguasa-penguasa kian tak bermutu, di luar istana, ada lubang yang menganga gersang, dan nyaris kosong. Monopoli itu telah menguras sumber daya yang dulu pernah tersimpan dan berkembang, di dasar-dasar sosial ekonomi negeri Aceh. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini