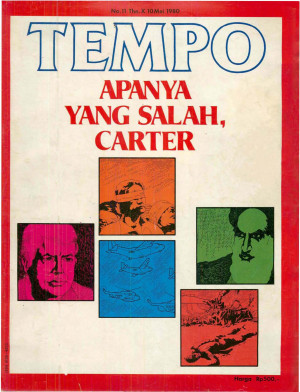WAKTU Gendut, anak saya yang bungsu, mulai dapat menulis dan
membaca habislah seluruh rumah kena bekas cakarannya. Juga semua
koran dan majalah habis diganyangnya dengan membacanya
keras-keras. Lantai pun tidak pernah sempat bersih karena bekas
coretan kapur selalu saja melekat di mana-mana. Begitu juga
tembok dan pintu, penuh dengan coretan pensil dan bolpoin.
Mula-mula coretan itu hanya coretan namanya sendiri dalam
berbagai versi. Seperti Gendut, gendut, gendut, gendut, gendut,
GENDUT dan entah versi yang bagaimana lagi. Lama kelamaan,
mungkin karena jenuh dengan namanya sendiri, ia pun mulai
ekspansif dengan nama-nama lain. Maka seisi rumah pun tidak
bebas dari bekas cakarannya. Mamah, bapak, Mbak, Yanem, Suti
semua dapat giliran juga dalam berbagai versi.
Ibunya anak-anak dan Mbak, kakak perempuan Gendut memutuskan
untuk membelikan Gendut sebuah papan-tulis besar. Maksudnya
supaya Gendut dapat berkiprah menulis dan menggambar di papan
itu dan tidak di sembarang tempat.
-- Bapak setuju, 'kan?
Biar Gendut bisa mengkespresikan dirinya dengan bebas!
Apa yang bisa saya katakan selain "setuju" kepada usul yang
begitu brilyan dan penuh pengertian terhadap perkembangan anak.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti
bulan. Papan itu terpancang dengan megahnya di gang antara
garasi dan kamar-mandi. Papan itu betul-betul menjadi papan
Gendut. Apa yang dipelajarinya di sekolah diulanginya di situ.
Pelajaran bahasa, berhitung dan menggambar. Kemudian juga
nyanyian dan sajak-sajak. Kemudian juga surat-surat pendek buat
Mbak dan kadang-kadang juga buat Ibunya.
Akan saya, ayah yang paling banyak cuma sekali seminggu pulang
dari Yogya, agaknya susah mendapatkan coverage di papan itu.
Sampai pada satu saat, bertahun sesudah papan itu ngendon di
tembok gang itu, saya melihat nama saya tertulis dengan nyata di
situ.
Waktu itu saya sedang terpakai, diikutkan dalam satu produksi
film memainkan satu peranan kecil yang tidak begitu berarti.
Tulisan Gendut di papan itu: UK main film dengan perempuan lain
....
Wah! Ini hebat, pikirku. Ini daya pikir kritis. Ini kreatif. Ini
keberanian. Ini....
Saya segera memerintahkan kepada ibunya anak-anak agar bakat ini
dipupuk. Agar seisi rumah didorong untuk mengekspresikan diri
secara kritis.
Pendeknya? papan-tulis itu mesti menjadi papan-demokrasi di
rumah ini . . .
Tahun pun berlalu dengan cepatnya. Gendut sudah kelas lima, Mbak
sudah mahasiswi dan saya masih mengglandang dan mengglinding
antara Yogya dan Jakarta.
Papan itu pun masih terpancang. Tapi berkembang dan melebar
fungsinya. Ia bukan lagi monopoli Gendut. Mbak dan Ibu mereka
sudah ikut-ikutan memanfaatkannya. Buat pesan-pesan,
instruksi-instruksi dan sekali tempo juga protes kecil-kecilan.
Pesan dan instruksi itu tentu saja lewat jenjang birokrasi yang
berlaku di rumah. Dari ibu ke anak, dari ibu ke anak ke
pembantu, dari kakak ke adik, dari kakak ke adik ke pembatu,
dari adik ke pembantu.
Akan protes-protes kecil itu? Mula-mula cuma dari Gendut buat
Mbak. Kalau Mbak tidak mau membantu menggarap pekrum-nya
Gendut akan menulis: Mbak sok! Kalau Mbak tidak mau membagi
sedikit dari uang jajannya tulisan itu akan berbunyi- Mbak
pelit!
Tapi kemudian Mbak pun jadi gatal membalas protes adiknya.
Biarin Emangnya kenapa Ini uang jajan kila sendiri dan
sebagainya lagi.
Eh, kemudian ibunya pun ikut-ikut latah memakai papan itu buat
berpolemik dengan anak-anaknya. Tentu saja anaknya yang memulai.
Kongkritnya Gendut dulu yang mulai. Mamah kalau pulang kerja
terlalu sore! Nggak bawa oleh-oleh lagi! Agaknya lama-kelamaan
ibunya jadi jengkel. Maka dibalasnya protes anak-anaknya. Kalau
nggak mau mamah pulang sore-sore harus mau kurang makan! Mau
nggak kurang makan dan kurang uang jajan ?
Tentu saja itu kurang adil. Tentu saja ibunya yang bakalan
menang dengan polemik yang berbau intimidasi begitu. Tapi toh
saya masih bisa menganggapnya lucu. Setidaknya papan itu jadi
"papan demokrasi" yang riuh. Ini kehidupan demokrasi yang sehat,
pikirku, biarpun kemudian saya akhirnya kena giliran kesrempet
juga. Pak seafood, pak! Sudah lama nggak makan di luar! Uang
jajan naikin dong, pak! UK, masih sayangkah U sama G. dan Mb.?
Ke Ancol yuk!
Mula-mula saya merasa senang diseret ke dalam klub polemik itu.
Tapi kemudian saya jadi melihat sesuatu yang aneh dengan
tulis-menulis di papan-demokrasi ini. Eh, anak-anakku kok tidak
atau kurang bicara langsung lagi sama orang tuanya. Minta dan
protes yang rutin saja kok mesti tertulis. Minta dan ngomel
langsung kenapa, sih?
Wah, ini ekses "revolusi Gutenberg", revolusi mesin cetak yang
sudah mengubah wajah keluarga. Anak-anakku sudah masuk
"tata-surya Gutenberg", The Gutenberg galaxy, yang dengan
kejamnya telah membuyarkan ikatan primordial puak karena semua
anggota keluarga asyik membaca dan menulis. Hingga mereka tidak
mau mengobrol lagi. Setidaknya begitulah menurut Marshall
McLuhan.
Wah, ini mesti diakhiri. Obrol-mengobrol mesti dikembalikan.
Makna kata-kata secara verbal mesti dikukuhkan kembali dalarn
keluarga. Bayangkan kalau-keluarga cuma terdiri dari anggota
yang tulis-menulis dengan sadisnya!
Kesempatan itu datang pada suatu hari di papan-demokrasi itu
juga!
Waktu itu hari Minggu pagi. Seperti biasa seisi rumah pada
bangun siang. Waktu saya jalan keluar dari kamar mandi begitu
saja terlihat tulisan itu. Ndoro, karena kenop dan gaji 14 sudah
lama lewat muhun janji kenaikan gaji kami dilaksanakan. Yanem
dan Suti.
Mata saya terbeliak tidak percaya. Dari mana mereka bisa
berbahasa Indonesia gaya koran begitu. Pasti ada yang
menggerakkan dari luar. Saya tersinggung. Saya merasa diejek,
dienyek bahkan dihina. Protes itu sudah cukup menyakitkan hati.
Tapi lebih dari itu, bagairnana mereka berani memakai
papan-demokrasi majikan mereka? Itu sudah keterlaluan!
Maka seluruh isi rumah segera saya kumpulkan Minggu siang itu.
Dekrit pun saya turunkan! Papan-demokrasi harus segera
diturunkan hari itu juga. Protes, polemik, sindir-menyindir,
surat-menyurat tidak diperkenankan lagi lewat papan-demokrasi.
Kalau ada ketidakpuasan salurkan itu lewat usul yang sopan
kepada ibu --lembaga kita yang sah. Selesai. Papan demokrasi
selesai.
Waktu kemudian saya mencukur kumis di depan kaca saya melihat
dan mendengar saya sendiri menggumam: Deng Hsiao-Ping, saya
mengerti sekarang kenapa kau tutup tembok kebebasanmu di Beijing
....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini