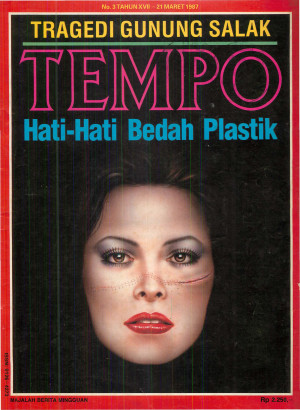KIRA-KIRA 20 tahun yang lalu tubuhnya dibakar matahari. Seperti banyak pemuda, ia ikut berduyun untuk solidaritas dan kesetiaan hampir tiap hari. Ia seorang demonstran. Yel dan nyanyian diteriakkan dari ulu kalbu. Poster dibikin tiap malam. Orang hidup dengan gelora hati dengan passion, dan titik apinya adalah politik. Namun, mulai 11 Maret 1966, perubahan pelan-pelan berlangsung dalam hidup. Tarikh baru datang: gelora hati seakan terpendam. Di jalan-jalan, bahkan di ruang-ruang rapat partai, passion tak ada lagi. Teman kita demonstran yang satu ini, juga punya kesibukan lain: menyusun rencana volum penjualan di depan komputernya. Tubuhnya tetap dibakar matahari -- tapi dari proyek-proyek bisnis di lapangan. Sayukah dia, tanpa passion lama itu? Atau menyesalkah ia, tentang masa 20 tahun yang lalu, ketika hati dan suaranya berseru? Teman ini cuma mengangkat bahu. Tiap sepuluh tahun (ia pun mengutip Goethe), hidup seseorang punya keberuntungannya sendiri, keinginan dan harapannya sendiri. Ia berbicara tentang dirinya, meskipun ia juga sebenarnya berbicara tentang sekitarnya. Seperti dia, sekitarnya tak memekikkan yel. Adem. Orang memang sibuk. Namun, mereka seakan sedang antre karcis di depan loket stasiun: berada bersama-sama di suatu tempat, tapi tak saling berbagi emosi. Tentu, (kali ini ia mengutip Sartre) di sana yang terjadi adalah sebuah deret: sekumpulan orang ada untuk tujuan yang "sama", tapi mereka tak punya tujuan "bersama". Bahkan, tiap oknum dalam antrean itu merupakan saingan dari oknum yang lain. Karena jumlah karcis terbatas -- begitu pula kebutuhan hidup -- tiap orang diam-diam mengharap agar orang lain dalam deret itu tak pernah ada. Antrean itu pada dasarnya hanyalah wajah majemuk kesendirian, a plurality of solitude. Tapi salahkah hal itu? Memang ada sesuatu yang hambar di sana, tapi bukankah dalam kenyataan, hidup terdiri dari pelbagai antrean? Tentu, mereka yang berharap, bahwa manusia akan selalu seia sekata, bahwa antara kita selalu ada tujuan "bersama", pasti kecewa melihat di sekitarnya: yang terbentuk hanya deret. Bukan kolektivitas. Dan mereka pun kangen, ingin kembali kepada gerak berduyun, demi solidaritas dan kesetiaan, ingin kembali kepada yel yang terungkap dari sanubari, ingin kembali kepada passion.... Wajar. Juga tak sia-sia. Hidup sendiri kadang-kadang bisa menciptakan gelora hati itu. Suatu masa untuk politik, suatu masa lain untuk hal lain. Seperti ketika orang datang dengan puluhan bis melalui jarak beratus-ratus kilometer untuk Persebaya, atau menahan lapar dan haus untuk PSIS atau menangis untuk Persib. Mereka berseru. Mereka menyanyi. Mereka memasang poster. Di hari itu, mereka bisa mengidentifikasikan diri dengan sesuatu yang lebih besar, yang sedang "berjuang". Di situ mereka menemukan diri dalam suatu kebersamaan, dengan gairah: mereka masing-masing bukan cuma unsur yang dalam deret duduk bersendiri-sendiri. Tapi tidak buat selamanya. Esok hari pertandingan usai. Passion reda, gairah jadi kuyu, seperti umbul-umbul yang kena hujan. Orang pulang dan berhitung, tentang ongkos beli karcis dan beli obat antiserak. Akuntansi, perhitungan utang dan piutang -- dan kecemasan untuk tidak kebagian tempat dalam hidup -- kembali mengambil peran. Bahkan, di tengah kegemuruhan kemarin pun, kalkulator telah berjalan: di meja penjual karcis, di kantor pemasang iklan di stadion, di rumah agen Porkas. Semua ikut meniup trompet buat jutaan manusia yang bergabung untuk satu kegilaan. Kegilaan itu pun sebuah target pen jualan. Mungkin itu juga bedanya kini dengan 20 tahun yang lalu. "Kepentingan, atau interes, telah mengepung gelora hati," kata teman kita bekas demonstran itu. Ia agaknya mengutip Hirschman kali ini, dan ia bergembira. Gelora hati, katanya yakin bisa menciptakan kejadian yang dramatis dan adegan yang mengharukan, tapi ia juga bisa meledak dan tak terduga. Stadion bisa runtuh, pemberontakan bisa terjadi, hak milik bisa punah, dan sejumlah orang bisa jadi korban. Kepentingan, sebaliknya, tak bisa meledak. Kepentingan bersemayam dalam perdagangan. Dan perdagangan, (teman itu kini mengambil Montesquieu) cenderung memoles dan melunakkan cara bersikap. Orang bermanis-manis meskipun tetap waspada dalam bersaing mencari "tangkapan". Memang, dengan itu terasa kita cuma deretan antre. Tapi seperti dalam tiap antrean, kita masing-masing dituntut tertib. Maka, hukum pun lahir, juga disiplin, karena kepentingan tiap orang menghendaki itu seperti kepentingan kita sendiri telah menyebabkan kita patuh pada lampu lalu lintas di hari sibuk.... Akhirnya teman itu berkata, "Biarkan kepentingan hadir di antara kita." Senyumnya tak saya temui 20 tahun yang lalu. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini