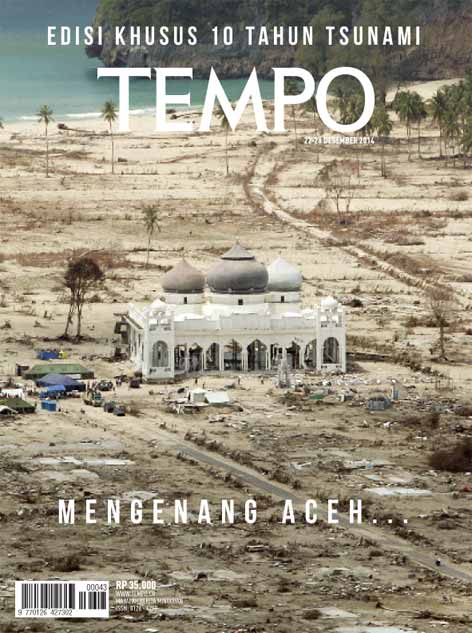Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SUNGGUH serampangan langkah polisi menetapkan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka penodaan agama. Aturan hukum pidana telah dibidikkan begitu sembrono dengan mengabaikan konteks karikatur yang dipajang harian itu. Perbuatan polisi jelas membahayakan kebebasan pers.
Karikatur yang dimuat pada edisi 3 Juli 2014 itu dimaksudkan mengecam perilaku pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Metafora yang ditampilkan menunjukkan kecaman itu: bendera ISIS dipelesetkan; sebagian gambarnya diganti dengan tengkorak. Semestinya dipahami, kritik Jakarta Post lewat karikatur yang diambil dari harian Al-Quds Palestina itu sebetulnya terbatas dalam ruang dan waktu tertentu. Terbatas pada sepak terjang pengikut ISIS, yang dilakukan pada hari-hari saat pemuatan karikatur.
Maka pengaduan Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta Edy Mulyadi, yang menganggap Jakarta Post menodai agama Islam, sebenarnya mengada-ada. Lebih aneh lagi, Kepolisian Daerah Metro Jaya pun seolah-olah tutup mata atas kelemahan pengaduan itu dan menjerat Meidyatama dengan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dewan Pers, yang telah berkomunikasi dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman, menyatakan penanganan kasus Jakarta Post dihentikan. Tapi masalah ini belum tuntas benar lantaran Polda Metro Jaya masih meminta pengadu dan teradu berembuk. Ini membuka kemungkinan kasus itu berlanjut apabila kedua pihak tidak mencapai kata sepakat.
Sikap tidak tegas itu merisaukan. Kepolisian semestinya melihat kejanggalan pengaduan tersebut. Bendera ISIS memang mengandung tulisan tauhid yang dijunjung tinggi umat Islam. Tapi bahan yang dijadikan metafora dalam karikatur bukan Islam sebagai agama, melainkan bendera organisasi. Pembedaan ini tidaklah sulit. Orang pasti mudah paham karena di Indonesia pun banyak sekali organisasi yang memunculkan simbol Islam dalam benderanya.
Penerapan Pasal 156 a terasa dipaksakan lantaran aturan pidana ini menyangkut penodaan agama dan bukan organisasi atau kelompok. Aturan pidana ini, antara lain, ditujukan pada "…barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia." Ancaman hukuman delik ini sampai lima tahun penjara.
Kepolisian semestinya bertindak profesional dan transparan. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, polisi seharusnya membuka prosesnya kepada publik, terutama menyangkut dasar dan alasan penerapan aturan KUHP itu. Apalagi Dewan Pers dan Kepolisian RI telah meneken nota kesepahaman pada 2012. Isinya, penggunaan Undang-Undang Pers lebih diutamakan ketimbang KUHP dalam menangani kasus pers.
Sikap polisi semakin terlihat aneh karena Dewan Pers telah menyatakan kasus itu sebagai pelanggaran etika jurnalistik. Dewan Pers menganggap kasus ini sudah selesai karena koran itu sudah meminta maaf sekaligus mencabut karikatur yang dianggap bermasalah tersebut.
Dalam kasus pertama pemidanaan pers di era pemerintahannya ini, Presiden Joko Widodo harus turun tangan. Setidaknya ia mesti memerintahkan Kapolri mengoreksi penyidikan serampangan itu. Pasal penodaan agama selalu kontroversial: penggunaannya kerap menabrak kebebasan beragama. Kini, gara-gara penerapannya yang kacau, aturan pidana ini pun mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo