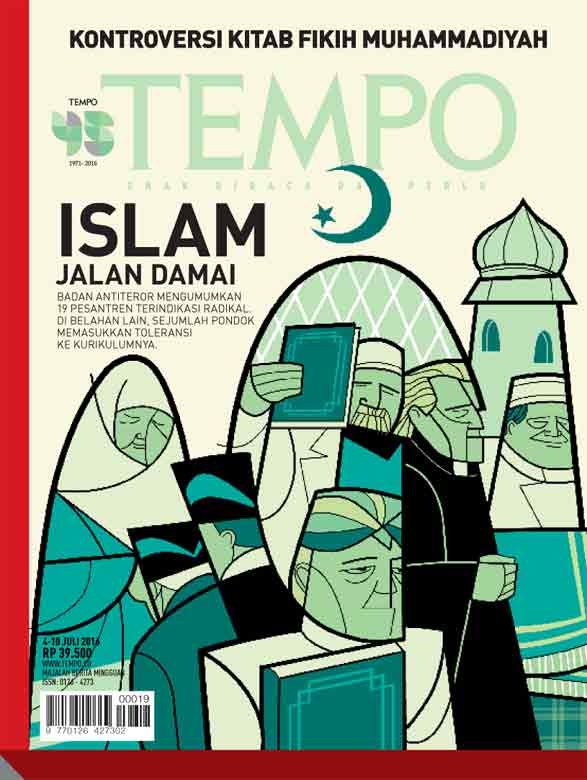Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENJELANG pelaksanaan referendum Brexit atau Bremain pada Kamis pekan lalu, hampir tak ada yang melihat pembunuhan Jo Cox, seorang anggota parlemen, sebagai isyarat sebuah keniscayaan bagi Inggris: bahwa rakyat, paling tidak jumlah yang lebih besar dari mereka, menginginkan keluar dari Uni Eropa. Tragedi yang menimpa Cox, yang gigih berusaha menjaga keberadaan Inggris di Uni Eropa, hanya menggerakkan gelombang duka—terutama di konstituensinya, Batley and Spen, di West Yorkshire. Perasaan ini sirna pada hari ketika suara harus diberikan.
Di luar London, Skotlandia, Irlandia Utara, dan kota-kota besar pada umumnya, ketidaksukaan terhadap Uni Eropa dan sikap anti-imigran jauh lebih kuat ketimbang apa pun. Nigel Farage, Ketua UK Independent Party yang mendukung pilihan keluar atau Brexit, meringkaskan suasana hati ini seusai pemberian suara dengan mengatakan rakyat telah memilih "tanpa sebutir peluru pun ditembakkan".
Pernyataan yang dikecam luas—dianggap tak berperasaan—karena mengabaikan fakta tentang Cox itu sebetulnya menegaskan bahwa secara demografi banyak pemilih merupakan bagian dari kelas pekerja yang cemas dan kehilangan harapan terhadap masa depan. Mereka umumnya tinggal di kota-kota pasca-industri yang perekonomiannya merosot dan diabaikan oleh pemerintahan demi pemerintahan sejak era Perdana Menteri Margaret Thatcher.
Alih-alih menunjukkan ketidakbecusan penguasa, para pemimpin kampanye Brexit justru mengeksploitasi suasana hati itu. Mereka memainkan kartu "Uni Eropa adalah musuh bersama". Mereka mengobral janji bahwa mencegah orang asing masuk ke Inggris bakal menjadikan negara lebih makmur, baik material maupun kultural—meski bukti nyata menunjukkan sebaliknya.
Respons sebagian pendukung pilihan tetap tinggal di Uni Eropa atau Bremain pun, sayangnya, gagal mengurai masalah; mereka tak bisa menenangkan perasaan orang-orang yang ingin keluar. Mereka menyamaratakan orang-orang itu sebagai kaum fasis atau anti-intelektual. Akibatnya, semakin dekat dengan hari penentuan, nada kampanye pendukung Brexit semakin dirasuki perasaan xenophobia dan bertambah irasional.
Uni Eropa memang tak sempurna. Perjanjian pembentukannya pada suatu saat bisa saja tak memuaskan negara-negara anggotanya, yang memang sangat beragam. Itu sebabnya peluang untuk memperbaikinya dibuka lebar, di antaranya melalui pemilu parlemen yang diikuti oleh partai-partai yang merupakan gabungan partai antarnegara yang memiliki kesamaan ideologi.
Perdana Menteri Inggris David Cameron sebetulnya juga telah berupaya merundingkan kembali syarat-syarat keanggotaan Inggris. Tapi, sebagaimana dia meremehkan besarnya sentimen anti-Uni Eropa, dia juga keliru menduga peluang yang ada untuk bermanuver. Di Uni Eropa, Inggris sudah terlalu banyak menerima keistimewaan, di antaranya pengecualian dari kewajiban mengadopsi mata uang tunggal dan kawasan bebas paspor, Schengen.
Apa yang terjadi di Inggris berpeluang merongrong Uni Eropa lebih jauh, karena kini muncul seruan di beberapa negara anggota lain untuk menyelenggarakan referendum serupa. Ini pengajaran yang tak bisa disepelekan oleh negara-negara lain yang berusaha mewujudkan sebuah masyarakat bersama seperti Uni Eropa. ASEAN, misalnya.
Di negara-negara anggota perhimpunan ini sauvinisme dan ketidaksukaan pada orang asing bercokol kuat. Ketidakmampuan mengelola sentimen ini bisa mendorong ekstremisme, seperti yang dianut pembunuh Cox, dan membawa persatuan yang bersifat supra-nasional ini ke perpecahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo