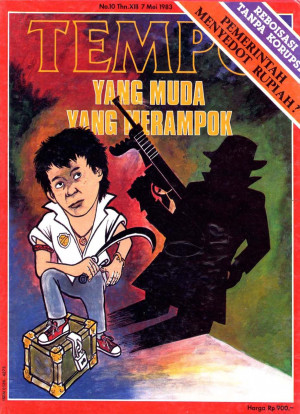1983
DI pesawat terbang itu, saya secara kebetulan ketemu Ota-san.
Ota-san (nama sementara, untuk kolom ini saja) adalah manajer
suatu cabang usaha sebuah multinasional Jepang. Ia duduk di
depan, saya di belakang. Artinya, ia di kelas wahid, saya kelas
benyamin. Namun dengan tergopoh-gopoh ia menyusul ke tempat
duduk saya. Menanyakan kesehatan, anak istri dan basa-basi
lainnya. Kabar tentang kawan-kawan kerja saya dan tentu saja
bagaimana saya bergiat dengan kegemaran saya. Jawabnya tentu
saja semua baik. Tak kurang suatu apa.
Kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Pembicaraan urusan
pekerjaan pun saya buka. Tentu saja hal yang baik-baik saya
kabarkan lebih dahulu. Mesin yang prima. Program latihan yang
efektif. Dan tenaga bantuan Jepang yang sigap. Namun saya cerita
juga soal agen perawatan perkakas yang ia jual, yang kerjanya
brengsek. Soal ketinggalan zamannya mesin-mesin yang telanjur
kami beli, dan beberapa masalah bisnis lain. Walapun seketika
itu reaksinya tidak mudah saya baca, kemudian terbukti ia amat
memperhatikan keluhan saya.
Manakala ia singgah di Jakarta, undangan makan siang saya
sampaikan. Maksud saya ingin membicarakan lanjut keluhan saya di
pesawat. Namun dengan halus dan sopan ia menolak. Alasannya
karena ia buru-buru harus kembali ke Tokyo. Ia berjanji memenuhi
undangan saya, pada lain kesempatan. Tetapi esoknya, dengan
sigap, sopan dan pakaian perlente, perwakilan usahanya di
Jakarta menemui saya. Ia ditugasi membicarakan keluhan yang saya
sampaikan. Di atas meja makan siang, tentu saja kali ini atas
beban perwakilan perusahaan Ota-san di Jakarta.
Biarpun istri saya sedang mengatur diet ketat buat saya, apa
boleh buat, jadwal makan apel dan air putih siang itu terpaksa
saya liburkan. Bukan lantaran sishimi dan susi yang selalu
mengingatkan saya pada Toshiko. Tetapi perkakas yang ngadat yang
dibeli dari perusahaan Ota-san itu memaksa saya berbuat apa
saja, demi menyelamatkan berfungsinya perkakas yang amat saya
perlukan itu.
Di seputar meja makan itu sudah duduk agen perawatan dan salah
seorang wakil kepala perwakilan. Setelah dozo serta domo silih
berganti, lalu haik haik secukupnya, urusan usai. Api di meja
dipadamkan. Pelayan membungkuk-bungkuk takzim laksana memberi
isyarat. Basa-basi upacara dan makan siang sudah harus diakhiri.
Selang seminggu setelah kejadian itu saya sampai di Tokyo untuk
urusan lain. Biarpun saya tinggal di hotel kelas tiga, di
kawasan Aoyama yang tidak beken, kedatangan saya ketahuan juga
oleh Ota-san. Suatu sore pesan sudah nyelip di tempat kunci.
Ota-san menelepon, dan minta dihubungi kembali. Sebagai orang
yang belajar sopan santun, saya tentu saja meneleponnya kembali.
Dengan terbata-bata ia meminta maaf. Tidak bisa memberikan
sambutan semestinya waktu saya tiba di Tokyo. Padahal ia tahu,
itu tidak perlu. Saya berterima kasih, namun Ota-san tak perlu
risau. Saya sudah dimanja oleh tuan rumah yang lain dalam
kunjungan ini.
Ia tetap mendesak. Dapatkah ia diberi kesempatan menjamu.
Setelah dengan sopan saya tolak, ia minta yang terakhir.
Mengantar dengan sedan perusahaan ke lapangan terbang Narita,
kelak bila saya pulang. Namun dengan sesopan mungkin, saya
bilang, saya telah diatur berangkat dari terminal kota. Padahal
tidak. Saya membilang banyak terima kasih atas kepeduliannya.
Tetapi tidak lupa saya khabarkan bahwa keluhan saya tempo hari
telah ditanggapi. Rupanya pernyataan itu yang ia tunggu-tunggu.
Dari segi bussiness service, baik yang beneran maupun yang
kembangan, kita patut belajar dari orang Jepang.
1975
Siang itu seorang tua yang tampak terhormat, membongkok-bongkok
mengetuk pintu kantor saya. Di kolom ini, sementara ia saya
namakan Naka-san. Sambil pertama dan utama menyodorkan kartu
nama, dengan takzim ia memperkenalkan diri dan keperluannya.
Seperti biasa saya tidak siap dengan kartu nama balasan.
Naka-san, manajer pemasaran sebuah produk pabrik kenamaan di
Jepang itu, sedang menawarkan suatu barang keperluan perumahah
penduduk kota. Tidak tanggung-tanggung, untuk keperluan seluruh
kota. Kalau anggaran tak cukup, toh Pemerintah Kota dapat
mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan tiap rumah tangga memakai
alat itu. Astaga, cerdik sekali orang tua ini menyodok jantung
pemasaran produknya.
Walau demikian dengan sabar saya mendengarkan uraian tentang
peralatan yang ditawarkan itu. Kemudian Naka-san masih mondar
mandir beberapa kali ke kantor saya. Desakan, bujukan, dan
imbauannya yang kesekian kalinya kemudian menjatuhkan belas
kasihan saya. Oke, saya bersedia melakukan uji coba alat itu,
asal tidak dibebani apa-apa. Dengan amat suka cita, Naka-san
pamit dengan langkah kemenangan. Dalam tempo singkat peralatan
didatangkan. Uji coba juga dengan sigap saya lakukan di beberapa
tempat. Dan pengamatan teknis dilakukan oleh tenaga teknis yang
kompeten dengan teliti. Uji coba dirancang berjalan satu bulan.
Sebagai insinyur yang patriotik, anak buah saya telah melakukan
tugas uji coba itu dengan sungguh-sungguh.
Dalam pada itu saya harus membacakan makalah di Nagoya. Kabar
itu disambut dengan suka cita oleh Naka-san. Ditawarkan apakah
saya bersedia menyisihkan beberapa hari untuk kunjungan ke
Osaka, menengok kawasan kota yang sudah memakai peralatan yang
ia tawarkan itu. Desak dan rayunya meluluhkan saya untuk satu
malam di Osaka sebagai tamu Naka-san.
Rupanya ia mencatat jadwal perseminaran saya di UNCRD di Nagoya
itu. Persis pada hari terakhir, sebuah sedan putih dengan
pelapis jok putih dan sopir berseragam putih serta bertopi pula
menjemput di tempat seminar di pinggiran kota. Seperti seorang
tahanan, saya merasa terkepung dan terperangah oleh layanan
aduhai yang mengagetkan. Namun saya sudah tak berdaya. Koper
butut saya diangkat dengan sigap, dikelilingi oleh orang-orang
yang membungkuk-bungkuk. Naka-san segera menggandeng saya,
mengajak masuk ke sedan itu.
Dalam perjalanan yang nyaman namun tetap melelahkan itu,
Naka-san bercerita tentang kerja di Jepang. Ia menanggapi
ketakjuban saya yang tampaknya ia ketahui itu. Lebih mengagumkan
lagi, persepsi budaya tentang bekerja, berprestasi, dan
berkompetisi dari sebuah anak bangsa yang tak kenal capek ini.
Di perkampungan yang dipamerkan menggunakan peralatan yang
ditawarkan itu, penampilan alat ternyata tidak meyakinkan saya.
Dan Naka-san tahu itu. Saya sebagai pengamat netral, tidak
merasa perlu gembira atau kecewa. Cukup mencatat apa adanya.
Namun tidak demikian dengan Naka-san. Ia berusaha keras memberi
kompensasi kekurangan itu. Maka perjalanan ke Kyoto pun
diekstrakan. Makan malam yang diteruskan survei ke kehidupan
malam pun ditambahkan. Sebagai pengamat yang netral, biar
kepingin sekali saya pun tidak boleh ngiler. Apa boleh buat.
Manakala tiba saatnya saya kembali, sepasukan pengiring pun
mengantar saya ke lapangan terbang Osaka. Semua sigap. Semua
siap berhormat. Naka-san tak lupa menitipkan pesan atas hasil
uji coba. Disertai "contoh" hasil uji coba dan surat rekomendasi
untuk alat serupa, yang telah ia peroleh dari Filipina dan
Muangthai.
Sampai di Jakarta, saya menerima laporan uji coba. Alat itu
perlu aliran listrik teratur, air ledeng yang tak pernah kurang
untuk pelontar jamban, lingkungan sekitar rumah tidak pernah
banjir dan tersedianya tablet kimia tertentu yang khas dari
pabrik itu. Syarat ini sulit dipenuhi oleh kondisi perumahan dan
hunian kota saat itu. Harganya pun masih mahal, di atas satu
setengah juta tiap rumah. Ini berarti tambahan biaya bagi setiap
pembangun rumah di Jakarta. Hal yang harus dihindari.
Kesimpulan: alat belum sesuai dengan kondisi kota. Berita itu
dengan terperinci dan lugas, apa adanya saya kabarkan kepada
Naka-san. Saya biasa bergaul sesama peneliti dan ilmuwan.
Biasanya findings semacam itu diterima dengan kepala dingin
biarpun kritis. Di luar dugaan saya, Naka-san ternyata amat
terkejut. Dengan terbata-bata ia memerlukan datang lagi ke
Jakarta. Kali ini ia mengetuk pintu rumah. Ia mengeluh dan
memohon belas kasihan. Pada umurnya yang lanjut dan akhir masa
pengabdiannya, ia tak siap menerima kegagalan. Kasihanilah saya,
katanya. Kalau tidak bisa membuat rekomendasi,
sekurang-kurangnya pernyataan bahwa barangnya itu telah lulus
uji coba oleh lembaga kami. Ini untuk sertifikat hasil jerih
payahnya bagi perusahaan.
Saya tertegun. Masygul karena hentakan Naka-san seolah-olah
memaksa saya untuk ingat utang budi. Namun saya pun sadar, saya
butuh melatih keperwiraan. Melatih ketebalan kulit dari ketukan
yang bertubi-tubi merontokkan keteguhan. Putra bangsa ini butuh
melatih diri menegakkan prinsip kejujuran dan integritas. Dengan
pedih dan pilu, saya terpaksa bilang tidak bagi Naka-san.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini