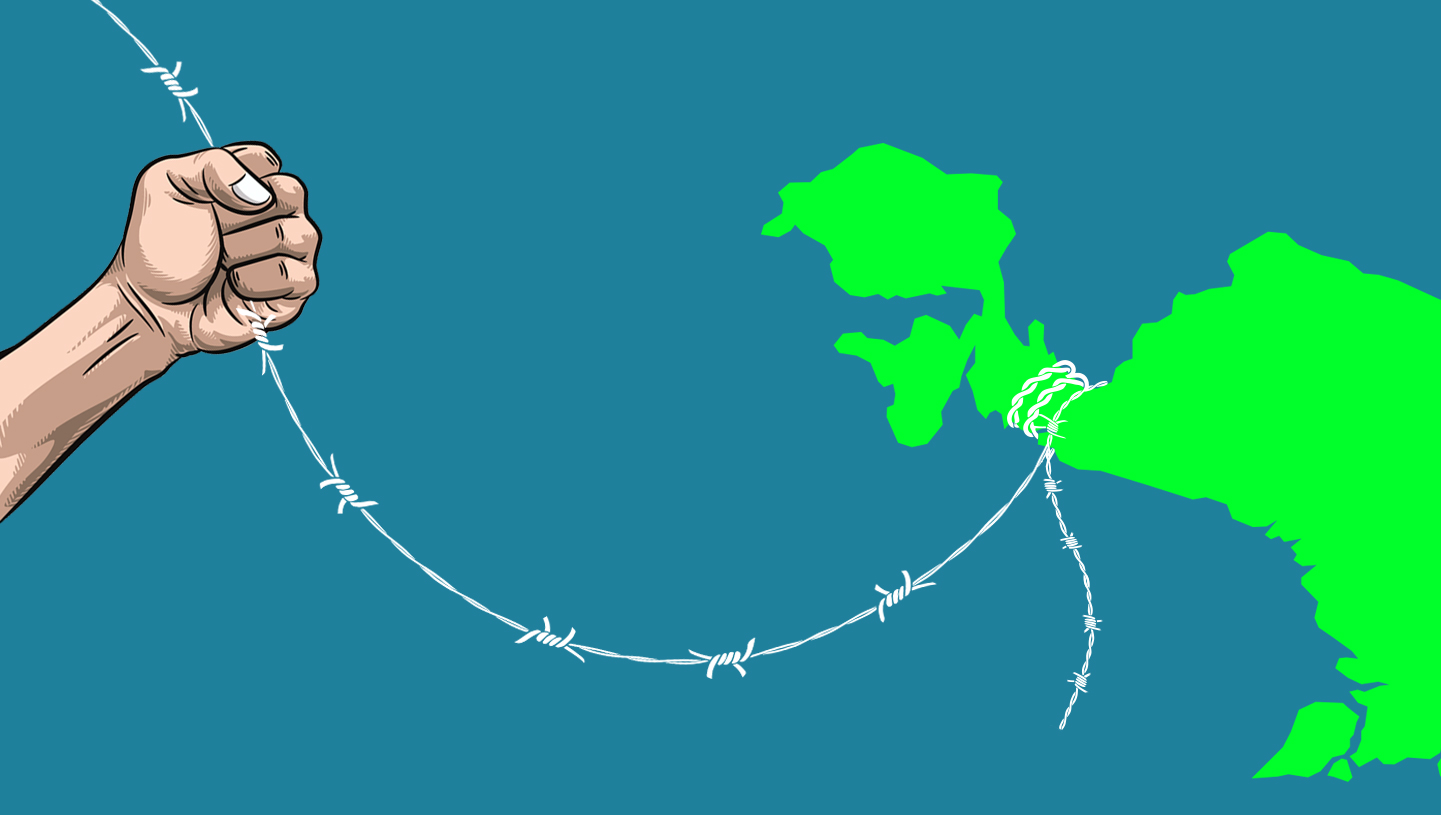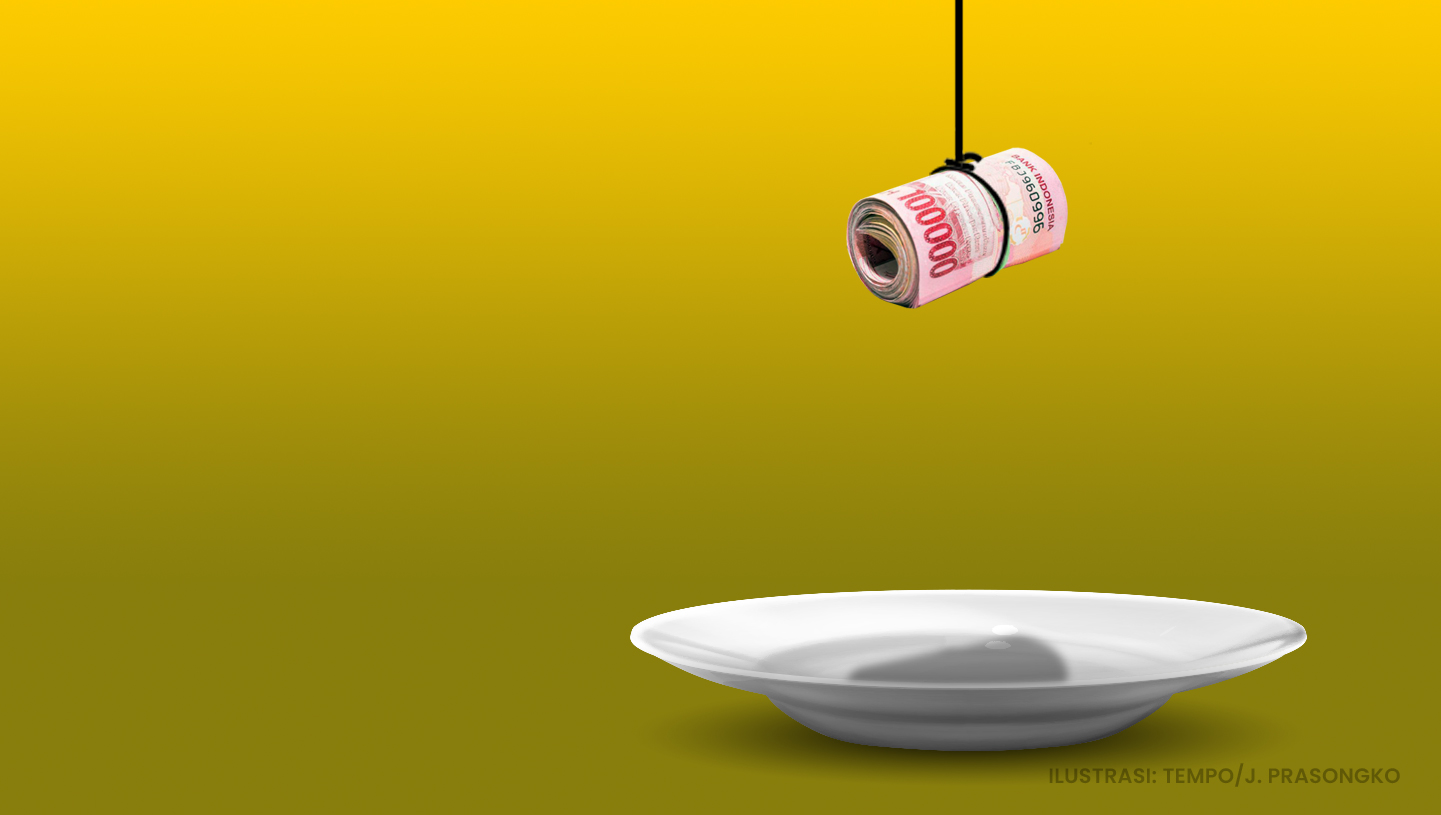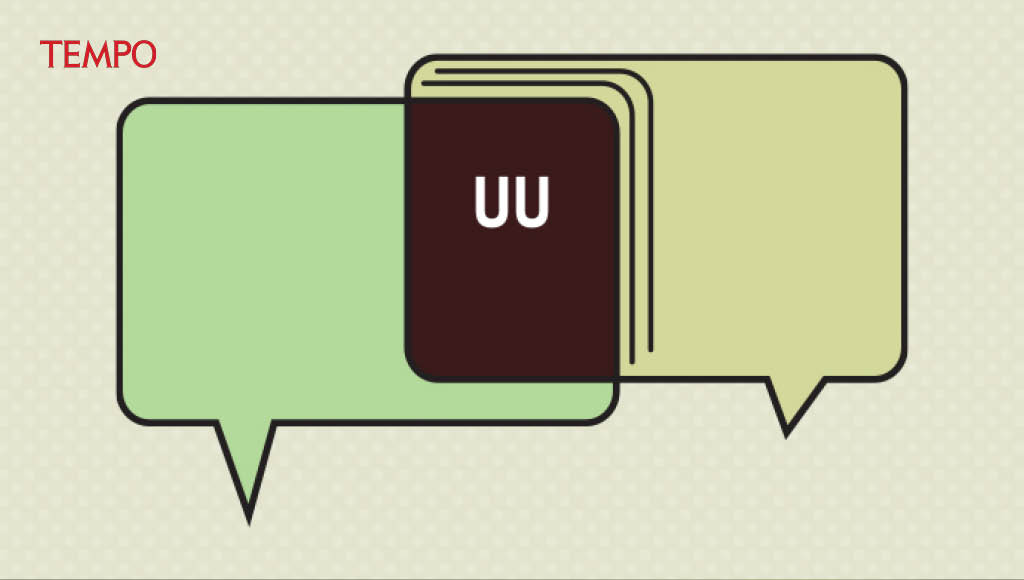Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fajri Siregar
Mahasiswa PhD Departemen Antropologi University of Amsterdam
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan skema kredit biaya kuliah merupakan sebuah kejutan. Ide itu seolah datang di siang bolong dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pemerhati pendidikan ataupun pemangku kepentingan. Meski tujuan dari inisiatif itu untuk memperluas akses memasuki perguruan tinggi, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum niat tersebut diwujudkan. Pemerintah sepatutnya juga mempertimbangkan opsi lain yang dapat ditempuh di luar kredit biaya kuliah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rencana itu sebetulnya menyalahi prinsip bahwa negara membiayai pendidikan. Soal apakah pendidikan tinggi termasuk salah satu layanan yang harus disediakan oleh negara memang masih diperdebatkan. Tapi, dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak ekonomi dan sosial budaya, pendidikan tinggi secara tegas dinyatakan sebagai salah satu layanan yang harus disediakan negara. Dengan kata lain, warga negara berhak menuntut negara untuk menyediakan pendidikan tinggi secara terbuka dan terjangkau.
Jika pemerintah Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, pendidikan tinggi merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhannya. Kredit biaya kuliah secara terang-terangan menyalahi prinsip tersebut karena menjadikan perkuliahan sebagai sebuah transaksi dan mengubah relasi mahasiswa dengan negara menjadi relasi transaksi. Warga negara tidak ubahnya konsumen pendidikan.
Di luar itu, ada baiknya para pengambil kebijakan juga mempelajari nestapa kredit kuliah yang dialami negara lain, terutama di Amerika Serikat. Angka di atas kertas menunjukkan bahwa kredit kuliah mendorong industri perbankan Amerika lantaran besarnya angka yang berputar sebagaimana disebutkan Jokowi, yakni US$ 1,3 triliun (hampir Rp 18 ribu triliun).
Namun angka yang mungkin tidak diketahui oleh Jokowi adalah bagaimana pada 2015 saja 10 juta mahasiswa tidak mampu melunasi kredit tersebut. Studi yang belum lama ini dirilis oleh Brookings Institution menunjukkan bahwa, hingga 2017, sekitar 28-29 persen penerima kredit kuliah tidak mampu membayar kembali pinjaman itu. Proses ini terjadi secara akumulatif, sehingga nyaris menciptakan krisis ekonomi baru di Amerika pada saat itu. Kredit macet menjadi keniscayaan karena produk kredit kuliah tidak diawasi dengan baik dan tidak ditunjang oleh pendanaan pemerintah. Hal itu memicu perlombaan baru di sektor perbankan untuk berburu mahasiswa yang rentan tertipu oleh janji manis pemberi kredit.
Dari gambaran tersebut, ada baiknya pemerintah justru berupaya memikirkan bagaimana biaya perkuliahan dapat tetap terjangkau. Ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan, terutama soal efektivitas anggaran dan alokasi anggaran pendidikan tinggi. Ada tiga ide yang saya tawarkan.
Pertama
Realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Selama ini pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam pembiayaan pendidikan tinggi karena status sebagian besar perguruan tinggi negeri (PTN) adalah satuan kerja alias dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi atau kementerian lain. Kontribusi pemerintah daerah sejauh ini hanya dalam bentuk hibah gedung, tanah, atau sarana lainnya. Sedangkan gaji dosen dan pegawai lainnya diperoleh dari APBN. Di sini ada lubang besar yang bisa ditutup jika anggaran operasional PTN bisa dialokasikan melalui dana pemerintah daerah. Hal itu ironis karena PTN selama ini seperti hanya menumpang di wilayah ia beroperasi, tapi keterlibatan pemerintah daerah sangat minim.
Model yang lebih optimal dan efisien serta berpihak pada prinsip aksesibilitas telah ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam waktu kurang-lebih tiga tahun terakhir, provinsi itu telah menunjukkan komitmennya untuk menyediakan pendidikan tinggi gratis bagi pemuda Sumatera Selatan dengan mengalokasikan anggaran Rp 40-50 miliar. Setidaknya, 2.000 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi provinsi itu telah dapat menikmati biaya pendidikan gratis meski sempat tersendat pada 2017.
Kedua
Optimalisasi beasiswa Bidikmisi. Program Bidikmisi telah berjalan cukup lama, tapi gaungnya masih belum terdengar. Ada banyak orang yang tidak tahu soal beasiswa itu. Padahal, serapan anggaran Bidikmisi tidak pernah menyentuh angka 90 persen. Hal itu menunjukkan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak pernah terserap habis. Jika banyak orang tak mampu tidak punya akses pembiayaan kuliah, mengapa Bidikmisi tidak bisa menjangkau mereka?
Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, tapi tidak pernah terserap dengan baik, Bidikmisi bisa dikatakan tidak pernah berhasil mencapai misinya. Untuk itu, lebih baik program ini dioptimalkan ketimbang beralih ke skema kredit kuliah yang mengandalkan keuangan perbankan.
Ketiga
Pemerintah pusat perlu pula mempertimbangkan skema dana abadi sebagai penunjang dana operasional untuk PTN berbadan hukum. PTN ini beroperasi sebagai badan otonom, yang berbeda dengan PTN satuan kerja, sehingga tidak dapat menerima alokasi langsung dari APBN ataupun APBD.
Otonomi khusus itu membutuhkan skema pendanaan yang lebih mandiri pula dan berorientasi jangka panjang. Dana abadi yang dikelola secara profesional dan berpotensi meraih laba dapat menjadi solusi pendanaan khusus untuk mereka. Bentuknya dapat menyerupai sebuah lembaga layanan sebagaimana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bentukan Kementerian Keuangan dengan tujuan membiayai kegiatan pendidikan dan beasiswa.