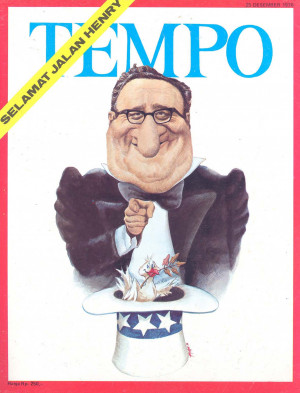KALAU si Mona gadis kecil 12 tahun berhasil meyakinkan ibunya
bahwa dia butuh sepatu baru dan blues merah jambu maka
terjadilah suatu persuasi. Ibu tetap berada dalam posisi tidak
terikat. Appeal si gadis terarah kepada kebaikan hati. Proses
pengambilan keputusan bersifat sefihak. Si ibu diminta dan
dibuat yakin untuk memenuhi permintaan anaknya. Seluruh
tawar-menawar berlangsung dalam kondisi "kalau boleh kiranya".
Naik helicak dari Menteng Raya ke Sarinah menurut tarif yang
diketahui umum supir helicak dan calon penumpang akan makan
ongkos Rp 10. Tetapi kalau anda menstop sebuah helicak maka
dialog seperti di bawah ini menjadi tak terelakkan Ye Sarinah,
berapa bang? Tiga ratus saja oom.
- Ah, yang benar bang, biasa seratus.
- Dua ratus oom.
-- Satu setengah, mau? Dan pintu akan segera dibuka buat anda.
Tawar-menawar itu kadang-kadang membuat kesal. Apalagi kalau
kesusu. Bagaimana pun bang supir tidak akan pernah langsung
menyebut tarif yang sebenarnya. Dan sulit untuk merasa yakin
bahwa sang supir akhirnya setuju dengan tarif Rp 150 karena
berhasil dipersuasi. Tawar-menawar itu cuma basa-basi. Semacam
ritus pendahuluan sebelum boleh numpang kendaraannya. Di sini
keputusan sudah sama-sama diketahui. Konsensus sudah tersedia.
Tawar-menawar itu bukan decision-making-process, tetapi
mirip-mirip ucapan "selamat pagi" atau seperti to say hallo.
***
Ketika Marx mulai tampil membela kelas buruh, maka soal persuasi
inilah yang dibabatnya habis-habisan. Menurut Marx, majikan
bukanlah bapak keluarga yang baik hati. Tidak banyak manfaatnya
mengharapkan kemurahan jenis apapun dari fihak dia. Upah buruh
jangan sekali-kali dipandang sebagai perwujudan rasa
belas-kasihan, tetapi adalah hak yang harus dituntut, kalau
perlu dengan paksaan. Perbaikan nasib buruh tidak datang sebagai
hasil proses sefihak dari majikan. Majikan malah harus dipaksa
dengan 'kekuatan' dan bukan lewat persuasi yang berlangsung
dalam kondisi "kalau boleh kiranya". Asas kekeluargaan tidak
bisa diterapkan dalam soal upah buruh. Bukan karena asas itu
kurang baik, tetapi justru karena terlalu baik untuk bisa
berlaku dalam bidang hubungan majikan-pekerja.
Buruh dapat memperbaiki nasibnya kalau dia ikut serta dalam
proses pengambilan keputusan dan tidak dengan berada di
luar.proses itu sambil mengharap-harap. Harus diciptakan serikat
buruh, majikan diancam dengan mogok. Ketenangan yang tadinya
aman, familier, tetapi merugikan kelas buruh, kini diganti oleh
ketegangan yang penuh was-was, zakelijk, tetapi menjamin
kebaikan bagi kedua belah fihak. Si Majikan tidak bisa hanya
serakah dan sewenang-wenang. Buruh dapat merencanakan perbaikan
nasibnya lewat jalan 'mengatur' majikan.
Dengan dimungkinkannya buruh mempengaruhi proses pengambilan
keputusan, dimulailah gerak demokratisasi dalam hubungan
majikan-pekerja- pengaturan bersama, putusan bersama dan nasib
bersama yang tercipta adalah distribusi keuntungan dan
distribusi kekuasaan dan kekuatan.
***
Ada dua hal yang kelihatan dalam penjelasan Marx tersebut.
Pertama ialah bahwa dalam soal kekuasaan, maka pendekatan
yang bersifat moralistis merupakan pendekatan yang tidak
kena. Artinya. Seorang majikan hampir tidak mungkin diharapkanl
untuk cukup berbaik-hati sehingga bersedia atas kehendak
sendiri memperbaiki nasib buruknya. Appeal kepada
hatinuraninya tidak akan berakibat banyak. Persuasi tak
berguna. Karena persoalan majikan adalah mengikhtiarkan
keuntungan yang berlipat ganda secara tetap dan bukannya
memikirkan nasib buruh. Nasib buruh berada di luar
kerangka-acuan pemikirannya buruh karena itu, tidak boleh
menyerahkan nasibnya kepada majikan. Dia harus mengambilnya
sebagai masalah dirinya sendiri, dan mencari jalan bagaimana
masalah itu diselesaikan secara efektip. Cara yang diajarkan
Marx ialah bahwa buruh harus dapat memaksa majikan (dengan
organisasi mogok misalnya, kalau upah tidak dinaikkan) agar
supaya majikan terpaksa memperbaiki nasib mereka. Buruh haruslah
memiliki sejumlah kekuatan di tangannya agar dapat 'mengatur'
majikan. Perbaikan nasibnya tidak akan datang lewat persuasi
tetapi lewat distribusi kekuasaan dan kewenangan dalam membuat
keputusan.
Hal kedua yang diramalkan Marx ialah bila kelas pekerja
terus-menerus ditindas oleh majikan, maka mereka akan bertahan
habis-habisan sampai pada suatu titik batas yang masih bisa
diterima (seorang teman menyebutnya tolerable margin). Lewat
batas itu akan terjadi ledakan berupa revolusi sosial yang
mengakhiri kekuasaan majikan. Anehnya, revolusi itu justru tidak
terjadi. Sebab buruh dengan alat organisasi mogoknya, setiap
saat dapat mengancam majikannya, sehingga majikan terpaksa
memperbaiki nasib buruh, sebelum buruh didesak sampai pada
'batas toleransi' mereka. Dengan proses serupa itu tolerable
margin senantiasa dihindari, revolusi sosial tidak meledak, dan
sebagai akibatnya kekuasaan majikan tetap bertahan. Sejarah
negara-negara industri kiranya membuktikan hal itu: revolusi
sosial hampir tidak pernah terjadi di sana.
***
Nampak dari proses itu bahwa bila buruh hanya memakai persuasi
yang menurut Marx tidak bakal mempan - maka besar kemungkinan
nasib mereka terus-menerus ditindas, yang berarti 'batas
toleransi' mereka terus bertambah dekat dan pada suatu waktu
akan dilanggar dan menimblkan revolusi sosial, yang mengakhiri
kekuasaan majikan. Yang terjadi adalah bahwa justru karena ada
distribusi kekuasaan, justru karena buruh juga diberi kekuatan
tertentu, majikan selalu terdesak memperbaiki nasib buruh untuk
menghindari 'batas toleransi' itu, yang mengakibatkan bahwa
revolusi sosial tidak terjadi dan kekuasaan majikan berlanjut
terus.
Yang aneh ialah bahwa kekuasaan majikan dipertahankan justru
karena kepada buruh diberikan juga kekuatan tertentu. Hal ini
terjadi dalam bidang hubungan majikan-buruh. Tetapi nampaknya
itu juga misteri dan paradox demokrasi: kekuasaan dimantapkan
justru dengan mendistribusikannya. Dan itu mungkin berlaku pada
semua jenis kekuasaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini