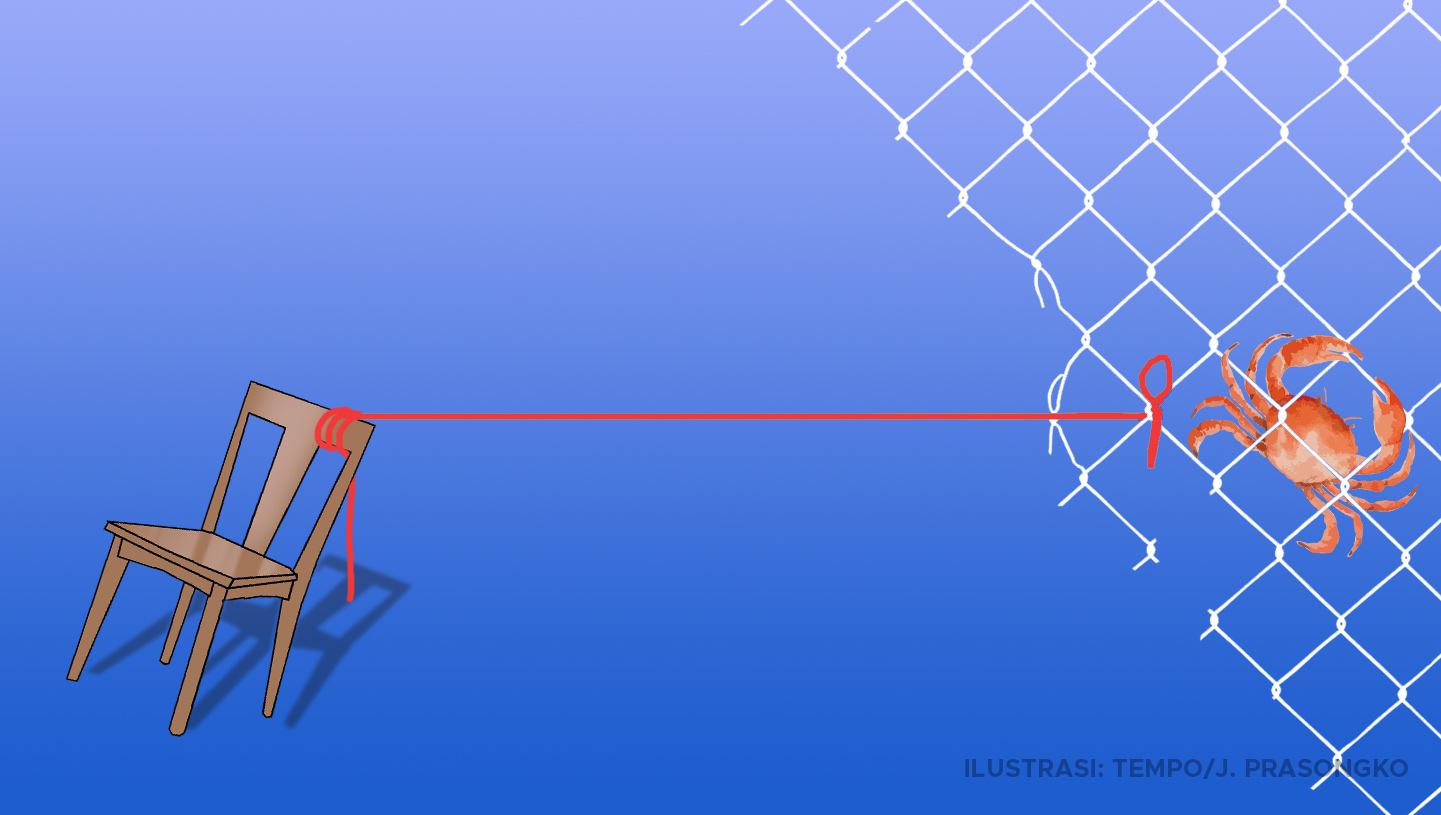Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada suatu hari Manuel Vargas, Jr. datang ke sebuah rumah sakit di Singapura untuk pemeriksaan kandung kemihnya. Di bagian pendaftaran ia harus mengisi formulir: nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel....
Dengan lancar ia jawab semua pertanyaan, kecuali satu kolom: ras, race. Ia tertegun. Pengajar psikologi di sebuah universitas di Manila itu heran bahwa di tahun 2017 faktor "ras" masih dibutuhkan dalam telaah medis.
Ia berpikir sejenak, lalu menulis, "Melayu."
Petugas: "Tuan tak salah tulis?"
"Tidak," Manuel tersenyum.
"Tapi nama Tuan bukan nama Muslim."
"Saya tak tahu apa maksud Anda dengan 'nama Muslim'. Saya Katolik dan ras saya, menurut kategori resmi, Melayu."
Lalu tambahnya, sedikit sarkastis: "Kalau Anda keberatan, saya tarik kembali. Apalagi saya tak tahu apa hubungan ras dengan kandung kemih."
Dr Manuel Vargas, Jr. (bukan nama sebenarnya) agak mencemooh: di bagian dunia ini orang peduli benar terhadap kategori rasial dengan kesimpulan yang aneh: bahwa "Melayu" berarti "Muslim", bahwa orang Melayu tak mungkin bernama Manuel Vargas atau Julia Perez. Di sini tampaknya orang masih percaya ada ciri biologis, gaya hidup, atau pola nutrisi yang tetap dalam sebuah "ras" dan sebab itu penting dalam analisis medis.
Vargas kesal tapi tersenyum. Baginya, tak ada "ras". Ia gemar mengutip Kwame Anthony Appiah, filosof Inggris-Amerika yang dalam In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture (1992) mengatakan, "Tak ada ras, dan tak ada sesuatu di kehidupan dunia yang dapat melakukan semua hal yang kita harapkan dari ras...."
Appiah malah pernah menegaskan, secara biologis, identitas rasial itu nonsens. Apalagi mengaitkan ras dengan budaya-misalnya sikap berbahasa dan cara makan atau bersetubuh. Dalam semua hal itu, tak ada konsistensi.
Appiah sendiri contoh tak adanya konsistensi itu. Ia lahir di London tapi dibesarkan di Kumasi, Ghana. Ayahnya seorang diplomat dari negeri Afrika bekas koloni itu, ibunya seorang aristokrat Inggris yang punya sejarah dalam tata kolonial. Bahkan dalam perkawinan Appiah berada di luar kategori yang ada: ia gay, menikah dengan lelaki keturunan Yahudi.
Apa boleh buat: identitas tak pernah tunggal dan mandek. Kita berenang dalam arus label demi label yang tak henti-henti: aku seorang ibu, aku seorang muslimat, aku seorang polisi.... Identitas hanya seakan-akan menetap ketika ia dilekatkan ke diri kita oleh masyarakat dan Negara-dan kita mengadopsinya, tak jarang dengan yakin, mengharukan dan menggelikan.
Tapi-jika kita ikuti pandangan Appiah-sesungguhnya tak pernah ada seseorang yang "Melayu" atau "Tionghoa". Hanya asumsi dari luar dan penentuan diri sendiri yang membentuknya. "Kita mengharapkan orang dari ras tertentu untuk berperilaku secara tertentu," kata Appiah. Sang label "membentuk laku intensional dari mereka yang dimasukkan di bawah label itu".
Walhasil, label atau identitas terbangun dan dirawat dari kondisi bersama-orang-lain. Terutama dalam persaingan, kecemasan, dan permusuhan. Ketika rezim Hindia-Belanda membagi penduduk Indonesia dalam kategori "Eropa", "Timur Asing", dan "Pribumi", tujuan utamanya adalah mengukuhkan otoritas kolonial-sebuah otoritas yang rapuh fondasinya di atas masyarakat jajahan yang sudah 300 tahun melawan.
Kategori itu kacau: "Eropa" tak dilihat dari asal-usul dan warna kulit, tapi dari "mutu" kebudayaannya; "Timur Asing" mengacu ke asal-usul geografis, tapi tak jelas apakah seorang Melayu dari Semenanjung masuk golongan ini. Sedangkan "Pribumi", inlander, kadang-kadang dikaitkan dengan sejarah, budaya, atau etnisitas.
Singkat kata: tak konsisten. Tapi rezim Hindia-Belanda mengukuhkannya dengan pelbagai cara-dari tata sosial-politik sampai dengan pakaian. Raden Saleh, pelukis ternama itu, ketika kembali ke Jawa, harus menulis surat kepada Ratu Belanda agar ia diizinkan mengenakan pantalon, sebab di Hindia-Belanda inlander hanya boleh memakai kain dan destar. Permohonan Raden Saleh ditolak.
Dalam apartheid seperti itu, sulit menyatakan tak ada ras. Appiah memang punya privilese untuk menolak taksonomi itu. Tapi dari latar yang pedih, orang justru merasa perlu menegaskannya. Kita baca Aime Cesaire (1913-2008), penyair Martinik, jajahan Prancis. Dalam keadaan disisihkan, bersama intelektual lain dari Afrika, ia buat gerakan Negritude. Ia menulis:
dalam kebisuan yang gelap dan luas, ada suara yang bangkit, tanpa penerjemah, tak diubah, tak bernyaman-nyaman,
sebuah suara keras dan stakato, menyebut buat pertama
kalinya, "Aku, Negre"
Bagi Aime, ia menulis "untuk identitas yang didapatkan kembali".
Politik identitas bermula dari sini: hasrat untuk diakui. Tapi ada yang bisa menjebak: identitas, juga identitas rasial, sering begitu menggelembung hingga lupa bahwa tak ada yang utuh dan hakiki dalam dirinya. Juga tak ada hubungannya dengan kandung kemih.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo