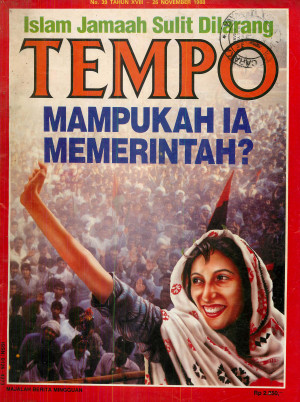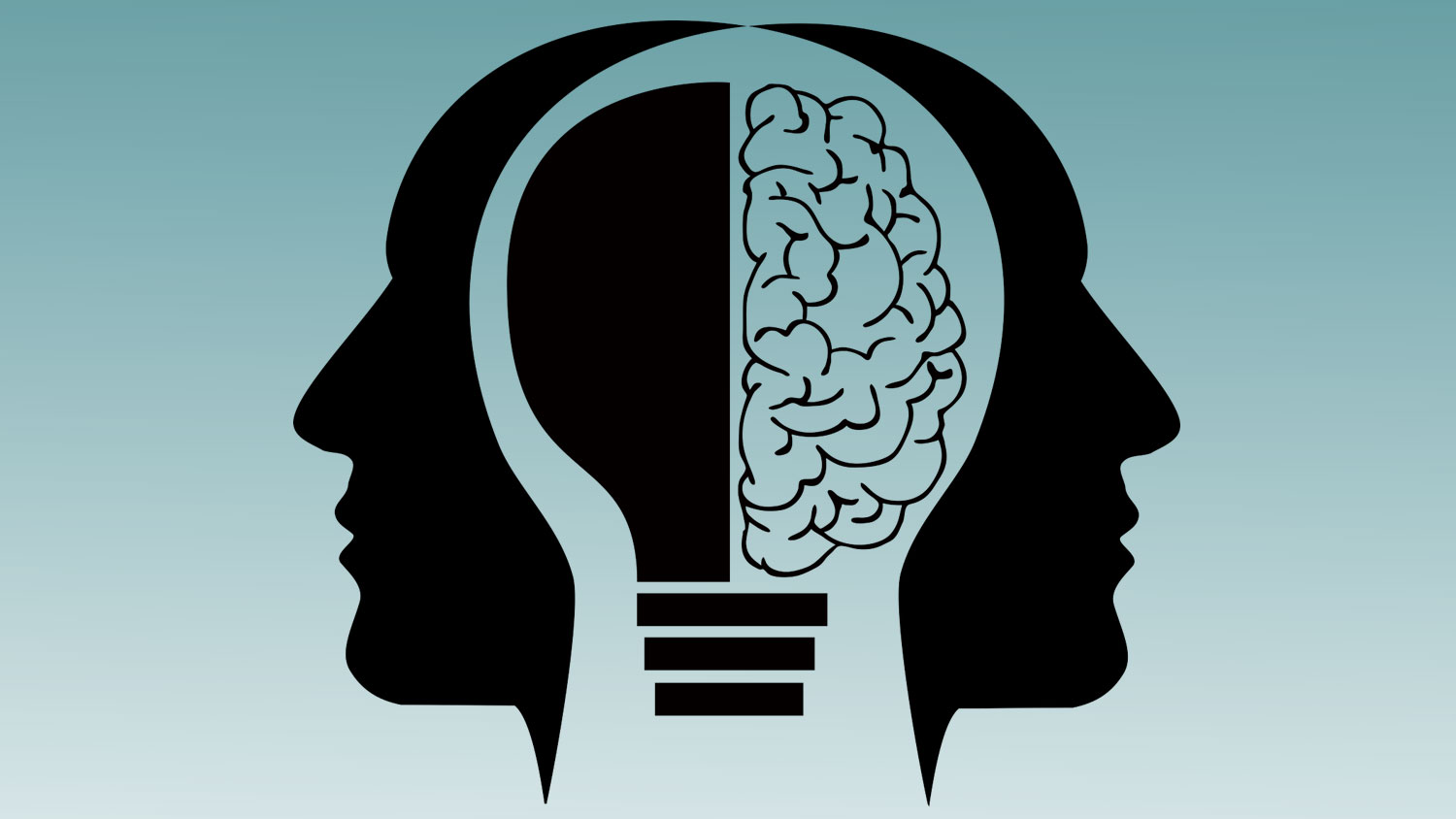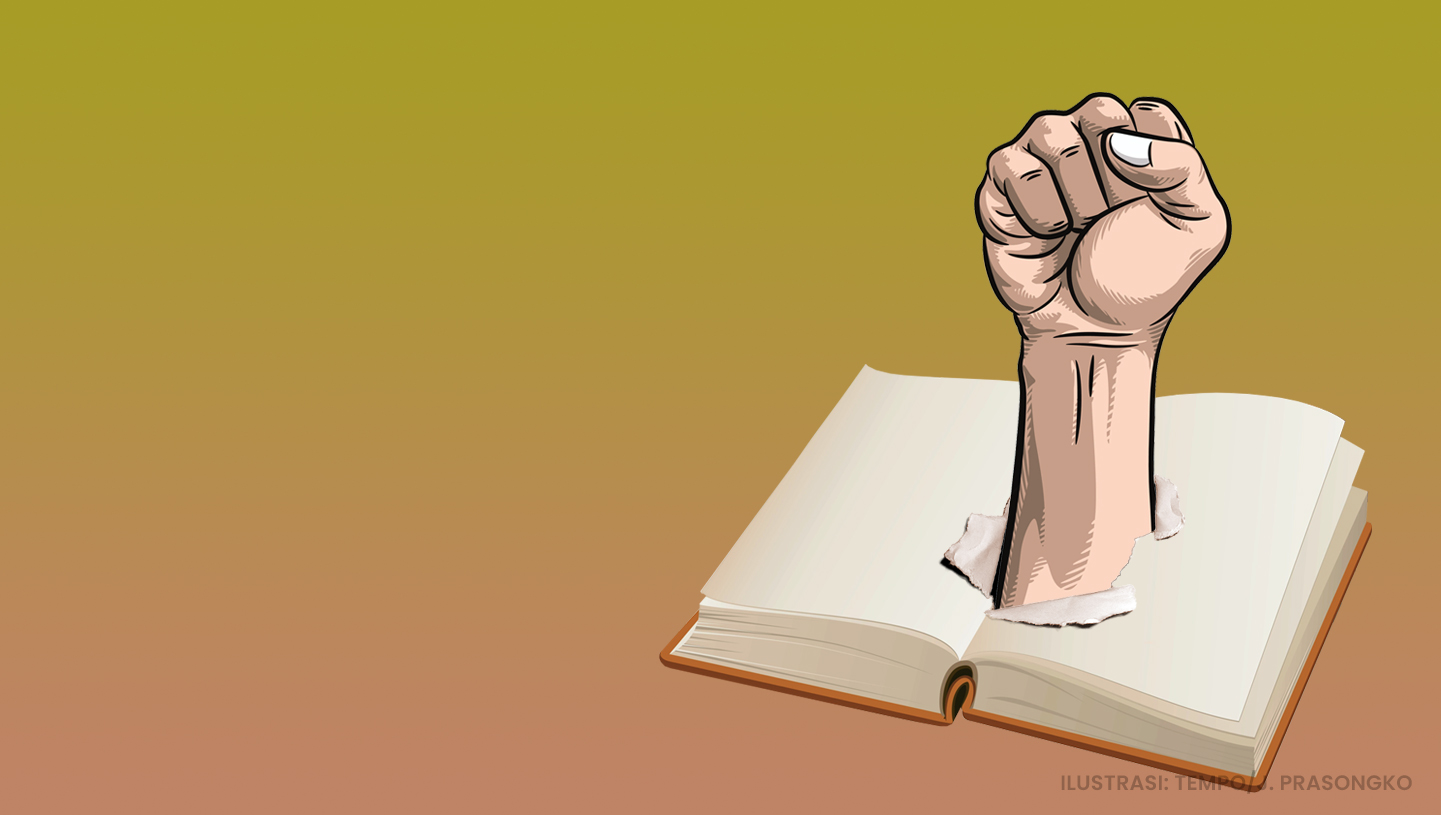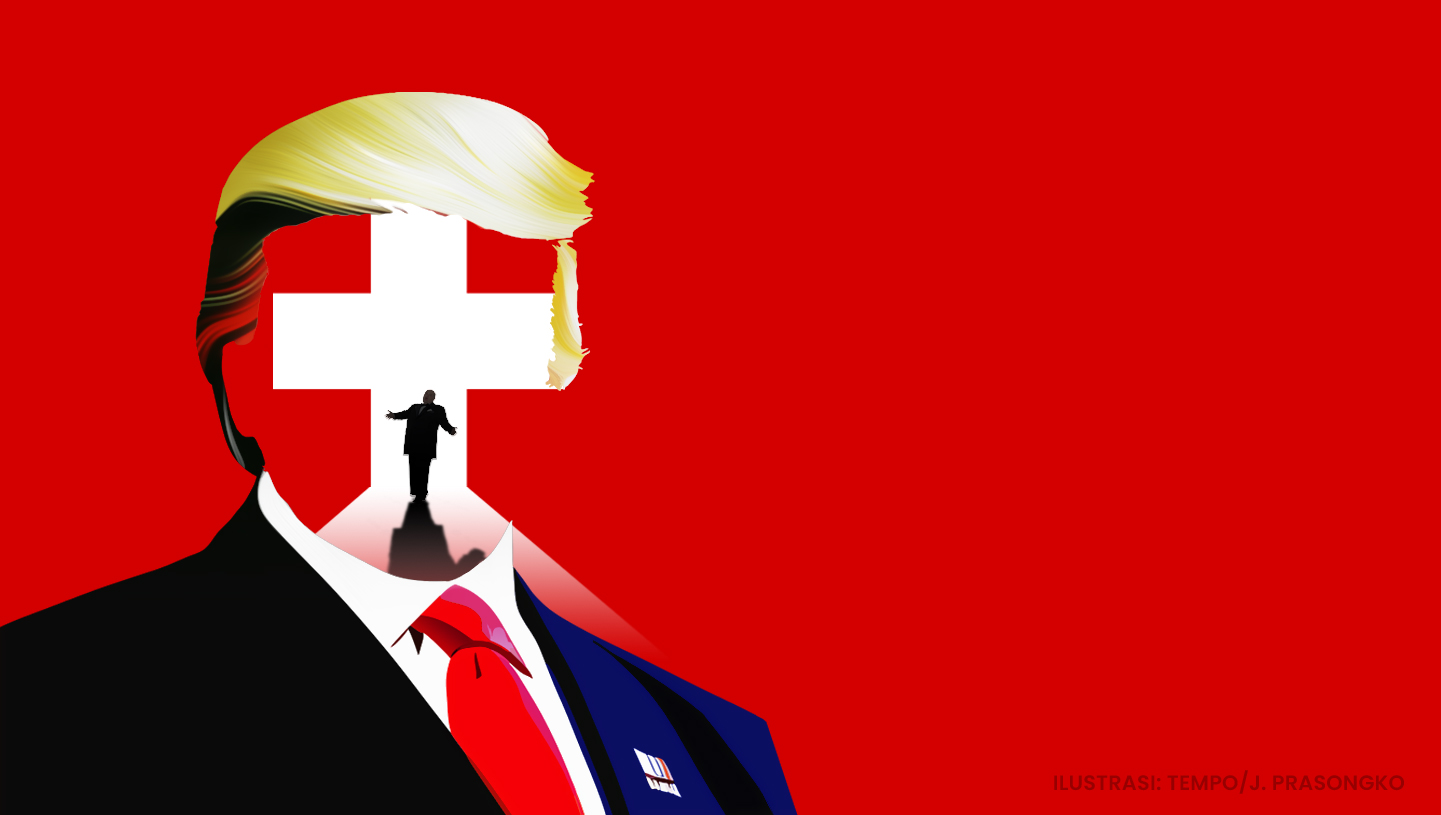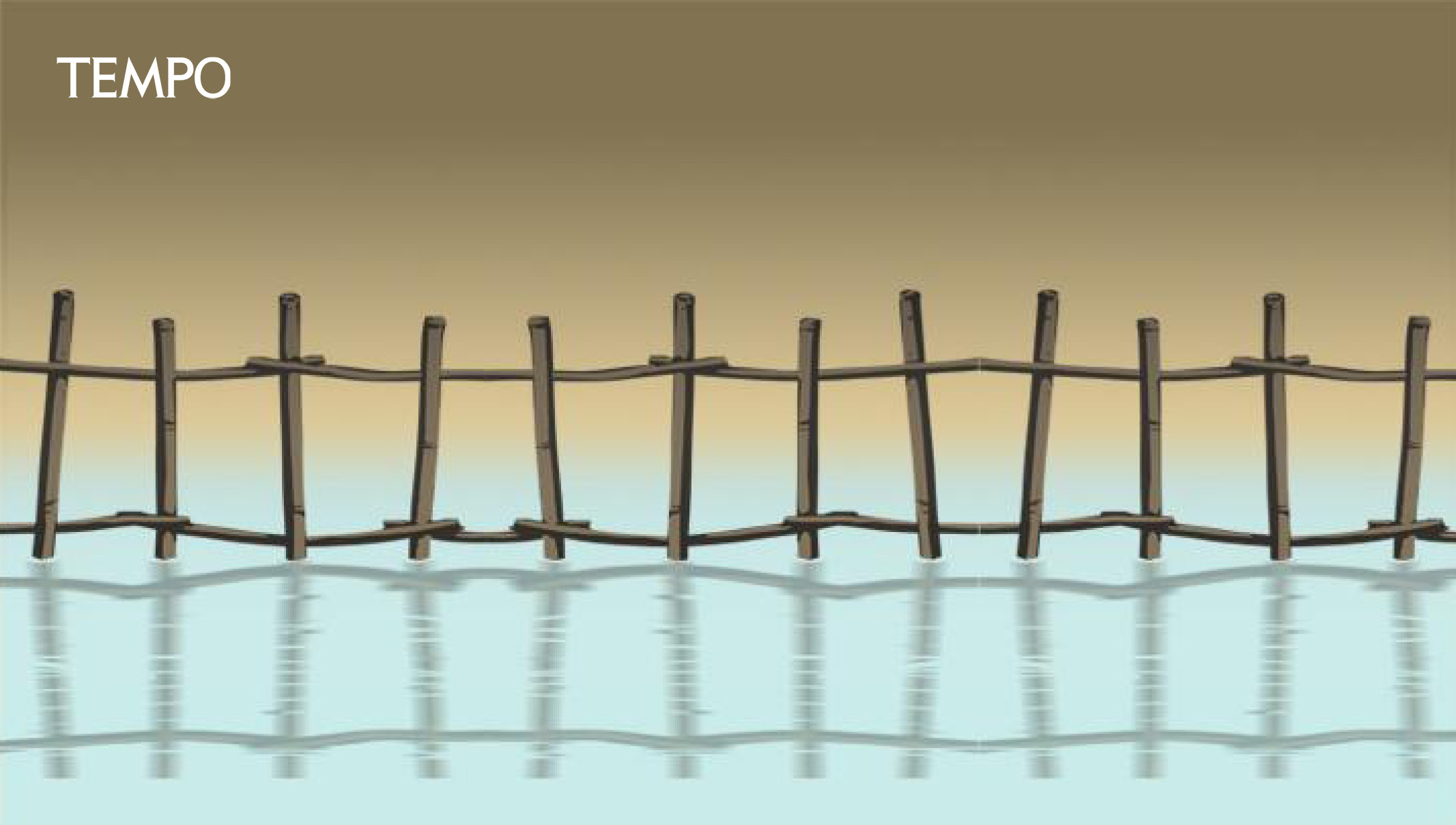ADA sebuah cerita tentang lapangan tenis dan deregulasi. Di Jakarta, di masa "demokrasi terpimpin' di tahun 1960-an, seorang bisa bermain tenis gratis di lapangan milik kota praja. Tapi untuk itu, ia harus mengisi sembilan kopi formulir. Semuanya harus diserahkan ke 12 jawatan pemerintah. Mungkin, dengan itu orang bakal lebih capek mengurus ijin main tenis ketimbang main tenisnya sendiri. Tapi tentu bukan itu tujuan pemerintah waktu itu. Alasannya barangkali "pemerataan": sebuah aturan harus dibuat agar orang bisa bergiliran main gratis di sebidang lapangan tenis. Dan siapa lagi yang mengatur kalau bukan pemerintah, yang -- atas nama rakyat -- punya kuasa atas lapangan itu. Saya tak melebih-lebihkan. Contoh kecil tapi ekstrim itu -- disebut dalam tulisan Herbert Feith, Dynamics of Guided Democracy yang terbit di tahun 1963 -- memang petunjuk tentang kenapa kemudian orang menginginkan "deregulasi" ketika "demokrasi terpimpin", bersama Bung Karno, jatuh. Feith memakai istilah overregulation untuk menggambarkan keadaan sosial-ekonomi dalam masa "demokrasi terpimpin", ketika pada akhirnya pemerintah mencoba mengatur segalanya -- kalau perlu hanya dengan dekrit. Contohnya banyak. Maret 1959, inflasi membubung. Pemerintah pun mengeluarkan dekrit, agar harga tetap seperti bulan Desember 1958. Jika ditanyakan bagaimana para produsen bisa hidup dengan itu, jawabannya kurang lebih ialah imbauan untuk berkorban. Hal yang sama terjadi di wilayah pedesaan. Petani diatur agar menjual sebagian panen mereka dengan harga yang ditentukan. Dalam hal tebu, sebuah undang-undang bernomor 38 di tahun 1960 memberi wewenang kepada negara untuk memaksa petani menangguhkan hasil finansial yang lebih baik: tanaman yang "tidak vital", seperti tembakau dan bawang yang menguntungkan, harus ditunda pembudidayaannya, agar tebu, yang "vital" bagi kepentingan nasional, tak ditinggalkan orang. Di tahun 1961 petani di daerah gula harus menjual tebu mereka pada harga Rp25 sekuintal: nilai yang tak menguntungkan sama sekali di tahun 1962, pemerintah mengeluarkan dekrit agar sebagian tertentu dan luas sawah harus ditanami tebu, yang hasilnya harus diserahkan ke pabrik. Penyerahan paksa seperti ini, seperti ditulis oleh seorang penelaah sejarah ekonomi memang merupakan ulangan dari kebijakanaan kolonial abad ke-18. Tapi siapa yang berani menyebut demikian di masa itu, karena masa "ekonomi terpimpin" yang revolusioner itu justru dinyatakan sebagai masa bangkitnya antikolonialisme, dan segala regulasi itu hanyalah tuntutan agar kita berkorban ? Pada akhirnya, pengaturan yang begitu banyak, pengelolaan perekonomian dengan dekrit, memang harus punya dalih. Dan harus punya efektivitas. Dalih itu disediakan oleh sebuah ideologi. Dan ideologi itu disebarkan, dan kalau perlu -- agar efektif -- digertakkan. Di tahun 1960, menurut catatan Feith, para redaktur surat kabar harus bersumpah menerima ideologi negara. Dan di tahun 1961, apa yang mulanya hanya terjadi di negara totaliter lain seperti RRC dijalankan di Indonesia: pemerintah mulai mengajarkan ideologi Manipol USDEK kepada para wartawan. Juga di universitas. Maret 1961, Bung Karno menunjuk Iwa Kusumasumantri jadi menteri peguruan tinggi dan ilmu pengetahuan. Tiap pelajar yang mau berangkat ke luar negeri harus ada izin dari menteri sendiri setelah sebelumnya menyatakan keyakinan kepada Manipol USDEK. Iwa bahkan menganjurkan mahasiswa untuk melaporkan tanda pemikiran "liberal" di kalangan guru mereka. Yang dituju memang satu pengaturan yang total. Bangsa dan negeri sedang ditransformasikan, dan sebuah cita-cita besar, suatu cause dimaklumkan. Tapi barangkali sebuah negeri bukanlah sebuah cause, bukan sebuah cita-cita, melainkan sehimpun kenyataan. Ketika kenyataan lebih kuat tampil ketimbang ideologi, ketika kehidupan ternyata lebih rumit ketimbang dekrit, ketika pengaturan dan kontrol yang total pada akhirnya tak bisa tercapai, terjadilah apa yang terjadi di tahun 1966. Para mahasiswa dan lain-lain di tahun 1966 membuat sebuah seminar di Universitas Indonesia. Mereka, meskipun dengan hati-hati, menolak apa yang dicoba diberlakukan selama hampir sepuluh tahun. Mereka, misalnya Emil Salim, menampik apa yang mereka sebut "etatisme". Dan saya ingat Widjojo Nitisastro hari itu mengutip sebuah kalimat lucu dari pengalaman Amerika: "Bila pemerintah tidur, ekonomi berjalan. Yang mungkin masih perlu dipelajari orang di Universitas Indonesia (atau di mana saja) ialah kenapa pemerintah punya kecenderungan insomania. Mungkin mau seperti Tuhan: Tuhan tak pernah tidur, bukan? Goenawan Mohammad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini