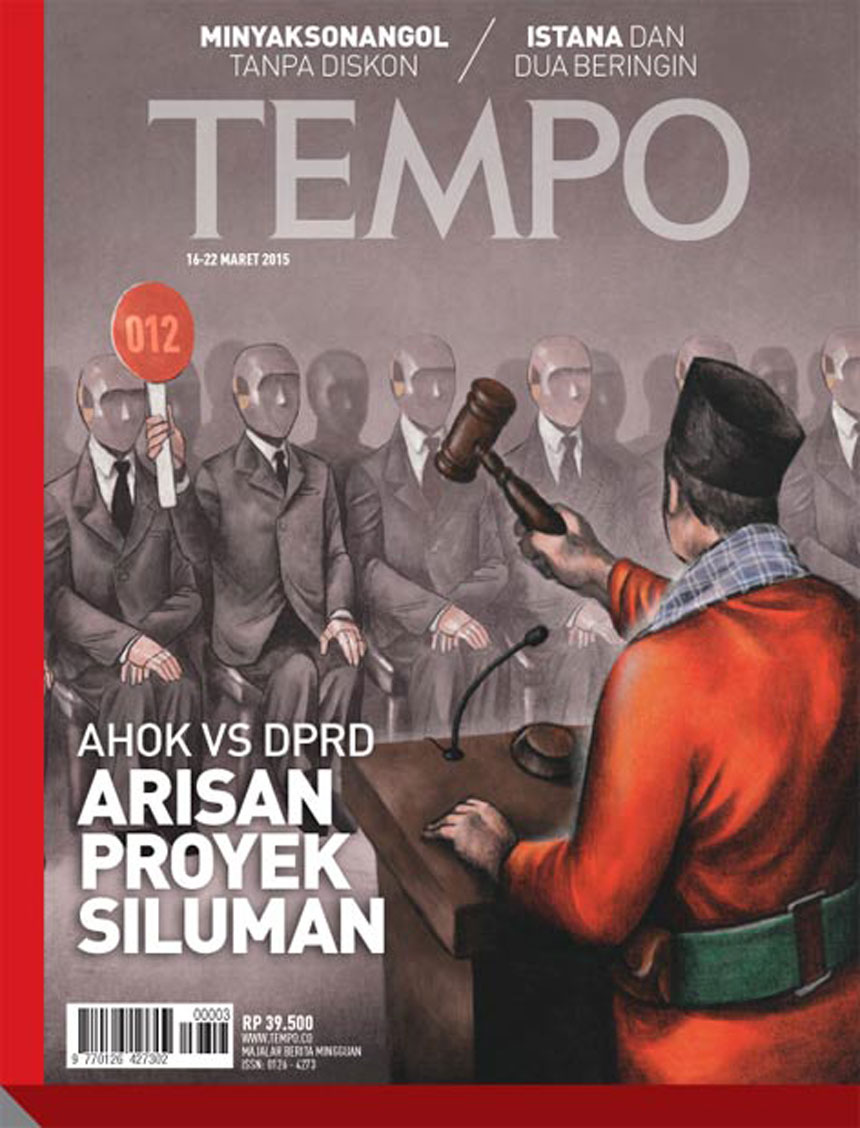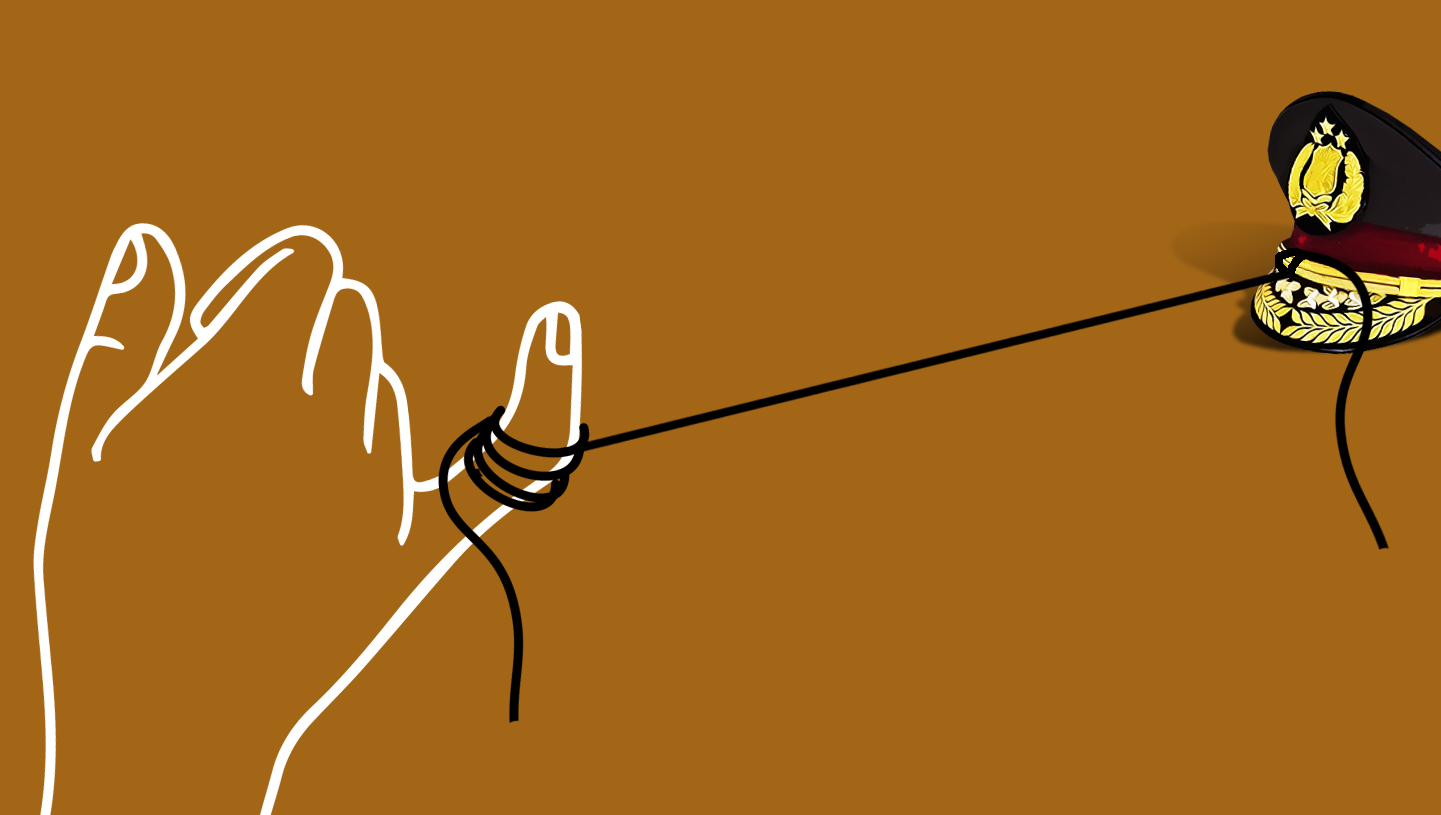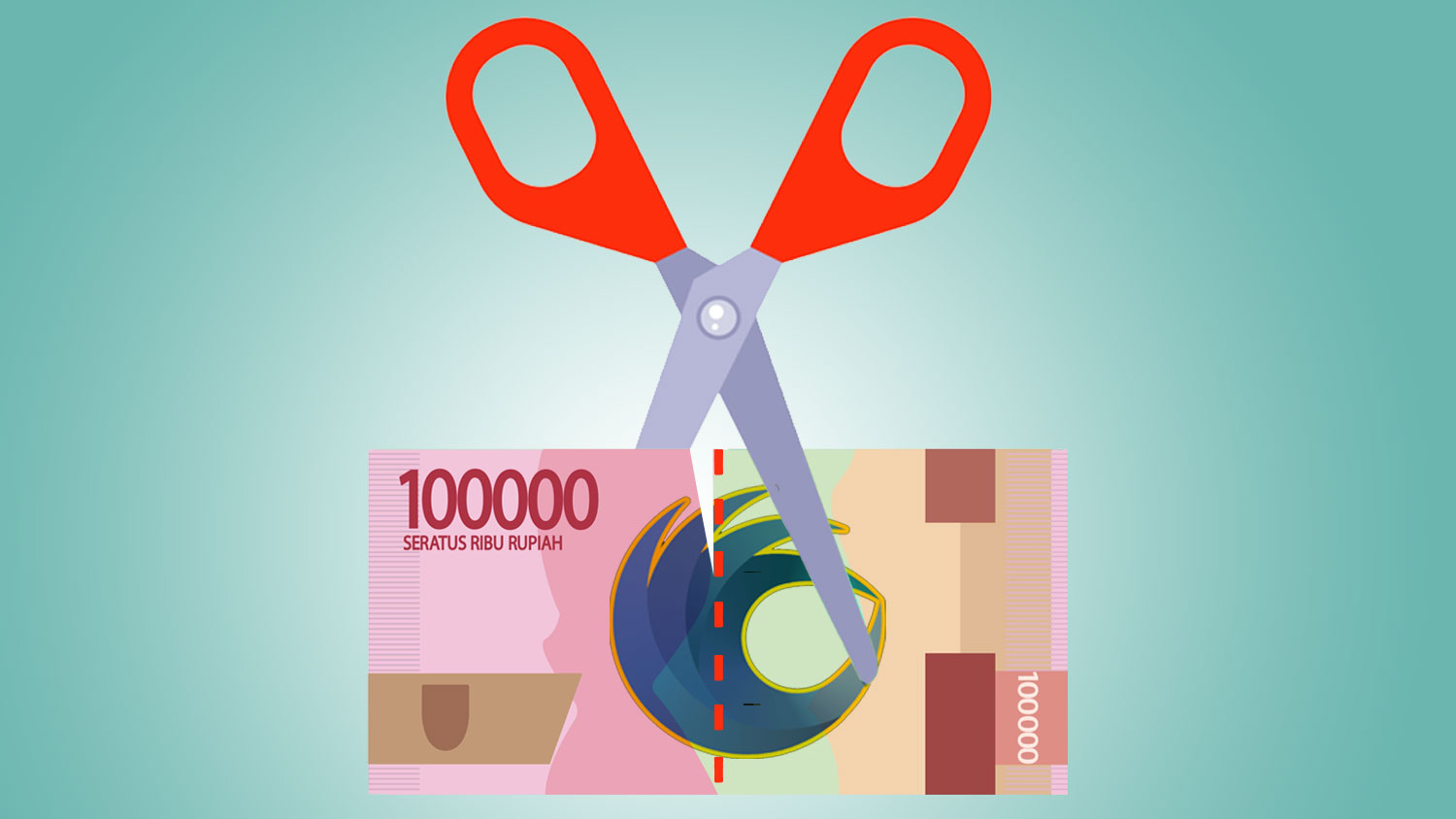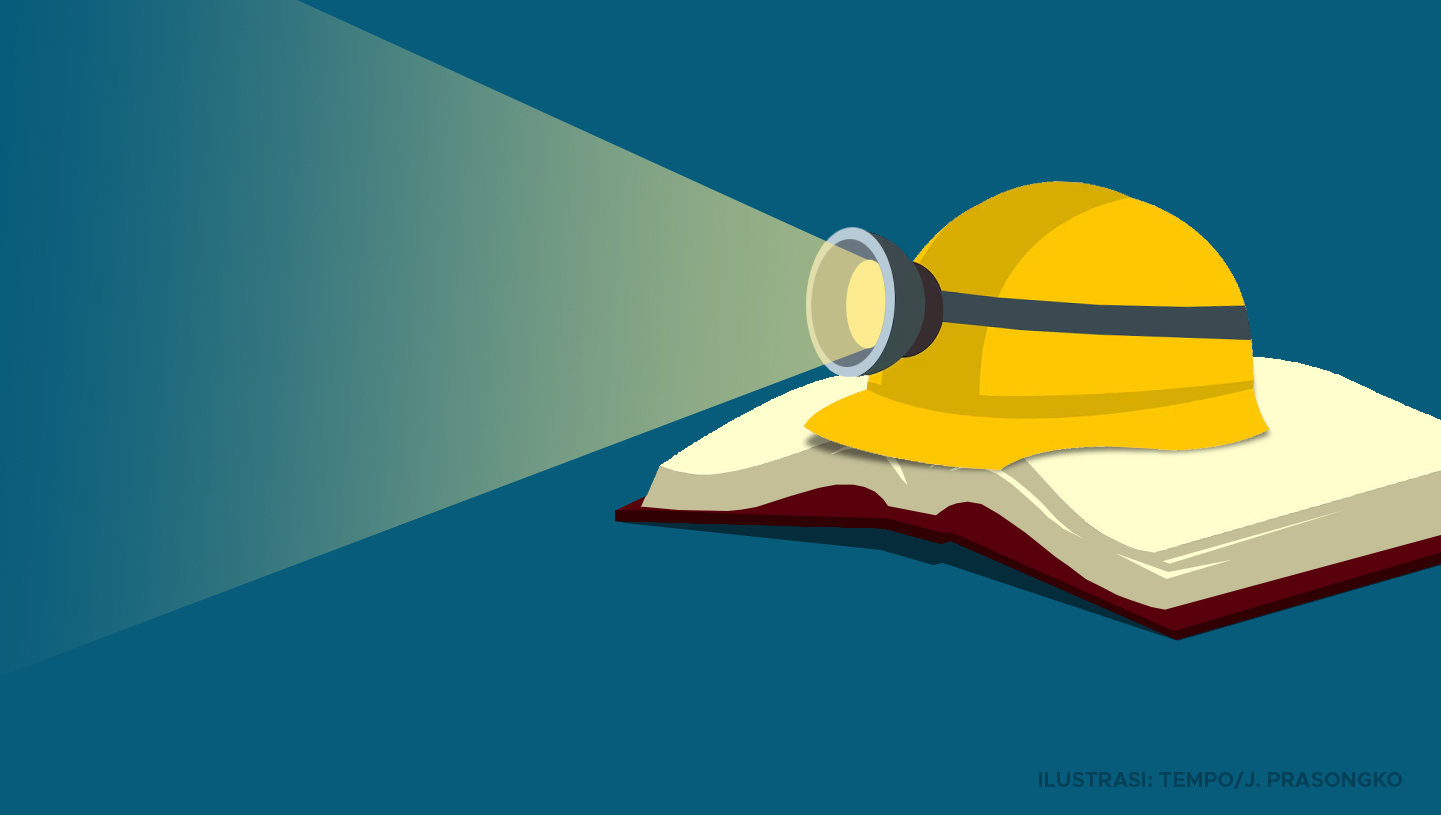Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEMERINTAH mendapat kesempatan terbaik untuk menata ulang kepemilikan dan sistem siaran televisi nasional. Momentum itu datang dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dua pekan lalu, yang mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial.
Selama ini, kanal televisi nasional dibagi secara kolusif. Hanya segelintir pengusaha yang mendapat hak istimewa dari pemerintah Soeharto. Akibatnya, seperti yang berkali-kali terjadi, ketika "pemilik" kanal ikut berpolitik, saluran publik itu digunakan untuk propaganda kepentingan pribadi. Pemerintah terkesan membiarkan keadaan ini.
Perubahan bermula dari Geneva Frequency Plan Agreement pada 2006, yang menyepakati migrasi dari televisi analog ke digital. Dengan teknologi digital, satu kanal analog bisa dicacah menjadi enam-sembilan kanal digital. Rencananya, Indonesia dibagi dalam 15 zona siaran. Di setiap zona akan ada enam kanal analog yang dialihkan ke digital. Seharusnya inilah peluang untuk menambah kanal dan mengundang lebih banyak pemain baru.
Ternyata muncul peraturan Menteri Tifatul Sembiring-Menteri Komunikasi dan Informatika ketika itu-yang celakanya malah melanggengkan oligarki lama. Hasil lelang di tujuh zona penyiaran menunjukkan pemain lama masih mendominasi dan hanya ada satu pendatang baru. Fakta mengecewakan ini kemudian memicu protes hingga muncul gugatan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia ke PTUN.
Dua asosiasi itu seakan-akan menantang kemapanan para baron televisi nasional yang berbilang tahun menikmati "madu" bisnis televisi. Pada 2013, misalnya, sampai triwulan ketiga, menurut data Marketing Research Indonesia, lebih dari separuh belanja iklan nasional-sekitar Rp 78,5 triliun-masuk ke televisi. Melihat angka fantastis itu, tentu pemain lama akan mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga agar kue iklan tetap menjadi milik mereka. Entah apa alasannya, Menteri Tifatul seperti segendang sepenarian dengan para baron itu.
Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru, Rudiantara, berpeluang besar melakukan perombakan. Setelah putusan PTUN itu, Menteri Rudiantara mesti memastikan kewenangan pengelolaan penyiaran multipleksing tidak lagi diserahkan kepada perusahaan media seperti pada zaman Tifatul. Prinsipnya, agar tak terjadi benturan kepentingan, perusahaan media televisi tak boleh merangkap sebagai pengelola penyiaran multipleksing. Badan usaha milik negara seperti PT Telkom bisa ditugasi menjadi "muks" atawa penyelenggara multipleksing itu.
Seiring dengan itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat segeralah menuntaskan perubahan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Ini penting agar penyelenggaraan televisi digital memiliki basis hukum kuat. Agar partai-partai di DPR membela kepentingan publik, bukan semata kepentingan kelompoknya, publik wajib mengawasi proses revisi undang-undang ini.
Televisi memiliki kemampuan sangat kuat untuk "menulari" publik. Pilihan orang ramai banyak dipengaruhi siaran televisi, termasuk preferensi politiknya. Di tangan segelintir oligark lama, frekuensi publik hanya menjadi alat menambang keuntungan besar dan sering menjadi media propaganda kepentingan sendiri. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara seharusnya tak melewatkan kesempatan terbaik mengubah lanskap televisi kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo