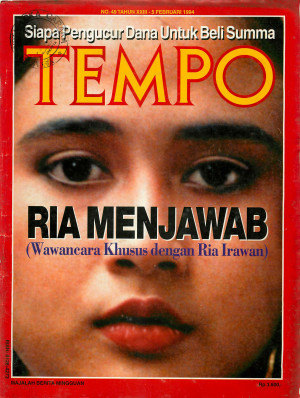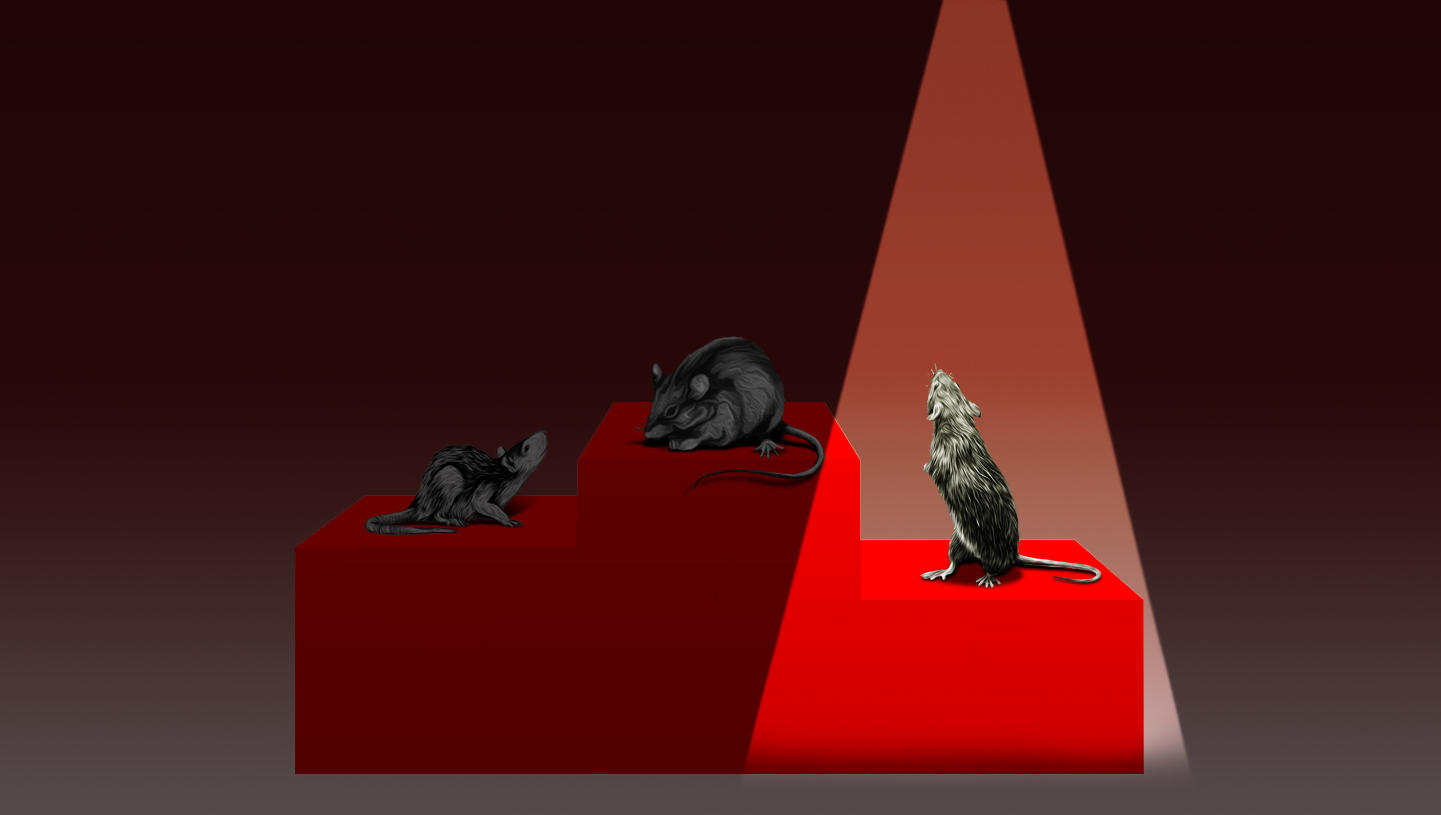BILA masyarakat merisaukan pembangunan kompleks resor di kawasan Tanah Lot Bali, memprotes upaya mengubah Keputren Keraton Solo menjadi hotel, menyesalkan rencana penggusuran Masjid Hidayatullah di Jakarta untuk sebuah bank, tentu karena pembangunan tersebut dikhawatirkan akan mencampuradukkan dua "isi" dalam sebuah ruang. Suatu hal "baru" akan dibangun pada roh kebudayaan yang telah bersemayam terlebih dahulu. Sebab, tiap ruang dan bangunan yang telah menjelma menjadi makna kebudayaan memiliki "roh" dan "isi", telah menjadi ruang publik. Itulah bagian kota yang paling banyak digunakan rakyat, yang telah menyerap rasa dan peristiwa kemanusiaan. Perwujudan ruang ini bisa berupa jalan dan arcade, lapangan terbuka seperti alun-alun, taman kota, atau berbagai halaman dan gedung semipublik dan publik seperti kampus, perkantoran, dan gedung DPR. Ruang publik menjadi penting karena memiliki ciri sebagai dunia publik. Bagi masyarakat, memasuki ruang publik adalah memasuki "dunia bersama". Di sana, masyarakat bisa duduk, berdiri, atau berlari. Mereka bisa membaca, melamun, menangis, bercengkerama, berpacaran, ataupun berteriak dalam suasana bebas dan dalam kesamaan derajat yang seutuhnya. Dalam dunia publik ini dimungkinkan pula berlangsungnya berbagai mode asosiasi dan forum opini publik. Berpidato atau berunjuk rasa di ruang publik semestinya sah-sah saja karena ruang publik pada dasarnya adalah ruang representasi bagi kepentingan masyarakat. Bahkan Hannah Ahrendt di tahun 1950 menyebutkan, idealnya ruang publik adalah sebuah dunia yang politis sifatnya. Ruang publik, selain sebagai institusi publik, juga sebuah konstruksi formal estetika. Secara formal, peran bangunan dalam ruang dapat diibaratkan seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam yang membuat riak di sekelilingnya. Begitu sebuah karya arsitektur terbangun dengan segera ia membuat dampak pula pada ruang di sekitarnya. Oleh karenanya, bentuk dan kualitas ruang publik sangat dipengaruhi oleh gubahan dan muka bangunan (facade) yang melingkupinya. Teori desain arsitektur dan kota modern selama ini mengabaikan relasi tersebut. Melalui praktek kapitalisme perkotaan, desain modern cenderung melihat ruang kota sebagai kekosongan, yang hanya menunggu untuk dirajang lurus-lurus oleh jaringan jalan agar setiap lahan bisa dicapai semudah-mudahnya oleh teknologi mobil. Tapak juga dipandang hanya sebagai kekosongan, yang menunggu untuk dikolonisasi oleh bangunan-bangunan yang berdiri lepas sendiri-sendiri sebagai figur. Ruang yang tercipta di antara bangunan-bangunan lantas menjadi sekadar sisa-sisa ruang. Ruang publik barangkali masih akan terproduksi, tapi berupa ruang sisa itu, yang awut-awutan tak berbentuk. Pemecahan kosmetik lantas tak terhindarkan: variasi ruang publik diciptakan melalui pertamanan, atau pembuatan bundaran- bundaran di jalan yang sering sulit diakses oleh pejalan kaki. Dalam pandangan Postmodernisme, teori modernisme seperti di atas harus direvisi karena telah terbukti tidak mampu melindungi atau menciptakan ruang-ruang publik yang artistik, koheren, dan manusiawi. Pembangunan kota harus menciptakan kembali ruang publik yang tidak sekadar menjadi latar belakang bangunan. Sebaliknya, bangunan-bangunan mestinya digubah untuk menjadi latar belakang dari ruang publik digubah untuk menciptakan ruang publik yang berbentuk dan memiliki pertalian dan koneksi dengan ruang publik lainnya, baik secara visual maupun simbolis, dan sekaligus sebagai ruang sosial yang manusiawi bagi pejalan kaki, pengendara sepeda, dan lain-lain. Ruang-ruang publik yang artistik, koheren, dan manusiawi dapat kita jumpai misalnya di Desa Tenganan di Bali, kawasan Malioboro-Keraton di Yogyakarta, Kota Kudus dan Lasem atau Oud de Staad di Semarang. Di kota-kota tersebut, tempat terbuka dan jalan selain menampung berbagai aktivitas sosial juga diorganisasikan melalui kategorisasi eksterior-interior, umum- khusus. Dan itu terangkai dalam sebuah sistem sirkuit ruang linier, yakni ruang-ruang yang dihubungkan lewat jalan-jalan yang terdeferensiasi dan berhierarki. Struktur ruang kota lantas bisa terasa bagaikan komposisi musik crescendo, bergerak bertahap menuju suatu klimaks, yang biasanya berwujud ruang publik tematik seperti kawasan pura, keraton, masjid, gereja, atau bangunan publik. Postmodernisme juga melihat kota sebagai peristiwa historis dan kultural. Aldo Rossi menawarkan perlunya kota dipahami sebagai Locus Solus. Locus adalah komponen dari artefak individual yang sekaligus menjadi tapak suksesi baik untuk peristiwa lama maupun mutakhir. Selain itu, kota juga harus dipandang sebagai teater peristiwa manusia. Ia tak sekadar representasi, tapi realitas. Sebab, kota menyerap kejadian dan rasa. Dan setiap kejadian baru mengandung di dalamnya memori masa lalu, dan potensi memori masa depan. Dengan demikian, locus selain sebagai tapak yang menampung berbagai peristiwa, ia juga akan membangun dirinya sebagai lapisan-lapisan peristiwa. Dalam pengertian ini, arsitektur perkotaan menjadi tempat dengan karakteristik yang sangat unik, atau Locus Solus. Keunikan ini dipertegas oleh Jacques Derrida: "...Sebuah kota yang tidak lagi dihuni bukanlah ditinggalkan, karena ia telah dihuni oleh roh yang berupa makna dan kebudayaan...." Dengan demikian, Locus Solus yang dihuni roh akan berkualitas sebagai artefak permanen. Sebagai artefak permanen, ia tidak bisa digusur dari ruangnya untuk digantikan artefak baru karena, menurut Sigmund Freud, "Bila kita ingin merepresentasikan rangkaian sejarah secara spasial, kita hanya bisa menjajarkan sejarah secara berdampingan di dalam ruang: sebuah ruang tidak mungkin memiliki dua isi." Itu sebabnya mengubah keputren keraton, menggusur masjid bersejarah, dan mengganggu kawasan sebuah pura mengundang protes masyarakat, protes publik. *) Penulis adalah arsitek, urban designer, dan perencana kota. Ketua Jurusan Arsiktektur Fakultas Teknik Unika Soegijapranata, Semarang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini