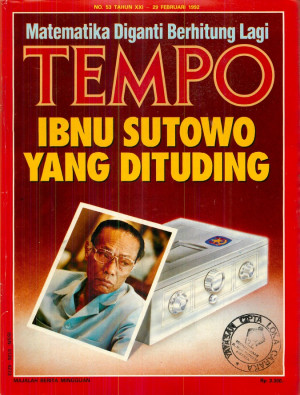PERTENGAHAN Februari lalu, di Fakultas Sastra UI diadakan seminar "Bahasa dan Sastra Melayu-Tionghoa". Setahu saya, ini seminar pertama yang membahas masalah bahasa dan sastra Melayu Cina. Yang hadir cukup banyak, terutama pakar dari dalam negeri seperti Prof. Harimurti Kridalaksana, Prof. Suripan Sadi Hutomo, Dr. Sapardi Djoko Damono, Drs. Jakob Sumardjo, Dra. Myra Sidharta, dan Dr. Dede Utomo. Saya juga diundang untuk menyajikan sebuah makalah. Sebetulnya, bagi generasi sebelum perang atau orang-orang yang dilahirkan tahun 1940-an, baik pri maupun nonpri, mereka sudah tidak asing dengan sastra Melayu Tionghoa yang ditulis dalam bahasa "Melayu Rendah" kemudian dikenal sebagai bahasa Melayu-Tionghoa. Tetapi sastra ini kemudian dilupakan begitu saja. Umumnya orang menganggap bahwa sastra peranakan Tionghoa ini ditulis dalam bahasa Melayu-Tionghoa, bukan bahasa Indonesia yang baku (maksudnya bahasa Balai Pustaka), karena itu rendah mutunya. Bahasa Melayu-Tionghoa yang juga dikenal sebagai bahasa "Melayu Rendah" dianggap bahasa kampungan, padahal bahasa itu juga dipakai oleh banyak pengarang pribumi dan wartawan pribumi, sekurang-kurangnya sebelum tahun 1930-an. Bahasa "Melayu Rendah" itu dipakai secara luas sehingga semua koran dan buku yang bukan diterbitkan oleh pemerintah dicetak dalam bahasa tersebut. Pramoedya Ananta Toer menyebutnya "Bahasa Kerja", lawan dari bahasa sekolah. Bukanlah secara kebetulan jikalau banyak penulis yang berhaluan nasionalis dan ideologi kiri sebelum dan sesudah berdirinya Bureau van der Volkslectuur (kemudian diubah menjadi Balai Pustaka) menulis dalam bahasa kerja itu. Misalnya Tirto Adhi Soerjo, Mas Marco, dan Somaoen, semuanya menerbitkan buah karya dalam bahasa tersebut. Sudah barang tentu karya-karya itu tidak disenangi oleh penguasa Belanda dan dianggap berbahaya untuk kestabilan masyarakat. Karena itu, penguasa Belanda menggunakan satu strategi untuk memencilkan tulisan-tulisan ini. Pemerintah kolonial Belanda berhasil mengasingkan bahasa "Melayu Rendah" Melayu-Tionghoa ini sehingga sejak tahun 1930-an, kebanyakan pengarang pribumi hanya menulis dalam bahasa Melayu-Indonesia baku, yaitu yang dipakai di sekolah-sekolah pemerintah. Bahasa itu adalah bahasa Balai Pustaka. Sejak itu, baik sastra "Melayu Rendah" maupun sastra peranakan Tionghoa menjadi sastra kelas kambing dan juga dianggap bukan bagian dari sastra Indonesia yang baik. Di luar Balai Pustaka, tidak ada sastra! Karena kebijaksanaan politik kolonial Belanda, sastra ini telah diabaikan sama sekali. Biarpun beberapa penulis pri seperti Takdir Alisjahbana dan Armijn Pane menaruh perhatian, tidak ada usaha untuk memperkenalkan sastra ini. Di kalangan peranakan sendiri juga ada yang menulis, misalnya Nio Joe Lan almarhum, tetapi juga tidak mendapat tanggapan yang hangat. Baru setelah Dr. Claudine Salmon, seorang sarjana Prancis, menerbitkan sebuah buku setebal 500 halaman dan mencantumkan buah karya "sastra" peranakan Tionghoa yang sebanyak 3.000 judul, dunia ilmiah mulai sadar bahwa sudah waktunya sastra yang dilupakan ini dikaji kembali. Salmonlah yang mengajukan pendapat bahwa sebetulnya, dari segi linguistik, bahasa Melayu-Tionghoa itu tidak ada. Karena bahasa itu dipakai oleh kebanyakan pri dan nonpri pada waktu zamannya. Hanya setelah pemberontakan PKI tahun 1926-1927, bahasa itu baru diberi julukan "Melayu-Tionghoa". Setelah Salmon, banyak sarjana seperti Dede Utomo dan Prof. Harimurti yang menelitinya secara lebih mendalam dan juga mengambil kesimpulan yang tidak berbeda. Jadi, rupanya telah disetujui bahwa apa yang dinamakan bahasa Melayu-Tionghoa itu sebetulnya adalah ragam bahasa "Melayu Rendah", bukan sebuah bahasa yang tersendiri yang di luar bahasa Indonesia. Jikalau bahasa Melayu-Tionghoa itu adalah ragam bahasa Indonesia, bagaimana tentang sastra Melayu-Tionghoa? Apakah ini juga satu bagian dari sastra Indonesia? Para peserta seminar ini umumnya mengakui bahwa sastra itu juga merupakan bagian dari sastra Indonesia. Cuma, apakah sastra itu juga dianggap tinggi mutunya, masih didebatkan. Ada sarjana yang menjunjung tinggi sastra itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa banyak hasil karya peranakan itu bukan main tingginya dan bisa dibandingkan dengan karya sastra Indonesia pri yang terbaik. Ada pula yang tidak setuju dan menganggap buah karya peranakan ini semata-mata roman picisan atau novel hiburan. Di samping persoalan itu, ada juga perdebatan tentang hubungan antara sastra peranakan Tionghoa dan sastra Indonesia modern. Tentang ini, ada pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa sastra peranakan berkembang lebih dulu dari sastra Balai Pustaka dan banyak buah karya pri yang mempunyai tema dan plot yang bermiripan dengan buah karya peranakan. Karena itu, sarjana-sarjana itu mengatakan bahwa sastra Indonesia dipengaruhi oleh sastra peranakan (juga sastra "Melayu Rendah" umumnya). Akan tetapi yang tidak setuju mengatakan bahwa sebetulnya kedua sastra itu sama-sama menimba bahan yang ada di bumi Indonesia, sehingga terjadi semacam perkembangan yang "paralel". Jadi, penelitian yang lebih seksama perlu diadakan. Satu hal lagi ialah sebutan "sastra Melayu Tionghoa" itu dan kapan kesusastraan itu lenyap dari bumi Indonesia. Para peserta seminar umumnya mengakui bahwa sastra Melayu-Tionghoa kurang begitu tepat karena istilah itu digunakan untuk menyebut sastra peranakan Tionghoa sebelum Perang Dunia II. Padahal, setelah Indonesia merdeka, sastra peranakan tetap hidup, terbukti dengan adanya koran dan majalah-majalah peranakan. Karena itu, lebih tepat lagi sastra Melayu-Tionghoa disebut sastra peranakan Tionghoa (atau disingkat menjadi sastra peranakan saja). Apakah sastra peranakan Tionghoa sekarang masih ada? Apakah buah karya Marga T. dan Mira W. itu masih merupakan sastra peranakan? Rupanya, banyak peserta yang lebih condong menganggap buah tangan para peranakan itu sebagai buah karya sastra Indonesia. Karena, selain dari latar belakang pengarang ini, hasil karyanya tidak banyak berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengarang pri. Sebetulnya, bahasa Melayu-Tionghoa itu adalah salah satu ragam bahasa Indonesia, dan sastra peranakan Tionghoa dalam kancah sejarah itu berangsur-angsur telah menjadi sastra Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini