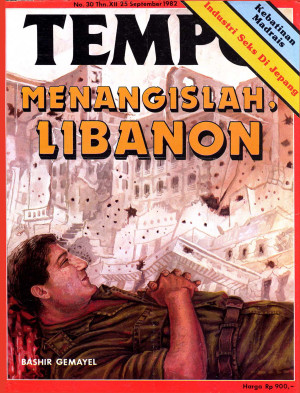DALAM berbicara soal kebudayaan, orang cenderung ingat kepada
masalah-masalah besar.
Masalah-masalah itulah yang memberi kesan seakan-akan daerah
pemikiran kebudayaan selalu harus melayang-layang jauh di atas
kesibukan manusia, yang lebih langsung hubungannya dengan
kebutuhan jasmani yang paling elementer, seperti makan-minum,
perbuatan seks dan pergi ke WC. Sebenarnya perbuatan itu
termasuk apa yang disebut kebudayaan sekalipun sudah merupakan
kesibukan yang rutin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
melaksanakannya tidaklah kompleks.
Bagaimana kita menyiapkan makan dan minum dan bagaimana cara
kita makan dan minum merupakan suatu seni, dan memasak adalah
suatu olah budaya tersendiri.
Juga seks merupakan perbuatan budaya, kalau hubungan jasmani
antara jenis kelamin yang berbeda tidak kita biarkan menjadi
pelampiasan nafsu hewan yang tidak bertanggung jawab. Faktor
tanggung jawab ini penting dalam laku budaya, sebab itulah yang
membedakannya dari dorongan dan gerak naluri yang alamiah.
Karangan-karangan seperti Kamasutra, Ars Amatoria dan Asmorogomo
dengan petunjuk-petunjuk teknik bersanggama adalah usaha
pengangkatan perbuatan alamiah ke tingkat kebudayaan.
Sekarang soal pergi ke WC. Kita bisa terjerembab dalam pemikiran
soal WC sebagai gejala budaya, kalau kita misalnya sedang
bepergian dari Jakarta ke Yogyakarta naik Bima, kereta malam
yang menurut sahibulhikayat paling top pelaanannya kepada
penumpang.
Ah, jangan lagi kalau kita pakai kereta senja utama atau lebih
payah lagi kalau naik senja biasa. Perut kita bisa tersiksa di
perjalanan, karena tak sampai hati pergi ke ruang WC nya yang
kotor dan bau, bahkan kerapkali tidak tersedia air atau
ciduknya.
Kita di kereta api itu langsung berhadapan dengan suatu gejala
budaya yang tidak pernah disinggung dalam seminar atau
konperensi. Kecuali itu juga diabaikan sebagai masalah budaya
oleh menteri-menteri dan pejabat-pejabat lain yang tidak pernah
secara incognito jalan jalan dengan kereta api.
Bahkan di hotel-hotel kelas satu di Jakarta, masih ada yang
kamar WC-nya tidak terpelihara, sehingga tidak sesuai dengan
harum namanya. Jangan lagi kita mencoba masuk ke kamar kecil di
gedung-gedung jawatan pemerintah. Segala niat yang baik bisa
urung karenanya.
Ketika cakal-bakal kita, atau moyang penanam kepala kerbau
pertama kita dulu mendirikan tempat bermukim dekat sungai atau
laut, saya kira bukan pertimbangan ekonomi saja yang bermain
dalam benaknya. Memang sungai lebih mudah mengaliri tanahnya
untuk bercocok tanam dan laut menopang pencarian nafkahnya
dengan menangkap ikan. Tetapi ada konsiderasi yang tidak pernah
tercatat di dalam buku sejarah yang serba resmi: tempat bertahan
dekat aliran air itu dicari juga untuk memenuhi kebutuhan badani
yang hakiki, yakni membuang kotoran manusia yang merupakan
muatan surplus .
Aliran air di sini tidak saja berfun,gsi sebagai tempat "plung
lap" atau mencemplungkan lalu seketika itu juga lengkapnya
barang kita, tetapi juga untuk membersihkan bagian badan yang
mencemplungkan itu. Jadi air sungai atau laut itu merupakan
saluran alamiah yang paling efisien untuk keperluan itu, dengan
tidak usah mengotak-atik dan mengangkatnya ke tingkat budaya.
Tetapi celakanya kalau nenek-moyang itu sesudah berhari-hari
berjalan tidak menemukan air mengalir, sedang yang dilihat hanya
pasir berbukit-bukit saja atau pantai berkarang yang terjal,
seperti misalnya di Gunung Kidul. Maka untuk keperluan hakiki
itu ia menggali lubang di tanah atau begitu saja dilempar
ballastnya di pasir, dan upacara pembersihannya diserahkan
begitu saja kepada daun dan angin. Menggali lubang itu sudah
merupakan olah budaya, hanya tingkatnya tetap berada pada tahap
primitip.
Budaya lubang atau 'jumbleng" itu adalah yang paling tinggi
kita jumpai di kebanyakan desa-desa. Bahkan setelah penduduk
mampu mendirikan rumah dari batu dan semen yang anggun
"magrong-magrong" di kelurahan, masih juga jumblengnya tidak
dikembangkan dari tingkat sahaja itu dan umumnya terhindar dari
pemeliharaan lingkungan hidupnya. Dalam bahasa Jawa, lingkungan
WC itu disebut "pakiwan" tempat sebelah kiri, yang secara
implisit berarti tempat yang patut dihindari.
Itu yang terjadi di Jawa. Di daerah-daerah lain, mungkin yang
berperanan sebagai jumbleng adalah babi atau anjing yang
berkeliaran di kampung.
Ketiadaan atau lumpuhnya perkembangan kebudayaan WC demikian
dibawa orang ke kota-kota waktu mengalami krisis urbanisasi.
Akibatnya, wanita-wanita dengan pipi-pipi segar dari hawa sejuk
di gunung dengan membawa muatan jualan kayunya di punggung
berdiri seenaknya di pinggir jalan Kraulggan dan pipis di sana.
Untung, atau sayang, pemandangan artistik itu mulai hilang dari
lanskap kota Yogyakarta Hadiningrat. Tetapi yang masih hidup
sehidup-hidupnya adalah kurangnya kepekaan kepada kebersihan
dan pemeliharaan WC di kota-kota. Sebab yang disuruh mengawasi
dan membereskan kamar kecil di hotel-hotel, kantor kantor dan
kereta-kereta api adalah mereka yang datang dari kelangkaan
kebudayaan WC.
Kebudayaan kota modern menuntut disiplin pengaturan hidup, dan
untuk melaksanakan disiplin itu sudah ditentukan saluran dan
tempatnya yang khusus, juga untuk melakukan hajat besar maupun
kecil. Di negara yang sudah lanjut perkembangan budaya kotanya,
seperti di Amerika Serikat, setiap pompa bensin dan kedai makan
di pingir jalan menyediakan kamar kecil buat umum. Tempat itu
kebanyakan be gitu apik dan bersih, sehingga kakus itu terbiasa
disebut secara manis 'Sestroom' kamar tempat kita istirahat
dengan senang, atau "powderroom' tempat kita berlena berpupr
dengan bedak yang harum.
Sebaliknya di Jakarta, di mana kita cepat-cepat harus mencari
lindungan batang pohon atau terbirit-birit berlari ke belakang
dinding parit untuk melepaskan hajat kita - karena WC di pompa
bensin tidak ada atau WC di hotel terdekat tak sedap aromanya -
maka WC tetap merupakan masalah, bukan saja masalah lingkungan
hidup, melainkan juga masalah budaya yang genting.
Mudah-mudahan di dalam kongres kebudayaan yang disarankan
Akademi Jakarta untuk diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta
tahun depan tidak lupa mencantumkan acara yang masih gawat ini:
soal WC.
Jakarta, 14 September 1982.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini