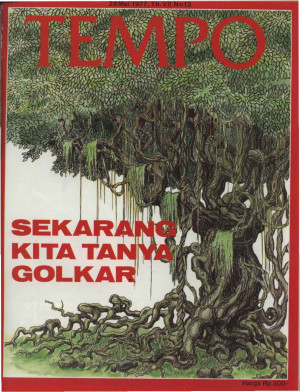SURABAYA, Nopember 1945, penuh kepahlawanan. Dan juga kekerasan.
Kita dapat membayangkan apa yang terjadi lewat novel kecil
Idrus, Surabaya, yang tersohor itu. Atau kita bisa memetik
sedikit dari kenangan Ruslan Abdulgani yang diterbitkan
Universitas Monash, 1973, dengan judul panjang: Nationalism,
Revolution and Guided Democracy in Indonesia. "Di Surabaya,
dalam beberapa minggu, berturut-turut bergantian semua tahap
dari Revolusi Perancis", tulis Ruslan, "sejak dari
pengambil-alihan pertama sampai dengan terornya".
Mahkamah-mahkamah rakyat didirikan. Orang Indo, orang Belanda,
Jepang, Gurkha dan bahkan orang Indonesia sendiri -- yang
dituduh jadi "mata-mata" -- dituntut. Beberapa di antaranya
diserahkan kepada kerumunan orang banyak untuk dipukuli dan
ditusuk bambu runcing sampai mati . . .
Memang kejam. Tapi kemudian orang dapat menghibur diri,
sebagaimana halnya Ruslan Abdulgani. Ia mengutip kalimat dari
buku Nehru, Glimpses of World History. "Kekejaman satu
gerombolan orang", tulis Nehru, "bukan apa-apa jika dibanding
dengan kekejaman suatu Pemerintah yang terorganisir ketika mulai
bertingkahlaku seperti satu gerombolan".
Sejarah memang menGatat pemerintah-pemerintah yang berlaku
seperti suatu mob dan melakukan kekerasan. Tapi adakah sejarah
dapat menghibur bagi mereka yang sedang terkena kekerasan itu?
Mungkin tidak.
Tapi setidak-tidaknya ia bisa berharga lain. Ada satu buku
menarik yang terbit tahun lalu tentang kehidupan di Uni Soviet.
Buku setebal 600 halaman lebih ini ditulis oleh Hendrick Smith,
koresponden Amerika pemenang hadiah Pulitzer yang pernah tiga
tahun tinggal di Moskow. Judulnya: The ussians. Satu babnya
mengisahkan bagaimana orang Rus kini mulai melupakan kekejaman
yang berlangsung di masa Stalin -- belum lagi 25 tahun pemimpin
itu wafat. Orang Rusia, kata Smith "menderita amnesia sejarah".
Ia mengutip cerita penyair Yevtushenko, yang terkenal sering
mengutuk masa kesewenang-wenangan itu dalam puisinya. Suatu hari
di musim panas di Siberia, Yevtushenko berkemah bersama 20
mahasiswa. Dalam suatu kesempatan seorang yang hadir usul untuk
minum bagi Stalin. Yevtushenko bertanya kenapa Stalin. "Karena
waktu itu semua rakyat yakin pada Stalin dan karena keyakinan
itu mereka menang", jawab si mahasiswa.
"Tiba-tiba saya mengerti", kata Yevtushenko, "bahwa generasi
muda kini benar-benar tak punya sumber untuk mengetahui
kenyataan tragis tentang masa itu, sebab mereka tak dapat
membacanya dalam buku atau buku pelajaran. Bahkan ketika artikel
terbit di koran-koran tentang para pahlawan Revolusi kami yang
mati dalam masa penindasan Stalin, koran-koran itu toh diam
tentang sebab kematian mereka... Kebenaran telah digantikan oleh
diam, dan kediam-dirian sebenarnya adalah sebuah justa".
Kediam-dirian, setidaknya, meniadakan keseimbangan. Kebenaran
dengan demikian diborong oleh pihak yang tidak diam: propaganda
pemerintah. Sejarah jadi timpang. Suatu bangsa dengan itu tidak
bisa berdialog dengan masa silamnya secara jujur. Maka ia pun
tak tahu bagaimana posisinya di masa kini. Benarkah yang
dialaminya kini suatu kemerGsotan? Benarkah yang dialaminya kini
suatu kemajuan? Pernah adakah pada dirinya suatu bekal untuk
berbuat mulia? Adakah kebobrokan yang dialaminya kini suatu
bagian dari watak yang permanen?
Sejarah, yang sudah dan sedang terjadi, memang kadang menakutkan
untuk didengarkan. Tapi sebuah bangsa perlu harga diri dari
prestasi masa lampaunya -- sebagaimana juga ia perlu
nembersihkan diri dengan pengakuan atas dosa masa silamnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini