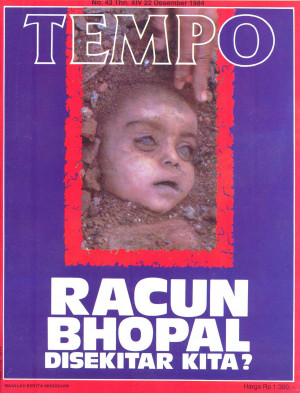DENGAN saksama saya mengikuti berita Muktamar NU ke-27 dari koran-koran. Juga dengan tekun saya merekam tanggapan umat Islam. Saya membaca yang tersurat, menafsirkan yang tersirat. Saya mendengar komentar yang terucap dan nada dan nuansa yang dapat saya tangkap. Jejak langkah H. Abdurrahman Wahid - saya memanggilnya Gus Dur - sejak persiapan sampai pelaksanaan muktamar itu memang mendebarkan banyak kawannya. Bagi mereka yang mengenal Gus Dur lebih dekat, ofensifnya tidak mengejutkan. Tidak setapak pun langkahnya menyimpang dari alur dasar pendiriannya, ideologi kulturalnya, ke-adreng-an pada perubahan strukturalnya: pendekatannya yang sarat kadar kemanusiaan. Bagi Gus Dur, semua manusia adalah kawan. Karena itu, temannya banyak sekali. Bagi Gus Dur, tiada uluran tangan yang harus ditampik. Kiai muda ini punya perhitungan yang jauh ke depan. Pertimbangan utama semua langkahnya adalah kepentmgan khalayak umat yang luas - utamanya justru yang naif, yang kurang paham seluk-beluk khilafiyah, bahkan yang masih membutuhkan tuntunan akidah. Mereka inilah, jemaah yang ikhlas beribadat dan mengamalkan ajaran agama, yang membutuhkan tuntunan ulama dan cerdik pandai secara bertanggung jawab. Bukan hanya terhadap berbagai mazhab dalam Islam ia sangat toleran. Terhadap agama-agama samawi, bahkan kebatinan, ia berusaha membaca untuk mengerti. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dari perjalanannya ke segala pesantren, ke pengajian dusun-dusun, majelis taklim kota-kota, atau diskusi dari kampus ke kampus, Gus Dur merekam desah santri dan Muslim di balik takbir dan wirid mereka. Kesan saya, ia terkesima oleh fenomena adanya perasaan ketersisihan, keterasingan, kesendirian mukmin, dan pemuka Islam di kancah pergaulan nasional. Persoalan umat Islam Indonesia bertumpu pada satu pasal saja: kesenjangan komunikasi - antarumat Islam, antara umat Islam dan umat beragama lain, antara umat Islam penguasa dari berbagai tingkatan. Bahkan antara umat Islam dan tantangan zamannya. Karena antara intelektual dan pemuka Islam sendiri terjadi pula kesenjangan komunikasi. Slogan dan jargon lama telah melilit, membungkus pemahamam hakikat ajaran yang mestinya menjadi pangkal anjak pendekatan dalam beramar maruf nahi munkar. Dan Gus Dur tahu, melepaskan lilitan ini tampaknya pekerjaan yang sangat sulit, nyaris mustahil. Namun, saya berkesan, ia bertekad melakukannya. Karena itu, langkah pertama yang ia tempuh ialah membangun kembali jaringan komunikasi itu, yang ibarat menenun ulang jaringan yang telah kusut dan tiada menentu ujung pangkalnya. Figur kiai-kiai yang ikhlas dan utuh integritasnya ditelusuri, didudukkan ke tempat semestinya. Institusi pesantren dengan segala kebanggaan, kekhasan, tetapi juga keterbelakangannya, menjadi tumpuan perhatiannya. Bersama kiai dan kawan-kawannya, pesantren hendak diangkat kembali kehadirannya di masyarakat luas, secara tegar dan terhormat. Tetapi Gus Dur juga meniti langkah yang berani dengan membangun embatan komumkasl dengan seniman, budayawan, bahkan pendeta, media massa, dan penguasa. Kesediaannya berteman dengan mereka diartikan sebagai keterbukaan umat Islam pada dunia luar dan terobosan isolasi. Kekinian visi kemasyarakatannya diasah secara berkala dalam forum internasional yang sangat terhormat. Ia bicara dengan pastor teolog pembebasan di Amerika Latin maupun kalangan Islam pembaharu di Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Filipina. Ia ketemu kaum orientalis di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Ia duduk di dewan penyantun hadiah Aga Khan yang prestisius. Tetapi juga mereka yang adreng hak asasi. Lembaga swadaya masyarakat pun dilayaminya. Saya memperhatikan, langkah-langkahnya dalam organisasi NU yang dengan tegap ia terjuni itu pun mencerminkan alur dasar keadreng-annya untuk menegakkan kelembagaan organisasi yang sudah lama terbengkalai itu. Pernyataan-pernyataannya tampak sekali mencerminkaan sikapnya yang akomodatif. Malah kesan saya tindakannya selalu berujung tombak rekonsiliasi, dan mereka yasa rujuk dengan menghidupkan semangat ukhuwah Islamiyah yang tulen. Selaku ketua panitia muktamar, Gus Dur memukul beduk silaturahmi ini bertalu-talu. Presiden, menteri, panglima, gubernur, bupati, camat, lurah, pendeta, intelektual, media massa, bahkan tukang obat, kaki lima, penjual soto, gegap-gempita menyambut. Reaksi teman-temannya? Amat beragam. Dari yang paling getir, "oportunis!", sampai yang paling simpatik, "kita doakan mudahmudahan ia tetap Gus Dur, dan tidak seperti yang lain-lain." Waktu seorang sahabat menumpahkan kejengkelannya kepada saya lewat telepon, saya gemetar. Untung, belum lama saya menyimak Cak Nurcholish Madjid bercerita di masjid. Cak Nur hari itu mengisahkan keberangan Sayidina Umar waktu Nabi Muhammad mengambil prakarsa mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy, yang mengandung bagian yang tampaknya amat tidak menguntungkan perjuangan kaum Muslimin. Tetapi dengan sabar Rasulullah berteguh dengan pendiriannya: tindakannya itu atas petunjuk wahyu. Gus Dur bukan nabi. Terkadang ia pun menggigil bila merasa telanjur berucap atau berbuat yang ia rasa tidak layak. Tetapi dalam situasi semacam ini, santri otomatis beristigfar dan mencari rujukan ayat suci Alquran yang analog dengan suri teladan Nabi Muhammad itu. Karena itu, saya pun ingat perjanjian Hudaibiyah, dan ayat yang turun sesudahnya: Kami telah memberikan kepadamu suatu kemenangan yang nyata supaya Tuhan mengampuni kesalahanmu yang sudah lalu dan yang akan datang, dan Tuhan akan mencukupkan karunia-Nya kepadamu serta membimbing engkau ke jalanyang lurus (Quran 48: 1-2).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini