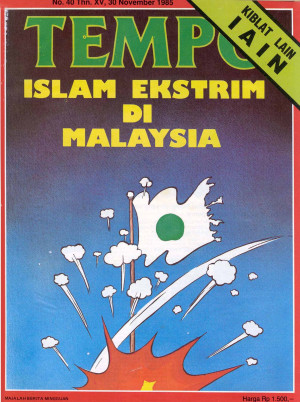BUKAN kematian benar menusuk kalbu, kata Chairil. Tapi entah kenapa sering benar saya ketemu orang macam itu: menangisi sesuatu yang baginya telah mati. Misalnya lelaki setengah baya ini: di stasiun bawah tanah yang pengap, larut malam. Ia minta sebatang rokok, saya lintingkan satu ler tembakau Javaanse Jongens, dan ia hisap ke kedalaman lorong sukmanya. Kemudian jelas ia tak memerlukan rokok ia sekadar ingin kawan Lewat satu dua menit, nongol kebiasaan Melayu yang buruk, menanyakan apakah ia sudah berkeluarga, beranak istri. "Doch! Kawin?" Pakde Wolfgang langsung meledak. "Jangan melucu. Saya tak mau menjadi saluran lahir anak-anak yang kelak meninggalkan saya, atau menyerahkan saya ke rumah jompo. Saya juga tidak memilih anjing buat mengganti tumpuan cinta, menciumi, dan menjilatinya. O Nak, dunia tidak bergerak ke hari depan. Menjadi tua ialah memasuki masa silam. Ini alamiah, tapi yang dialami generasiku ini keterlaluan. Meskipun demikian, tuhan saya bukan anjing, sungguhpun bagi banyak orang anJing memang kekasih Ideal. Tuan-tuan dan Puanpuan, Anda tahu, kini tak bisa diperoleh budak secara langsung . . . ." Apakah saya percaya? Saya hanya bertanya: "Apa yang terjadi di rumah Anda?" Pernyataan itu autentik dari hidupnya, dan makin autentik lagi ketika ia lantas menangis. Sungguh-sungguh menangis, ngguguk-ngguguk menangis, dan Anda tidak memerlukan argumen apa pun untuk menangis. Situasi itu sungguh tak enak. Sepur nge-ground terakhir tiba. Saya egoistis, saya mesti pergi. Bagai orang tua, saya tepuk-tepuk bahunya, saya lontarkan kata-kata klise seperti seorang kiai hendak melepas muridnya pergi mengarungi samudra hidup. Terus lari masuk ke sepur. Dari kaca, tampak ia bangun dan tersenyum memandang saya. Saya acungkan tinju ke udara, dan ia menyambut, seolah kami sama-sama anggota gerakan petani Ratu Adil. Ia buka jaket, nongol dua botol minuman keras dari saku dalamnya. Sambil kasih kode cheers. Ia meneguk. "Perjuangan diteruskan." Sepur cabut menembus bumi. Karena sok jantan, saya mengejek lelaki itu. "Terlalu tua untuk masih bisa menangis," kata saya kepada tetangga di sepur. "Anda salah," bantahnya. "Apa hubungan menangis dengan tua atau muda?" Saya ingat: di sebuah pesantren, di ruang tamu, seorang ustad menemui saya dengan wajah para sufi penangis: "Pak Kiai dulu juga suka mengemukakan seperti yang ente kemukakan. Tapi dunia ini demikian dahsyat. Mau apa kita? Maka, Pak Kiai setiap malam hanya sembahyang, menangis tersedu-sedu kepada Tuhan." Dan kita, kita menghimpun segala yang bisa merekahkan tawa, meski mungkin dengan ongkos air mata orang lain. Semua orang berjuang, baik berjuang untuk menghidupkan perjuangan itu atau berjuang menghalangi perjuangan orang. Akal-akalan ekonomi, negoslasl politik, perdagangan senjata, pertempuran gali dan star-wars, menghasilkan tawa dan air mata bersama-sama. Hari ini sangat fantastis jumlah biaya proyek peredaan air mata Dunia Ketiga. Bumi sudah seperti akan kehabisan modal untuk mengobati sakit yang dibikinnya sendiri. Toh orang bisa tertawa dengan alasan amat sepele, tanpa harus menunggu suksesnya program jangka panjang atau rampungnya diskusi perubahan struktural. Ketika, di pojok pasar, si India Suriname itu menyapa dan ngomong bahasa Jawa dengan riuhnya, terasa kemewahan Eropa Barat di satu sisinya seperti memasang iklan: halo, siapa mau menyapa saya? Siapa punya waktu untuk tersenyum kepada saya? Siapa masih punya ruang dalam dirinya untuk melihat bahwa saya lebih dari segumpal benda? Di wilayah-wilayah amat miskin di tanah air, belum pernah saya bertemu dengan frustrasi seperti yang sering memergoki saya di sini. Kalau soal "metode berbahagia", Gareng Petruk amat ahli, dan bisa tanpa biaya. Maka, si Pincang itu perlu diajak ke Indonesia, belajar menyulap apa saja menjadi tawa. Ia berjalan di atas rel trem, orang-orang memperhatikannya. Tampak ia bermain-main dengan rel, melangkah sedikit akrobatik, bermaksud menutup cacatnya, ingin tampak sengaja pincang. Makin ke tempat sepi, geremangnya menjadi pidato keras: "Kalau X mampu melampaui satu detik lebih cepat dari Y, lantas? Kalau Larry Holmes sukses menyamai rekor Rocky Marciano, lantas? Kalau Belanda berhasil jadi juara dunia sepak bola, lantas? Kalau Amerika bisa menjadi bangsa paling besar, lantas? Kalau orang menjadi paling jantan, paling gagah, paling sukses, paling kaya, paling menang, paling hebat, paling besar, lantas? Mau apa?" Ia menangis. Ingin saya memperkenalkannya kcpada scorang kawan yang kaki sebelahnya tak bisa bengkok. Setiap senam pagi ia menyapa kakinya, "Gut moning Mister Anarkis!" Kawan-kawan selalu bertanya, "Si Anu belum juga sembuh kakinya, ya?" Lalu ia bermain drama. Dan penonton tertawa kagum. Tidak menangis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini