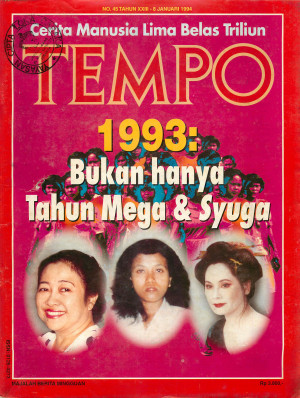KATA konglomerat telanjur mempunyai konotasi jelek di Indonesia, sedangkan istilah itu sendiri mempunyai pengertian yang netral. Konglomerat adalah kumpulan dari banyak perusahaan yang banyak pula macam ragamnya, yang dimiliki oleh satu keluarga atau satu perkongsian usaha. Maka, patut dipertanyakan apa yang salah pada konglomerat sampai ia berkonotasi jelek. Kalau ditinjau dari sudut ideologi maupun kebiasaan yang ada di negara kita, juga tidak ada yang salah. Sebelum dijajah, selama penjajahan, dan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak pernah ada yang melarang orang partikelir memiliki kekayaan yang dijadikan modal usaha. Berusaha tentunya dengan maksud memperoleh laba. Juga, tidak ada yang melarang ditumpuknya laba ini sampai menjadi kapital yang besar, dan dipakainya kapital ini untuk mendirikan perusahaan yang lain lagi. Demikianlah seterusnya, seseorang bisa mempunyai banyak perusahaan yang tidak perlu memproduksi barang dan jasa yang sama. Dengan begitu, konglomerat terbentuk dan pembentukannya sah-sah saja. Tapi, kalau konglomerat dibentuk dengan cara ini, prosesnya akan lambat. Pertama-tama, perusahaan harus untung terlebih dahulu. Labanya lalu dipakai untuk memperluas perusahaan yang sudah ada sampai skalanya mencapai optimal. Setelah itu, tumpukan laba yang menganggur dipakai untuk mendirikan perusahaan yang baru lagi. Kalaupun modal tidak cukup, dan kekurangannya dibiayai dengan modal utangan dari bank, perbandingan antara uangnya sendiri dan kredit dari bank dibuat yang aman, sehingga modal sendiri cukup berfungsi sebagai bumper kalau-kalau perusahaan mengalami kelesuan usaha. Dari proses seperti itu, bisa kita bayangkan berapa banyak perusahaan yang bisa didirikan oleh satu generasi. Pasti terbatas, sehingga terbatas pula jumlah perusahaan yang harus diawasi oleh satu orang atau satu keluarga. Maka, rentang kendali lalu tidak terlampaui, bank aman, karena setiap perusahaan mempunyai perbandingan antara modal sendiri (equity) dan modal pinjaman (debt) yang pas. Kalau terjadi apa-apa, yang jadi bumper adalah modalnya sendiri. Tapi gambaran konglomerat kita tidak seperti itu. Dalam waktu sekitar sepuluh tahun, puluhan sampai ratusan perusahaan didirikan oleh satu keluarga atau satu perkongsian. Pada periode tertentu, setiap hari kita membaca didirikannya perusahaan baru yang sangat besar skalanya, dengan modal tertanam ratusan miliar sampai triliunan rupiah. Dari mana modal didapat? Ternyata berbagai trik dipraktekkan untuk mengelabui bank dan investor publik, sehingga bisa diperoleh dana dalam jumlah sangat besar. Trik-triknya mengandung risiko besar buat bank dan para investor di bursa efek. Gambaran yang rinci tentang ini bahkan pernah saya tulis dalam artikel berjudul "Saya Bermimpi Jadi Konglomerat." Yang pasti hakikatnya selalu sama, utang sebanyak-banyaknya. Kalau bunga atau cicilan utang pokoknya tak dapat dibayar, bank diancam bahwa perusahaan akan bangkrut, jadi kreditnya harus ditambah. Kalau kredit tidak ditambah, dijadwalkan kembali skema pembayarannya. Bank juga dipersilakan menyita semua perusahaannya. Setelah dihitung, ternyata seluruh asetnya lebih kecil daripada seluruh utangnya. Benarkah semua lakon ini? Apa indikasinya? Indikasinya adalah besarnya kredit macet. Gubernur Bank Indonesia mengaku kepada DPR, dari kredit sekitar Rp 131 triliun, yang macet sudah 3,3%. Tapi perkiraan realistik mengatakan bahwa yang macet bisa sekitar 8%. Ya, katakanlah 5%. Ini berarti, modal milik sendiri dari semua bank di Indonesia sudah lenyap sama sekali karena CAR dari bank-bank kita masih 5%, yang dengan susah payah baru akan dinaikkan menjadi 8%. Lalu, ke mana uang mereka? Habis disedot perusahaan-perusahaan yang menyatakan diri sudah tidak dapat membayar utangnya kembali. Tapi mengapa bank-bank maupun perusahaan-perusahaan besar masih saja tetap berputar? Jawabnya adalah karena perusahaan itu tidak lagi membayar bunga dan cicilan utang pokok. Bank- bank masih berputar karena masih likuid dari likuiditas yang 100% uang milik masyarakat yang dipercayakan penyimpanannya pada bank. Sementara itu, bank yang tidak tahan lagi, karena bekingnya kurang, sudah ambruk seperti Mantrust, Bentoel, dan Bank Summa beserta Summa Group-nya. Bagaimana keluar dari kemelut ini? Kalau mau cepat tuntas, harus ada pemaksaan. Maka, pemikiran Menteri Keuangan untuk mengadakan pengadilan khusus bagi kredit macet adalah gagasan yang baik. Jadi, harus ada pemaksaan melalui pengadilan. Kalau masih mempunyai uang yang disembunyikan, mereka akan membayar. Kalau memang sudah tidak bisa membayar lagi, pemiliknya dinyatakan bangkrut, bank menelan kerugiannya, perusahaan disita. Setelah direstrukturisasi, manajemen diserahkan kepada para manajer profesional atas nama bank. Kemudian, setelah sehat, saham-sahamnya dimasyarakatkan melalui bursa efek. Dengan demikian, keroposnya konglomerat dan kredit macet ditarik hikmahnya dengan cara memecah-mecah perusahaan sampai menjadi perusahaan-perusahaan individual, yang terfokus perhatiannya pada spesialisasi produk dan jasa tertentu saja. Manajemen diserahkan kepada manajer profesional yang bukan pemilik, atau diberi kepemilikan minoritas sebagai insentif. Bank melepaskan kepemilikannya yang sementara kepada masyarakat investor, melalui bursa efek. Sampai di situ, masih ada masalah keadilan. Apakah dapat diterima bahwa ada penjahat-penjahat ekonomi yang menjadi kaya setelah mengacak-acak perbankan dan uang milik banyak orang? Tentang ini, jawabannya ada pada pengadilan khusus tadi. Kalau terbukti kriminal, mereka harus dihukum penjara seperti layaknya penjahat ekonomi di negara mana pun yang berasaskan negara hukum. Ini semua kalau ditanya bagaimana nalarnya. Prakteknya tidak akan demikian selama orang yang berkuasa masih doyan duit. Maka, rasanya, penyelesaian kredit macet yang merupakan sisi lain dari kekeroposan konglomerat kita akan merupakan proses yang sangat panjang, mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini