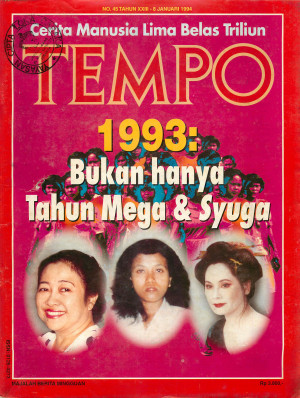ADA yang optimistis, tapi ada pula yang pesimistis memandang prospek demokratisasi di Indonesia. A. Rahman Tolleng, anggota kelompok kerja Forum Demokrasi, mungkin termasuk yang sedikit meragukan bakal datangnya demokrasi bila sejumlah faktor demokratisasi ternyata tak jalan. Rahman Tolleng pada awal Orde Baru duduk dalam kepengurusan DPP Golkar. Ia juga menjadi anggota DPR dan pemimpin redaksi harian Suara Karya. Tapi, kemudian ia menjadi korban Peristiwa Malari 1974. Tokoh yang dekat dengan kalangan mahasiswa ini ditahan selama setahun lebih tapi kemudian dilepas karena tak ada bukti, dan dicopot dari kepengurusan Golkar. Kini ia banyak terlibat diskusi-diskusi politik, di samping kesibukannya di perusahaan penerbitan PT Pustaka Utama Grafiti. Apa pendapatnya mengenai demokratisasi, hak asasi manusia tahun 1994 ini, atau suksesi? Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan TEMPO Ardian T. Gesuri: Bagaimana Anda melihat tahapan demokrasi di Indonesia? Kehadiran lembaga-lembaga seperti partai politik, parlemen, pemilu, di sebuah negara belum merupakan bukti bahwa negara itu demokratis. Di negara komunis dan fasis pun lembaga-lembaga semacam itu ditemukan. Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengukur ada tidaknya demokrasi adalah ada tidaknya hak-hak dan kebebasan politik di negara itu. Sekadar memperlihatkan sebuah contoh, salah satu unsur penting dari kebebasan politik atau political liberties ialah kebebasan membentuk atau menjadi anggota suatu organisasi politik. Di sini undang-undang telah membatasi kebebasan berserikat. Hanya tiga organisasi politik: Golkar, PPP, dan PDI. Bukankah DPR, Golkar, dan partai itu sudah menjalankan fungsinya? Memang, kalau kita terpaku pada lembaga-lembaga formal, kita bisa terkecoh. Padahal kita semua tahu bahwa sistem politik Orde Baru mempunyai dua wajah. Pertama, "wajah simbolis", yaitu lembaga-lembaga formal itu beserta aktivitasnya. Yang kedua, "wajah yang riil" dengan dua pilar utama, yaitu Presiden dan ABRI. Dari sinilah sebenarnya kebijakan dan keputusan penting itu mengalir untuk dijalankan oleh lembaga- lembaga formal. Ambillah APBN, kecuali mengesahkan, apakah DPR pernah melakukan perubahan subtansial? Di bidang kontrol, sidang- sidang yang berlangsung di lembaga ini pada umumnya tidak konklusif. Soal penghapusan SDSB? Secara resmi, keputusan Menteri Sosial memang menyebutkan pertimbangan masukan DPR. Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa keputusan sudah diambil jauh hari sebelumnya sebagai hasil lobi tingkat tinggi. Dalam hal penampilan parpol, fakta telanjang telah cukup berbicara melalui dua Kongres PDI. Baik tragedi Soerjadi di Medan maupun rintangan terhadap Megawati di kongres Surabaya merupakan bukti betapa hak untuk dipilih memegang jabatan dalam orpol memerlukan restu dari luar orpol itu. Bagaimana prospek demokrasi terjadi bila campur tangan Pemerintah semakin besar di parpol maupun Golkar? Kalau faktor-faktor lain tidak berubah, terus terang saya agak pesimistis. Pemerintah selalu mengimbau agar mereka yang ingin berpolitik memasuki salah satu orpol itu. Tetapi, jika orang bersungguh-sungguh memenuhi imbauan itu untuk menyalurkan aspirasinya apalagi untuk menjadi pemain yang berpribadi ternyata ia masih harus merunduk-runduk untuk tak ditebas oleh "pedang Democles". Syukurlah bahwa kini telah muncul pelbagai faktor baru. Kita melihat adanya semacam kejenuhan kalau tidak mau menyebutnya kebosanan atas penunjukan dan penjatahan dalam berbagai organisasi dari atas. Pada awalnya, sistem itu memang dapat diterima. Tapi, tatkala sistem ini harus melayani banyak orang yang merasa sama-sama berjasa, sama-sama pintar, dan sebagainya, sistem penunjukan atau penjatahan akan terasa tidak adil. Gejala inilah yang muncul dalam KNPI, dan mungkin juga dalam Kadin untuk beralih ke sistem "pilihan" yang terasa lebih adil. Di Kongres PDI, bukankah juga timbul desakan sistem pilihan dari bawah? Kongres PDI memperkuat sinyalemen saya tadi. Dalam hal ini saya angkat topi kepada peserta kongres, khususnya kepada Megawati, yang sekurang-kurangnya selama kongres berlangsung tetap teguh dan konsisten dalam menghadapi teror dan intervensi birokratis yang hendak memaksakan semacam "sistem penunjukan atau penjatahan" terselubung. Kekuatan politik riil adalah Presiden dan ABRI. Semakin banyaknya sipil yang naik, apakah itu bisa menjamin kehidupan politik lebih demokratis? Saya kira harus dibedakan antara "sipilisasi" dan "demokratisasi". Pokok soalnya apakah seseorang berhasil memegang jabatan politik itu lewat proses dan cara-cara "sipil" yang demokratis? Jika tidak, terlepas apakah sipil atau militer, potensi ke arah keotoriteran akan sama saja. Apakah kelas menengah bisa diandalkan untuk menunjang demokratisasi? Kita tak bisa membuat analogi begitu saja dengan Eropa Barat karena kondisinya berbeda. Di sana, pada masa Revolusi Industri, ada suasana kebebasan, khususnya kebebasan berserikat. Sementara di sini kita berbicara tentang kelas menengah di dalam kondisi yang sarat dengan pembatasan- pembatasan. Kelas menengah yang muncul, sebagian besar sangat dependen pada kekuasaan. Kelas menengah sebenarnya tak otomatis bisa diharapkan menjadi pelopor demokratisasi. Kecenderungannya, apakah mau keluar atau justru mempertahankan status quo, banyak tergantung keterikatannya pada struktur sosial. Bagaimana Anda melihat pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia? Bukankah pembentukan Komisi itu untuk menangkis kritik dari luar mengenai pelaksanaan hak asasi di Indonesia? Kalau semata-mata itu tujuan itu, ibarat mencoba menegakkan benang basah. Menurut saya, untuk menangkis kritik luar tiada jalan lain kecuali pelaksanaan dan penghormatan terhadap hak asasi itu sendiri. Dalam era globalisasi sekarang ini tidak bisa dielakkan berlakunya apa yang disebut horizontal accountability atau tanggung jawab horisontal di antara bangsa- bangsa. Sebagaimana kita alami sendiri, misalnya perkosaan hak- hak asasi di Vietnam, telah mengakibatkan Indonesia terpaksa menampung manusia perahu dari negeri itu. Hak-hak asasi bersifat universal. Tapi apakah dalam penerapannya memang bisa berbeda-beda tergantung budaya lokal? Tolong sebutkan secara spesifik apa yang dimaksud dengan budaya lokal itu. Kekeluargaan, kegotongroyongan, musyawarah? Saya kira, hal itu tidak khas Indonesia, dan tidak sukar untuk ditemukan di Eropa pada Abad Pertengahan. Ini kan unsur-unsur budaya agraris yang di sana telah luluh oleh gempuran modernisasi. Yang saya tahu pasti apabila seseorang diinjak- injak, apakah orang sini atau orang bule, ia akan merasa kesakitan dan memandangnya sebagai suatu kesewenang-wenangan. Apakah demokratisasi dan hak asasi manusia seperti yang di negara maju bisa terwujud di sini? Mengapa tidak? Tetapi di atas segalanya barangkali perlu dijernihkan terlebih dahulu apakah demokrasi dan penegakan hak- hak asasi itu telah menjadi pilihan etis kita. Sebab, sekali lagi, yang dihadapi adalah pilihan etis, bukannya pilihan ilmiah. Bagaimana Anda memandang munculnya organisasi-organisasi cendekiawan seperti ICMI dan PIKI? Saya menyesal harus menyebut ulang di sini bahwa pada awal Orde Baru ada semacam komitmen untuk tidak melembagakan apa yang disebut "politik aliran" pada dataran "political society". Pancasila sebagai asas tunggal sesungguhnya bertitik tolak dari komitmen ini. Harus diakui bahwa organisasi- organisasi cendekiawan ini tidak tergolong orpol. Persoalannya lalu apakah organisasi-organisasi cendekiawan itu tidak akan banyak bergerak pada dataran "political society". Problem lain, apakah tidak seyogianya kaum intelektual berperan untuk memperbanyak kesetiaan yang lebih luas dan tidak justru membangun sekat-sekat di dalam lingkungan mereka yang memperkuat pengkotakan masyarakat. Ini kritik saya pertama. Kritik kedua, dewasa ini kita berada dalam suatu konstelasi yang ditandai oleh posisi state yang terlampau kuat daripada society. Oleh karena itu, seyogianya kaum cendekiawan memperkuat society dan bukan sebaliknya. Dalam kaitan ini sukar menghilangkan kesan bahwa kehadiran ICMI ditopang oleh state yang tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk itu. Bagaimana Anda melihat suksesi? Suksesi itu pasti datang. Hanya yang merisaukan adakah peran manusia dan masyarakat dalam suksesi itu. Pada hemat saya, peran warga negara dan masyarakat itu perlu untuk menanamkan tradisi demokratis dalam masyarakat kita. Lagi pula, saya kira, mereka yang menantikan suksesi bukanlah semata-mata demi kelangsungan suksesi itu sendiri. Tetapi mendambakan bergulirnya suatu perubahan sistem ke arah yang lebih demokratis. Di dalam konstelasi sekarang dan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang niscaya peran ABRI yang menentukan, yang decisive, dalam proses penggantian kepemimpinan itu. Bagaimana pandangan Anda mengenai dwifungsi ABRI? Fungsi sebagai kekuatan sospol melekat di tubuh ABRI? Dulu, pada akhir tahun 1960-an, saya dan rekan-rekan memberikan semacam jalan keluar yang cukup pragmatis. Okelah fungsi sospol itu melekat, inheren. Tetapi, sebagaimana halnya dengan fungsi hankam, apakah fungsi sospol harus selalu diejawantahkan? Dengan kata lain, volume atau intensitas penggunaan fungsi sospol itu akan banyak bergantung pada situasi dan kondisi. Harap dicatat, yang ditekan volume penggunaannya. Fungsi itu sendiri tidak hilang. Ada suatu sikap dasar ABRI, sebagaimana sering dilontarkan oleh para pemukanya: ABRI tidak ingin sekadar menjadi pemadam kebakaran. Masalahnya, apakah pelaksanaan sikap dasar itu bisa terjamin dengan kehadiran ABRI secara fisik di dalam sistem politik. Dengan kehadiran itu, ABRI justru terus-menerus bertindak sebagai pemadam kebakaran termasuk untuk soal-soal kecil kalau tidak mau menyebutnya sebagai penjaga malam yang tidak pernah istirahat. Saya pikir, terlampau berat beban yang dipikul oleh ABRI. Yang tentu mengkhawatirkan, itu akan menimbulkan benih-benih desintegratif. Misalnya, gejala dalam pemilihan pejabat di daerah. Apakah Golkar bisa diharapkan mendorong perubahan ke arah demokratisasi? Kalau mau jujur, faktor integrasi Golkar untuk sebagian besar berasal dari luar tubuhnya, yaitu dari kekuatan riil di dalam sistem politik, dalam hal ini Presiden dan ABRI. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan orpol ini jika kekuatan riil itu tidak lagi memberikan pengayoman. Sungguhpun Golkar mengenal anggota, dalam prakteknya ia lebih menampilkan diri sebagai organisasi pengurus. Pengurus pada umumnya tokoh- tokoh dengan konstituensi yang tidak jelas. Dan karena itu, orang bisa menjadi pemimpin seketika dan, diturunkan tanpa kehendaknya. Golkar juga mengembangkan faktor integrasi di tubuhnya karena adanya pertentangan kepentingan di antara golongan kekaryaan itu sendiri. Kebersamaan mereka hanya bisa dipertahankan oleh faktor-faktor luar. Maka, dalam jangka pendek, mustahil ia akan mandiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini