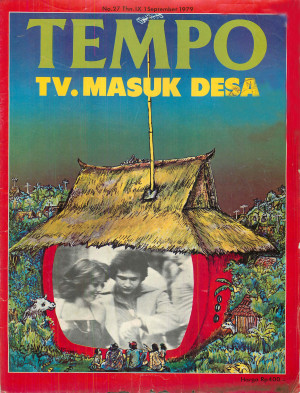DARI pinggiran kota, mobil John Morgan meluncur dengan kecepatan
tinggi menuju Washington. Ia berusaha keras menepati janji, pada
jam 10.00 pagi menemui penasehtnya di Universitas George
Washington. John sadal, batas kecepatan maksimum 50 mil per jam
di jalan yang tidak terlalu lebar dan sepi itu telah ia langgar.
Tetapi ia juga tidak ingin terlambat dari janji dengan gurunya.
Setelah beberapa menit ia melaju dengan kecepatan 70 mil, raung
sirine patroli jalan raya pun terdengar seperti yang dapat ia
duga. Setelah mendahului beberapa puluh meter, mobil polisi itu
pun berhenti.
Dengan sikap sempurna, hamba hukum itu pun berhormat sopan.
Ujarnya: "Sir, maaf saya telah mengganggu perjalanan Anda. Saya
dapat memahami, anda mungkin perlu cepat sampai di tujuan.
Tetapi telah 15 mil batas kecepatan maksimum telah anda lampaui.
Silakan tanda tangan pada lembar tiket ini, dan denda dapat anda
selesaikan pada bank terdekat. Selamat Jalan."
John Morgan tersenyum, penuh penghargaan pada polisi yang
menjalankan tugas dengan korek itu. Tetapi yang lebih
mentakjubkan ialah bahwa pada kesempatan pertama ia melihat
bank, John segera mampir. Dituliskan di atas ceknya sejumlah
dollar yang tercantum dalam tiket denda. Begitu wajar, tiada
maki, tiada sesal. Sewajar ia minum coke atau makan hamburger.
Kesadaran hukumnya tidak lagi terasa sebagai beban. Juga tidak
sebagai pemenuhan panggilan suci. Biasa saja.
***
Di West Terminal, London, Sakala, anak muda dari Uganda yang
baru tiba itu, tertegun. Ia hendak ke Oxford Street, dengan bis
kota bersusun. Di pinggir jalan yang ditandai hanya dengan
sekeping kaleng bergambar bus dan bertuliskan nomor-nomor, satu
deretan yang terdiri dari belasan orang berdiri bertumpu pada
tiang penyangga rambu tersebut. Mereka antri. Padahal bus
kelihatan pun belum. Begitu otomatis, begitu tabularasa, tiada
berdesak, tiada berjqal. Masing-masing dengan kesibukannya
sendiri membaca koran, membaca buku saku, atau mengunyah perman
karet, sambil antri. Untuk antri dengan tertib teratur itu, bagi
orang Inggeris ternyata tidak dibutuhkan patriotisme yang
meluapluap. Sebaliknya untuk Sakala, terbiasa dengan cara naik
bus di negerinya, tidak dapat memahami sama sekali rituil
perantrian ini. Ia tidak mau jadi nomor. Sakala adalah insan
yang mempunyai identitas dan kepribadian yang dibawa dari
kampungnya yang merdeka.
Maka tatkala si bus susun yang meliuk-liuk, menyeret penumpang
dan ketuaan usianya itu datang, Sakala pun tiada sabar. Ia
menerobos, memotong konvensi antri yang tradisinya telah tegak
berabad-abad di Inggeris itu. Dengan ketidakpedulian, aturan
main telah dilanggar. Nenek-nenek kondektur yang galak mulut
itupun sia-sia memaksa turun Sakala yang kekar. Pandang
kejijikan dan kebencian penumpang lain tidak menyentuh perasaan
hatinya yang membatu. Pelanggaran konvensi itu tampaknya tidak
terselesaikan dalam bus. Tetapi sesungguhnya telah ada
penyelesaian. Sakala memang berada dalam bus itu. Tetapi ia
bukan sebagian dari keutuhan kesadaran hukum yang dihayati
penumpang-penumpang lainnya.
Bus nomor 41 itu meluncur dengan kecepatan sekitar 40 km per jam
di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta. Supir begitu cekatan,
sehingga tarikan berangkat maupun injakan rem waktu berhenti
tiada terasa menghentak-hentak. Begitu halus, begitu hati-hati,
begitu trampil. Kecepatan pun hampir rata sepanjang jalan. Mesin
mobil terpelihara, dan plat kopling tiada menunjukkan keausan
yang mencemaskan.
Bus yang sederhana namun terpelihara itu hanya berhenti di
tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Dengan sigap
kondektur mendahului turun, dengan wajah cerah mengamati
penumpang yang mengakhiri perjalanannya. Ia begitu ringan tangan
terhadap orang tua atau ibu-ibu yang membutuhkan pegangan, untuk
menuruni tangga bus yang cukup tinggi itu. Semuanya dikerjakan
dengan ikhlas tiada gerutu, tiada bentakan. Di sana-sini ia
menyapa penumpang yang baru dikenal itu dengan lelucon segar,
menghalau kepenatan.
Penumpang yang baru naik, mengatur diri sendiri. Mereka yang tak
kebagian tempat duduk, menggeser tempat berdirinya, sehingga
beban berjubel itu kurang menyiksa karena tersebar merata. Tanpa
diminta, uang limapuluhan telah mereka siapkan. Begitu kondektur
lewat, dengan santai ongkos itu dibayarkannya.
Supir itu bersiul kecil, menggambarkan wajah yang sabar dan
cerah. Gaji memang kecil tetapi pasti. Tiada yang mengejar dalam
pelaksanaan tugasnya, kecuali keselamatan penumpang, kehormatan
perusahaan dan integritas ketrampilannya menyetir Bus yang
dapat ia andalkan dalam menjamin kepastian masa depan diri dan
keluarganya.
Saudara, jangan salah sangka. Saya memang sedang bermimpi
tentang tertib lalu lintas di Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini