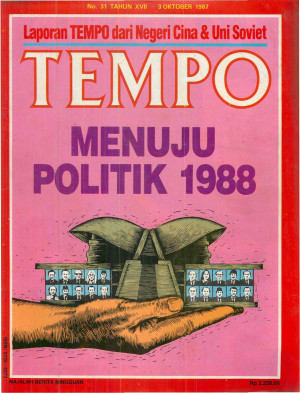RAMBUTNYA gondrong, kusut kemerahan. Tulang pipinya menonjol, menyangga matanya yang cekung. Wajah anak muda gembel itu tampak lebih tua dari umurnya yang 27 tahun. Ia memang lagi "bertapa" -- karena tak berdaya. Ini terjadi di Solo, menjelang 1 Oktober 1965. Anak muda itu, yang menulis puisi, tersingkir dari arus yang dominan waktu itu. Arus "Revolusi", yang digerakkan Bung Karno dan dikobarkan PKI -- dengan kekuatan yang menggebrak hampir di mana-mana. Ia harus minggir, karena seperti banyak temannya, para sastrawan, pelukis, dan cendekiawan lain, dituduh "kontrarevolusi". Ia baru didepak dari RRI Surakarta, tempat ia dan kawan-kawannya menyelenggarakan acara sastra dari Warta Minggu, tempat ia mencari nafkah. Dan namanya, yang "kontrarevolusi", diumumkan di sebuah koran Jawa Tengah. Memang kedengaran ganjil, di tengah gejolak "revolusi belum selesai", ada seorang Jawa ngugemi budaya bertapa. Tapi itulah sikap para sastrawan saat itu, yang bertekad menulis sesuai dengan kodrat dan hati nuraninya. Seperti bunyi surat teman penyair dari Jakarta, Januari 1965, " . . . bagi kita, kebudayaan kini sedang bertapa, bagai Ratu Kalinyamat yang tapa wuda aneng ukir, asesinjang rambut (bertapa telanjang di bukit, berkain rambut)...." Ketika itu, memang tak ada ruang sejengkal pun baginya. Itu tak berarti udara revolusi yang pengap mampu menyumbat napasnya. Seperti surat rekannya itu (Mei 1964), "... kita mungkin akan terpukul mundur karena kekuatan politik (bukan kebenaran) lawan kita, tapi kita masih memiliki suatu daerah yang tak ternilai harganya, yang tak dipunyai lawan (yang tak kreatif), yakni daerah penciptaan." Namun, suatu malam, keyakinannya guncang. Dalam grup diskusi terbatas ia menyimpulkan, kesewenang-wenangan PKI tak bisa dilawan dari "daerah penciptaan". Bukankah sajak-sajaknya misalnya, tak bisa menggerakkan rakyat? Ini soal politik. Ini soal "penyusunan dan penggunaan kekuatan" -- seperti tulis Bung Karno. Tapi bukankah ia tak punya massa? Ia hanya anak muda yang belajar menulis puisi. Bahkan, waktu itu, ia seorang buronan. Jantung ayahnya suka berdetak keras ketika beberapa kali anggota Pemuda Rakyat mencari anaknya. Mungkin gara-gara ceramahnya tentang Manifes Kebudayaan di Klaten dan Semarang, yang mengkonfrontasikan Pancasila dengan Manipol -- doktrin resmi saat itu -- dan Marxisme. Ceramah yang nyaris mengundang sabetan celurit. Di sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu basis PKI itu, ia menginap berpindah-pindah. Dari masjid ke sekolah, dari rumah satu ke rumah lain. Dari rumah pelukis di Warungmiri, ke rumah pegawai toko sepatu di Keprabon. Dari rumah pengusaha batik di Lawiyan, ke pemondokan mahasiswa di Kauman. Dari rumah rekan pengarang di Mesen, ke bedeng seorang sutradara teater di Jagalan. Hampir setiap malam ia "menguliti" Manipol, membaca brosur terbitan Lembaga Kader (Katolik), menelaah Marxisme dan brosur-brosur politik PKI, meminjam majalah Langkah Gerakan Pemuda Sosialis Padahal, ia, yang pernah belajar di Madrasah Aliyah Darussalam Jayengan, sesungguhnya seorang religius. Maka, ketika Letkol Untung melancarkan kudeta, ia gampang menduga: pasti PKI dalangnya. Dan anak muda itu pun semakin berhati-hati ketika 1 Oktober 1965, S.K. Wirjono -- kenalan yang pernah mengganyangnya -- muncul sebagai Sekretaris Dewan Revolusi Surakarta yang dibentuk "Gerakan 30 September" itu. Ia tambah yakin, tak mungkin melawan komunis dengan puisi. Ia harus y'bergerak" bersama kekuatan masyarakat yang sudah mulai bangkit d sana-sini. Maka, kelompok diskusinya, yang antara lain didukung seorang pejabat Kota Madya Surakarta, menstensil selebaran gelap -- dalam bahasa Indonesia dan Jawa -- berusaha membuka mata wong Solo akan kepalsuan PKI. Ia juga menyusun teks khotbah untuk seorang ulama politikus beken dalam sembahyang Jumat di Masjid Agung Solo, 22 Oktober 1965, dengan tema yang sama. Khotbah yang, seperti biasanya, disiarkan RRI itu, sarat dengan semboyan revolusioner, dicampur ayat Quran, membakar semangat jihad mengganyang kaum syimal (kiri). Ia tak terlalu yakin khotbah itu berhasil "menghasut" pendengarnya. Tapi menjelang asar, 22 Oktober 1965 itu, ketika panser pasukan baret merah RPKAD menerobos Kota Solo yang adem ayem, massa nonkomunis yang lama berdiam diri dan menunggu -- tanpa khotbah Jumat sekalipun -- bergerak melawan PKI. Spontan. Anak muda bersandal jepit itu pun -- bersama massa pemuda lain -- berlarian di Jalan Slamet Riyadi, "dikawal" tembakan si baret merah ke udara. Di depan asrama Batalyon 444, di perempatan Gladag, ia tertegun. Sebuah peluru dari batalyon pro-PKI itu. menembus tubuh sahabatnya. Muhammad Chanan, pemuda lembut berkaca mata minus itu, gugur di halaman gereja Protestan yang tua. Anak muda itu segera menyelinap masuk kampung, bergabung dengan massa yang lain menuju rumah seorang Tionghoa, pengusaha batik yang dituduh sebagai donatir PKI. Ia dapati rumah kuno yang bagus di Jalan Nonongan itu sudah hangus. Ketika matahari terbenam, kumandang azan magrib dari RRI Surakarta terdengar seperti suara kesaksian: Hayya 'alalfalab (mari merebut kemenangan). Tapi anak muda itu merasa "kalah". Ia tertunduk, ketika senja itu seorang sahabat kecilnya hilang. Sartono, remaja kelas II SMP Negeri X Solo yang berkulit hitam, cerdas, dan suka bertanya soal politik itu -- bersama 20-an remaja yang lain usai berdemonstrasi menyambut pasukan RPKAD, dicegat Pemuda Rakyat dan dibantai di tepi Bengawan Solo. Hari-hari berlalu. Para pemuda dan mahasiswa dilatih RPKAD dipersenjatai. Suatu malam, anak muda yang berusaha kembali menulis puisi itu tersentak. Ia mendengar adiknya, mahasiswa bersenjata itu, mentalnya terguncang. Ia tergagap, tubuhnya tak bergerak, tangannya kaku menggenggam bedil. Dalam sebuah operasi di luar kota, anggota resimen mahasiswa itu menyaksikan seorang lurah PNI, dalam posisi berdiri ditanam hidup-hidup oleh PKI, dengan kepala menyembul di permukaan tanah. Sebatang paku besar berkarat terhunjam di ubun-ubunnya. Kekerasan pun berkecamuk, pembunuhan bergelombang. Tak jelas lagi, mana yang mempertahankan diri, yang "kiri" atau yang "kanan". Indonesia, sekali lagi, berdarah. Dan orang bertanya: sampai kapan ....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini