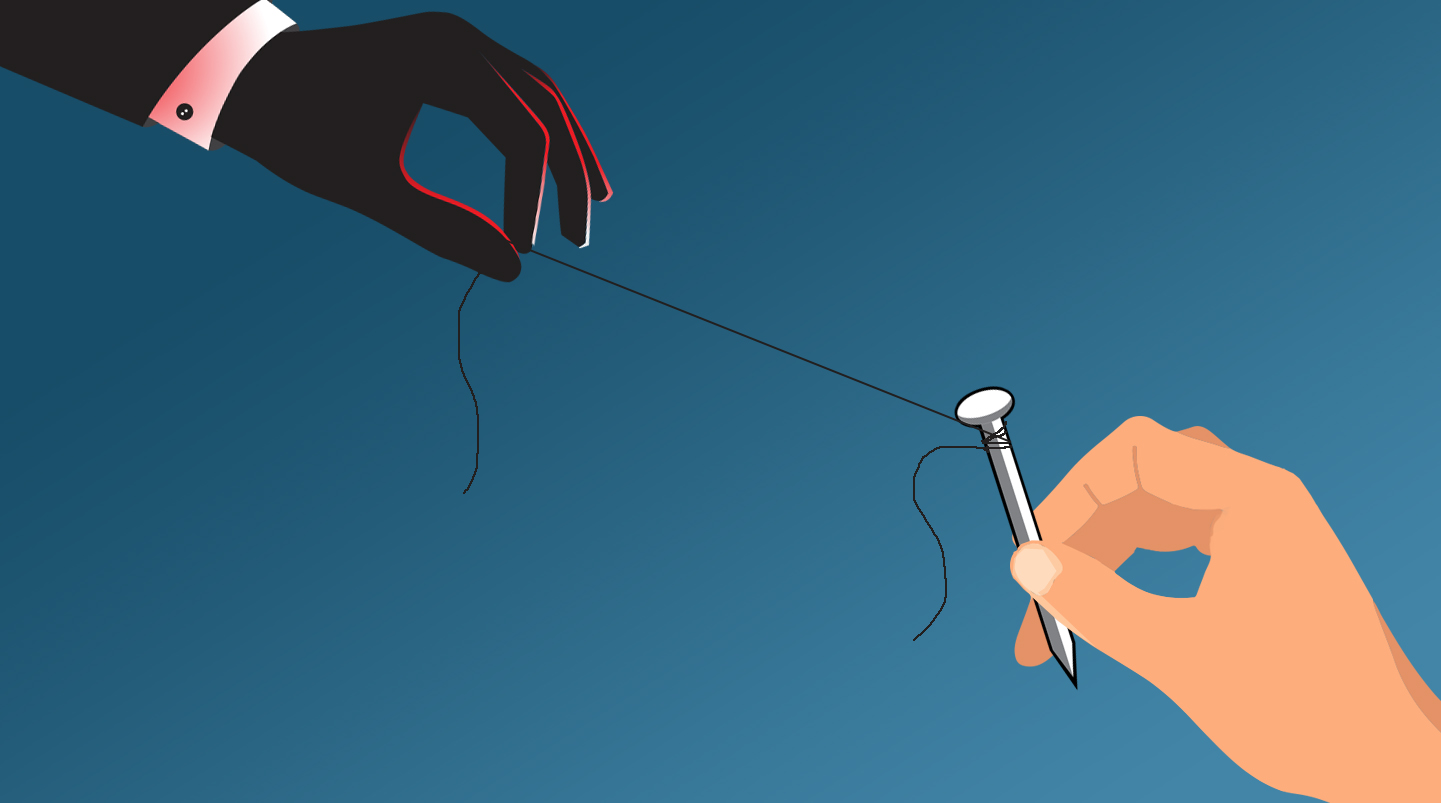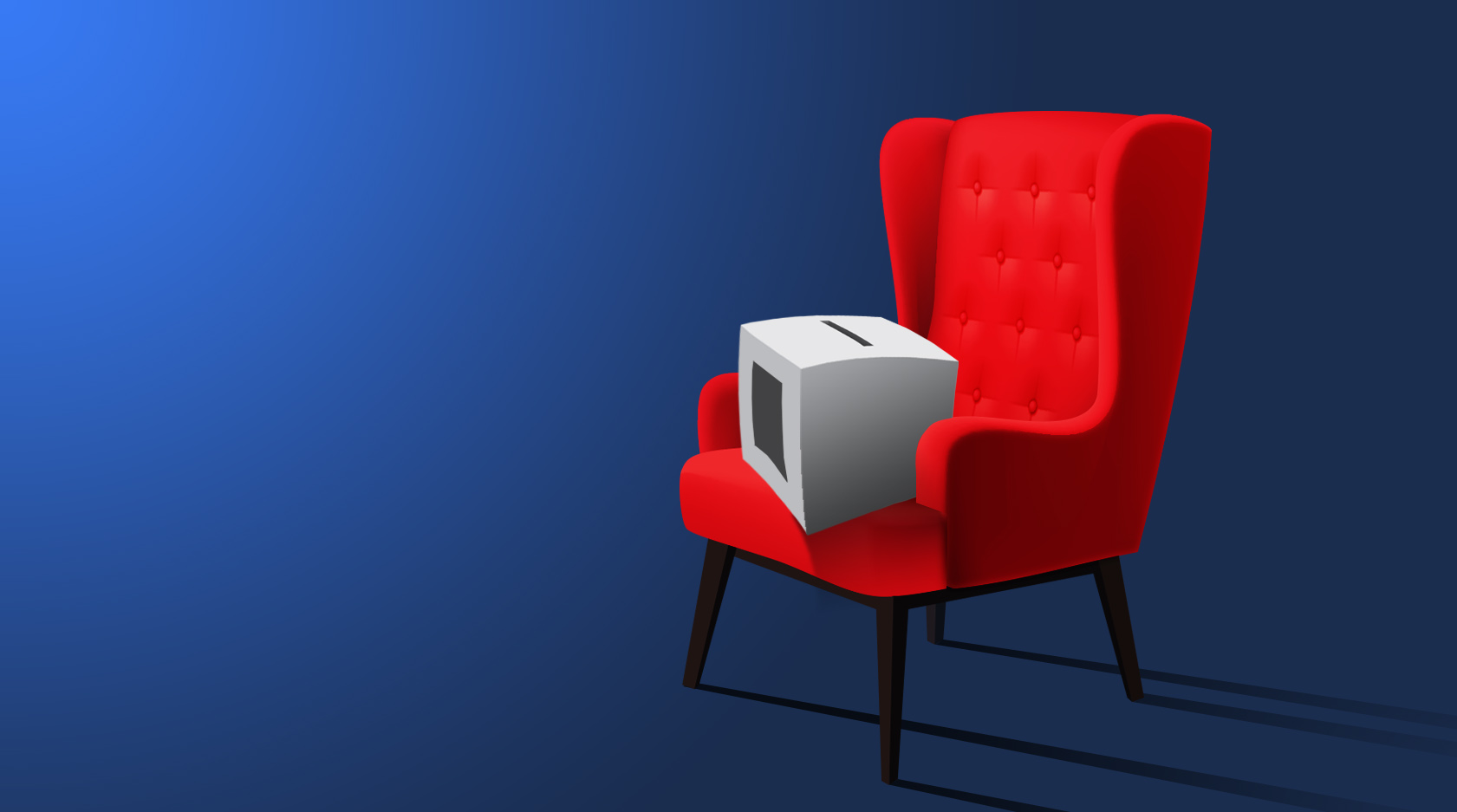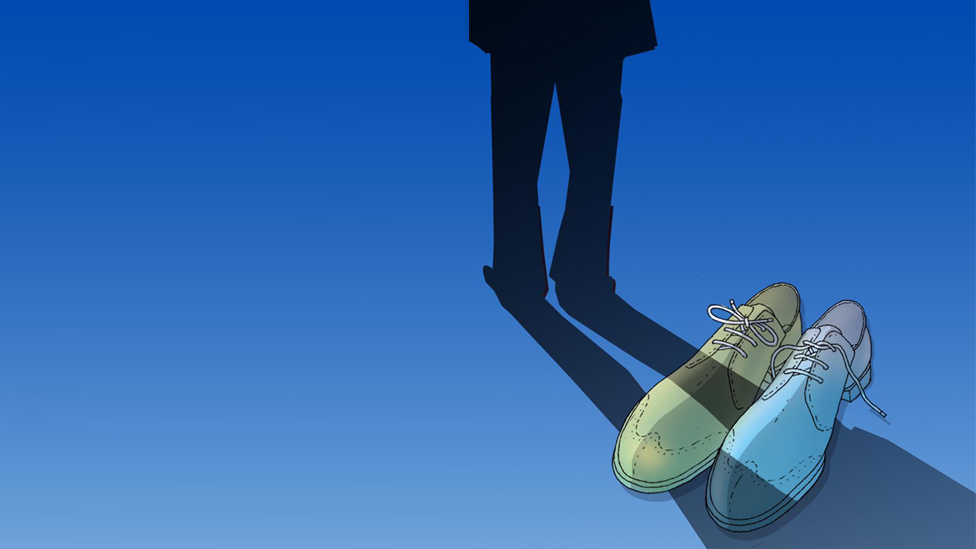Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang terjadi justru sebaliknya: protes melebar di berbagai penjuru dan muncul kesan tak tertanggulangi.
Bermula dari penghinaan rasial dan persekusi terhadap penghuni asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, sehari sebelum peringatan kemerdekaan negara ini, unjuk rasa merebak di berbagai penjuru Papua dalam dua pekan terakhir. Patut disayangkan, Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dipimpin Inspektur Jenderal Luki Hermawan gagal memprediksi potensi rusuh. Luki adalah perwira senior yang membina karier di bidang intelijen.
Demonstrasi yang berujung kerusuhan pun terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Huru-hara juga melanda Kabupaten Deiyai, Papua, pada Rabu, 28 Agustus 2019, dan diduga mengakibatkan tiga orang tewas—satu di antaranya anggota Tentara Nasional Indonesia. Sehari kemudian, kerusuhan membakar Jayapura, ibu kota Papua.
Sesungguhnya tak sulit bagi intelijen untuk mengendus cikal kerusuhan di Papua, yang kerap dilanda konflik sosial. Dampak dari tindakan rasisme bisa dengan mudah diperkirakan seandainya intelijen dan aparat keamanan tak memandang sepele persoalan tersebut. Personel intelijen yang tersebar di seluruh Papua seharusnya bisa mendeteksi gerakan berbagai elemen di Papua, dari mahasiswa, aktivis, hingga orang tua, yang menggelar protes dan menuntut referendum untuk menentukan kemerdekaan provinsi itu. Intelijen polisi, tentara, dan Badan Intelijen Negara seperti tak sigap mencium gelagat. Padahal Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak—untuk menyebut salah satu aparat keamanan—adalah perwira senior yang telah malang-melintang di dunia antiteror.
Kerusuhan sangat mungkin diminimalkan jika polisi cepat mengusut kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua. Namun Polda Jawa Timur baru menetapkan satu tersangka, yaitu bekas calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Tri Susanti, 12 hari setelah peristiwa. Sedangkan TNI baru mengumumkan pencopotan personelnya yang ikut bertindak rasis sekitar sepekan setelah kejadian.
Alih-alih sigap menyelesaikan persoalan, pemerintah dan aparat keamanan malah membuat blunder. Di Bandung, Jawa Barat, polisi malah menyiramkan bensin ke arang panas dengan memberikan sekardus minuman keras kepada mahasiswa asal Papua. Tindakan konyol penegak hukum ini menjadi viral dan kian memanaskan hati orang Papua yang tak terima diidentikkan dengan pemabuk.
Pemerintah pun bertindak tak hati-hati dan terkesan panik dalam menyikapi konflik. Berdalih mempercepat pemulihan keamanan di sana, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses Internet di Bumi Cenderawasih. Padahal belum ada situasi darurat yang menuntut pembatasan akses informasi. Pemerintah akhirnya ikut melanggengkan diskriminasi dengan mengisolasi warga Papua dan menghilangkan hak terhadap akses informasi. Alih-alih membatasi penyebaran kabar bohong, pemblokiran itu malah membuat hoaks sulit diverifikasi.
Pemerintah dan aparat keamanan selayaknya mengetahui pergeseran peta konflik di wilayah itu, terutama pada aktor gerakan. Dulu aksi protes bergantung pada kepala suku dan tetua adat. Kini anak-anak muda tampil di depan untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua secara keseluruhan—bukan hanya hak-hak suku mereka.
Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menunjukkan kepedulian kepada warga Papua dengan kerap mengunjungi daerah itu. Di era kampanye dalam Pemilihan Umum 2014, ia pertama kali berkunjung ke sana betapapun Papua tak memiliki banyak pemilih. Tapi, dalam masa pemerintahan selanjutnya, ada kesan pemerintah menyederhanakan persoalan: masalah Papua diatasi hanya dengan membangun infrastruktur.
Sudah selayaknya pemerintah membuka kembali pelbagai studi yang telah dilakukan kampus dan masyarakat akademis tentang Papua. Masalah Papua bukan semata soal akses jalan antarkabupaten, melainkan juga kesenjangan, ketidakadilan, dan tidak adanya penghargaan kepada mereka sebagai manusia. Presiden harus memastikan warga Papua tak diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.
Selain meminta maaf, Jokowi mesti secepatnya menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Para pelaku kejahatan hak asasi harus dihukum. Pemerintah serta kepolisian dan TNI juga mesti mengedepankan dialog dan tak boleh lagi bertindak represif terhadap warga sipil. Tanpa solusi yang menyentuh pangkal persoalan, konflik di Papua tak akan pernah berakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo