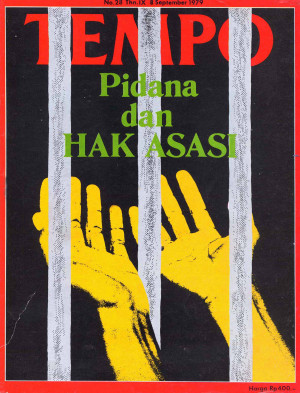BANJAR Sangging adalah banjar yang kecil. Tidak lebih dari 87
keluarga yang menggugus membangun suatu komunitas pelukis gaya
tradisional dan pengrajin perak. Dalam peta pariwisata yang
lantang berbicara tentang Ubud Tampaksiring, Sanur, Kuta, Mas,
Celuk dan sebagainya itu Sangging hampir-hampir tidak
terucapkan. Paling, Kamasan, desa yang membawahinya, saja yang
kadang-kadang tersentuh oleh tangan pariwisata. Itupun hanya
oleh para kolektor barang-barang seni atau peminat-peminat
khusus.
Soalnya, banjar Sangging dan desa Kamasan itu memang bukan
desa-desa yang seindah Ubud atau Tampaksiring yang hijau dan
berbukit. Juga yang tidak sarat dengan pura-pura yang
mengagumkan atau yang hiruk-pikuk oleh pukulan gamelan Bali yang
bertalu-talu. Dengan pendek, Sangging, Kamasan, "tidak memenuhi
syarat" sebagai tempat yang bisa dibayangkan dalam buku gambar
wisata tentang Bali yang penuh kemilau itu.
Toh, desa itu desa yang penting. Di situlah senilukis
tradisional gaya Klungkung-Kamasan yang cemerlang itu masih
dikerjakan terus dengan cara dan bahan yang hampir tidak berubah
sejak satu-dua abad yang terakhir ini. Kecuali mungkin pada
Nyoman Mandra dan Mangku Mura, pelukis-pelukis terkemuka dalam
gaya ini, yang sendirian mengerjakan lukisan mereka, lukisan
Kamasan itu masih dikerjakan secara kolektif oleh berbagai
tangan laki, perempuan dan anak-anak.
Dengan tekunnya mereka membagi pekerjaan menyeket mewarnai, dan
menyelesaikan seluruh lukisan itu. Dengan gairah yang seakan tak
kunjung mengendor mereka meramu berbagai bahan cat alam, dari
batu, dari daun-daunan, melukis berbagai dongeng dan cerita yang
turun-temurun telah merupakan bagian dari jagad mereka. Tentang
berbagai episoda dari Mahabarata (Bima Swarga, Arjuna Wiwaha),
Ramayana Rama Tambak, Sugriwa-Subali), Suthasoma, Lubdaka Panji
Malat) atau Brayut. Lukisanlukisan terbaik hasil
seniman-pengrajin banjar Sangging, Kamasan, ini tersebar di
seluruh dunia di rumah-rumah para kolektor asing serta menjadi
koleksi dari berbagai museum terkemuka.
Hatta, sejak dua-tiga tahun yang lalu banjar Sangging tersentuh
oleh listrik. Byar! Bagaikan sentuhan tangan gaib para dewa,
desa yang biasanya remang-remang di waktu malam karena cahaya
lampu minyak, sekarang menjadi terang oleh cahaya listrik. Dan
Banjar yang sebelumnya hanya diramai-kan oleh suara radio
transistor itu, Sangging yang hanya dihuni 87 keluarga itu,
sekarang berbangga hati memiliki 10 buah televisi.
Salah satu televisi yang ramai dengan pengunjung adalah televisi
di rumah pelukis Nyoman Mandra. Setiap sore, begitu jam televisi
dimulai, anak-anak, muda-mudi dan orang-orang tua pada
berkerumun di teras Mandra yang sempit itu berdesakan menonton.
Suara azan maghrib yang kedengaran aneh, ibu-ibu Persit yang
main angklung dengan penuh dedikasi, pengalaman-pengalaman Lucy
yang konyol dalam kehidupan bule yang aneh, tembakan dan kebutan
maut dari Steve MacGarrett di jalanjalan Honolulu, omongan
berbagai pejabat dalam baju-baju safari, Benyamin dan Bagio yang
tanpa capeknya menjajakan kain caterina dan ajinomoto serta
bakso.
Semua acara itu mereka telan dengan lahapnya sama dengan bila
mereka menikmati arja atau drama gong atau tontonan tradisional
mereka. Mereka akan datang dan pergi, duduk dan berdiri,
menggumam "beh, beh, beh . . . ", untuk kemudian duduk mencakung
kembali mengamati kotakajaib itu lagi ....
***
Apa yang terjadi di banjar kecil itu?
Pada siang hari, pada waktu matahari memancar dengan terangnya,
di keteduhan pohon jambu atau atap ilalang, komunitas itu
bercanda dan berbicara dengan dunia yang dengan akrabnya
mengajar mereka bagaimana keseimbangan di jagad itu mesti
dijaga. Suthasoma yang rela dimakan harimau, seperti terlukis
dengan indahnya oleh Nyoman Mandra itu, memberi tahu komunitas
itu bahwa kesediaan berkorban untuk kepentingan yang dianggap
lebih besar itu baik. Bima yang menggugat para dewa di Suralaya
menuntut sorga bagi ayah dan ibu-tirinya, seperti terlukis oleh
Mandra lagi, memberitahu bahwa kebaktian yang gigih dan tulus
terhadap orang-tua itu penting bagi komunitas. Lewat lukisan
mereka anggota-anggota banjar itu secara gotong-royong
melaksanakan berbagai dialog akrab itu dengan santainya hampir
tanpa suatu kompleks.
Pada malam hari, waktu bola lampu listrik itu menyala, komunitas
itu--sebagian--bercanda dan berbicara dengan dunia asing.
Berbagai informasi baru, yang bagaikan pelangi yang tak kunjung
habis, datang menghambur memenuhi indera mereka. Mereka
mencernakan itu semua dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu
seorang bocah.
Tidak semua dongeng baru itu cocok dan "sinkron" dengan
Suthasoma, Bima dan Lubdaka. Tapi toh semua cerita baru itu
menarik dan kudu diberi tempat. Sebagai orang Hindu-Bali
mestinya mereka sudah lama diberitahu untuk selalu berakomodasi
dengan berbagai unsur yang menyangga kehidupan. Agar
keseimbangan dan keselarasan jagad selalu terjaga. Bukankah Kala
yang angkara itupun kadang-kadang perlu diberi sesaji?
Tetapi televisi bukanlah Kala, yang mungkin sudah akan puas oleh
sekali-duakali sesaji. Televisi adalah satu kotak ajaib yang
teramat cerewetnya yang tidak terlalu sabar dalam membangun dan
mengembangkan dialog. Ia menuntut sangat banyak dari
penontonnya. Ia menuntut agar sang penonton tidak puas dengan
dongeng yang dibangun lewat atu jalur lurus oleh lingkungannya
selama beberapa abad --seperti Suthasoma atau Bima Swarga.
Ia menuntut agar sang penonton siap dengan tidak hanya satu-dua
dongeng yang dicerna secara santai dengan pengendapan berhari,
berbulan. Ia ingin penonton itu sekaligus sanggup mencerna
berpuluh dongeng yang datang dari berbagai arah yang mesti
dicerna sekilas-sekilas sesuai dengan watak elektronika yang
berkecepatan kilat itu.
***
Alangkah repot! Ada berapa banyak masyarakat-masyarakat di
negeri kita, di Asia, di seluruh dunia yang mesti mengalami
akomodasi simultan seperti masyarakat Sangging itu? Tidak
terbilang!
Pada waktu ia sedang terbiasa memahami keseimbangan jagad lewat
media visual yang membangun pencernaan informasi secara
sepotong-sepotong, ia sudah ketemu televisi. Yakni, satu media
yang mengajar bahasa keseimbangan dengan idiom yang gelisah,
menjerit dan merangsang.
Pada waktu satu masyarakat baru beranjak berangkat ke dalam
dunia tulisan dan bacaan, ia harus sudah "memuak kembali" dalam
ikatan komunitas yang kolektif. Cuma, kali ini kolektivitas yang
lebih gelisah dan menuntut lebih banyak.
Tentu saja kehidupan berjalan terus di banjar Sangging. Orang
masih terus menggumam "beh, beh, beh " waktu mengagumi satu
lukisan Mandra tentang ciptaan dunia dalam episoda Muter Cunung
di siang hari. Orang menggumam "beh, beh, beh " juga waktu
melihat Hawaii Five O di malam hari. Sementara anak-anak yang
mandi di kali sudah menyerap dengan enaknya:. eeee, ketemu lagi,
copot, copot, copot, copot .....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini