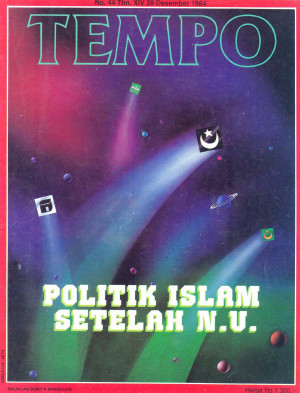SEORANG wartawan pernah bertanya kepada Ronald Reagan, "Siapakah yang Anda jadikan pola hidup Anda?" Jawab Reagan, " The man from Galilee." Tentu saja Reagan tak bersendiri. Berjuta-juta manusia kini merasa mengikuti jejak itu, meskipun tak cmua sama dan sebangun dengan Reagan, yang makmur, yang necis, yang mensyukuri tanah airnya sebagai negeri pilihan. Di tahun 1965, misalnya, seorang padri Katolik bernama Camillo Torres bergabung dengan para gerilyawan di Colombia yang panas. Dia juga merasa mengikuti apa yagn telah dinyatakan he man frorn Calilee. Berbeda dengan Reagan, dia tak bersama orang-orang yang kaya. Di Amerika latin yang bergelimang kemiskinan yang terinjak-injak, Torres ikut perjuangan bersenjata. Yang makmur, yang gembil, yang berpakaian halus di istana-istana, bukan berada di pihaknya. Bukankah yang miskin yang justru kepadanya telah dijanjikan, oleh the manrom Calilee itu, kebahagiaan? Bukankah mereka yang lapar, yang akan dipuaskan? Padri Torres karena itu tak merasa asing untuk bahu-membahu dengan orang-orang Marxis. Bahkan di sebuah pertemuan di Santiago, Chili - sebelum Presiden Allende yang kiri ditumbangkan orang militer yang kanan sejumlah pemimpin agama bertemu. Mereka bicara tentang "perjuangan kelas", memuji Marxisme, mengutuk CIA, mengutuk Washington. Bayangkan seandainya Reagan, yang juga Kristen, mendengar langsung cercaan itu. Maka, di mana jadinya titik temu? Atau mungkinkah, untuk dua kubu seperti itu, tak akan ada titik temu, di dunia yang retak-retak ini, juga dengan iman? Saya sendiri bukan seseorang dalam iman seperti Reagan atau Camillo Torres. Saya tak cukup berani untuk menawarkan suatu jawaban yang patut, yang bagaimanapun jawaban "orang luar". Tapi di hari Natal ada seorang teman yang datang, dan berkata (dia seorang Kristen yang saleh), "Yesus datang ke Yerusalem tidak dengan kuda putih kemenangan, melainkan dengan keledai pinjaman." Ia datang dari udik. Di Yerusalem, waktu itu, yang memegang tampuk kekuasaan adalah orang-orang Yahudi dari golongan Saduki. Mereka diwakili oleh 70 orang, dan dipimpin seorang pendeta agung. Inilah yang mengurus segala soal: perkara keagamaan, perdata, administrasi, dengan hukum Taurat yang ketat - meskipun waktu itu Yerusalem berada di bawah kontrol Romawi. Tak heran bila jauh di bawah, orang tak merasa berbahagia. Ketidakpuasan tampaknya meruyak: ada banyak ramalan tentang akan datangnya Juru Selamat, dan orang-orang Zelot bersiap dengan revolusi. Tapi Yesus tidak tergolong kepada mereka. Bukan karena sebuah sikap yang halus dan lembut hati. Yesus bahkan bisa keras, bisa berapi-api, seperti halnya para nabi Yahudi dalam Perjanjian Lama. Ia mengecam kota-kota Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ia mengutuk sebatang pohon ara. Ahli-ahli Taurat serta orang larisi pun dituding "munafik", terang-terangan, dan malah disebut "keturunan ular beludak". Tapi di balik itu, Yesus tetap bukan orang Zelot yang mau menghumbalangkan segala tata yang ada. Ia tak mau terpancing untuk menganjurkan orang menolak membayar pajak kepada kekuasaan Romawi. Ia tak mau terbawa mengobarhan amarah, ketika orang datang menceritakan bahwa penguasa asing itu telah mencampurkan darah Yahudi dengan darah hewan korban mereka. Yesus justru menghentikan pertumpahan darah ketika seorang murid menyabet kuping seorang prajurit di Tarnan Gestamani. Di situ, kata teman saya pula, masalahnya bukanlah sekadar soal antikekerasan dan mencintai musuh kita. Yesus jelas tak dapat dikatakan telah memberi teladan kepada Reagan untuk menumpuk senjata dan kepada Torres untuk mengangkat bcdil. Tapi soalnya lebih dalam: the man from Galilee menerima manusia bukan sehagai hasil abstraksi, melainkan sebagai kehadiran-kehadiran yang kongkret. Yang disebut "sesama manusia" adalah sesuatu yang aktual: orang yang menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Persamaan suhu, agama, bangsa, ras, kelas - semua itu tak masuk perhitungan. Sudah jelas bahwa batasan "sesama manusia" seperti itu bukan sebuah kategorisasi. Karena itu, nasionalisme, persamaan kelas, dan pelbagai garis revolusi politik akan mustahil memakainya: dengan itu tidak akan pernah pasti benar, siapa 'kawan" siapa "lawan. Maka, segala hasrat revolusi pun tak tersalur lewat tokoh dari Galilea ini. Godaan untuk kemenangan politik, untuk kekuasaan di dunia, telah sejak mula ditampik. Beberapa pertanyaan memang kemudian menggantung: Bagaimana, tanpa kekuasaan, kebaikan bisa terwujud di dunia? Tentu sulit, dan sejarah manusia kemudian tak henti-hentinya mencoba. Tapi pertanyaan pertama memang harus dikemukakan, siapa gerangan yang bisa disebut "baik". Bukankah Yesus sendiri pernah menolak disanjung, dan mengatakan yang baik hanya Allah ? Saya terdiam mendengar cerita teman saya itu, yang, menurut pengakuannya, hanya sebuah penafsiran pribadi. Dan itu pun, katanya, ia ambil dari Christ Sein, terjemahan Inggris, karya Hans Kung. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini