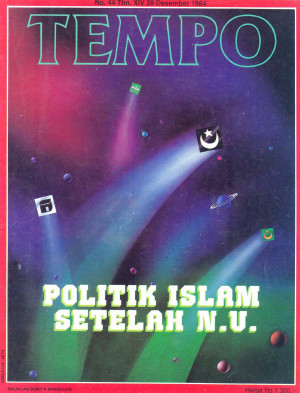NAMANYA agaknya tak akan terpisahkan dari sejarah politik umat Islam di Indonesia. Tapi Snouck Hurgronje adalah sebuah nama yang cemerlang dan sekaligus ternoda. Seorang kiai, tokoh Masyuml tahun 1950-an, menjulukinya sebagai "mufti imperialis" Belanda. Nama "Snouck Hurgronje" sendiri akhirnya bahkan jadi semacam cercaan, yang sering dilontarkan kalangan Islam di Indonesia, kepada tokoh yang mereka curigai melakukan "tipu muslihat" terhadap mereka. Di tahun 1967-1968, misalnya, H. Rosihan Anwar, oleh sementara mahasiswa Islam dicap "Snouck": wartawan terkemuka ini banyak menulis tentang Islam, padahal ia, seorang sosialis penganjur modernisasi, tak berasal dari kalangan pergerakan Islam. Belakangan ini, nama Snouck pun disebut - setidaknya diingat - lagi. "Saya," kata seorang pejabat tinggi di Jakarta, "juga sudah dituduh sebagai Snouck Hurgronje". Agaknya ini berhubungan dengan niat pemerintah untuk memisahkan semangat pengelompokan keagamaan dari perjuangan politik. Dan bagi sebagian aktivis organisasi Islam, itu berarti "pemisahan Islam dari politik", yang pernah diusahakan pemerintah Hindia Belanda atas petunjuk sarjana terkemuka C. Snouck Hurgronje menjelang akhir abad ke-19. Sejauh mana hal itu benar, agaknya harus ditelaah lebih dulu - tentu saja dengan kembali menggali zaman Snouck Hurgronje, ketika kantor penasihat urusan pribumi masih berdiri di Indonesia, sejak akhir abad ke-19. Dalam tesis untuk gelar doktornya di tahun 1984 ini, Husnul Aqib Suminto, dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, khusus menampilkan sejarah kantor yang sangat penting itu. Dengan judul Politik Islam Pemerintah Hindia Pelanda: Het Kantoor voorInlandsche Zaken 1899-1942, Husnul Aqib memang mengumpulkan banyak bahan penelitian, terutama di Negeri Belanda. Dan tentu, nama Snouck Hurgronje sangat menonjol di situ. Dari sekian penasihat pemerintah kolonial yang mengepalai kantor itu, tulis Suminto, "Snouck Hurgronje memang tampak paling besar." Snouck memang tak setengah-setengah. Seperti dikatakan Sejarawan Taufik Abdullah kepada Bambang Harimurty dari TEMPO, di kalangan sarjana Barat yang mempelajari dunia Timur, kaum orientalis itu, Snouck dianggap satu dari tiga atau empat tokoh besar di awal abad ke-20. Hidupnya, agaknya, memang diabdikan buat ilmu - dan juga buat kebesaran Kerajaan Belanda. Anak pendeta yang dipecat dari gereja ini (akibat "skandal hubungan gelap", tulis H.A. Suminto), dalam umur 27 tahun, bahkan untuk memperdalam pengetahuannya, nekat pergi ke Mekkah. Itu terjadi pada tahun 1884. Di kota yang tertutup bagi orang bukan Muslim itu ia memakai nama "Abdul Gaffar". Ada indikasi, doktor dalam bidang sastra Semit dari Universitas Leiden ini mengaku diri sebagai orang Islam. Seorang sarjana Belanda lain kemudian menyebut bahwa tindakan "pura-pura" itu telah menodai gambaran umumnya sebagai ilmuwan. Tapi betapapun, dengan itu ia membuktikan diri sebagai pegawai Kolonial yang cakap. Ia membuktikan bahwa nasihatnya untuk memadamkan perang Aceh berhasil. Jalan yang dirintisnya, sebagai penasihat Gubernur Jenderal di bidang urusan dengan umat Islam di negeri jajahan ini, diikuti para ahli terkemuka laim. Memang, dengan demikian ia kadang lebih bersemangat sebagai perumus garis politik ketimbang sebagai penelaah - dengan akibat Snouck pun bisa meleset dengan hebat. Yang agaknya kini tak banyak diingat lagi ialah bahwa poiitik tcrhadap Islam ala Snouck bukanlah suatu politik pernusuhan. Seperti ditulis H.A. Suminto dalam tesisnya, Snouck telah "melawan ketakutan Belanda selama ini terhadap Islam". Ia menegaskan, "Ulama independen bukanlah komplotan jahat, mereka hanya menginginkan ibadat." Dan ia jelas bukan pendukung "Kristenisasi" orang jajahan. Jika ada yang dimusuhi Snouck, itu bukanlah Islam sebagai agama, melainkan, demikian ditulis dalam tesis H.A. Suminto, "Islam sebagai doktrin politik." Snouck Hurgronje membagi masalah Islam dalam tiga kategori. Yang pertama bidang agama murni, yang kedua bidang kemasyarakatan, dan yang ketiga bidang polittk. Pemerintah Belanda, dalam resep yang dltawarkan Snouck, harus membantu kedua yang pertama, tapi menghantam yang ketiga. Ternyata, usaha "menjinakkan" umat Islam ini tak berhasil. "Kritik terhadap Snouck ialah," kata Taufik Abdullah, "ia tak hanya membeda-bedakan ketiga hal itu, tapi juga memisahkannya." Seandainya Snouck lebih bersikap sebagai penelaah ketimbang sebagai orang yang ingin cepat bertindak, akan tampak ketiga hal itu bisa bergabung dalam satu manifestasi Islam, dalam kenyataannya, bukanlah cuma soal sembahyang, puasa, berzakat, dan naik haji. Dan itu bukan terutama karena melihat ketentuan ajaran, melainkan karena kenyataan yang terjadi dalam sejarah sosial indonesia. Seperti ditulis H.A. Suminto, mengutip pendapat para sarjana lain, orang Islam di negeri ini, "Memandang agamanya sebagai alat pengikat yang membedakan dirinya dari orang lain." Dan di masa penjajahan, Islam "berfungsi sebagai titik pusat identitas", semacam bendera perlawanan terhadap pemerintah asing yang bukan Islam. Dalam konfrontasi seperti itu, Islam tidak lagi bergerak dalam tiga bidang yang dilihat Snouck secara necis. Islam jadi tempat penyusunan kekuatan - yang tampaknya harus dilakukan orang pribumi untuk melepaskan diri dari susunan masyarakat kolonial yang mencekik. Kenyataan susunan nasyarakat kolonial itu menang boleh dikata diabaikan Snouck. Akhirnya, itulah yang menggagalkan cita-citanya: menggabungkan "rakyat Islam di negara Nederland dengan orang-orang Nederland", tanpa membeda-bedakan agama. Snouck tak melihat ada yang lebih terasa pedih bagi "rakyat Islam" itu. bukan perbedaan agama, melainkan perlakuan sosial yang timpang. Adakah kenyataan seperti itu masih berlaku di zaman kini, agaknya masih perlu ditelaah lebih jauh. Yang jelas, dari banyak peristiwa sejarah, tampak bahwa kenyataan sosial dan problem-problemya sering lebih menentukan ketimbang fatwa, dari atas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini