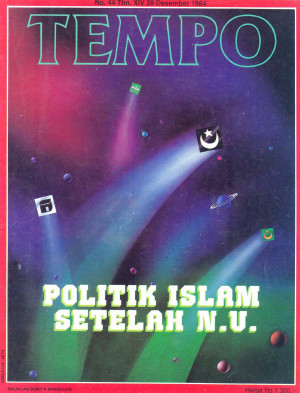ADA yang terjadi di tahun 1953. Kiai Masjkur, sebagai menteri agama, mengadakan rapat para ulama di Puncak untuk, antara lain, membahas masalah DI. Tidak kurang dari empat hari empat malam, ditengah segudang kitab, para kiai berbincang untuk akhirnya memutuskan: memberi kuasa kepada Presiden Soekarno buat menumpas DI. Presiden sendiri diangkat sebagai waliyul amridh dharuri bisy syaukah alias pemegang urusan darurat dengan kuasa penuh. Para kiai yang bersidang itu tidak semuanya orang pemerintah, tentu - meski kalau tak salah semuanya orang NU. Waktu itu memang belum ada Majelis Ulama, dan Departemen Agama dikenal sebagai "departemen NU". Dari kejadian itu sebenarnya sudah jelas sikap kalangan NU terhadap keabsahan Republik Indonesia dan pemimpin tertingginya. Di belakang hari, K.H.A. Siddiq bisa pula mengingatkan kita bahwa di tahun 1945, tanggalnya 22 Oktober, NU juga mengeluarkan Resolusi Perang Sabil. Di situ disebutkan, berperang melawan NICA adalah fardhu 'ain wajib untuk tiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. "Jadi, membela negara RI wajib hukumnya, menurut agama. Juga menjaga stabilitasnya," demikian rais am NU yang baru itu. Pihak penentang seperti DI sudah tentu akan menolak. Toh, di luar NU, pendapat berbagai kelompok dalam Islam tentang topik itu sebenarnya tidak jauh berbeda walaupun tidak semua pihak mengaku adanya lembaga waliyul amridh dharuri bisy syaukah itu. Bukti penerimaan bulat - atas nama agama - kepada keabsahan RI adalah ini: diterimanya lembaga wali hakim, dalam kasus kawin lari, misalnya, atau untuk pengantin yang tak punya wali. Wali hakim di situ adalah salah satu rukun nikah (bukan sekadar pencatat seperti penghulu), dan ia dalam fiqih disebut sebagai wakil amir atau khalifah (pemerintah). Kalangan DI dulu tak mau mengakui lembaga RI itu. Tetapi, pendapat bahwa sebuah negara sah menurut agama tak dengan sendlrinya berarti keyakinan bahwa negara itu ideal. Dan di sinilah masuknya, antara lain, kemungkinan pembicaraan topik negara Islam, khususnya karena pengaruh perkembangan di luar negeri. Tetapi, dari semua tokoh yang diwawancarai TEMPO, didapat pernyataan bahwa baik dari Quran maupun Hadis - atau fiqih umumnya - sebenarnya tidak ada perintah tentang "negara Islam" itu. Setidak-tidaknya bila itu berarti bentuk ataupun model. "Kesalahan Iran," kata Abdurrahman Wahid, misalnya, "adalah karena menganggap negara mereka sebagai satu-satunya model Islam - dengan menyerang bentuk negara Arab Saudi dan sebagainya." Secara garis besar, umumnya disepakati bahwa yang ada dalam Islam adalah pengaturan sosial atau kemasyarakatan, dan bukan negara itu sendiri. Tentu, masyarakat yang ideal menurut Islam adalah yang mencerminkan tata krama Islam dan, maksimal, syariat Islam - khasnya yang berbentuk hukum-hukum. Syariat ini, memang, pada gilirannya membutuhkan perlindungan dari negara - apa pun bentuk perlindungan itu. Tapi di sini sebenarnya diskusi bisa lebih fundamental yakni bila yang dipersoalkan ialah seberapa jauh hukum-hukum Islam bisa berubah. Pada bagian cukup besar umat Muslimin di mana-mana, yang sudah demikian lama mendapat bandingan dari hukum Barat, tak jarang terdapat rasa asing kepada bentuk-bentuk hukum yang sering dikatakan di sana sini banyak mengangkut udara padang pasir abad VII Masehi alias tidak mengalami pengembangan itu. Mereka bertanya bukankah yang dikehendaki Islam sebenarnya kebaikan, alias ruh atau moral hukum itu, dan tidak selalu bentuknya sendiri setidak-tidaknya di luar hukum-hukum mengenai tata ibadat dan hukum keluarga. Haruskah orang Islam mengambil oper semua bentuk hukum dalam Quran, alias yang dipraktekkan Nabi dan para sahabat, ataukah memilih berbagai alternatif dalam sejarah kaum Muslimin seperti yang termuat dalam berbagai kitab kuning model NU, misalnya, ataukah bisa lebih jauh dari itu - dengan keyakinan bahwa sejarah, dalam pandangan Islam, sebenarnya tidak mandek? Di sini pendapat para tokoh tidak seluruhnya sama. Masalahnya ialah ini: bila Tuhan memberi kepercayaan kepada manusia (Muslim, di sini) untuk lebih banyak mengatur dirinya sendiri, meski dengan tetap meletakkan Wahyu di depan mata, dan mengikutsertakan sejarah masanya sendiri dalam mencoba memahami kemauan Tuhan itu, masalahnya agaknya jauh kurang kompleks. Hukum Islam - menyangkut pidana dan kriminal, misalnya - di sana sini menjadi bisa "sama saja" dengan yang resminya bukan dari Islam. Ini memang salah satu topik yang kadang membikin ajaran Islam mengenai negara terasa kadang-kadang "angker". Tapi, sampai berapa jauh penafsiran itu? Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang bicara: K.H. ACHMAD SIDDIQ, 58, rais am NU. Islam memang tak pernah memerintahkan kita mendirikan negara. Baik di dalam Alquran maupun Hadis, tak pernah ditemukan tentang bentuk tuntas negara. Yang ada adalah tugas pemerintahan yang paling prinsip: menegakkan keadilan, dan menyampaikan amanat kepada ahlinya, misalnya. Tapi Indonesia adalah negara Muslim, ini dilihat bukan dengan kaca mata politis, tapi semata-mata dari fiqih Islam. Muktamar NU ke-ll pada 1936 sudah menyatakan begitu. Sebagai referensi adalah kitab kuning, Bughyah al-Mustarsyidin, bab Al Amaan (keamanan) dan Al Hudnah wal Jizyah (gencatan senjata dan upeti), yang menyebutkan: Setiap wilayah atau tempat yang pernah dikuasai oleh orang Islam, nama negara atau wilayah itu tetap Muslim dan tidak berubah selamanya. Pada abad pertama Hijriah, Islam sudah masuk dan berkuasa, sekalipun dalam ukuran Samudera Pasai (kerajaan Islam pertama di sini yang didirikan oleh Sultan Malikush Shaleh, persis di tepi Sungai Pasai, Lhokseumawe, Aceh). Sekalipun kemudian kekuasaan itu terputus oleh penjajahan Belanda, negara ini tetap Muslim. Jadi, negara ini adalah negara Muslim yang sah menurut fiqih, yang wajib kita jaga stablhtasnya. Tidak usah memimpikan yang macam-macam. Melaksanakan pembangunan (Pelita) juga wajib, karena itu adalah keputusan MPR yang mayoritas anggotanya Muslim. NURCHOLISH MADJID, 45, doktor lulusan Universitas Chicago dalam ilmu filsafat dan teologi Islam: Sekarang makin banyak orang yang berpegang kepada ide masyarakat Islam (Moslem society), bukan negara Islam (Moslem state atau Islamic state). Menurut dia, masyarakat Islam tak lagi menekankan pada soal-soal kenegaraan, tapi lebih menekankan kepada soal-soal kemasyarakatan. Perkataan negara Islam sendiri, yang dipeloporl oleh Pakistan, sebenarnya tak pernah dikenal dalam sejarah Islam. Di zaman Ottoman, di Persia dulu, memang ada sebutan daulah, yang akhirnya menjadi negara karena Persianisme. Perkataan daulah itu sendiri mula-mula bukan berarti negara, melainkan berarti giliran. Maksudnya, sejak Islam datang ke Persia, orang Persia atau bangsa Aria itu mempunyai paham bahwa manusia hidup dikuasai oleh roda nasib, yang selalu berputar: kalau lagi baik ya di atas menjadi penguasa, tapl kalau nasib tak baik, ya di bawah. Jadi, kekuasaan itulah yang disebut daulah. Kita mengenal daulah Abassiyah, daulah Umawiyah. Tapi tak ada yang menyebutkan daulah Islamiyah. Munculnya daulah Islamiyah di Pakistan pada mulanya memang bagus, yakni sebagai suatu cara untuk membedakan diri dari negara Marxis atau kapitalis. Nabi Muhammad sendiri tak secara tegas merumuskan bahwa yang ia bentuk itu sebuah negara. Buktinya, sementara beliau sendiri menganjurkan bahwa orang yang meninggal harus cepat dikuburkan, itu tak berlaku pada dirinya, yang dimakamkan setelah tiga hari meninggal. Kejadian itu disebabkan karena penggantinya tak jelas, pola suksesi tidak jelas. Dan resultante dari semua itu adalah ketidakjelasan. Dan itu menunjukkan bahwa masalah kenegaraan tidak menjadi bagian yang integral dari Islam. Perumusannya: Negara itu hanya merupakan ekstensi - suatu alat - dari Islam, untuk memperkuat dirinya dari segi ajaran. Bentuknya bisa macam-macam, misalnya partai politik, organisasi, masjid, dan madrasah. Hijrahnya Nabi ke Medinah, menurut saya, karena beliau tak bisa melaksanakan agamanya di Mekkah, bukan karena tak bisa mendirikan negara di Mekkah. Nabi sendiri tak pernah menamakan Medinah sebagai negara Islam. Ajaran Islam bisa saja membuat konsep tentang negara, meskipun konsep itu tak eksklusif Islam, melainkan inklusif, dan bisa diikuti oleh orang lain. Islam bahkan bisa menjadi dasar untuk suatu negara yang modern. Masalahnya tinggal implementasinya, yang dulu, misalnya, pernah berbentuk di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Ali, dan termasuk Ummayah. Saya sendiri cenderung pada pendekatan kultural, yang di dalamnya sudah termasuk politik. Itu akan lebih awet ketimbang pendekatan yang melulu politik. Jadi, titik krusialnya adalah: Apa kita ini akan memaksakan segi politik itu atau membiarkannya tumbuh dengan wajar. Kalau yang terakhir ini kultural namanya, sedang yang memaksakan itu politis. JALALUDDIN RACHMAT, 35, dosen Etika Agama dan Syariat Islam di Institut Teknologi Bandung. Master dari Iowa State University dengan tesis persepsi politik tokoh-tokoh Islam Indonesia ini juga mengajar di Ushuluddin IAIN Sunan Gunungjati, Bandung. Negara itu bisa berarti banyak. Bisa berarti state, bisa juga berarti nation state. Yang belakangan itu baru digali kira-kira pada abad ke-19. Kata Ad-daulah adalah kata baru bahasa Arab untuk nation state. Jadi, kata Ad-daulah itu dibuat orang untuk mengartikan definisi negara. Dari kerangka pemikiran ini, sia-sialah mencari kata Daulah Islamiah baik di Quran maupun dalam Hadis. Jadi, jika dengan negara yang dimaksud adalah Daulah ini, memang tak ada dalam Islam. Tapi, negara bisa juga bermakna suatu executve power, suatu imstitusi kekuasaan yang melaksanakan hukum-hukum dan peraturan. Untuk definisi yang ini, Islam memang merupakan rangkaian peraturan atau syariat yang tidak bisa jalan tanpa kekuasaan. Mana bisa hukum potong tangan bagi pencuri dijalankan tanpa ada kekuasaan. Zakat dilaksanakan juga karena ada eksekutif. Tak berarti negara Indonesia dengan demikian diganti menjadi negara Islam. Alternatifnya, negara menerlukan konsep-konsep lslami dalam kehidupan bernegara di dalam negara Pancasila ini. Sebab, Arab Saudi dan Pakistan pun, yang mengaku sebagai negara Islam, tak menerapkan konsep Islam secara menyeluruh. Pakistan, misalnya, tidak sepenuhnya menerapkan konsep ekonomi dan politik Islam. ABDURRAHMAN WAHID, 44, ketua Tanfidziyah NU. Dalam Islam, negara itu adalah hukum, al-hukmu, dan sama sekali tak memiliki bentuk negara. Yang ada hanya kemasyarakatan dan komunitas. Selama etik itu diberlakukan, selama itu pula tak ada keberatan dengan sistemnya. Dan etik ini tak bisa dicegah begitu saja. Rusia, yang mencoba menekan etik Islam, kewalahan. Tapi begitu diberikan kebebasan beragama, tak ada perlawanan lagi. Jadi, jika etik itu dijalankan, tak ada alasan lain bagi umat Islam selain harus ikut mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Di sini jelas sekali munculnya keharusan taat kepada pemerintah. Karena itu, Islam tak butuh bentuk negara tertentu. Ada tiga bentuk kekuasaan dalam Islam, yang diuraikan dalam kitab Al Bajuri, alassyahri Qaribil Mujib. Yaitu imamah melalui ahlulhalli wal aqdi, kedua, istikhlaf atau pelimpahan kekuasaan, dan istila atau kudeta. Ini semua sah. Jadi, apa sebenarnya tujuan bernegara bagi Islam? Hanya untuk menegakkan keadilan. Itu saja. Pemimpin dalam konsep Islam harus memiliki sifat adil. Dalam politik di Indonesia, apakah etik Islam sudah dilakukan? Kalau ini sudah jalan, berarti sudah terpenuhi. H. ENDANG SAIFUDDIN ANSHARI, 46, Master dari McGill University, Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Bekas aktivis PII, HMI, dan pernah menjadi ketua KAPPI Jawa Barat, telah menulis 15 buku, antara lain Piagam Jakarta. Kini pergerakan politik Islam di Indonesia tamatlah riwayatnya. Yang sesungguhnya, pergerakan itu punya akar kuat dalam sejarah dan masyarakat Indonesia ini. Dalam konsep negara menurut Islam, ada nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi Islam, yang terkandung dalam Quran dan Sunnatu'r Rasul, yang memberikan patokan pokok mengenai pelbagai kegiatan sosio-kultural manusia. Termasuk melakukan aktivitas politik kenegaraan. Sebuah negara, yang diletakkan atas dasar Islam, menjunjung tinggi nilai dan norma Islam, dapat saja kalau mau disebut negara Islam, atau "Negara Utama", atau "Negara Adil Makmur", atau nama lain apa pun. Muslim sejati tidak komitmen dengan nama, tapi dengan milai dan norma. Jadi, negara yang menjunjung tinggi nilai dan norma-norma Ilahi dalam kehidupan bernegara adalah "negara ideal". Menurut saya, negara yang bisa disebut begitu yaitu yang pernah berdiri dalam Sejarah Islam, negara di bawah pimpinan Muhammad Rasolullah saw. dan Khulafa ar-Rasyidin, terutama dua khalifah pertamanya - Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di luar itu, kecuali negara dinasti Umawiyyah khusus ketika di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masih harus dipertanyakan keidealannya, walau negara-negara itu disebut negara Islam. Sekali lagi, yang penting adalah isi, bukan label atau papan nama. HARUN NASUTION, 65, bekas rektor IAIN Jakarta. Yang ada di dalam Alquran dan Hadis cuma dasar-dasar bernegara, seperti keadilan, demokrasi, persamaan hak, dan toleransi. Ajaran Islam itu sangat fleksibel. Pada zaman Nabi, sebagai contoh, orang-orang mualaf (orang yang baru menjadi Islam) diberi santunan. Itu karena, pada masanya Islam belum kuat. Padahal, di zaman Umar, ketika Islam tak lagi lemah, Khalifah Umar tak lagi memberi uang pada para mualaf. Memang, untuk hukum-hukum Islam, harus ada kekuasaan pemerintahan. Tapi Indonesia, yang berdasarkan Pancasila ini, sudah mencerminkan diri sebagai salah satu negara Islam, dengan bentuk republik berasaskan musyawarah seperti yang berlaku di masa khulafurrasyidin. Toh di mana pun di dunia ini tidak ditemukan negara yang memberlakukan hukum Islam sepenuhnya. Republik ini malah lebih banyak memenuhi syarat-syarat negara Islam dibandingkan dengan negara-negara yang menyebut dirinya negara Islam di Timur Tengah. Di sini, pelaksanaan hukum Islam - misalnya hukum waris - bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat. Tapi persoalan yang sebenarnya bukan melaksanakan hukum itu, melainkan: apakah fiqih yang dibuat oleh para mujtahid 1.000 tahun yang lampau masih cocok untuk kita sekarang? Ini harus ditinjau. Hukum perkawinan, misalnya, mesti disesuaikan dengan emansipasi. Dulu, ketika hukum dibuat, banyak wanita tidak terdidik. Padahal, kini, banyak wanita terdidik, malah tak kurang yang punya penghasilan melebihi gaji suami. H. DJARNAWI HADIKUSUMA, sekretaris jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam Islam, negara Islam atau konsep negara Islam tidak ada. Yang ada, katanya, hanya penafsiran dari beberapa ulama. Misalya dalam Quran disebutkan, wajib hukumnya memberi hukuman sesuai dengan agama Allah. Lalu ada yang menafsirkan hal tersebut, pemerintahan yang mayoritas penduduknya Islam, diwajibkan memberlakukan hukum Islam. Bagi Muhammadiyah tidak begitu. Sebab, yang harus mewajibkan berlakunya hukum Islam tidak harus pemerintah. Bisa juga oranisasi sosial, pemimpin masyarakat, guru, dan sebagainya. Jadi, Muhammadiyah mengambil aspek kemasyarakatannya. Yang diislamkan itu masyarakat melalui dakwah pendidikan, serta amal sosial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini