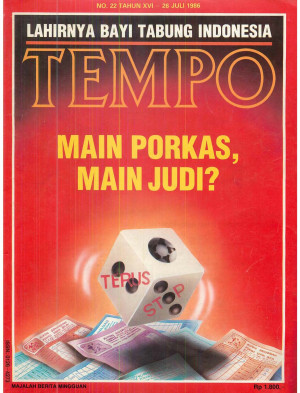ALKISAH, adalah seorang arif bijaksana yang terkenal di seantero negeri. Ia tinggal di kota yang sama dengan Tuparev, teman yunior Jalaluddin Rachmat, malah barangkali mereka itu saling mengenal. Tapi, berbeda dari Tuparev yang datang ke Jalaluddin sesudah panel di ITB, 13 April lalu, sang arif menelepon saya sebelum panel. Tidak seperti Tuparev yang menggebu-gebu protes karena Jalaluddin dalam panel tidak membabat habis saya, sang arif menyampaikan pesan dengan penuh harapan, "Cak Nur, besok Anda jangan sampai melewatkan kesempatan dalam panel untuk membabat habis Jalaluddin yang Syiah dan menganjurkan nikah mut'ah itu!" Mendengar kata-kata Syiah, saya tidak begitu kaget. Meskipun saya penganut paham Sunah, saya tidak ingin dilihat sebagai anti-Syiah. Sebab, sikap anti-antian dalam soal agama itu tidak benar. Saya hanya kebetulan tidak setuju dengan beberapa ajaran Syiah saja. Maka, ketika mendengar kata-kata nikah mut'ah (nikah sementara), saya memang mbregidik, lalu sepenuhnya setuju dan membenarkan pesan sang arif. Apalagi, konon, sudah jatuh korban di kalangan kaum muda di sana. Keesokan harinya, ketika saya datang di aula ITB, yang telah penuh sesak oleh mahasiswa, saya disambut oleh seseorang dengan senyum cerah dan ramah. Dialah, Jalaluddin. Saya duduk di sebelahnya, dan dengan penuh persahabatan kami mulai omong-omong menjelang panel. Seorang teman lain mendekat, dan mengatakan bahwa ia merasa kasihan kepada Kang Jalal (begitu sebutan akrabnya di sana) karena banyak mengalami penyensoran. Jalal tidak lagi sepenuhnya bebas bicara di depan umum, kecuali pada beberapa kesempatan tertentu, dan di beberapa tempat tertentu saja. Kebebasan! Alangkah seringnya kata-kata itu diucapkan, tapi alangkah sedikitnya orang yang benar-benar memahami dan mampu menaksir nilainya. La syai' atsman min al-hurriyah (tiada sesuatu pun yang lebih berharga daripada kebebasan), begitu kata para ahli hikmah. Dan kebebasan itulah yang, menurut teman di sebelah saya mulai dirampas dari Jalal. Maka, timbul rasa simpati saya kepadanya. Saya ajak ia menggunakan forum panel itu guna "belajar" menggunakan kebebasan itu dan mengembangkannya. Terutama, kebebasan berpikir. Dan, Jalal setuju. Sesuai dengan rencana panitia, saya kebagian waktu yang pertama memberi urun rembuk. Dan, saya sedikit canggung. Ketika Jalal menerima gilirannya, ia tampil dengan amat mengesankan. Dengan gaya retorikanya -- konon, ia memang terkenal jago pidato -- ia mengajukan argumen-argumen yang lancar tentang pentingnya peranan intelek, dan perlunya mengembangkan kebebasan berpikir. Semua hadirin setuju dan kagum, termasuk saya. Maka, dengan sedikit rasa salah kepada sang arif, saya tidak membabat Jalal. Justru kami saling menopang. Saya tidak sempat melapor kepada sang arif, tapi saya yakin ia paham dan setuju. Apalah artinya persoalan nikah mut'ah jika dibandingkan dengan kebebasan yang terancam. Maka, kebebasan patut sekali ditempatkan pada skala prioritas yang sangat tinggi. Ironisnya, justru seruan kepada kebebasan berpikir ini yang sangat mengecewakan Tuparev, seorang pengagum Jalal. Lebih ironis lagi, justru seorang Tuparev, pemilik masa depan republik, yang pertama-tama kecewa. Secara tidak sadar ia telah menyiapkan masa depannya sendiri yang buram. Tidak mustahil ia akan tak pernah lagi sempat menyesal. Tapi ironi terjadi tidak hanya pada Tuparev, tidak hanya di ITB dan tidak hanya di Bandung. Ironi bisa terjadi pada orang lain, di lembaga lain, dan di kota lain. Ada tokoh yang mendalami teori-teori tentang kebebasan, misalnya karena ia menekuni kajian suatu ilmu sosial, tapi cara berpikir dan tingkah lakunya tidak lebih dari seorang fanatikus yang memuakkan. Bila orang serupa itu sempat mempunyai akses, apalagi pengaruh, kepada suatu lembaga, maka yang ditanamkan terlebih dahulu biasanya ialah semangat sensor: khususnya, tentang siapa yang boleh dan tidak boleh bicara di situ, buku apa yang boleh dan tidak boleh dibaca, atau masalah mana yang boleh dan tidak boleh dibahas. Maka, jika ia sempat berkuasa, tak peduli pada tingkat mana dan format apa, besar sekali kemungkinan ia akan tampil sebagai tiran. Bibit-bibit tiranik itu sangat boleh jadi bersemai dengan subur dalam Tuparev. Maka, Tuparev telah berubah menjadi Contradora. Jika cukup banyak Tuparev di suatu lembaga akademis, yang seharusnya menjadi bastion kebebasan berpikir, maka inilah peringatan untuk masa depan bangsa kita. Karena itu, janganlah kita biarkan Tuparev tumbuh menjadi Contradora! Saya sendiri insya Allah menyadari betul bahwa saya tidak bisa sepenuhnya luput dari berbagai ironi di atas. Jangan-jangan saya ini menganjurkan kebebasan dan keterbukaan, tapi menjadi sesak napas setiap kali ada orang yang berbeda pendapat dengan saya. Apalagi, demikian seringnya saya menyatakan pendapat bahwa tak seorang pun dari kita, sesama manusia, yang dibenarkan mengklaim kebenaran mutlak. Namun, jangan-jangan tindak-tanduk saya justru mencerminkan orang yang hendak melakukan klaim itu. Sebenarnya, dan seandainya saya bisa memilih, saya lebih suka melakukan sesuatu secara diam-diam, tanpa harus tampak oleh semua orang. Karena itu, ketika menjelang Lebaran lalu, TEMPO menyatakan maksudnya untuk membuat Laporan Utama tentang saya, saya merasa kikuk dan waswas. Yang saya lakukan pada awal tahun 1970-an itu, seperti dikatakan Almarhum Mohamad Roem, hanyalah sekadar suatu statement of intent -- pernyataan niat. Ia lebih merupakan konstatasi tentang pentingnya pembaruan pemikiran dalam Islam dengan beberapa tema pokok tertentu, dan belum merupakan pembaruan itu sendiri. Karena permasalahan sedemikian besar, waktu itu juga saya tegaskan, pembaruan pada zaman sekarang tidak lagi bisa dilaksanakan secara individual, tapi harus secara kolektif dengan penggabungan dan pengerahan berbagai keahlian dan bakat dari banyak orang. Tapi kemudian saya putuskan untuk membiarkan diri saya menjadi sasaran pengamatan TEMPO, dan terserah kepada mereka untuk menarik kesimpulan. Karena itu, saya manfaatkan benar kesempatan diskusi di kantor TEMPO itu, selama tiga jam, untuk mencoba menelaah bersama segala aspek mengenai kebangkitan Islam di Indonesia dewasa ini. Begitu pula pembicaraan selanjutnya, juga selama tiga jam. Setelah terbit, tak ayal Laporan Utama itu mengundang reaksi. Kemudian TEMPO mengambil inisiatif, meminta tanggapan dari beberapa orang, dan saya setuju. Tanggapan-tanggapan itu, berwujud tiga kolom yang diminta dan sebuah komentar yang spontan, dari segi keperluan kepada adanya dialog terbuka, sangat membesarkan hati. Sayang, dua daripadanya, yaitu kolom Amien Rais dan komentar Hasbullah Bakry, terfokus hanya kepada keberatan atas semangat Laporan Utama yang "menobatkan" saya sebagai pemegang "peran besar" dalam kebangkitan Islam itu. Keberatan yang sangat bisa dipahami. Pernyataan keberatan mereka itu, apa pun motif dan latar belakangnya, saya hargai. Selain mereka benar, juga dengan adanya pernyataan itu, saya mempunyai alasan lebih kuat untuk menjelaskan duduk persoalannya. Sebetulnya, jika diperhatikan dengan teliti -- harus amat teliti, memang -- keberatan itu tidak perlu ada. Sebab, ketika saya menjawab pertanyaan TEMPO apakah semua itu hasil usaha saya saya katakan, "Saya ingin sekali mengakui itu hasil saya." Jawab ini saya maksudkan sebagai kalimat pengandaian, setara dengan ungkapan Inggris, "I wish I could claim ...." ("Saya ingin seandainya saya bisa mengakui"). Sebagai suatu kalimat pengandaian, maka dengan sendirinya ia mengandung makna kemustahilan, yaitu mustahil mengakui bahwa kebangkitan Islam di Indonesia ini hasil usaha saya. Gambaran yang paling tepat tentang kebangkitan Islam di Indonesia sekarang ini, menurut bahasa dalam Laporan Utama TEMPO itu bahwa ia hasil kodrati perkembangan Indonesia. Itu berarti melibatkan keseluruhan proses. Dan, proses itu sendiri melibatkan banyak orang, tak terhitung jumlahnya. Amien Rais menyebut-nyebut Natsir dan Roem sebagai yang sangat berjasa. Mungkin saja. Hasbullah menyebutkan banyak lagi orang secara lebih adil dari berbagai golongan, dan tak lupa menyebut dirinya sendiri. Boleh jadi. Tapi, jika harus menyebut seseorang, saya hendak mengajukan tokoh Agus Salim, yang kebetulan juga paling sering saya kemukakan dalam berbagai forum sebagai orang yang berjasa tiada terkira. Salim adalah Bapak modernisme dan intelektualisme Islam yang sebenarnya. Kemudian Bung Karno, yang dalam hal keagamaan banyak mendengarkan Agus Salim (mendirikan Masjid Baiturrahim dan Masjid Istiqlal, mengadakan peringatan-peringatan Islam di Istana, naik haji, sembahyang Jumat, dan sebagainya. Bung Karno menjadi model bagi para pejabat saat itu sampai sekarang). Bahder Djohan, Wahid Hasyim, dan Syarif Thayeb juga harus disebut, karena jasa mereka dalam merintis dan menegakkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum sejak SD sampai perguruan tinggi. Bung Hatta pun besar sekali jasanya, justru, menurut saya, karena ia berhasil menghapus "tujuh kata-kata" dari Piagam Jakarta. Orde Baru juga tak mungkin diingkari peranan dan jasanya, apalagi dengan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, tempat Kang Muttaqien pernah berperan. Masih banyak lagi tokoh dan lembaga yang harus disebut. Pendek kata, seperti kata Amien, kesemarakan Islam di Indonesia sekarang adalah hasil proses banyak faktor dan kompleks. Dan proses itu, kata TEMPO, kodrati saja, bukan perbuatan perseorangan. Keterangan cukup canggih tentang proses kodrati itu, dari sisi tertentu, diberikan oleh Fachry Ali. Tetapi, mungkin istilah "kelelahan intelektual"-nya harus diganti dengan yang lebih tepat. Mirip Fachry, namun lebih persis ialah seperti kata Kuntowidjojo, yaitu bahwa kebangkitan Islam sekarang ditandai oleh pergeseran dari persepsi keagamaan yang Ideologis-politis kepada persepsi yang intelektual-kritis. Jadi, sebetulnya lebih fundamental, bukan "tampil seadanya" seperti kata Fachry. Memang harus diakui, semuanya itu masih dalam tahap permulaan yang dini. Tapi, lebih baik daripada teriakan sloganistis. Di tengah kompleksitas permasalahan itu, peranan saya hanyalah ibarat beberapa butir pasir di pantai. Dan, yang saya perbuat, jika pun patut menyebutkannya di sini, hanyalah ibarat menggarami lautan. Betapapun tidak signifikannya, kami memang pernah mencemplungkan sebungkah garam ke lautan. Itulah bentuk partisipasi dan rasa tanggung jawab saya. Harapan saya, cukup baiklah itu, dan saya yakin, kelak saya akan menyaksikannya, meskipun hanya seberat zarah (atom). "Setelah itu semua, lalu apa?" tanya Fachry. Tidak ada jawab yang gampang. Tapi coba kita renungkan kemungkinan ini: dengan rasa keagamaan yang mbalung-sungsum, hangat dan merata kepada sebanyak mungkin warga negara (melalui pengamalan Islam, dan pengamalan agama-agama lain oleh penganut masing-masing), kita berharap mata rantai paling lemah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, yaitu mata rantai etika sosial, akan menguat, sekuat tuntutan pembangunan yang semakin dahsyat. Dan, itu berarti kepentingan umum nasional kita, bangsa Indonesia. Jika Anda tidak khawatir dibilang stereotipikal, itu semua adalah pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Begitu, 'kan, kira-kira?!
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini