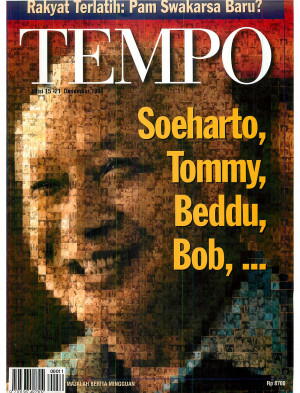Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BUKAN kejutan besar, tapi transaksi besar: 60 persen saham Indofood dilepas. Penjualan ini juga membuat ''silau", tidak hanya karena nilai transaksi mencapai US$ 570 juta, tapi penjualan Indofood disetujui ketika usaha privatisasi tujuh BUMN—yang dimotori Menteri Tanri Abeng—terancam gagal berhubung situasi di Indonesia tidak berketentuan. Akibatnya, pemerintah tidak memperoleh Rp 1,5 triliun yang diharapkan dari privatisasi tersebut, sehingga bolonglah APBN 1998-1999. Untuk menutupnya, pemerintah akan menerbitkan obligasi yang ditawarkan di pasar internasional, dengan jaminan saham tujuh BUMN tersebut.
Memang kontras gambaran ini: ketika pemerintah masih menawar-nawarkan obligasi, Grup Salim sudah mengantongi setengah miliar dolar. Kontras itu semakin lengkap dengan beberapa hal: Bank Dunia menunda pencairan pinjaman sampai 1999, investor asing lebih bersikap menunggu. Dan kalaupun ada yang berminat pada aset perusahaan di sini, nilainya ditawar terlalu rendah. Aset itu dianggap barang obralan, sedangkan saham Indofood dinilai 100 persen lebih tinggi dari harga pasar. Di mana letak kelebihan Indofood—kalau memang ada?
Tiga puluh persen saham Indofood dibeli oleh Nissin Food Products Co. (Jepang), dan 30 persen lagi diborong oleh First Pacific Co. yang berdomisili di Hong Kong. Dengan demikian, kepemilikan Grup Salim pada perusahaan ini tersisa 2,66 persen saja (pemerintah Indonesia 10,18 persen, pemegang saham publik 27,16 persen). Implikasi hukum dari pelepasan saham sebanyak 60 persen ke pihak asing itu ialah, PT Indofood menjadi perusahaan PMA (penanaman modal asing). Kendati ia tercatat di Bursa Efek Jakarta, peraturan yang berlaku terhadap badan hukum Indonesia tidak dengan sendirinya dapat dikenakan pada Indofood. Kelak, misalnya, kalau ada keharusan melakukan aliansi strategis dengan sebuah koperasi, hal itu tidak serta-merta dapat dikenakan pada Indofood. Apalagi jika saham pemerintah (10,18 persen) juga dibeli pihak lain, unsur PMDN (penanaman modal dalam negeri) pun semakin ciut. Kesimpulannya: bisnis Indofood akan tetap likuid.
Di sisi lain, divestasi saham Indofood tidak berpengaruh secara mendasar pada perusahaan itu sendiri. Sebabnya: First Pacific, pemilik baru 30 persen saham Indofood itu, adalah perusahaan milik Grup Salim juga karena 55 persen sahamnya berada di tangan kelompok ini. Jadi, pemegang saham terbesar di Indofood tetap Grup Salim, tapi kepemilikannya diatur melalui First Pacific. Selain berhasil menghimpun US$ 570 juta, kelompok bisnis ini juga terselamatkan dari badai redistribusi aset yang sewaktu-waktu bisa menjungkirbalikkan peta bisnis di Indonesia. Dalam hal divestasi saham Indofood ini, Grup Salim ibarat pasien yang selain diberi kekebalan terhadap penyakit, sekaligus dibayar untuk memperoleh kekebalan itu.
Dan itu tampaknya, mungkin, karena sebagai perusahaan pembawa bendera Grup Salim, Indofood masih memiliki prospek cerah. Kendati rugi selisih kursnya Rp 1,2 triliun (1997), pada tahun itu juga penjualannya melonjak sampai Rp 3,5 triliun. Utang luar negerinya memang tidak dilindung-nilai (sekitar Rp 1 triliun), tapi utang itu baru akan jatuh tempo pada tahun 2000. Sedangkan untuk tahun 1998, Indofood cukup membayar US$ 85 juta saja. Dan sebagai pemilik saham terbesar, kelak utang itu akan dilunasi bersama oleh Grup Salim dan Nissin Food Products Co., perusahaan Jepang yang sudah mendunia itu. Sungguh suatu divestasi yang cermat dan saling menguntungkan.
Soalnya kemudian, yang menarik, adalah kontrol usaha yang kini berada pada sebuah perusahaan di luar negeri. Upaya semacam ini sudah dirintis sejak 1996-1997, ketika stabilitas politik di Indonesia diperkirakan akan terganggu, berhubung pemerintahan Soeharto mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhannya. Kecurigaan akan larinya modal ini bahkan sudah disindir-sindirkan sejak 1992, ketika Soeharto terpilih sebagai presiden untuk keenam kalinya. Sekitar waktu itu pula, Eka Tjipta Widjaya mencatatkan perusahaannya di bursa saham New York, begitu pula Sukanto Tanoto. Berdasar nilai investasi, lima besar pengusaha Indonesia yang menanamkan modal di luar negeri berturut-turut adalah: Eka Tjipta Widjaja, Liem Sioe Liong, Sukanto Tanoto, Mochtar Riyadi, dan Prajogo Pangestu.
Dari segi bisnis, langkah yang cemerlang. Pilihan waktunya pas, duit yang diraup banyak. Yang menimbulkan kontroversi agaknya adalah karena Indofood jadi besar berkat subsidi terigu. Dengan kata lain, berkat bantuan pemerintah Indonesia. Sekarang, modalnya dilindungi oleh sistem hukum yang lain. Tentu di sini kelangsungan usaha jadi terjamin. Bukan mustahil, pola divestasi ala Indofood akan diikuti oleh banyak perusahaan lain yang kini tinggal menunggu peluang dan kesempatan untuk menyeberang. Pilihan bagi Indonesia memang tak banyak—selama keadaan politik dan pemerintahan tidak menentu seperti sekarang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo