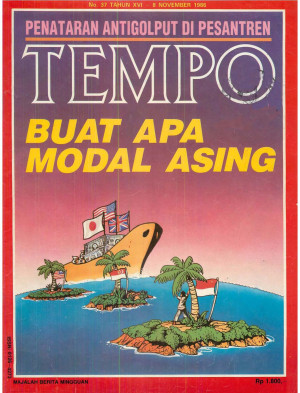YURIKO, lahir tahun 1910, berasal dari kaki Gunung Fuji, sepanjang tahun menggigil dan pegal linu, karena kerja keras. Pipinya seperti tomat. Dan, pantatnya penuh. Ia seorang Budha dan Shinto dan Konfusius sekaligus. Ia telan paham-paham itu tanpa banyak cingcong dan banyak periksa, pokoknya bisa hidup dengan perut terisi, dan arwah saat mati tidak ngelantur. Selaku, pengikut Budha, ia amat berkepentingan dengan keadaan sesudah mati. Sebagai pengikut Shinto, ia memuja wujud dan gejala alam. Selaku Konfusianis, ia menjaga harmoni dan etik. Dan, selaku Jepang? Ia maklum arti kemenangan angkatan laut negaranya atas Rusia tahun 1905, dan sepakat atas penyerbuan terhadap Taiwan, Korea, Manchuria, dan selatan Sakhalin. Negerinya sebetulnya kere, hanya bisa bernapas jika memperoleh bahan mentah dari luar, dan bisa menjual barang-barang produksinya. Setiap pagi ia memandang gunung yang bagaikan kipas terbalik itu, seraya berkata kepada diri sendiri, "Sepeser pun kau tiada harga jika pendudukmu begini-begini saja." Maka, Yuriko berangkat menjadi penghuni lokasi WTS Kembang Jepun di Surabaya, membawa serta dua perangkat kimono dan rok secukupnya beserta gincu, menjadi pelacur yang tak henti-hentinya tersenyum sembari membungkuk. Ia bukan pelacur sembarangan. Ia seorang putri Matahari Terbit, seorang nasionalis percaya diri, kupu-kupu pengumpul uang untuk dipindahkan ke negeri nun jauh di sana, dan sekaligus pengumpul keterangan dari para pejabat kolonial Belanda, yang tergolek di ranjang sesudah jasmaninya digencet habis-habisan. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, kata Yuriko. Negeri kere mesti kaya akal. Bunga sakura perlu makan, bahan baku, serta pasar. Tubuh Yuriko sudah melengkung ketika tentara Nippon menginjak negeri ini. Namun, ia puas. Puas sebagai nasionalis, dan puas selaku pelacur. Naomi, cucunya, lahir tahun 1950. Selain amat sadar akan jaminan Konstitusi 1947 tentang persamaan hak dengan lelaki, ia tidak seperti neneknya. Ia merasa tak ada urusan dengan Budha, Shinto, maupun Konfusius. Ia seorang sekuler. Sesekali Naomi mengunjungi kuil dewi matahari Ise, Meiji, dan Yasukuni. Tapi, tak lebih sekadar piknik sambil beli balon gas dan es loli. Gadis ini merasa cukup jadi anggota Soka Gakkai, agama baru yang tak peduli alam sesudah mati, melainkan bagaimana hidup sehat bebas kanker dan banyak duit, punya banyak relasi bukan malaikat melainkan direktur bank. Pemujaan animistis terhadap air terjun dan jeram serta bukit seperti dilakukan neneknya, kini berubah jadi pemujaan terhadap kalkulator dan cek. Naomi bukan seorang hipernasionalis yang militeristis, seperti moyangnya, melainkan seekor binatang ekonomi yang tak henti-hentinya menggigit apa saja yang tampak oleh mata dan tercium hidung. Ia membayangkan negeri-negeri di seberang lautan dengan meneteskan air liur, bertekad mengekspor apa saja mengeduk bahan baku dengan segala cara, menanam modal sebanyak-banyaknya, membujuk pejabat setempat sehabis-habisnya sampai semaput. Maka, Naomi pergi ke Bali selaku turis. Sesudah mengamati baik-baik potensi negeri dan aturan yang ada, Naomi (bukan melacur seperti neneknya) kawin dengan orang Bali. Cakrawala pun terbuka luas. Ia buka biro perjalanan, sehingga praktis 100 ribu wisatawan Jepang yang datang dalam setahun ke sana habis ditelannya. Berhubung turis perlu jalan-jalan, ia pun buka usaha transpor. Karena turis perlu tidur, ia pun buka hotel. Karena turis perlu makan, di samping buang air besar, ia pun buka restoran. Karena turis perlu oleh-oleh, ia pun buka toko seni. Karena turis kepingin lihat tari Legong, ia pun menghimpun penari dari pelbagai banjar. Kadang-kadang ia memang berpikir, akan habis tampaknya usaha turisme anak negeri. Khayal saja mereka mengharapkan tambah devisa dari turisme. Namun, Naomi tidak bisa lagi membendung nafsu memindahkan semua uang yang diperolehnya ke Jepang. Semboyan "dari Jepang kembali ke Jepang" sudah jadi darah dagingnya. Sedangkan pria Jepang yang tak mungkin kawin dengan pria Bali (tanpa timbulkan onar) ataupun dengan gadisnya, langkah ekonomi bukan berarti tertutup. Belum adanya UU Pokok Pariwisata yang melarang penanaman modal asing di sektor turisme, belum adanya kepastian tentang batasan kegiatan asing, mudahnya mengambil hati para pejabat merupakan lubang-lubang yang bisa dilalui tanpa bersusah payah. Empat juta tiap tahun pelancong Jepang berhamburan ke pelbagai negeri bukanlah jumlah yang sedikit. Bilamana urusan dan kebutuhan mereka bisa ditangani oleh warga Jepang di negeri tujuan, apa salahnya? Bilamana industri pariwisata di mana-mana dikuasai modal Jepang, langsung atau tak langsung, bukankah artinya yen keluar dari kantung kiri dan masuk ke kantung kanan ? Suatu hari raya "Nyepi" di Bali, kehidupan seperti berhenti. Naomi tidak bisa berhenti. Ia berangkat ke kaki Gunung Fuji. Ia nyekar di kubur nenek moyangnya. Naomi tidak menangis, bahkan tersenyum. Bangsa Jepang ini memang bangsa yang hebat. Dewa-dewa lama memang sudah tersingkir, tempatnya digantikan oleh dewa-dewa baru yang lebih maklum arti penting ekspor-impor serta paham ihwal perbankan yang berbelat-belit. Bahkan mereka pun memberi berkah restu bukan saja kepada turis-turis Jepang yang melancong ke mana angin bertiup, melainkan juga kepada tiap usaha bangsa senegeri yang menampung mereka ke mana pun mereka melangkah, di pantai Waikiki maupun Sanur. Ya, Naomi tersenyum. Seekor bangau terbang melintas, pertanda datangnya musim semi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini