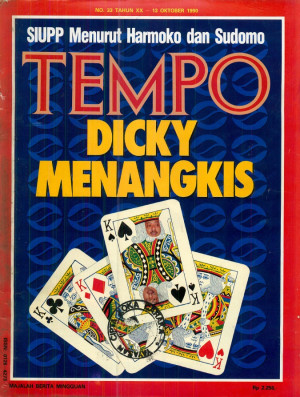"KEMER~DEKAAN~ adalah laut semua suara," kata Penyair Toto Sudarto Bachtiar, "Janganlah kau takut padanya." Bagi mereka yang hidup di tahun 195~0-an, nampaknya itu memang baris puisi yang tepat. Coba saja ingat kejadian ini: Sejak akhir tahun, kabinet jadi bulan-bulanan pengungkapan harian Indonesia ~aya dan Abadi. Akhirnya, 23 Februari 1952, Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo jatuh, dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Di zaman demokrasi parlementer, kabinet (waktu itu disebut "pemerintah") memang mudah jatuh dan berganti. Tapi betulkah pemerintah bisa ditumbangkan oleh pers ? "Secara langsung atau tidak langsung, pers telah membantu menggulingkan kabinet lama," tulis tajuk rencana Abadi dua hari kemudian. Memang kabinet Sukiman (Masyumi) tak sepenuhnya dijatuhkan berita koran. Sebagaimana tentunya, Nixon juga tak turun panggung cuma karena berita Washin~gton Post. Dalam hal kejatuhan Sukiman, jelas karena ia kehilangan dukungan dari partai-partai, terutama PNI. Sukiman dihantam karena membebek pada Amerika Serikat, bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif. Masa itu, Indonesia baru sewindu merdeka. Suasana tertekan di masa penjajahan ingin dilepaskan total. Maka, kritik sekali pun terhadap pemerintah, bahkan Presiden Soekarno -- rupanya tak jadi barang terlarang. Malah koran-koran berani mengecam Presiden Soekarno ketika ia kawin lagi dengan Nyonya Hartini. Perilaku pejabat yang kurang dianggap patut juga bisa dibongkar. Indonesia Raya, koran yang terkenal keras suaranya, misalnya, dalam edisi 14 Agustus dan 6 September 1956, menuding Menlu Roeslan Abdulgani telah menyelundupkan devisa ke Amerika Serikat. Hasilnya menarik. "Karena berita itu Roeslan diadili dan dihukum pengadilan, tapi dapat amnesti dari Presiden Soekarno," kata Mochtar Lubis, bekas pemimpin redaksi Indonesia Raya, kepada TEMPO, Senin pekan ini. Memang ketika itu sang Menlu sempat dihukum denda oleh Mahkamah Agung. Tetapi karena berita itu pula, Mochtar Lubis diajukan ke pengadilan. Ia dituduh menghina pejabat negara. Memang ketika itu pengadilan jadi ancaman wartawan. Tapi di zaman bebas itu bukan cuma pers yang merdeka berbicara. Tampaknya pengadilan cukup independen. Rosihan Anwar, 1961, dibebaskan oleh Hakim Sutidjan dari tuduhan menghina dua anggota DPR. Karena pengaduan kedua anggota DPR itu, Jaksa Agung memerintahkan agar Rosihan diadili. Tapi J. Naro (kini politikus) yang menjadi jaksa dalam perkara itu ~malah menuntut ~~agar Rosihan dibebaskan dari segala tuduhan. Wartawan memang dengan mudah dapat jadi semacam hero. Ketika Asa Bafaqih diadili dengan tuduhan membocorkan rahasia negara -- di pengadilan ia menolak membocorkan sumber beritanya -- sejumlah wartawan, calon wartawan dari akademi pers, dan buruh percetakan, mengadakan unjuk rasa bersimpati di pengadilan. Untung bagi almarhum Asa Bafaqih, Jaksa Agung Soeprapto mendeponir perkara itu dengan alasan: belum jelas apa yang dimaksud rahasia negara. Tapi tak berarti pers selamanya jadi semacam raja. Harian Merdek~, misalnya pernah dibredel beberapa hari karena berita sekitar peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika itu terjadi demonstrasi massa, dan sejumlah tentara mengarahkan senjata ke arah Istana Merdeka, minta agar Parlemen dibubarkan. Apalagi setelah Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante (MPR) di tahun 1958, dan "demokrasi terpimpin" berlaku, pers pun kian dikekang. Semua harus "mengabdi pada revolusi". Menjelang tahun 1965, akhirnya hanya pers pro-PKI yang berkibar. Amran Nasution
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini