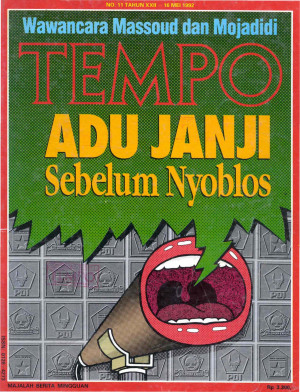KETIKA sekitar 3.000 orang yang mewakili 37 ormas Islam yang kebanyakan bernaung di bawah Golkar membacakan doa untuk Presiden Soeharto, beberapa pihak menyebut peristiwa ini sebagai "doa politik". Seandainya memang begitu, lalu apa soalnya? Kiai Haji Quraish Shihab, dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menulis di harian Pelita, tentang kaitan antara doa dan khalifah atau kepala negara. Ia mengutip ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal (yang hidup pada abad ke-8), yang bisa ditafsirkan mengesahkan doa untuk kepala negara: "Seandainya kita mempunyai doa yang (kita ketahui) makbul, niscaya itu kita gunakan mendoakan kepala negara." Yang jelas, dalam sejarah Islam, doa yang sifatnya politis bukan hal yang jarang. Misalnya saja bagaimana khalifah Muawiyah memanfaatkan doa untuk mengukuhkan kekuasaannya. Sayangnya, Muawiyah tak menganjurkan doa yang lurus mendukung kekhalifahannya. Tapi, yang dianjurkannya adalah agar umat pendukungnya mendoakan supaya musuh-musuh mereka -- kaum Alawy (Syiah), pengikut Ali bin Abi Thalib -- celaka. Ketika itu di pihak kaum pendukung Ali pun menganjurkan dibacakannya doa agar Muawiyah dan pengikutnya celaka. "Mereka saling melaknat," kata cendekiawan muslim Nurcholish Madjid. Suasana negatif itu berubah di masa khalifah Marwan bin AlHakam (684-685). Ketika itu doa-doa yang dibacakan adalah doa-doa positif. Maksudnya, doa-doa untuk mempertahankan kekuasaan. Khalifah, gubernur, atau qadli yang biasanya menjadi khatib salat Jumat mulai membacakan doa yang memohon agar seorang penguasa yang mereka dukung tetap dalam posisinya. Doa tak lagi mengutuk lawan. Mode membacakan doa bagi penguasa yang mereka dukung terus berlanjut. Bahkan waktu itu kelompok-kelompok agama dari kalangan tasawuf, fikih, dan ahli ilmu kalam bersaing, masing-masing mencari penguasa yang menurut mereka layak didukung, kata Dien Syamsuddin, Ketua Pemuda Muhammadiyah yang mengkaji masalah agama dan politik. Tapi, doa negatif atau positif hanya untuk pihak tertentu rasanya masih kurang enak. Setidaknya itu dirasakan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720). Maka, Umar bin Abdul Aziz lalu mengintroduksi doa yang sekaligus menyebut nama empat khalifah: Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Dengan kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz itu tampaknya selesailah permusuhan antara Muawiyah dan Ali, setidaknya tak ada lagi acara saling mendoakan agar musuhnya celaka. Bahkan oleh Umar bin Abdul Aziz khotbah Jumat ditambah kalimat, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian berbuat adil dan baik" (Q.S. An-Nahl: 90). Kebijaksanaan politis Umar bin Abdul Aziz ternyata diterima semua pihak, dan itu masih berlangsung hingga kini, bergaung di sejumlah masjid. Umar bin Abdul Aziz berhasil mengubah doa politik lebih berbau tradisi. Lihat saja di sejumlah masjid di Jakarta yang masih berbau suasana lama, atau katakanlah itu masjid Betawi. Doa buat empat khalifah masih selalu dibacakan, dan tentu saja sifatnya bukan lagi politis zaman kekhalifahan sudah tutup. Doa itu bila dibacakan juga sekarang tentulah sifatnya sekadar semacam catatan sejarah, bukan politik. Mungkin analog dengan kebijaksanaan itu, di Indonesia ada beberapa khatib yang dalam membacakan doa dalam salat Jumat kemudian "mendoakan negara", kata Nurcholis. Khatib yang muncul di Masjid Istiqlal Jakarta, misalnya, hampir selalu mengucapkan doa keselamatan negara ini. Jadi, bagaimana mendudukkan doa di Gedung Granada itu? Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia K.H. Ibrahim Hosen sendiri terus terang mengatakan, "Doa kadang kala tak bisa dipisahkan dari politik." Yang dimaksudkannya tentulah doa yang ada hubungannya dengan negara. Menurut Quraish Shihab, dosen IAIN Syarif Hidayatullah itu, doa yang dilakukan untuk meraih keuntungan politik jelas ada. "Itu boleh-boleh dan sahsah saja," katanya. Sebagaimana dalam artikelnya di harian Pelita, faktor terpenting adalah ketulusan dan keikhlasan para pendoanya. Memang ada pendapat yang agak berbeda. Ini datang dari Jalaluddin Rakhmat dari Yayasan Mutahhari, Bandung. Intelektual muslim ini berpendapat, doa yang berbau politik rasanya tak begitu enak. Apalagi dilakukan dalam sebuah upacara resmi dengan suara keras, ada pengumpulan tanda tangan pula. Yang dikhawatirkan Jalaluddin Rakhmat adalah ekses dari doa politik itu. Jangan-jangan "nanti ada salat hajat untuk, misalnya, memenangkan Golkar," katanya. Tampaknya diperlukan rasa proporsional agar doa politik tak melenceng. Batasnya, mungkin itu tadi, yang disebutkan oleh Quraish Shihab, keikhlasan dan ketulusan. Masalahnya, bukankah agama dan politik dalam Islam, kata Nurcholish Madjid, "memang menyatu sejak awalnya." Agus Basri, Wahyu Muryadi, Siti Nurbaiti (Jakarta), Ida Farida (Bandung)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini