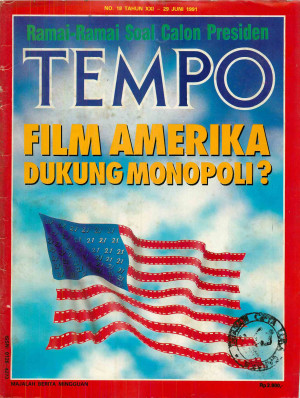Bila Idul Adha punya dua dimensi, dimensi sosialnya bisa diatur menurut zaman. Lalu, dimensi spiritualnya, ketaatan pada Allah itu, bisakah diperoleh dengan bukan hewan kurban? TIAP Lebaran Haji, di Arab Saudi, daging kambing bertimbun, dan sebagian membusuk, mubazir. Itu karena banyaknya hewan kurban, hingga tak sempat dibagikan pada yang membutuhkan. Kemubaziran ini berlangsung sampai awal 1980-an. Pada tahun 1982 sebuah gagasan jitu dilaksanakan oleh pemerintah Saudi. Penyembelihan dilakukan dengan peralatan modern, dipusatkan, dan dagingnya dijadikan daging kalengan. Dengan pengalengan yang tahan waktu itu, daging tak cuma dibagikan pada fakir miskin di Saudi, tapi bisa juga dikirimkan gratis ke negeri-negeri yang membutuhkan. Misalnya untuk para fakir miskin dan pengungsi di Yordania, atau Pakistan, atau Bangladesh, atau Ethiopia. Adapun pembelian hewan kurban cukup dengan hanya membeli kupon di tempat-tempat tertentu di Jeddah sampai Mekah, di dekat para jemaah berada. Dengan cara itu, ada anggapan panggilan Nabi Ibrahim sekitar 3.700 tahun lalu dipenuhi secara komplet. Yakni dimensi vertikalnya- keikhlasan berkorban- dan dimensi sosialnya- bersedekah untuk yang papa, kata K.H. Ma'ruf Amin, 48 tahun, Khatib Syuriah Pengurus Besar NU. Bukankah itu, yang terjadi ketika Ibrahim yang hanif (pasrah dan taat) itu, diperintah Tuhan lewat mimpi untuk menyembelih putranya, Ismail? Bertahun-tahun sejarah Idul Adha tak berubah: ketika hewan kurban masih mudah diperoleh bagi yang mampu, dan tempat penyembelihan masih terbuka luas. Dan ketika dimensi sosial Idul Adha menjadi masalah dengan bertumpuknya daging yang tak terbagikan, di Arab Saudi, cara mengatasinya pun ditemukan. Lalu, bagaiamana dengan dimensi vertikalnya? Kini, coba bayangkan, seandainya nanti, mencari hewan kurban tak lagi mudah, bagaimana melaksanakan ibadah ini? Muhammad Atho Mudhar, 42 tahun, seorang doktor lulusan University of California, Los Angeles, tak menjawab langsung masalah itu. Ia malah melihat sesuatu yang lain, sebelum hewan kurban sulit didapat. Di Idul Adha kemarin, ia berbisik pada temannya, "Kalau Islam terus dilambangkan dengan penyembelihan hewan kurban, memang mestinya Islam itu untuk masyarakat berkembang, bukan masyarakat maju." Ada yang mesti dipikirkan kembali, kata dosen pascasarjana IAIN Jakarta ini. Ia lalu menengok pada ayat Quran yang selama ini jadi pegangan para ulama, ayat yang berkaitan dengan penyembelihan kurban. Yakni Surat Al Kautsar. Dalam surat pendek tiga ayat itu, dalam ayat kedua ada kata wanhar, yang oleh kebanyakan ulama, termasuk K.H. Sahal Mahfudz, Rais Syuriah PB NU, diartikan sebagai menyembelih binatang. Padahal, kata Atho, ada tujuh sahabat Nabi yang membantahnya. Tujuh sahabat itu mengartikannya, dalam salat, setelah takbir, angkatlah kedua tanganmu setinggi kuduk. Jadi, ayat itu tidak ada kaitannya dengan kuduk kambing. Ia menilai, ini merupakan kekeliruan dalam penafsiran, yang terlalu memihak pada tradisi. Sebetulnya, untuk masyarakat sekarang tidak perlu lagi memotong hewan, kata Atho. Karena hewan itu, katanya, lambang investasi kekayaan bagi masyarakat pasturalis (penggembala). Lambang itu dalam masyarakat petani adalah lumbung padi. Pada masyarakat modern adalah Tabanas. Jadi, bagi Atho, memotong hewan pada masyarakat penggembala waktu itu sama halnya membuka tabungan di zaman sekarang. Ini berarti, kata dosen yang sering berbicara tentang pembaruan di bidang fikih itu, mengganti hewan kurban dengan bentuk uang, sah. Dengan begitu, katanya, ajaran Islam bisa diterapkan di negara maju yang aturan kesehatanya sudah tinggi. Sebab, darah tidak lagi berhamburan di mana-mana, yang berakibat tidak baik bagi kesehatan. Selama ini memang belum ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam soal pemotongan hewan ternak untuk kurban. Bila itu ada, hanya terbatas dalam menentukan mana yang afdhal bagi seseorang, mengorbankan sepertujuh unta, sepertujuh sapi, ataukah seekor kambing. Pendapat Atho, dapat dipastikan, akan mengundang banyak ulama yang tak sependapat dengannya. Jalaludin Rakhmat, misalnya. Intelektual Islam yang bermukim di Bandung ini berpendapat bahwa penyembelihan hewan kurban itu merupakan simbol ketaatan pada Allah, bukan simbol menyantuni fakir miskin. "Itu ibadah, yang hikmah sampingannya menyantuni orang miskin," katanya. Memelihara simbol, tambah Jalal, berarti memberikan nilai pada ketaatan. Sedangkan H. Asymuni A. Rahman, Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dengan tegas mengatakan bahwa perintah menyembelih hewan kurban itu sudah jelas nashnya. Misalnya, pada surat pendek Al Kautsar, orang harus berkorban karena Allah telah memberi nikmat yang banyak. Bentuk ibadah penyembelihan kurban, kata fukaha ini, harus seperti yang dijelaskan dalam Surat Ash Shafaat ayat 102-108. Pada Surat Ash Shafaat ayat 108, kata Asymuni, Allah menjelaskan bahwa bentuk yang dilaksanakan Ibrahim- menyembelih Ismail yang diganti dengan hewan kurban- diabadikan Allah untuk umat-umat yang akan datang. Memang, bila ketaatan itu yang diminta, seberapa beratkah kini bagi seorang konglomerat menyembelih seekor sapi (dan ini pun tak usah ia lakukan sendiri) dibandingkan ujian bagi Nabi Ibrahim, yang harus menyembelih sendiri Ismail, putranya? Mungkin bukan pada soal berat-ringannya melaksanakan perintah, melainkan pada hakikatnya, mencoba menghayati pengalaman Nabi Ibrahim a.s., insya Allah. Julizar Kasiri, Wahyu Muryadi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini