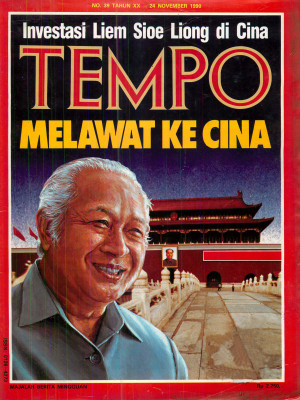SESUNGGUHNYA Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka segeralah dirikan salat karena-Nya. Mereka yang ingkar sebenarnya telah memutuskan hubungan. (Q. Al Kautsar). DI antara kesibukan lalu lintas dan toko-toko sepanjang Jalan Dongsimen Selatan yang tak begitu lebar, di sebuah halaman yang tak begitu luas, ada kesibukan lain. Sejumlah lelaki 50-an tahun, bercelana dan berjas Cina abu-abu dan berpeci putih, berderet menyambut para tamu yang berassalamualaikum. Itu memang halaman sebuah masjid, dan kesibukan di Jumat siang pekan lalu, setelah salat Jumat, adalah penyerahan sumbangan berupa uang 30 ribu dolar Amerika, empat Quran, dan sebuah kaligrafi Arab berupa surat Al Kautsar. Itulah dana pribadi dari Presiden Soeharto yang diterimakan pada Persatuan Umat Islam Beijing lewat ketuanya, Haji Saleh An Shiweix, di Masjid Dongsi. Di masa republik yang komunis ini mulai menggelindingkan keterbukaan, salah satu acara perjalanan Soeharto ke RRC yang pertama kalinya ini tampaknya punya banyak makna. "Kami bahagia sekali Presiden Soeharto bersedia datang ke masjid ini," kata Haji Saleh kepada TEMPO, dua hari sebelum kunjungan. "Indonesia negeri yang mayoritasnya Islam, karena itu tentu banyak manfaatnya bagi kami." Di negeri yang Islamnya berkembang bebas, mungkin ucapan itu terdengar sebagai basa-basi. Namun, di RRC, diucapkan oleh pimpinan sebuah masjid yang sudah lebih dari 500 tahun berdiri, dan mampu bertahan dari serangan Pengawal Merah di masa Revolusi Kebudayaan, itu kata-kata yang jauh gemanya, dan bermakna ganda. Haji Saleh mungkin hendak menekankan umat Islam RRC tak terpencil dan mendapat perhatian dari masyarakat Islam dunia. Dengan kata lain, kekuatan Islam di RRC bisa lebih besar dari kenyataannya. Kekuatan yang penting karena sejak Revolusi Kebudayaan dihancurkan, 1976, dan kemudian undang-undang kebebasan beragama dihidupkan lagi. "Namun, masih banyak masjid di daerah yang belum berfungsi," tutur Haji Abdurahim Amin, Wakil Ketua Perhimpunan Islam se-Tiongkok. Sering Perhimpunan yang berkantor pusat di kawasan Masjid Niujie, masjid tertua di Beijing, itu harus mengirimkan orangnya, untuk merundingkan sebuah pabrik atau hotel yang dahulunya masjid, untuk dikembalikan fungsinya. Sebenarnya, hubungan antara umat Islam dan pemerintah (baik di masa kerajaan maupun di masa pemerintahan komunis) di Tiongkok memang tak konsisten. Meski Islam masuk Tiongkok sudah pada tahun 650-an, dari sekitar semilyar penduduk negeri luas ini hanya kurang dari 2% yang muslim -- sekitar 16 juta. Pada abad ke-13 ketika Dinasti Yuan berjaya, banyak pejabat masuk Islam. Bahkan dinasti berikutnya, Ming, menyumbangkan banyak masjid. Namun, pada waktu itu pun sudah ada dualisme. Dinasti Ming pun dikenal dengan sikapnya yang menindas suku Hui yang muslim untuk tak memakai pakaian, bahasa, dan nama warganya sendiri. Maka, perkembangan Islam seperti diulur dan dikekang berbarengan -- alias mandek. Dalam zaman Dinasti Qing, mula-mula Islam mendapat tempat yang baik. Namun, pemberontakan suku Hui pada abad ke-18 mengubah sikap Dinasti Qing: penindasan pada Islam berlangsung intensif. Barangkali itu menjelaskan mengapa baru pada abad ke-19 Quran dengan tafsir bahasa Cina pertama kali ditulis. Sebelumnya, Quran diajarkan secara lisan. Toh, waktu itu tafsir itu belum sepenuhnya lengkap -- baru beberapa surat. Tafsir Quran lengkap baru dibuat pada 1920-an, justru ketika Tiongkok sudah jadi Republik dan waktu itu terjadi perang segitiga -- pendukung kembalinya feodalisme, kaum nasionalis, dan komunis. Kemenangan komunis pada 1949, ternyata, tak langsung mematikan perkembangan Islam. Bahkan empat tahun setelah berdirinya Republik Rakyat Cina, lahir organisasi Islam nasional pertama. Setahun kemudian berdiri madrasah pertama di Beijing. Madrasah inilah yang menyiapkan imam-imam masjid untuk seluruh Cina. Ketika Revolusi Kebudayaan meletus, 1966, masa suram pun kembali memaksa umat muslim Cina tiarap. "Waktu itu umat Islam jadi kelompok tertutup," tutur Haji Abdurahim, 56 tahun. Masjid kosong karena umat tak berani mendatanginya. Itu soalnya bila kemudian rumah ibadah itu banyak diambil alih oleh Pengawal Merah dan diubah menjadi apa saja, semau mereka. Memang, di daerah barat laut, di Xinjang, yang mayoritas warganya muslim, sejumlah masjid masih hidup sebagai pusat kegiatan umat Islam. Namun, di Beijing, di ibu kota yang dekat dengan kekuasaan, praktis ibadah hanya dilakukan oleh umat Islam di rumah masing-masing. Hanya dua masjid bertahan: Niujie dan Dongsi karena di situ banyak umat Islamnya. Kawasan Niujie memang semacam kauman di Solo atau Yogyakarta, yakni kampung Islam. Toh, menurut Haji Abdurahim dan Haji Saleh, hanya pada salat Jumat orang berani datang ke masjid. "Pengawal Merah tak berani mengganggu bila kami berkumpul dalam jumlah banyak," kata Abdurahim, bapak dua anak. "Untuk salat subuh dan lain-lain, orang tak berani ke masjid." Setelah RRC menjalankan politik terbuka, pelan-pelan masjid kembali berfungsi. Namun, dari 16 juta muslim di seluruh Cina kini, "kami akui sebagian besar memang generasi tua." Umat dan panitia yang menyambut Presiden Soeharto di Masjid Dongsi umpamanya, dari sekitar 30 orang tak sampai 10 orang yang berusia 30 tahun ke bawah. Madrasah Ceng Da, yang mendidik calon guru Islam, untuk sementara ini istirahat. Madrasah yang dikelola Masjid Dongsi itu belum punya siswa. Lalu Institut Islamiyah di Masjid Niujie, yang sudah lama berdiri, yang mestinya mencetak ulama untuk kemudian bekerja di masjid-masjid seluruh Cina, gagal membangkitkan cara pendakwah itu. Sejak institut itu dibuka lagi, awal 1980-an, sebagian besar lulusannya tak kembali ke daerah tempat mereka berasal. "Setelah pandai berbahasa Arab, lulusan Institut Islamiyah memilih bekerja di perusahaan patungan Cina dan Timur Tengah," kata Haji Abdurahim sambil tertawa, hingga ruang tamu Perhimpunan Islam se-Tiongkok yang hanya diisi tiga kursi dan sebuah sofa, sebuah meja, dan sebuah almari, tak terasa kosong sebentar. Mulai tahun lalu, Abdurahim punya akal. Para siswa di institut ini tak dipungut bayaran. Kemudian, biaya hidup dan pondokan diharuskan ditanggung masjid yang mengirim. Ini kira-kira seperti sistem beasiswa yang mengikat. Setelah lulus (pendidikan berjalan empat tahun), mereka diharuskan kembali ke masjid masing-masing. Selain itu, institut kini juga menerima murid di atas 50 tahun, dengan crash program dalam satu tahun. Diharapkan dengan cara itu kebutuhan ulama bisa dipenuhi. Masalahnya, angkatan sistem baru itu, ada sekitar 60 orang, belum diuji keteguhan keulamaannya -- mereka belum lulus. Seandainya mereka juga lari, karena tak jelas sanksi apa yang bisa dijatuhkan kalau mereka tak memenuhi perjanjian, apa yang bisa diperbuat oleh pihak masjid dan institut? Namun, keuletan pihak masjid memang harus diakui. Masjid Dongsi dan Niujie bertahan hidup hanya dari sumbangan umat, keuntungan usaha, dan sekali-sekali datang bantuan pemerintah dan dari luar negeri. "Yang cukup kontinu bantuan dari Arab Saudi dan Libya," tutur Abdurahim. Adapun soal usaha, sejak keterbukaan dicanangkan oleh Deng Xiaoping, masjid diberi hak membuka toko dan rumah makan. Misalnya, Masjid Dongsi punya toko daging kambing, antara lain di sebelah kiri bangunan masjid. Toko ini buka dari pagi sampai sore, dan selalu ada yang antre. Rumah makan Islam kini mendapat tempat di masyarakat Beijing, yang jumlahnya kini sekitar 10 juta itu. Ada dua atau tiga rumah makan Islam di Beijing, yang tak cuma dilanggani oleh 200 ribu umat di Beijing, tapi juga yang nonmuslim. "Para perantau dari Indonesia, meski bukan Islam, suka makan di rumah makan Islam," kata seorang pemilik rumah makan kecil, yang lahir di Semarang, Indonesia, yang mengaku sekali-sekali makan di restoran Islam di kawasan pertokoan Wangfuying. Benar. Di deretan pertokoan teramai, di Jalan Wangfuying, bersebelahan dengan toko buku bahasa asing, di lantai 4, adalah sebuah rumah makan Islam. Masuk di restoran ini, serasa tak berada di Beijing. Ornamen di dinding kuningnya adalah bentuk kubah masjid berwarna hijau. Para pelayan wanita yang berseragam biru tak tampak seperti orang Han. Mereka memang gadis-gadis suku Uighur, berhidung mancung bak Arab, tapi berkulit pualam. Seorang pelayan menyambut ucapan salam dengan fasih, "Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu menu pun dibawa ke meja. Teh susu kambing sate ayam sate kambing kari ayam kari kambing juga ada masakan terpopuler di kalangan turis asing di Cina, masakan bebek peking. Rumah makan Islam di Wangfuying ini memang belum lama. Bila kemudian cepat dikenal, bisa jadi harganya yang termasuk murah. Segelas es teh di hotel berbintang 4 bisa sampai 7 yuan. Di rumah makan di luar hotel, setidaknya segelas es teh itu 2 yuan. Namun, di rumah makan Islam ini, segelas teh susu kambing cuma setengah yuan (1 yuan: Rp 407). Adakah tanda-tanda kembali hidupnya Islam di Cina? Dahulu, di awal 1980-an, tutur Abdurahim, orang-orang Hui atau Uighur yang biasanya muslim tak suka mengenakan topi putih sebagai identitas muslimnya bila berjalan-jalan di luar "kauman". Kini, di sebuah sore, ketika banyak orang pulang kerja, di pertokoan Wanfuying, ke mana mata memandang lautan manusia yang bergegas pulang atau keluar masuk toko itu, pasti ada dua-tiga, atau lebih, peci-peci putih. Malah, dua gerobak kaki lima di depan toko serba ada terbesar di Beijing, di kawasan pertokoan tersebut, yang menjual es krim dan satunya menjual sate, mengenakan peci putih. "Assalamualaikum," dan langsung ada jawaban, "Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh," biasanya, meski salam diucapkan pendek, jawaban selalu komplet. Komunikasi hanya sampai di situ karena hambatan bahasa. Ketika magrib, dalam jarak sekitar 1 km dari Masjid Dongsi, memang sudah tak terdengar azan. Seruan salat tanpa pengeras suara memang lenyap ditelan derap pejalan kaki, kayuhan penunggang sepeda, atau deru mobil-mobil yang memacetkan lalu lintas. Namun, bagi mereka yang mau mencari, di kota hampir 17.000 km (lebih dari 20 kali luas DKI Jakarta), ada saja bau Islam di sana-sini. Tiba-tiba saja, di satu warung kaki lima di sebuah pasar bebas, pemiliknya memasang nama warungnya dengan huruf Arab. Dalam statistik pun napas Islam terasa adanya. Di Beijing kini ada 56 masjid, dan di seluruh RRC ada 23.000 masjid besar dan kecil. Tahun-tahun sebelumnya jemaah haji dari Cina yang sejak awal 1980-an dikoordinasi oleh Perhimpunan Islam se-Tiongkok di Niujie (dulu jemaah mendapat visa haji di Pakistan) hanya ratusan orang, tetapi tahun lalu tercatat 2.000 jemaah. Itu termasuk jemaah kelas menengah, dengan naik pesawat bertiket pulang balik seharga US$ 2.000. Lalu, sejumlah pejabat adalah muslim yang tak perlu bersembunyi lagi bila mau menjalankan salat atau puasa. Syaifuddin, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat, adalah Islam. Juga Ketua Komite Urusan Bangsa, yang jabatannya setingkat dengan menteri, bernama Ismail Achmad, dari suku Uighur. Institut Islamiyah di seluruh RRC kini berjumlah sembilan buah (termasuk dua di Beijing). Semangat keterbukaan, termasuk dalam beragama, tampaknya akan terus merebak di Cina. Bambang Bujono, Linda Djalil (Beijing)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini