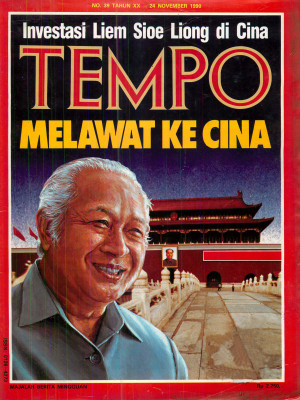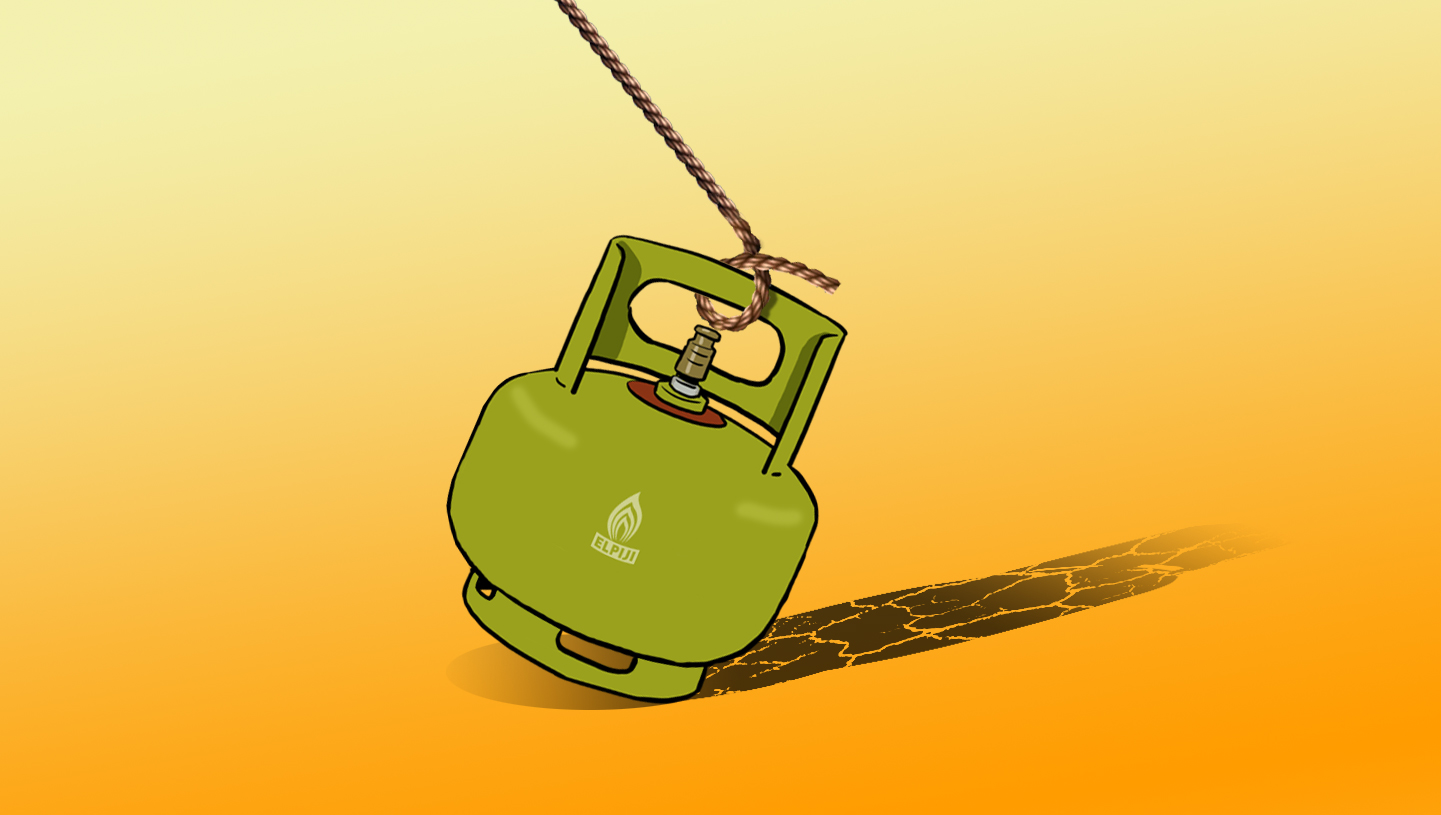SEJAK hubungan diplomatik RI-RRC pulih, banyak orang Indonesia, yang pri maupun nonpri, khawatir bahwa ini akan menyebabkan orang Tionghoa di Indonesia berkiblat ke tanah leluhur lagi. Salah satu buktinya: ketika Asian Games diadakan di Beijing baru-baru ini, ribuan WNI keturunan Tionghoa mendaftar untuk menjadi supporter. Apakah benar bahwa dengan pulihnya hubungan diplomatik, mendadak orang Tionghoa di Indonesia menjadi lebih condong ke tanah leluhurnya? Apakah ini akan menghambat pembauran keturunan Tionghoa di Indonesia? Sebetulnya masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak merupakan sebuah kelompok yang homogen. Para ilmuwan mengakui bahwa orang Tionghoa di Indonesia terdiri dari peranakan dan totok. Peranakan Tionghoa adalah keturunan imigran yang sudah lama bermukim di Indonesia dan banyak yang telah kawin dengan pri, terutama sebelum abad ke-19, selagi wanita Cina masih langka di Hindia Belanda. Kelompok peranakan ini tidak lagi menguasai bahasa leluhurnya dan menggunakan bahasa setempat atau bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Kebudayaan mereka itu merupakan suatu sintesis antara kultur Cina dan lokal. Secara individu, ada peranakan yang kemudian terlebur ke dalam tubuh penduduk pri dan lenyap, tapi secara kelompok, Tionghoa peranakan masih terpisah dari pri. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ini, banyak imigran baru secara besar-besaran datang dari Daratan Cina. Mereka masih memiliki kebudayaan leluhurnya, masih berbahasa Cina, dan tidak lagi berbaur karena besar jumlahnya dan juga adanya wanita Tionghoa. Pendatang baru ini, dan generasi kedua, akhirnya membentuk masyarakat totok yang lain daripada masyarakat peranakan. Sejak krisis ekonomi dunia pada 1929, imigrasi masal dari Daratan Cina berhenti, tapi masih saja ada imigran baru yang datang ke Hindia Belanda, walau jumlahnya tidak besar. Jadi, sebelum merdeka, di Indonesia terdapat dua macam masyarakat Tionghoa yang berbeda, yaitu masyarakat peranakan yang berbahasa Indonesia dan masyarakat totok yang berbahasa Cina. Kedua kelompok ini tetap hidup sampai sekarang, meski jumlah totok semakin berkurang dan jumlah peranakan semakin bertambah. Salah satu sebabnya adalah berhentinya imigrasi bangsa Tionghoa ke Indonesia sama sekali. Sebelum Perang Dunia II, keluarga peranakan yang agak mampu mengirimkan anak-anaknya ke sekolah Belanda, sedangkan yang miskin menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah bahasa Cina atau sekolah Melayu. Mereka yang sekolah bahasa Cina mengalami semacam pen-Cina-an kembali. Melalui sekolah Cina, pers Cina, dan organisasi Cinalah masyarakat totok di Indonesia berhasil mempertahankan kebudayaan Cinanya. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia tidak segera menjalankan kebijaksanaan politik pembauran. Baru tahun 1950-an politik, pembauran ini dilaksanakan. Berangsur-angsur Pemerintah melarang WNI keturunan Tionghoa masuk sekolah Tionghoa. Hanya anak-anak WNA yang boleh sekolah Cina. Sejak zaman Orde Baru, semua sekolah Cina ditutup, jadi anak WNI asing dan yang s-tateless (tanpa kewarganegaraan) hanya bisa mengirim anak-anaknya ke sekolah Indonesia swasta. Ini mempercepat proses Indonesianisasi anak-anak Tionghoa di Indonesia. Sebetulnya sejak berdirinya Orde Baru, kebijaksanaan pembauran ini ditingkatkan. Selain semua sekolah Cina ditutup, semua surat kabar Cina pun dibredel (koran Harian Indonesia yang setengah Cina setengah Indonesia tidak bisa dipandang sebagai surat kabar Cina). Di samping itu, semua organisasi Cina yang bersifat politik dan sosial pun dibubarkan. Jadi, ketiga institusi yang menunjang masyarakat totok itu tidak lagi berfungsi di bumi Indonesia. Akibatnya: masyarakat Tionghoa di Indonesia makin bercorak Indonesia. Anak-anak totok yang lahir sesudah tumbangnya pemerintahan Soekarno juga mengalami peranakanisasi dan Indonesianisasi. Peraturan ganti nama yang menganjurkan WNI keturunan Tionghoa untuk mengindonesiakan namanya telah membuat orang Tionghoa generasi muda menjadi lebih Indonesia. Namun, masyarakat Tionghoa tetap majemuk. Di Jawa, orang Tionghoa umumnya telah menjadi peranakan, tapi di luar Jawa proses Indonesianisasi itu rupanya tersendat-sendat, karena umumnya mereka itu adalah pendatang baru (dibanding dengan peranakan Jawa), sedangkan pola pemukiman juga berlainan: mereka hidup terasing dari pri. Kondisi pembauran tidak seperti di Jawa. Sekarang ini, biarpun mayoritas orang Tionghoa boleh dikatakan sudah menjadi peranakan, Tionghoa totok, meskipun merupakan minoritas, masih belum lenyap. Mereka adalah imigran generasi pertama dengan anak-anak mereka yang dulu berpendidikan Tionghoa. Sebetulnya, orang-orang yang masih berkebudayaan totok inilah yang sukses dalam bisnis. Di sini bukan tempatnya untuk membahas kiat sukses mereka. Yang perlu dicatat di sini: Tionghoa totok inilah yang lebih unggul dalam bidang bisnis ketimbang peranakan. Kebanyakan tokoh konglomerat Indonesia masuk golongan totok. Yang perlu dijelaskan di sini, bukan semua orang Tionghoa di Indonesia warga negara. Dua puluh tahun yang lalu, kira-kira satu juta orang Tionghoa di Indonesia masih berwarga negara asing, dan kini hanya 320.000 yang masih belum memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dengan kata lain, orang-orang ini selama belum memiliki kewarganegaraan adalah warga negara RRC, dan RRC bisa mencampuri urusan mereka kalau dianggap menguntungkan negara tersebut. RRC, yang kini sedang membangun ekonominya, telah mengatakan bahwa Beijing tidak akan lagi mencampuri urusan orang Tionghoa yang bukan WN RRC, tetapi adalah rahasia umum bahwa RRC masih memerlukan kapital, investasi, dan tenaga ahli dari luar. Beijing mengharapkan Tionghoa perantau bisa memberikan sumbangan dalam hal ini. Namun, respons orang Tionghoa dari negara-negara ASEAN berbeda-beda. Umumnya tanggapannya tidak sehangat yang diharapkan. Tidak banyak ahli keturunan Tionghoa dari negara ASEAN yang ingin "berbakti kepada tanah leluhur". Kecuali dari Singapura, investasi langsung dari negara ASEAN masih kecil sekali, terutama dari Indonesia. Namun, tidaklah diketahui apakah nanti dengan lebih terbukanya sistem ekonomi di RRC, investasi itu akan bertambah. Mungkin saja orang Tionghoa dari kawasan ini akan menanam modal kalau ada keuntungan yang bisa mereka tarik. Tetapi ini hanya terbatas pada usahawan yang berskala kakap, dan mereka itu sangat kecil jumlahnya. Apakah investasi di negeri leluhur berdasarkan sentimen primordial atau pertimbangan bisnis semata-mata? Ini sukar dijawab, tapi yang pasti, pengusaha dan pedagang tidak akan menanam modal kalau tidak untung. Bagi mayoritas orang Tionghoa, apakah mereka akan berduyun-duyun ke negara leluhurnya? Bagi yang lahir di Cina, pulihnya hubungan diplomatik Jakarta-Beijing membuka kesempatan untuk meninjau tanah kelahirannya secara terbuka. Dulu bukan tidak ada, tapi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Umumnya mereka hanya mau meninjau dan tidak berniat menetap di sana. Sedangkan orang Tionghoa yang sudah terbaur, yaitu peranakan, kurang begitu tertarik. Di antara mereka, mungkin saja ada yang ingin meninjau tanah leluhurnya. Tetapi, lain daripada totok yang umumnya lahir di sana, bagi para peranakan, RRC adalah bumi asing. Kunjungan mereka ke negara leluhur lebih merupakan turis asing, bukan "pulang kampung". Peranakan tidak akan kerasan tinggal di sana karena kultur dan nilai mereka sangat berbeda. Entah berapa banyak bekas huaqiao dari Indonesia yang hijrah ke Hong Kong dan Macao selama 30 tahun ini. Banyak lagi yang ingin keluar kalau mereka ada kesempatan. Padahal, eksodus ini juga terjadi di kalangan penduduk Cina asli. Apakah kunjungan ke Bumi Naga di utara akan mentransformasikan mereka dari peranakan menjadi totok kembali? Saya kira ini tidak mungkin selama mereka hidup di bumi Indonesia. Karena di Bumi Burung Garuda, institusi-institusi yang mustahak yang bisa menunjang masyarakat totok itu sudah tiada lagi. Tidaklah sukar diterka bahwa masyarakat Tionghoa akan menjadi lebih Indonesia dari masa ke masa. Namun, mereka itu masih mempunyai identitas peranakan. Dengan runtuhnya teori melting pot dan menjalarnya "demam mencari akar" (in search of roots), banyak kelompok etnis mulai timbul kembali. Di kalangan peranakan di Indonesia, ada keinginan untuk mengetahui kebudayaan dan asal-usul mereka. Tidaklah mengherankan, akhir-akhir ini banyak buku cerita Cina yang diterbitkan. Tetapi, yang menarik, buku-buku itu dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks "pencarian akar", mungkin ada peranakan yang ingin ke negara leluhur-nya untuk menelusuri jejak nenek moyang mereka. Sebetulnya ketika kita membicarakan hubungan tanah leluhur dengan peranakan, persoalan yang fundamental ialah identitas peranakan Tionghoa Indonesia. Apakah peranakan Tionghoa yang berwarga negara Indonesia orang Cina atau Indonesia? Ada yang mengatakan bahwa mereka orang Indonesia keturunan Cina. Ada yang berpendapat bahwa mereka disebut saja orang Indonesia. Kalau mereka melawat ke RRC, apakah mereka masih akan disebut huaqiao alias warga Cina yang merantau oleh negara leluhurnya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini