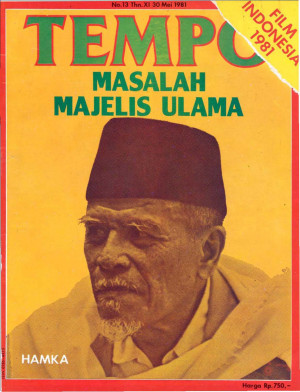MENDUNG menggantung di puncak-puncak kelenteng. Dan enam belas
tokoh Khonghucu, dipimpin ketua umum organisasi mereka yang
disebut Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)
menemui Fraksi Karya Pembangunan DPR 19 Mei kemarin. Mereka
mengadukan nasib.
Dalam surat yang mereka bacakan di hadapan para wakil Golkar
itu, disebutkan berbagai hambatan dalam pengembangan keagamaan.
Status pembinaan mereka di Departemen Agama, misalnya, dikatakan
tidak jelas. Kurikulum pendidikan agamanya juga tidak
dicantumkan di sekolah-sekolah. Lalu ada kesulitan menerakan
'Khonghucu' pada kolom 'agama' dalam KTP. Ditangguhkan pula
kongres-kongres Matakin oleh yang berwajib. Sedang permohonan
siaran mimbar agama Khonghucu di TVRI, ditolak. Pembangunan
rumah ibadat Khonghucu pun, seperti yang pernah dijanjikan di
Taman Mini Indonesia Indah diurungkan .
Sementara itu, umat Khonghucu sendiri pada rontok. Lihatlah
misalnya perkembangan di kalangan keturunan Cina di Tanah Abang,
Jakarta, sebagai hanya satu contoh. Tjandra Rahardja, d/h Lie
Foeck Tjen, 34 tahun, bonsu alias ulama muda di Kelenteng Hok
Tek Ceng Sin di wilayah itu, punya perkiraan di situ pernah
terdapat 5.500 umat Khonghucu - pada 1973. Itu menurut catatan
Kecamatan Tanah Abang. Tapi sekarang? Tinggal sekitar 1.000
orang. Dari jumlah itu yang aktif sebagai jemaat tercatat
sepersepuluhnya.
Tak sedikit pula, di tanah air, kelenteng yang tidak lagi
dipakai -- atau kegiatannya pelan-pelan berubah jadi peribadatan
Budha. "Setelah sehabis G30S dulu umat Khonghucu banyak diserap
oleh Katolik dan Kristen," kata Suryo Hutomo, Ketua Umum Matakin
kepada TEMPO, "kini mereka banyak yang masuk Budha."
Khonghucu lalu jadi makin samar. Jadi kabur bagi banyak orang:
benarkah, misalnya, ia termasuk agama yang "diakui "?
Suryo Hutomo, 45 tahun, tentu saja akan menjawab ya. Dan memang
maksud mereka ke DPR tak lain untuk minta perhatian pada status
itu. Mereka menyebut Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965. Di
situ memang dicantumkan, dalam memori penjelasan, nama-nama
agama yang dipeluk warganegara -- termasuk ke dalamnya
Khonghucu. Penpres itu dikukuhkan menjadi UU No. 5 Tahun 1969.
Di bawah Menteri Syarif Tahyeb dulu, agama Khonghucu tidak
dicantumkan dalam kurikulum sekolah Departemen P & K. Maka di
tahun 1975 Suryo Hutomo berusaha bertemu dengan Menteri -- dan
gagal. "Sebab sudah 15 tahun Khonghucu diajarkan sebagai agama
di sekolah-sekolah," kata Suryo yang kelahiran Sala dan punya
sekolah khusus Khonghucu itu.
Dan terkenallah kemudian kasus buku pelajaran agama Khonghucu
yang menyebabkan Suryo harus berurusan dengan pengadilan.
Mereka, konon berdasar "lampu hijau" dari Ketua BP3K, waktu itu
Drs. Soedarto, berusaha menyusun buku yang akan diusulkan untuk
dipakai. Dalam lokakarya kalangan Khonghucu sendiri, konsep itu
diperbanyak 70 eksemplar -- menurut Suryo - dan sudah lengkap
dengan tiruan sambutan Menteri, sekedar memakai contoh buku
pelajaran Kurikulum 1975. Dan di situlah Menteri marah. Betapa
pun kemudian ada surat permintaan maaf. Suryo toh dihukum
Pengadilan Negeri Surakarta enam bulan kurungan -- sekarang ini
sedang dalam proses kasasi.
Nasib sial itu kemudian diikuti dengan penangguhan Kongres IX
Matakin -- tahun 1979 ,16 April di Sala -- oleh Laksusda
Ja-Teng, hanya sehari sebelum Kongres dibuka. Juga temukarya
yang diinginkan dilangsungkan di Jakarta sebagai pengganti
kongres, 10 Mei berikutnya, tak dapat izin. Idem ditto usaha
mengadakan Mubes tahun kemarin.
Suryo sendiri memang menyadari, usai G30S/PKI, Khonghucu seakan
jadi sasaran kecurigaan -- dan ia memahami. Apalagi oleh isu
pembauran dan kesetiaan kepada tanah air -- bukan kepada "negeri
leluhur". Karena itu pula "indonesianisasi" mereka lakukan.
"Bahkan saya ini Ketua RT 010/06 di Kampung Bali Tanah Abang
sini," kata bonsu di Kelenteng Hok Tek Ceng Sin yang sudah
disebut.
"Negeri Leluhur"
Sebab masalah integrasi memang serius. Barangkali bonsu itu,
maupun Suryo, hanya tidak menyebut adanya Instruksi Presiden No.
14 Tahun 1967 - yang membatasi pelaksanaan peribadatan dan
budaya Cina hanya untuk lingkungan tertutup. Yang dimaksud
ialah: "agama dan istiadat Cina yang berpangkal pada negeri
leluhur yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh
psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warga
Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi
. . ." Itu berarti, segala perayaan dan arak-arakan Cina, liong,
barongsai, pesta agama atau adat secara terbuka, tidak dianggap
menguntungkan kesatuan bangsa.
Bahkan, seperti dituturkan H.R. Djatiwijono SH, Kepala Biro
Hukum dan Humas Departemen Agama, ada penelitian dari Badan
Koordinasi Masalah Cina (BKMC)-BAKIN bersama Badan Litbang
Departemen Agama. Isinya menyimpulkan: Khonghucu bukan agama.
Antara lain karena tak mengenal kehidupan afterlife alias
akhirat.
Dalam paper BKMC-BAKIN untuk Proyek Asimilasi di Bidang
Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing disebutkan lagi:
Khonghucu adalah ajaran susila. Kelenteng sendiri lebih banyak
hanya 'tempat mengadu untung' (ingat ciamsi, misalnya) dari
orang Cina di sana, yang kemudian oleh orang Khonghucu Indonesia
dijadikan tempat ibadat. Di Cina sendiri, demikian disebut, di
abad XIX sekelompok politikus ingin menjadikan Khonghucu sebagai
agama -- namun gagal. Sedang penyembahan mereka di sini
sebenarnya sudah banyak dimasuki unsur tiruan Kristen atau
Islam.
Bisa dipaham, ketika timbul masalah sehubungan dengan rencana
pembangunan Kelenteng di TMII, Djatiwijono mengirim surat yang
mengakibatkan penangguhan pembangunan itu. Dan tempat itu
terletak paling selatan setelah bangunan kelima agama, konon
kini menjadi "tempat pertemuan semua golong".
Menteri Agama juga ada mengirimkan surat kepada Menteri P & K,
1 Februari 1978. Isinya termasuk fundamental. Menyebut,
misalnya, pemerintah sebenarnya tidak pernah mengeluarkan
pengakuan terhadap agama apa pun. Yang ada ialah agama yang
langsung diatur (bukan doktrinnya) oleh pemerintah -- yang lima
buah itu, dan tidak termasuk Khonghucu. Itu berdasar Keputusan
Presiden No. 44 dan 45 Tahun 1974.
Tak heran bila Mendagri, dengan suratnya tanggal 14 Juli 1978,
memberi pedoman pengisian kartu penduduk yang menegaskan: untuk
mereka yang tidak menganut salah satu dari lima agama, kolom
agama bisa diisi dengan (-).
Dan sekarang ini semua pejabat di Departemen Agama, khususnya
dari kalangan Budha dan Hindu, akan mengatakan bahwa Khonghucu
memang bukan agama. Tapi bagaimana dengan Penpres No. 1 Tahun
1965, yang menyebut nama Khonghucu itu?
Jawabannya ada pada UU No. 5 Tahun 1969. Pasal 2 UU ini menyebut
Penpres di atas itu sebagai: termasuk salah satu Penpres yang
diakui sebagai UU -- hanya saja, materi Penpres tersebut
ditampung atau dijadikan bahan penyusunan UU baru.
Dan bulan Januari 1979, Presiden menginstruksikan kepada Menteri
Agama untuk, antara lain, mengusahakan menarik UU yang dianggap
"mengakui Khonghucu sebagai agama" itu. "Sebab sebenarnya UU
tersebut berbicara tentang penyalahgunaan dan atau penodaan
agama, sesuai dengan judulnya. Dan bukan soal pengakuan," kata
Djatiwijono. Lantas berita terakhir datang dari Menteri Agama.
Dalam keterangannya di DPR, persis sehari setelah kedatangan
rombongan Khonghucu itu, Alamsyah menjelaskan bahwa masalahnya
sebenarnya "sedang menunggu UU baru".
Ada Khotbah
Entah kapan. Tapi sekedar soal hak asasi dalam beragama, dalam
petunjuk Presiden kepada Menteri Agama 27 Januari 1979, antara
lain tetap dimungkinkan dipeluknya Khonghucu -- sepanjang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya. Artinya,
Khonghucu bukan aliran terlarang. Pun ada pengurusannya di
Departemen Agama: di bawah Ditjen Bimas Hindu & Budha. Di situ
ia bisa dianggap semacam aliran yang bernaung -- seperti juga
agama Sikh, misalnya, -- dan bisa juga sebagai salah satu aliran
Tridharma (Budha, Tao dan Khonghucu) yang merupakan satu dari
tujuh sekte Budhis di sini. Yang terakhir ini menurut Suparto
Hs., Ketua Umum Perwalian Umat Budha Indonesia.
Masalahnya ialah, umat Khonghucu sendiri selama ini sedang
membangun agamanya. Sambil mengalami penyusutan ibadat rupanya
mereka atur. Di kelenteng Tanah Abang itu misalnya, kebaktian
sekarang diadakan seminggu sekali (Ahad malam), setelah dulu
hanya setengah bulan sekali. Dibikin pula khotbah, seperti dalam
Kristen atau Islam. "Memang kami dalam sembahyang masih bersujud
pada foto leluhur, tapi itu hanya untuk konsentrasi." kata Suryo
Hutomo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini