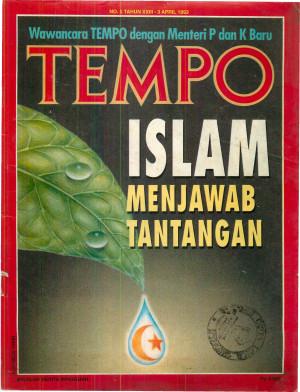BULAN-bulan belakangan ini nama Nurcholish Madjid acap disebut- sebut. Yang mencaci dan memuji sama-sama keras. Dan itu berawal dari ceramah budayanya di Taman Ismail Marzuki, 21 Oktober tahun lalu. Ceramah itu oleh sebagian orang dianggap melontarkan gagasan-gagasan yang menyesatkan, dari soal penyamaan semua agama sampai Islam bukan nama agama. Sebagian yang lainnya menganggap ide-ide Nurcholish menawarkan pemahaman dan pengamalan Islam yang ''baru'', yang boleh jadi bisa mengguncangkan kejumudan penghayatan keagamaan. Ceramah itu panjang gemanya. Dan kabarnya pihak Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah masih berencana mempertemukan Nurcholish dengan para pengkritiknya setelah pertemuan seperti itu gagal dilaksanakan beberapa waktu lalu karena pihak pengkritik tak hadir. Terlepas dari benar atau tidaknya Nurcholish, Azyumardi Azra, dosen Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, mengingatkan bahwa di luar Nurcholish tumbuh sejumlah harakah (gerakan) yang juga bersemangat menawarkan pembaruan penghayatan dan pengamalan Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berupaya menafsirkan ajaran Islam menurut paham yang mereka anggap pas untuk dirinya berharap juga untuk orang lain. Singkat kata, sebenarnya Nurcholish tak sendirian. Bedanya, Nurcholish tampil terbuka, sementara bermacam harakah itu bergerak diam-diam. Kelompok-kelompok itu tumbuh di Indonesia sekitar delapan tahun terakhir ini. Azyumardi Azra menyebut kelompok ini revivalisme, kelompok yang ingin kembali kepada ajaran murni Islam. Menurut Dr. Martin van Bruinessen, dosen Pascasarjana IAIN Yogya, kelompok-kelompok itu lahir, antara lain, karena NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam utama, akhirnya menerima asas tunggal Pancasila. Maka sejumlah generasi muda yang ingin mencari tempat berteduh dan tempat bertanya dalam organisasi bercap Islam menjadi ragu pada NU dan Muhammadiyah. Mereka lalu mencari alternatif sendiri, dan berkembangbiaklah gerakan usroh (gerakan kelompok kecil) di mana- mana. Banyak mahasiswa, guru, atau masyarakat umum yang ikut kelompok semacam usroh. Kegelisahan mereka, dalam mencari jawab bagaimana hidup sebagai muslim di tengah perubahan sosial di Indonesia, menemukan tempat berlabuh. Di sini kesimpulan Nurcholish tentang berbagai gerakan yang disebut fundamentalis di Amerika sebetulnya secara tak langsung menyinggung sikap berbagai gerakan usroh itu, yakni memberikan semacam hiburan sementara kepada mereka yang goyah terhadap perubahan sosial yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan NU dan Muhammadiyah itu. Sebab, usroh-usroh itu umumnya menawarkan pemahaman agama yang sederhana, yang mudah ditelan, sebagaimana kaum ''fundamentalis''. Menurut Martin van Bruinessen, yang meng- amati usroh, pengikut gerakan ini memahami Islam secara sempit, tapi mereka menganggap paham mereka sebagai alternatif yang lebih Islami. Menurut pengamatan Azyu, paham-paham semacam usroh itulah yang justru kemudian berkembang. Dan anehnya, betapapun terbukanya pemikiran Nurcholish, di kalangan kebanyakan umat pemikiran itu agak susah diterima. Kata Azyu, diperlukan ''lapisan kedua'' un- tuk menerjemahkan pikiran Nurcholish secara lebih populer. Tapi hal Nurcholish tak hanya terjadi di Indonesia. Banyak pemikir Islam kontemporer di dunia yang pikirannya susah diterima oleh kebanyakan umat. Karena itu, mereka sangat prihatin terhadap masa depan pemikiran Islam, sebab mereka merasa sudah mencoba menawarkan semacam metode untuk memahami Alquran yang ''sesuai'' dengan tuntutan zaman. Dalam pandangan mereka, seperti dikatakan oleh Nurcholish, penafsiran kita terhadap agama tidak mutlak benar. Penafsiran itu dipengaruhi iklim pemikiran yang terikat oleh ruang dan waktu dan tingkat pemahaman masing-masing individu. Karena itu, diperlukan penyegaran setiap saat. Tanpa penafsiran baru, penafsiran lama yang terikat pada zamannya itu akan menjadi absolut. Bahayanya, sebagai kelanjutan dari pemutlakan ini, penafsiran itu sendiri dianggap sebagai hal yang final sama dengan Alquran itu sendiri. Banyak pemikir Islam masa kini sependapat bahwa penafsiran para fukaha atau teolog masa klasik tak lagi relevan pada zaman sekarang di antaranya Mohammad Arkoun, seorang kelahiran Aljazir yang menjadi guru besar pemikiran Islam di Universitas Sorbonne, Perancis. Menurut Arkoun, para teolog dan fukaha itu tidak me- nguasai antropologi, antara lain. Padahal antropologi merupakan alat berpikir untuk memasuki kedalaman makna Quran. Soalnya, dalam pandangan Arkoun, kisah nabi-nabi yang ditemui dalam Quran disajikan secara mistis. ''Semua kisah dalam Quran berstruktur mistis,'' kata Arkoun. Dan mitos adalah konsep antropologi. Dengan konsep ini bisa dipahami bahwa para nabi dan rasul sebenarnya ajarannya berkesinambungan. Pandangan seperti ini juga dimiliki oleh almarhum Fazlur Rahman, guru besar pemikiran Islam di Universitas Chicago, AS, kelahiran Pakistan. Bagi Fazlur, persoalan-persoalan yang tengah dihadapi dunia Islam hanya mungkin bisa dipecahkan kalau Quran ditafsirkan secara utuh di bawah sinar latar belakang sosio-historisnya. Rahman menawarkan metode baru untuk memahami kitab suci, yakni dengan proses penafsiran ''gerakan ganda'': dari situasi sekarang ke zaman ketika Quran diturunkan, lalu kembali ke masa kini. Gerakan pertama menggali dan menyistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjang hal-hal yang spesifik Quran. Gerakan kedua merumuskan dan merealisasi pandangan spesifik masa kini dari prinsip-prinsip umum tadi. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum ''ditubuhkan'' dalam konteks sosio-historis masa kini. Cara ini, menurut Rahman, bisa berhasil bila kajian cermat dilakukan terhadap situasi masa kini sehingga tergambar situasi objektifnya. Kemudian prioritas-prioritas baru dipilih agar bisa mengimplementasikan nilai-nilai Quran secara baru pula. Ini memang telah dipraktekkan Rahman dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tema Pokok Quran. Namun sejauh ini pikiran-pikiran Arkoun dan Rahman di Indonesia sulit dicerna orang. Itu menjelaskan mengapa harakah-harakah Islamiyah yang cenderung eksklusif di kampus-kampuslah yang laku. Itu misalnya terlihat di Universitas Sumatera Utara, Medan. Selama ini semaraknya semangat beragama di kalangan mahasiswa universitas tersebut dimotori oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, tapi sejak empat tahun terakhir digantikan oleh Jamaah Tabligh dan Darul Arqam dua harakah yang menawarkan ajaran yang eksklusif, yang lebih menitikberatkan pada simbol-simbol beragama (cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya). Sebagai bukti bahwa dua harakah tersebut lebih mementingkan simbol-simbol beragama, dua gerakan itu tak berkembang di kampus- kampus IAIN. Soalnya, ''Aliran ini mudah diterima oleh orang yang kurang dalam pengetahuan agamanya,'' kata Ketua MUI Sumatera Utara, Syekh Hamdan Abbas, kepada Mukhlizardi Muchtar dari TEMPO. Tapi, bagaimanapun, harakah-harakah itu bersama gagasan Nurcholish merupakan jawaban yang dicari oleh mereka yang membutuhkan pegangan. Kelompok mana yang lebih memiliki masa depan, itu soal lain. Ada saran dari Armahedi Mahzar, dosen ITB yang juga intelektual Islam Indonesia, agar harakah seperti di kampus-kampus itu bertahan, yakni harakah-harakah itu diisi dengan dimensi esoterik dalam penghayatan beragamanya. Diharapkan, dengan cara itu, cara beragama mereka, yang lebih menitikberatkan pada simbol-simbol, yang lebih eksklusif, dan kaku, bisa dinetralisasi. Dengan demikian, akhirnya, harapan terciptanya kehidupan beragama yang pluralistik lebih terbuka. Julizar Kasiri dan Biro-Biro
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini