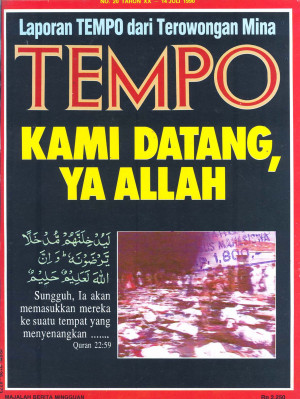JEMAAH haji Indonesia sekarang duduk tenang di kursi pesawat dan melayang cuma 11 jam. Dulu mereka harus menghadapi ganasnya laut selama berminggu-minggu. Dan, sebelum kapal api ditemukan, nasib mereka tergantung layar. Sekali jalan bisa makan setengah tahun. Dr. Martin van Bruinessen menceritakan dalam "Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci" -- dimuat Jurnal Ulumul Qur'an -- betapa jemaah harus berganti-ganti kapal di berbagai pelabuhan sebelum sampai di pantai Arab. Di Nusantara, hingga abad ke-18, Aceh merupakan persinggahan terakhir sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Itu sebabnya Aceh disebut Serambi Mekah. Di India jemaah masih harus ganti kapal yang menuju Jeddah. Bisa juga mampir dulu di Hadramaut atau Yaman baru kemudian ke Jeddah. Selain gelombang dan badai, momok perjalanan adalah bajak laut, yang tak sungkan-sungkan membunuh. Abdullah Abdul Kadir Munsi, sastrawan Melayu akhir abad ke-19, melukiskan betapa gawatnya perjalanan itu. Tahun 1854, tatkala dia naik haji, kapalnya diserang angin kencang sebelum mencapai Tanjung Gamri, Sri Lanka. Dan Abdullah cuma bisa pasrah. "Allah, Allah, Allah! Tiadalah dapat hendak dikabarkan bagaimana kesusahannya dan bagaimana besar gelombangnya, melainkan Allah yang amat mengetahuinya. Rasanya hendak masuk ke dalam perut ibu kembali. Gelombang dari kiri lepas ke kanan, dan segala barang dan peti-peti dan tikar bantal berpelantingan. Maka sampailah ke dalam karung air bersemburan, habislah basah kuyup. Maka masingmasing dengan halnya. Tiadalah lain dalam pikiran, melainkan mati." Demikian tulis Abdullah dalam buku Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Jeddah, yang disusun kembali oleh Kassim Ahmad. Pada akhirnya Abdullah memang mati setelah beberapa hari sampai di Mekah. Kematian di perjalanan adalah hal yang lumrah. Pemerintah Belanda pernah mencatat, antara 1953 dan 1958, jemaah haji yang pulang ke Hindia Belanda tidak sampai separuh dari yang berangkat. Memang tidak semuanya meninggal ditelan keganasan laut. Di antara mereka ada yang menetap di Arab atau terserang penyakit. Maklum hingga tahun 1930-an, ketika pelayanan kesehatan sudah lebih baik, sekitar 10% jemaah Indonesia meninggal di Tanah Suci karena sakit. Perjalanan laut ternyata bukan satu-satunya ancaman. "Hantu" di darat tak kalah mengerikan. Penyamun-penyamun dari suku Badui juga suka merampok para jemaah. Dulu, sebelum bis-bis ber-AC menghuhungkan pantai dengan Mekah atau Mekah dengan Madinah, orang harus berjalan berombongan di atas punggung unta. Dari satu tempat ke tempat lain, diperlukan paling tidak sepuluh hari. Di bukit-bukit, para penyamun sudah siap membegal, bahkan membunuh. Belum lagi bahaya badai gurun yang ganas dan panas terik yang bukan main. Kisah-kisah sebelum ditemukannya pesawat terbang dan kapal mesin tak jauh berbeda dengan kisah delapan ratus tahun lalu. Seperti yang diceritakan Ibnu Jubair dalam Al-Rihlah (Perjalanan). Jubair adalah putra seorang pejabat di Valencia, kota pantai yang cantik di Spanyol. Untuk melaksanakan rukun Islam ke-5 pada 1189, dia memulai perjalanan haji ke Mekah. Padahal, waktu itu Perang Salib sedang hebat-hebatnya. Dari berangkat sampai kembali lagi ke Spanyol, Jubair membutuhkan waktu dua tahun. Jubair mencatat bagaimana dia terapung berbulan-bulan di Laut Tengah, di atas perahu layar. Bagaimana dia harus bertemu dengan para pemungut cukai, baik dari orang-orang Kristen maupun Islam. Bagaimana ia terpaksa singgah dulu di Kairo, memudiki Sungai Nil, baru kemudian menyeberangi Laut Merah sebelum ke Jeddah, Mekah, dan Madinah. Jubair menyajikan cerita seram kaum Hijaz, yang hidup di bagian barat Arab Saudi. Suku-suku terpecah dalam berbagai doktrin, yang intinya menolak agama alias kafir. Mereka selalu mencoba menguasai, menangkap, atau merampok harta benda para jemaah. Tekanan tanpa ampun itu, tulis Jubair mungkin akan terus berlangsung bila penguasa Mesir, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (1171-1193), tidak turun tangan. Salahuddin mencabut pajak bea. Tetapi sebagai gantinya dia mewajibkan para jemaah menyerahkan sejumlah uang atau persediaan makanan kepada Mukhtir, amir (kepala pemerintahan) Mekah saat itu. Celakanya, sang amir tergolong manusia serakah. "Ketika sampai di Jeddah, kami ditangkap. Amir memerintahkan para jemaah agar sama-sama menjamin pembayaran sebelum memasuki Tanah Suci. Tanah Tuhan itu diperlakukan seakan-akan harta pusaka pribadi yang disewakan kepada para jemaah," tulis Jubair dalam bukunya. Demikianlah, berangkat haji di zaman dulu sama dengan perjalanan menempuh maut. Bahkan hingga tahun 1950-an, mereka yang berniat ke Mekah harus bersiap-siap menghadapi ajal. Itu sebabnya mengapa selama jemaah di Mekah, kerabatnya menyelenggarakan tahlilan, bagai sedang mendoakan jenazah. Dan bila ternyata si jemaah kembali dan berhasil menyandang predikat haji, maka itu dianggap sebagai mukjizat. Priyino B. Sumbogo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini