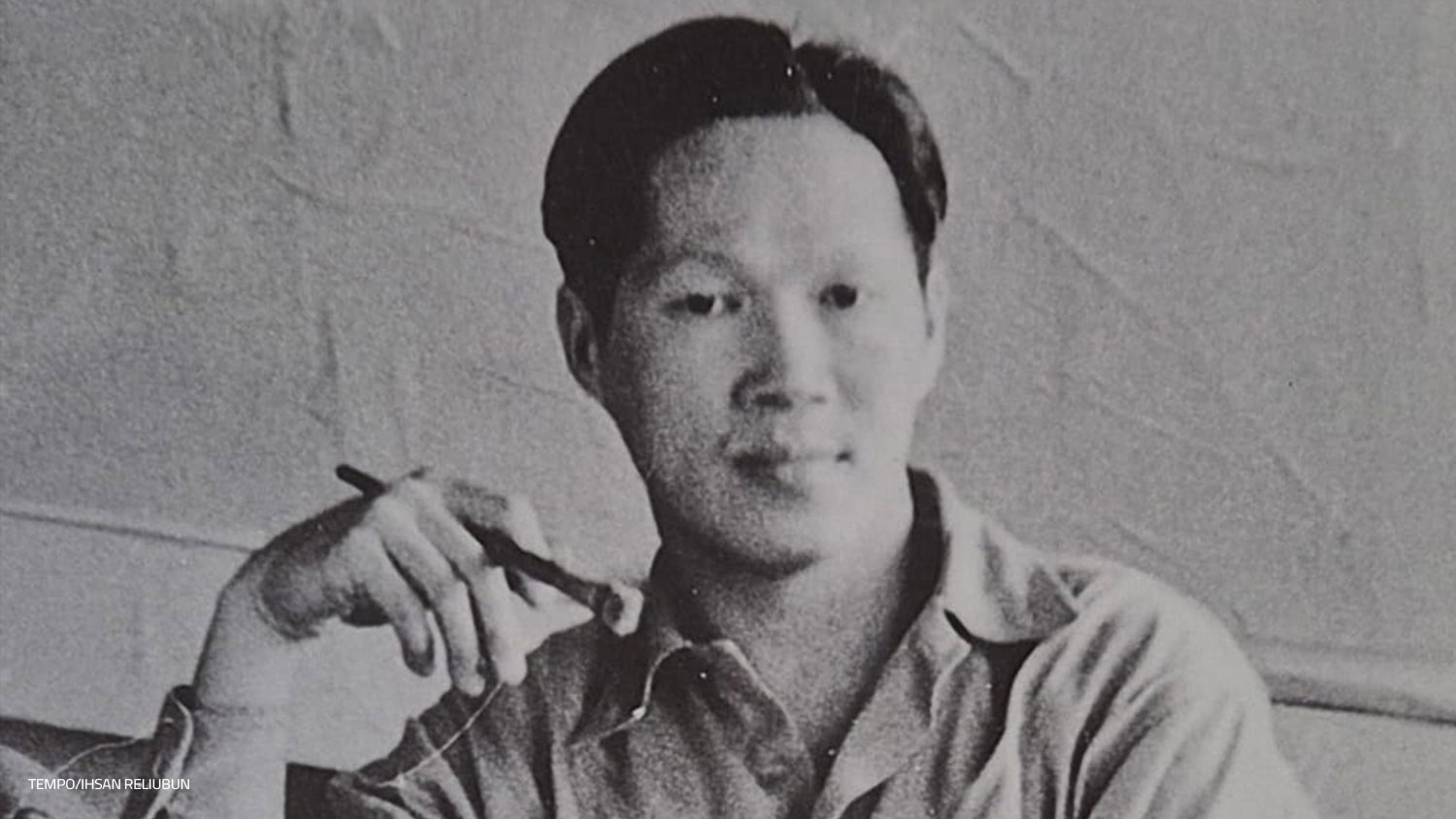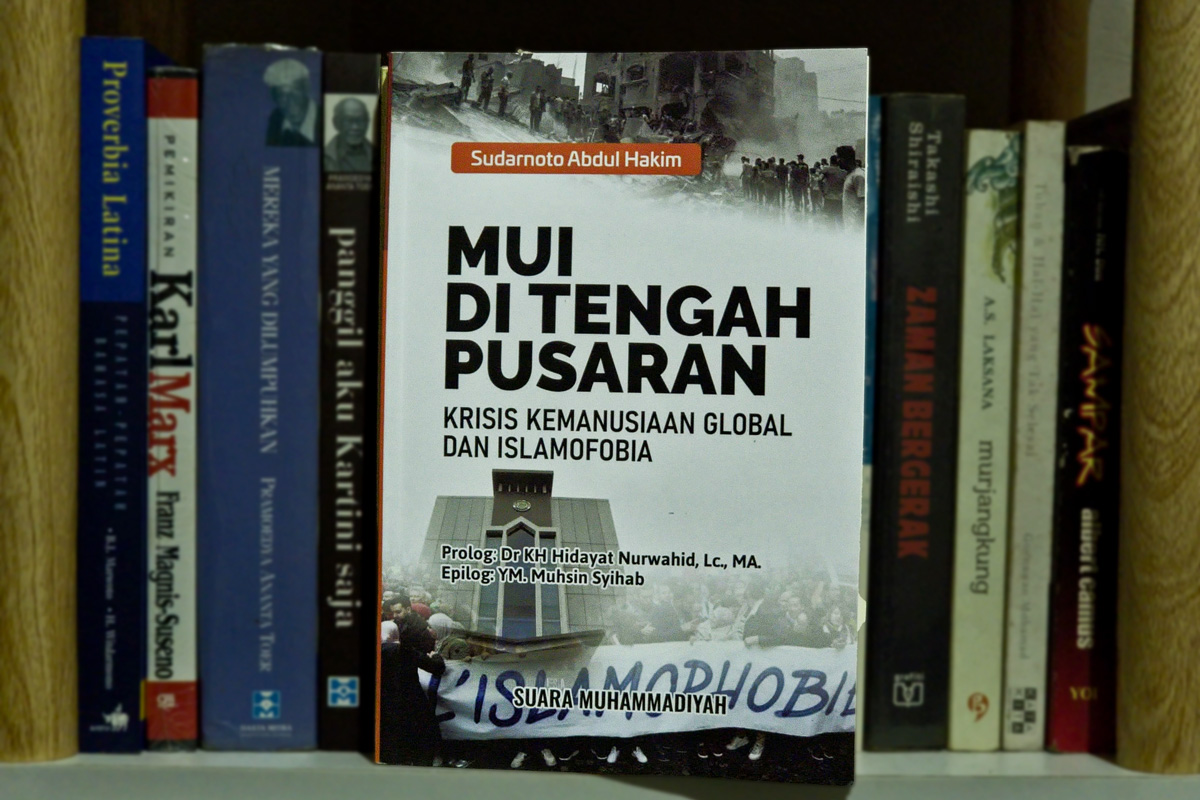Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
IA masih merokok di jendela yang menghadap balkon. Posisinya menyamping, kakinya jenjang tak memakai celana. Atasannya hanya memakai baju tidur yang menutupi tubuh indahnya. Putingnya yang mengeras nampak begitu kokoh terlihat dari samping. Rambutnya jatuh bergelombang, seakan ia sudah menatanya untuk sebuah pertemuan penting. Nyatanya, ia baru beranjak dari ranjang. Ia sedang membaca buku jilid keenam À la recherche du temps perdu-nya Marcel Proust yang berjudul Albertine disparue. Kopinya masih mengebul. Kebul itu bersatu dengan asap rokoknya. Ketika aku mengambil minum di meja dekat dapur, matanya bergerak ke arahku. Ia membelakangi jendela, cahaya pagi khas Kota Paris tak secara langsung menerpa wajahnya, namun keindahannya tak bisa disembunyikan semudah itu. Perempuan itu adalah kekasihku.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
***
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

AKU adalah lelaki yang berasal dari Yogyakarta dan terdampar di Paris. Kata orang-orang, aku terdampar dari satu surga ke surga lainnya. Menurutku, justru aku sedang jatuh dari satu kesialan ke satu kesialan lainnya. Paris tak jauh beda dari Yogyakarta, jujur saja. Di sini bau kencing. Bau-bau itu sama saja seperti yang ada di sekitaran Terminal Giwangan. Pun di sini banyak para gelandangan. Yogyakarta pun sama. Bedanya, para gelandangan di sana adalah gelandangan yang tak diberi kesempatan untuk merasakan kemajuan kotanya. Bayaran mereka rendah dan mereka tak protes akan hal itu. Sama seperti para gelandangan di Kota Paris yang hanya diam ketika pendapatan harian mereka tak lebih dari 5 euro.
Aku awalnya adalah gelandangan tersebut. Aku bekerja sebagai juru tulis di sebuah media yang bayarannya rendah sekali. Setiap hari, aku disuruh menulis puluhan berita terkini, dan per bulan aku hanya diupah sebesar UMR kota sialan ini. Bayangkan saja, aku hampir mati karena terlalu banyak menenggak kopi. Salah satu berita yang kutulis ada kesalahan dan yang kudu menanggung adalah penulisnya sendiri. Itu adalah kondisi yang amat gila di kota yang tak kalah gila.
Aku mencari kehidupan yang baru. Awalnya aku berpindah ke Jakarta. Selama tiga bulan di sana, aku tak kuat. Persetan dengan mereka yang mengatakan, “Jakarta hanya untuk para petarung.” Bangsat sekali bahwa aku bekerja itu untuk mencari uang, bukan untuk bertarung atau apalah itu. Tiap hari di Jakarta yang ada hanyalah kegilaan. Aku menaiki KRL seperti wahana wisata yang mengantarkan menuju neraka. Aku tiap hari melihat seorang lelaki menggesekkan batang kemaluan kepada perempuan—atau bahkan lelaki lain—dengan memanfaatkan desakan di dalam gerbong. Aku juga melihat wajah-wajah kelelahan bagai zombie yang tinggal menunggu waktu kapan ia mati untuk kedua kali. Gila. Jakarta bagai kota setan.
Maka aku mencoba peruntungan dengan mengirim sebuah laporan berupa penelitianku tentang Yogyakarta. Penelitian itu tentang kekerasan jalanan yang sering terjadi di kotaku. Tanpa disangka, sebuah universitas kenamaan di Paris tertarik. Mereka mempekerjakanku sebagai peneliti paruh waktu, namun bayarannya minta ampun banyaknya. Bayaran itu berkali-kali lipat dari UMR di kota asalku. Namun, pajak di Paris sungguh mencekik. Mereka hampir mengambil 25% pajak dari gaji bersihku.
Demo besar sering terjadi di Place de la Republique guna menggoyang pikiran pemerintah agar memikirkan sekali lagi perihal potongan pajak yang luar biasa banyak itu. Aku sering ikut demo itu. Di tahun ketiga, aku sudah memegang toa dan menyampaikan aspirasiku di hadapan orang-orang. Sesekali aku suguhi umpatan khas Jogja seperti asu dan bajingan, mereka semua senang. Tanpa disadari, aku menjadi penting dalam perkumpulan pedemo yang biasanya menggoyang pemerintahan Paris. Aku lebih sering menceburkan diri dalam aksi massa ketimbang bekerja rutin di universitas.
Hari Buruh lalu, Presiden Prancis berupaya untuk menaikkan usia pensiun. Tentu saja kami, para demonstran, marah karena usia tua tak seharusnya diperas lagi. Mereka sudah layak mendapatkan tunjangan dan pensiun. Aksi makin berlipat ganda manakala salah satu tuntutan lainnya adalah kenaikan gaji. Pajak yang besar harusnya diimbangi dengan kenaikan gaji. Kami menggempur pusat-pusat pemerintahan. Aku berorasi secara berapi-api di kawasan Place de la Republique.
Polisi memukul mundur para demonstran sampai terdorong ke Place de la Nation. Tembakan gas air mata dan water cannon menambah ketegangan Kota Paris saat itu. Akulah yang berada di tengah-tengah amuk redam itu. Aku mengambil toa dan berkata, “Aku di sini. Sampai kuasa mendengar. Sampai kami menang. À Midi ou À Minuit—pada siang atau tengah malam.”
Massa bergandengan tangan, kemudian sayup-sayup terdengar nyanyian La Marseillaise. Aku menangis di antara mereka. Menangis karena lagu kebangsaan sebuah negeri yang pernah menjajah bangsaku sendiri. Begitu ironi.
Lebih menyedihkannya lagi, aku dihukum kurung beberapa hari sebelum seseorang menebusku dan bertanggung jawab untukku. Aku memperjuangkan pekerjaan orang lain, justru aku yang kehilangan pekerjaanku. Visaku tak bisa diperbarui. Aku menunggu waktu untuk dideportasi dengan kondisi tak berduit. Kondisi ini begitu mengerikan. Namun, kengerian tidak hanya sampai di sini saja.
Ya, seperti yang aku bilang, hanya mengunjungi satu kesialan ke kesialan yang lain. Namun, urusan pajak, demonstrasi, dan pemecatan itu bukan sebuah kesialan satu-satunya. Ada satu kesialan lagi yang diciptakan oleh Paris untukku. Dan kesialan ini adalah kesialan yang paling mengerikan. Kesialan itu diberikan kepadaku dalam bentuk kekasihku yang terlalu cantik.
***
“BAGAIMANA kelanjutan buku itu?” tanyaku. Aku mengambil beberapa plume di kulkas. Aku langsung memakannya. Aku duduk di sebuah kursi dekat dapur dan pelan-pelan mataku mulai menyesuaikan pandangan terhadap kekasihku yang membelakangi jendela. Benar sekali, ia sedang tersenyum melihatku. Senyum yang indah sekaligus tercantik di dua benua yang pernah aku singgahi.
“Seperti Proust pada umumnya. Seperti lima jilid sebelumnya. Aku harus mengulang pelan-pelan. Terlalu berbelit apa yang ia tuliskan,” jawabnya. Ia menaruh buku itu. Mengisap rokoknya dengan pelan dan mengembuskan asapnya ke arah balkon. Paris amat gerah di pengujung musim panas. Ia kembali mengamati luar jendela. Aku mendengar beberapa petugas pos berseru dengan riang, sisanya adalah suara decit sepeda yang melewati kawasan flat kami di Marais yang sempit.
Aku mendekati kekasihku itu. Aku cium rambutnya yang putih dan aku lingkarkan tanganku pada perutnya. Aku hirup dalam-dalam aroma tubuhnya. Sebenarnya semua nampak sempurna, kan? Tadinya juga aku menganggap begitu. Sebelum aku memulainya lagi pagi ini. Rasa cemburu dan rendah diri yang berkecamuk dan makin membadai tiap harinya.
“Aku akan bertemu Jean pukul dua siang,” katanya. Ia mengusap tanganku. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri dengan pelan. Mau tak mau, tubuhku juga ikut bergoyang.
Aku tarik pelukanku perlahan. Aku mengusap kepalanya tiga kali. “Lagi?” tanyaku.
“Lagi? Apanya yang lagi, sayang?” ia melihatku. Matanya yang biru itu seakan mengintimidasi rasa curigaku. Tiap sisi wajahnya adalah kesempurnaan belaka.
“Lagi-lagi bertemu Jean. Kau sudah dua kali bertemu Jean dalam satu minggu ini.”
Kekasihku menarik napas. Ia menumbuk rokoknya secara asal-asalan di jendela. Abunya beterbangan ke luar. Terbawa angin entah ke mana. Ia berdiri, memelukku. Flat kami terasa hampa beberapa saat. Tak ada suara yang kami ciptakan, kecuali suara napas kami. Napas kekasihku yang berat karena bercampur dengan rasa lelah. Juga napasku yang berat karena rasa cemburu dan penuh curiga.
Jean adalah mantan kekasih Carla—nama kekasihku. Mereka berdua model ternama di kota ini. Mereka berdua dielu-elukan karena serasi. Tapi itu dulu. Sebelum Jean ketahuan menjalin hubungan lain dengan lelaki lain. Cukup sulit untuk dijelaskan, namun cukup mudah dipahami jika kau berada di Paris.
Carla, selain menjadi model, menjadi seorang penulis lepas di tempat bekerjaku yang dulu. Katanya, gaji menjadi model memang besar, namun ia lebih senang memiliki uang dari hasil menulis. Sebenarnya, tulisan Carla benar-benar bagus untuk ukuran penulis pemula di Kota Paris. Tulisan Carla adalah anak kandung murni Prancis yang selalu memuat satire dan sarkas yang amat kejam. Walau ia hanya menulis sebuah cerpen untuk La Monde, ia selalu selingi kritik tajam untuk pemerintah Prancis.
Sampai detik ini, aku tak tahu kenapa ia mau menjadi kekasihku. Jika karena aku terlihat keren di depan para demonstran, ah ini Paris. Kota ini terlalu sibuk untuk mengembangkan benih cinta heroik yang biasanya tumbuh kembang dengan subur di Yogyakarta. Di Yogyakarta, senioritas dan abang-abangan entah mengapa masih laku. Sebagian dari mereka, yang merasa senior dan aktivis paling keren, seakan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Toh kami berpacaran jauh sebelum aku mulai rutin berorasi di tengah demonstrasi.
Sebenarnya, Carla justru menyuruhku untuk jangan ambil sikap terlalu ekstrem dalam aksi Mayday tempo lalu. Katanya, beberapa orang sudah ditarget untuk ditangkap. “Barangkali kau salah satunya. Imigran diincar dan ditangkapi di beberapa kawasan region Île-de-France bagian pinggiran. Puncaknya tentu saja pusat Kota Paris,” katanya. Dan prediksi Carla benar semata.
Carla yang menebusku dan memberi jaminan. Beberapa bulan berlalu, tak ada surat kabar yang mau menerima hasil tulisan, riset, dan cerpenku. Aku begitu beku di flat yang kami sewa bersama. Harusnya, membayar ongkos bulanan flat rasanya ringan karena kami bagi dua. Namun, keputusasaanku membuat Carla harus bekerja sendirian dan aku menunggu waktu untuk dideportasi oleh pihak berwajib.
“Honorarium tulisanku tak sebesar tulisanmu, sayang. Aku mau tak mau harus bekerja sebagai model. Nah, kebetulan Jean juga ada dalam pementasan kali ini di Concorde,” jelasnya dengan pelan. “Kau tahu itu. Kita sudah sering membahasnya, bukan? Lagi pula, keuangan kita belakangan ini…” ia tak melanjutkan. Kalimatnya berhenti dengan mengambang.
Aku berjalan pelan ke arah jendela yang menghadap balkon kecil. Balkon itu sebenarnya tak bisa kami pijak. Balkon itu hanya bisa ditempati oleh dua pot. Dan di sana sudah ada beberapa bonggol bunga iris yang sengaja ditanam oleh Carla. Aku melihat beberapa orang sedang melewati jalanan Charlotte yang sempit. Pukul delapan pagi, Paris masih menggeliat.
Hubungan Carla dengan Jean sering aku cemburui. Dekatnya mereka dalam beberapa waktu ini juga karena salahku. Carla harus mengambil banyak pekerjaan agar bisa membayar flat kami yang harganya 700 euro per bulan. Itu adalah angka yang besar ketika kami bisa menyingkir ke kawasan pinggiran Paris, seperti Massy atau Palaiseau yang lebih murah. Namun, Carla tetaplah Carla. Ia terlalu Paris untuk aku yang Yogyakarta. Ia sudah dari lahir merasakan gegap gempita kota ketimbang mengasingkan diri di kawasan perdesaan.
Aku juga tak mengetahui mengapa Carla masih mau menampungku. Hampir enam bulan setelah kejadian Mayday, anehnya, ia belum juga meninggalkanku. Aku selalu menghitung hari, kira-kira kapan waktu yang tepat ketika ia meninggalkanku. Sampai hari ini, ia belum juga meninggalkanku. Namun, sejak ia dekat lagi dengan Jean, aku merasa waktu yang aku tunggu itu makin dekat.
“Kau bebas meninggalkanku kapan saja, Carla,” kataku yang sedang menghadap balkon. Aku melihat bonggol yang ditanam oleh Carla secara asal-asalan dan tak akan tumbuh di musim gugur dan akan mati seutuhnya di musim dingin.
Carla tertawa kecil. Suaranya bagai malaikat yang sedang menyanyikan kidung-kidung pemujaan kepada Tuhan. “Iya, sayang. Aku akan meninggalkanmu. Ke Concorde. Beberapa jam saja.”
“Bukan itu maksudku, Carl.”
Carla menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. “Baswara, seminggu ini kau sudah dua kali berbicara seperti itu. Kau terlalu banyak menonton opera sabun murahan di televisi,” katanya. Ia mendekatiku dan mengelus pundakku.
“Tak ada alasan lagi kita bersama, Carla. Faktanya, aku hanya menyusahkanmu.”
“Kau meremehkanku. Meremehkan cintaku. Meremehkan jalan pikiranku. Meremehkan upayaku,” katanya sembari melepaskan pelukan. Ia berjalan masuk ke dalam kamar kami dan beberapa saat berikutnya ia keluar dari flat kami.
Aku melihatnya dari atas. Ia keluar dari bangunan utama apartemen kami dan menyusuri jalan Charlotte yang lengang. Rambutnya yang putih makin cocok ketika diterpa matahari pagi. Rambutnya bergelombang dan terombang-ambing ketika berjalan. Ia terlalu sempurna. Sedang aku takut dengan kesempurnaan yang ia ciptakan.
***
KITA melangkah jauh tiga tahun yang lalu, di waktu diriku dan Carla pertama kali bertemu di bulan Desember dan tak ada salju di Paris. Saat itu musim dingin sudah membuat siapa saja menggigil. Saat itu Rue de la Sorbonne masih dalam suasana pukul delapan pagi. Aku memakai pakaian hangat dengan syal yang melilit leherku. Aku gosokkan kedua telapak tanganku, hangat enggan mampir. Aku rogoh kantong mantelku, aku cari ponselku. Gadis itu belum membalas apa pun seusai aku mengirimkan pesan bahwa aku sudah di depan kampus Sorbonne bagian timur. Aku tak bisa masuk karena kartu aksesku tertinggal.
Tak ada kafe yang nyaman di sekitar Rue de la Sorbonne. Kalaupun ada, kafe itu sudah masuk ke area Rue des Écoles. Di sekitarku, hanya ada beberapa toko buku yang lampunya masih redup. Beberapa orang berjalan kaki karena berdiam diri di satu tempat adalah hal bodoh. Dingin akan menggerogotimu sampai kupingmu sakit dan kepalamu terasa pening.
Lima belas menit setelahnya, gadis itu keluar. Ia mengenakan balutan mantel berwarna marun dengan syal serupa. Celananya ketat, sepatunya berwarna kelabu. Ia keluar dari pintu besar bagian timur Fakultas Sastra Universitas Sorbonne. Aku melambaikan tangan kepadanya, aku berjalan mendekatinya. Ia mengulurkan tangannya dan kami saling berjabat. Ia tarik tanganku, pipi kami saling menempel. Pertama pipi bagian kananku bertemu dengan pipi bagian kanannya, begitu juga dengan pipi kiri kami. Tradisi Prancis yang belum bisa aku maklumi sampai saat ini.
“Maaf merepotkanmu, Carl. Aku membutuhkan data itu,” kataku.
Ia tersenyum. Kemudian melihat langit. “Tak ada salju di hari minggu,” katanya. Kemudian ia menatapku. Matanya biru. Padu dengan rambutnya yang putih. “Selain tak ada salju, harusnya tak ada pula obrolan tentang kerjaan di hari minggu.”
Aku merasa bahwa ia terganggu dengan pesanku yang datang memburu pagi itu. Aku benar-benar membutuhkan data yang sedang digarap oleh Carla dan timnya. Data itu adalah data perihal transportasi di Kota Paris. Timku tak pernah menyentuh penelitian tentang itu. Aku dan timku selalu bertungkus lumus di hadapan buku-buku sastra dan filsafat yang lama-lama membuatku bosan. Aku rindu sekali penelitian tentang darah, mayat, dan kekerasan.
“Ah, aku memang bodoh. Hari ini harusnya aku tak mengganggumu,” kataku.
“Nah, kau tahu itu,” satu alisnya naik. Senyumnya terlihat sangat menyebalkan. Namun, cantiknya tak pernah menyingkir walau ia memperlambat kerjaku. “Sebagai hukuman kau telah mengganggu hari mingguku, kau harus mentraktirku minum kopi hangat dan ceritakan kepadaku tentang Zola.”
Sudah lama aku tak merasakan romansa. Sudah aku tinggal jauh-jauh semua itu di Jogja. Namun, ketika Carla bilang seperti itu, rasanya alunan musik klasik berkeliaran di kepalaku. Kidung-kidung Jawa juga sekelebat mengalun pelan dan tanpa aku sadar, aku tersenyum kepadanya.
“Senyuman itu aku anggap sebagai bentuk lain dari penolakan. Bukan begitu, Jok?”
Carla tahu aku dan tim sedang meneliti tentang Émile Zola. Aku sedang menguliti habis-habisan karyanya yang berjudul The Belly of Paris. Sebab itu, aku membutuhkan penelitian Carla tentang transportasi, terutama akses pembangunan bawah tanah untuk Metro. Apalagi pada saat itu, akses pembawa sayuran dari sekitaran Kota Paris menuju Les Halles hanya melibatkan pedati atau sudah melibatkan monorel di permukaan tanah atau malah sudah di bawah tanah. Penelitian Carla punya jawabannya.
Di kafe di kawasan Jardin du Luxembourg, kami malah ngobrol ngalor-ngidul tentang penulis dan filsuf yang lain. Aku bercerita tentang betapa kagumnya aku dengan Pramoedya Ananta Toer. “Dan kau harus membaca Gadis Pantai. Kau harus tahu perjuangan perempuan Jawa pada tahun-tahun tersebut,” kataku dengan berapi-api. Carla sibuk menatap mataku dan terus mengangguk-angguk.
Carla suka sekali dengan Marcel Proust. Katanya, membaca In Search of Lost Time itu adalah proyek seumur hidup. Aku bilang bahwa aku pernah membacanya. Dan itu sukses membuat Carla terkagum-kagum. Padahal, aku hanya membual. Aku cukup mual ketika membaca jilid pertama tulisan Proust. Bagiku, Proust tak memenuhi seleraku terhadap sastra. Aku justru teringat Bonsai-nya Alejandro Zambra.
Yang membuat kami tertawa lepas, saat aku bercerita ketika Hemingway mengajak Scott Fitzgerald ke Museum Louvre untuk melihat penis-penis kecil yang melekat pada patung-patung Yunani, Etruskan, dan Romawi. “Hal itu karena Scott tidak percaya diri dengan ukuran penisnya. Sebab, istrinya, Zelda Fitzgerald, bilang bahwa ukuran penis suaminya tak bisa memuaskan perempuan mana pun,” kataku.
Carla tertawa. “Besok kita jalan-jalan ke sana, ya?” katanya. Aku mengangguk dan tertawa. Aku lihat lagi wajahnya, ia nampak serius. Aku menganggap itu adalah ajakan kencan.
Aku tak pernah menganggap perasaan Carla kepadaku adalah bentuk kasih sayang. Aku hanya menganggap bahwa itu semacam bentuk orientalisme belaka. Meniduri gadis seindah Carla, aku pun sebatas bentuk kemenangan semata. Aku tahu ini adalah bentuk seksisme yang jahat, namun aku meragukan bahwa perempuan secantik itu mencintaiku. Ia dikelilingi oleh banyak lelaki tampan. Apalagi mantan kekasih Carla itu adalah model yang amat terkenal di Paris. Pengikut TikTok-nya jutaan dan kerap kemesraan mereka ketika masih pacaran berseliweran di beranda media sosialku.
“Mungkin kau hanya menyukai cerita-ceritaku yang tak pernah kau dengar,” kataku suatu kali. Hal ini adalah amarah pertama yang terjadi pada hubungan kami.
“Maksudmu? Aku suka kau karena kau bercerita tentang penis Scott Fitzgerald? Merde!” katanya.
Aku merasa bahwa perasaan Carla kepadaku hanya sebagai bentuk antusiasme terhadap kebudayaan yang benar-benar berbeda dari apa yang ia alami sejak kecil. Tiap menjelang malam, aku selalu mengisahkan tentang aksi heroik pewayangan Jawa kepadanya. Ia terpikat. Matanya berkilat-kilat, walau lampu sudah padam. Juga aku menceritakan hantu-hantu yang ada di Yogyakarta, seperti genderuwo dan kuntilanak.
Cerita-cerita itu bisa membuat Carla terbahak-bahak. Bahkan suatu saat, ia menangis tersedu-sedu karena aku menceritakan keluarga korban klitih di Yogyakarta. Malam-malam kami begitu luar biasa. Sampai pada akhirnya, malam yang luar biasa itu berubah menjadi amat sempurna setelah Carla bilang, “Aku benar-benar mencintaimu, Jok. À midi ou à minuit.” Aku suka dengan malam yang luar biasa. Namun aku takut dengan kesempurnaan.
***
VISAKU habis dan aku tak menceritakan apa pun kepada Carla. Aku meninggalkannya begitu saja di Paris dan tepat hari ini sudah memasuki tahun kedua aku meninggalkannya. Aku kembali ke kampung halamanku di Giwangan, Yogyakarta.
Satu tahun yang penuh dengan perasaan berat. Perasaan bersalah berkecamuk dalam hatiku tiap hari. Aku menghapus semua media sosial dan menghilangkan segala jejak tentangku bagai seorang buron mancanegara. Aku tak pernah lagi berhubungan dengan Carla dan itu membuatku makin tersiksa.
Di Yogyakarta, aku tak mempunyai pekerjaan tetap. Aku hanya menulis esai dan cerpen lalu mengirimnya ke berbagai media. Sayangnya, tak pernah ada media online ataupun koran yang menerima tulisan-tulisanku secara rutin. Kalaupun ada, hanya media kecil yang memberiku honorarium sebesar seratus ribu untuk sepuluh tulisan.
Para tetangga mulai mempertanyakan kondisiku dan pertanyaan-pertanyaan itu membuat ibuku makin terpuruk. “Bilang saja aku nganggur,” kataku. Ibuku bilang, nganggur tak masalah, yang penting aku tak mengurung diri macam ini. Ibuku mulai resah dengan kondisi pikiranku. Ia juga mulai bertanya, apa saja yang terjadi di Paris. Aku tak pernah menjawab. Aku juga tak ingin ibuku ikut-ikutan berpikir keras, mengapa anaknya menjadi begundal sampai-sampai mendapat ancaman deportasi dan tak bisa memperpanjang visanya.
Aku tahu bahwa berat badanku menyusut banyak sekali. Kantong mataku makin hari makin menghitam dan ia cekung menakutkan. Rambutku mengalami kebotakan dengan keparahan yang sudah menyentuh tanda gawat. Aku hanya menghabiskan waktu di depan laptop tuaku yang layar LCD-nya sudah bergaris-garis. Aku mengetik apa saja, dari bangun pagi sampai isya. Setelah itu, aku menghabiskan waktu di teras sampai badanku tak kuat dan mataku meminta untuk beristirahat.
Pukul dua belas siang, ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku diam sejenak, ibuku tak membukakan pintu. Aku cek kamar ibu, ia tengah tertidur dengan pulas. Aku beranjak ke ruang tamu, memegang gagang pintu dengan gemetar. Satu tahun ini, aku jarang berinteraksi dengan seseorang.
Ketika aku buka pintu itu, aku terkejut bukan main. Sosok itu berambut putih dan tersenyum kepadaku. “Sudah lama tidak bertemu,” katanya. Aku ambil tangan itu. Aku letakkan di jidatku. Ia adalah Pak Sodiq, ketua RT sekaligus ustadz di kampung kami. Ia berambut putih karena tua dan dialah guruku mengaji dari kecil sampai besar. “Ini ada paket untukmu. Jam sepuluh tadi, kurir mengetuk rumahmu dan tak ada jawaban. Jadi dia menitipkan kepadaku,” katanya.
Aku berterima kasih dan Pak Sodiq berlalu. Sebuah kotak besar yang dibungkus begitu rapi. Aku tahu ini dari Carla. Ada alamat yang amat khas Prancis, yakni 75003, yang menandakan paket itu beralamatkan dari kode pos Arondisemen 3, kawasan Le Marais. Entah bagaimana, surat ini bisa melaju mulus sampai rumahku. Setahuku, jika aku mendapat surat dari luar negeri, aku harus mengambilnya secara langsung di kantor pos. Juga membayar beberapa biaya administratif lainnya. Keanehan lainnya, bagaimana caranya dia tahu alamat rumahku? Benar-benar gadis yang luar biasa.
Aku meletakkan kotak itu di meja. Aku tarik napas dalam-dalam dan mulai membukanya pelan-pelan. Bungkusnya yang rapi mempermudah diriku untuk membuka bagian plastik sampai kardusnya. Di bagian paling atas, sebuah mantel berwarna marun yang pernah ia gunakan untuk bertemu denganku pertama kalinya di Sorbonne. Ia juga menyemprotkan harum parfum yang kerap ia gunakan. Ada selembar kertas yang bertuliskan amat singkat, “Barangkali kau merindukan aroma tubuhku. Xoxo.” Aku tersenyum. Aku merasa seperti hidup kembali.
Aku letakkan mantel itu di paha. Kemudian yang terpampang jelas adalah sebuah buku yang dibungkus dengan plastik berwarna biru. Aku ambil lekas-lekas. Aku buka dengan tak sabar. Sebuah album foto? Sudah menikahkah dia dengan lelaki yang diinginkannya? Hatiku bagai debam langkah raksasa Gulliver yang memasuki pulau orang-orang pendek. Mataku mulai terasa buram, aku tahu ada campur tangan kesedihan yang membuat mataku meremang.
Isinya hanya sebuah buku dengan kover polos. Buku itu nampak seperti sebuah draf belaka. Namun, ada stempel penerbit besar asal Prancis di sisi kanan atas. Ada selembar kertas di dalam bungkusan biru itu. Aku baca pelan-pelan. Isinya begini:
“Joko, sudah setahun kau tak menghubungiku. Kau tak merindukanku, sayang? Namun, sebelum itu, aku mau berkata jujur kepadamu. Maaf jika membuatmu tersinggung,” begitu alinea awal. Dadaku bergemuruh.
Lantas, ia melanjutkan:
“Kepergianmu begitu mendadak. Kau membuatku tersiksa. Hatimu dipenuhi prasangka orientalisme yang sering kau katakan kepadaku dan itu tak benar belaka. Selain kata-kata itu menyepelekanku sebagai manusia Barat, kau selalu didera oleh inferiority complex yang menyedihkan.
“Aku mencintaimu layaknya kau dicintai oleh manusia Indonesia lainnya. Berbedakah caraku mencintaimu, sayang? Tak pernah aku menunjukan bahwa aku hanya terpesona oleh kisah-kisah eksotis yang selalu kau bilang kepadaku. Kau berkisah tentang rekan kerjamu yang menyebalkan saja aku jatuh cinta kepadamu. Tak harus kau bercerita tentang Yogyakarta dan Indonesia jika itu meninggalkan prasangka dalam hatimu.
“Jean adalah seorang homoseksual. Bukan biseksual. Kisah kami sudah berhenti sejak lama dan kau tak perlu khawatir perihal itu. Sebab itu, aku membaca Marcel Proust. Aku hanya mencoba memahami bagaimana posisi seorang homoseksual ketika melihat dunianya. Walau buku itu tak hanya menjelaskan tentang dunia seorang homoseksual.
“Kau benar, aku pernah mencintai Jean. Namun aku juga memahami ketika kami usai dan kami masing-masing menemukan cinta yang tepat. Dirinya dengan lelaki yang menurutnya sempurna, pun dengan diriku yang bertemu denganmu. Kau tahu, bagaimana rasa gemuruh dalam hatiku ketika kau ingin meminjam data transportasi beberapa tahun yang lalu? Data yang harusnya rahasia, waktu mingguku yang harusnya aku habiskan untuk membaca, kau rusak semua dan aku menyukai itu.
“Aku cari datamu di Kedutaan Indonesia yang berada di Paris. Pula aku meminta datamu di tempat kita bekerja dulu. Untuk itu, aku mohon maaf. Aku tak berusaha mengusik ketenanganmu seperti penguntit yang menyebalkan. Aku hanya ingin menyerahkan naskah novel yang kubuat. Terbit atau tidak naskah ini, tergantung denganmu. Karena naskah ini semua berhubungan denganmu.”
Tentu mudah bagi seorang Carla mendapatkan penerbit. Pengikutnya di media sosial begitu banyak. Selain itu, tulisan yang ia buat selalu bagus. Aku selalu menyukai apa yang ia tuliskan. Sindiran menyebalkan, seperti pembahasan orientalisme di atas, sempat membuatku tersinggung. Namun, aku bangga dengannya karena bisa menulis khas manusia Paris pada umumnya. Namun ini versi yang paling bagus di antara para Parisian.
Pada halaman pertama, tertulis bahwa inti cerita naskah ini adalah kisah seorang lelaki asal Yogyakarta yang berjibaku dengan uang. Dan uang membuatnya sampai ke Paris. Di sana, ia menemukan cintanya. Kecemburuan, rasa rendah diri, dan ekonomi adalah premis utama. Kisah yang amat hangat. Kisah yang amat kami sekali. Halaman berikutnya tertulis, “Bagaimana agar aku bisa menunjukkan rasa cintaku kepadamu? Apakah buku ini bisa membuatmu sedikit percaya bahwa aku mencintaimu? À Midi ou À Minuit.” Air memegang kepalaku, air mataku jatuh ke pipi. Aku menangis sesenggukan.
Paris 2024
Gusti Aditya, penulis lepas asal Yogyakarta. Tulisannya tersebar di berbagai media massa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo