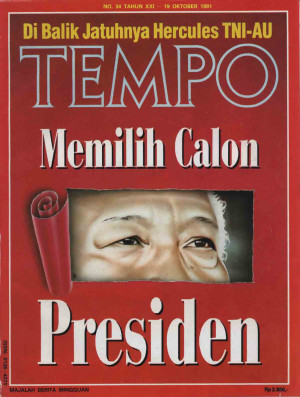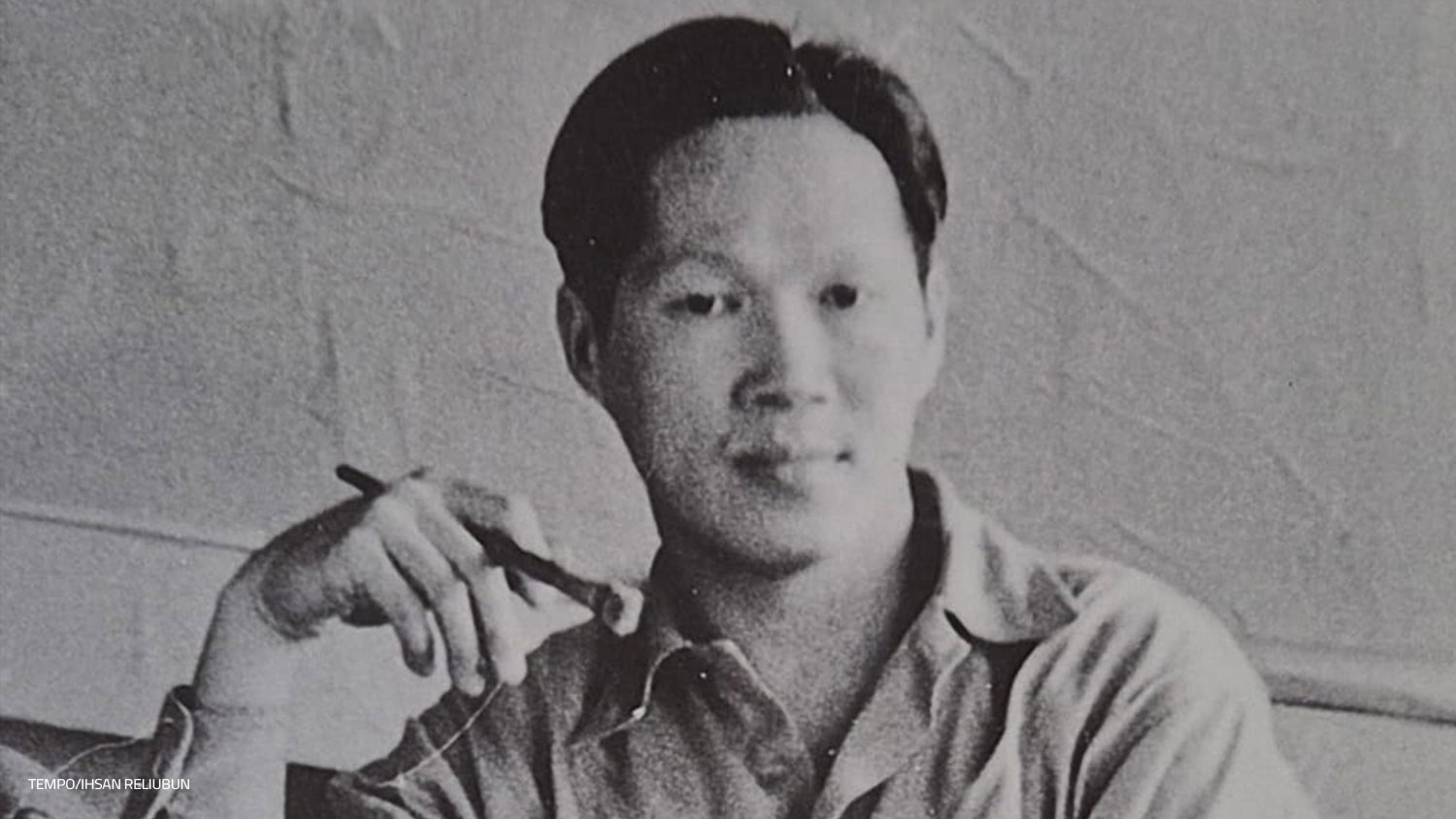Berbagai upaya ditempuh agar anak muda suka wayang. Semarang mementaskan wayang kolosal, Yogya menggelar wayang dengan sinar laser. Tapi ada yang tak suka. ORANG menyemut di Simpang Lima, Semarang. Sekitar 50.000 penonton tak beranjak sampai dini hari. Malam itu, Rabu pekan lalu, mereka riuh berkeplok dan tertawa ger-geran menyaksikan tontonan gratis: pergelaran wayang kulit dengan lakon Prahara di Teluk Mandura. Pergelaran ini dimotori Ki Haji Anom Suroto. Karena waktu pergelaran hanya enam jam, tidak semalam suntuk seperti lazimnya, acara unik ini disebut Enam Jam di Simpang Lima. Dalang dari Solo itu bahkan menyebutnya pergelaran kolosal, dan dengan dana besar pula. Antara lain dari dompet perkumpulan dalang Ganasidi dicomot biaya Rp 10 juta. Di Lapangan Pancasila itu dibuat pentas ukuran 40 x 15 meter, dipasang tiga layar dan tiga perangkat gamelan dengan 73 penabuh dan 21 pesinden. Wayangnya: tiga kotak wayang kulit sekaligus. Iringan gamelan juga unik, menampilkan seorang konduktor seperti halnya pada konser musik. "Pada pergelaran biasa, konduktornya adalah dalang dan penggendang. Tapi, pada pergelaran ini, peran itu tidak bisa dilakukan karena jumlah penabuh sangat banyak," kata Subono, sang konduktor, yang juga membuat aransemen gending. Setiap aspek pergelaran ini unik. Pada adegan goro-goro, ketika para punakawan sedang ndagel, gamelan pun tampil pula dengan "gending Inggris", My Bonnie, atau "gending" luar Jawa, Lembe-Lembe. "Gamelan itu mampu membawakan irama apa saja: jazz, cha-cha, mars," ujar dosen sekolah tinggi karawitan Solo itu. Tiga pelawak menambah gerr: Jujuk (primadona Srimulat), Didik Nini Thowok, dan Dirun (pelawak asal Ponorogo). Mereka disorot lampu, hingga bayang-bayangnya tampak di layar seperti wayang kulit. Seperti permainan lenong Betawi, mereka berdialog dengan dalang. Dialog-dialog itu umumnya memang banyolan untuk mengusir kantuk. Dan ketika tiba giliran Ki Anom Suroto mendalang, para penonton benar-benar melek terjaga. Dalang populer yang sangat laris ini melontarkan dialog yang berbau kritik sosial: "Baru dicalonkan saja, ada tokoh yang sudah minta dukungan, tapi setelah jadi, lupa pada wong cilik". Enam dalang dikerahkan pada pergelaran ini. Selain Ki Anom Suroto, yang juga bertindak sebagai sutradara, ada dalang cilik, putranya sendiri, Moh. Pamungkas Bayuaji. Ada pula dalang wanita, Nyi Suharni Sabdowati. Lainnya? Ki Sofyan Hadi Waluyo, Ki Mulyanto, Ki Purbo Asmoro. Mereka rata-rata terampil memperagakan sabetan. Dan masing-masing punya keistimewaan. Pergelaran yang berkisah menjelang pecahnya perang Bharata Yudha ini juga menampilkan duet dalang. Adegan raksasa Cakil melawan kesatria Abimanyu, misalnya, dimainkan secara duet oleh Ki Mulyanto dan Ki Purbo. Sambutan penonton meriah. Saking bergairahnya, penonton rela berlarian dari layar kiri ke kanan, dan sebaliknya. Tapi ternyata tak semua penggemar wayang menyukainya. Sukarman, 60 tahun, misalnya. Gemar nonton wayang sejak anak-anak, ia menyayangkan pergelaran ini hanya melulu menyuguhkan dagelan, tanpa piwulang atau ajaran hikmah kehidupan. "Saya lebih suka Ki Anom mendalang sendiri dengan sabetan yang lebih hidup," katanya. Bersama rekan-rekannya, ia mencarter truk dari Gunung pati, 20 km di selatan Semarang. Ada pula penonton, dari pinggir kota yang mencarter bus. Anak muda seperti Budi Maryono juga kurang menyukai pergelaran seperti ini. "Wayang kulit harus tampil sebagai wayang kulit. Jangan dimasuki unsur seni yang lain," katanya. Mahasiswa FS Universitas Diponegoro ini melihat pergelaran Enam Jam di Simpang Lima bukan sebagai pergelaran wayang kulit, tapi sebagai peristiwa kesenian kreatif "yang patut mendapat pujian". Yang jelas, Ki Anom dkk. tengah menarik simpati anak-anak muda terhadap seni pewayangan dengan berbagai upaya dan taktik. Upaya yang sama dilakukan pula oleh Sukasman. Dalang asal Yogya ini menggelar wayang kulit -- dan beberapa kali ditayangkan TVRI Yogya -- dengan cara yang tak lazim pula. Dimainkan sekitar dua jam, oleh dua dalang di belakang dan di depan layar ukuran 2 x 1 meter, wayang buatan sendiri ini disebut "wayang ukur". Disebut begitu karena, menurut Sukarman, yang pernah belajar di ASRI Yogya, proses pembuatan wayangnya melalui pengukuran-pengukuran berdasarkan apa yang ia sebut sebagai "hukum seni rupa". Maka, ia pun menamakannya wayang ukur. Beberapa bagian tubuh wayang ia ukur: garis wajah, lengan, kaki, pundak, dan seterusnya. Sementara pergelaran di Semarang menampilkan pelawak, wayang ukur gaya Sukasman mengikutsertakan penari. Pertunjukan diawali dan diakhiri dengan tarian, masing-masing ditarikan penari pria dan wanita. Selain dua dalang yang memainkan wayang, ada empat narator yang membawakan dialog, yang kadang melontarkan humor dan sindiran. Yang membikin pergelaran ini menarik ialah digunakannya sinar laser warna-warni dari berbagai penjuru ke arah layar. "Sinar dari belakang layar untuk mengurangi bayangan wayang," kata Sukasman, yang pada usia 50 tahun masih membujang. Sudah lama orang prihatin atas semakin tipisnya minat anak muda terhadap kesenian tradisional, sedangkan orang asing begitu bersemangat mempelajarinya. Bagaimana agar mereka mencintai seni pewayangan? Mungkin dengan cara memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk mempelajari seni pewayangan secara gratis. Budiman S. Hartoyo, Heddy Lugito dan Nanik Ismiani
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini