Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Pemerintah dan DPR diwanti-wanti untuk mematuhi dua putusan MK tentang UU Pilkada.
Sejumlah pakar menilai ada tiga skenario yang patut diwaspadai.
Jika pemerintah dan DPR tetap mbalelo, sanksi pun menanti.
SEJUMLAH pakar hukum tata negara mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengikuti dua putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas dan usia minimal pencalonan kepala daerah. Mereka khawatir kedua lembaga itu masih akan berakrobat, meski rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah batal terlaksana pada Kamis, 22 Agustus 2024. Baik DPR, pemerintah, maupun Komisi Pemilihan Umum dinilai bisa mendapat sanksi jika terus berupaya membegal putusan MK itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, menyatakan putusan MK tak bisa ditawar-tawar. Alasannya, hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Putusan MK itu harus dipatuhi dan langsung mengikat karena memang begitu dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MK itu sendiri," kata Denny saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Denny menyinggung soal Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Pasal itu menyatakan MK berwenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Aturan itu juga tertera dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa putusan MK bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 47 UU MK juga menegaskan sifat final tersebut dengan menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
Denny menjelaskan, dengan aturan-aturan itu, putusan MK bersifat self-executing. Artinya, putusan MK itu langsung berlaku ketika MK membuat putusan sehingga DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah undang-undang. "DPR dan pemerintah, ya, harus tunduk dan patuh karena itu adalah norma konstitusi yang mengatakan bahwa putusan MK itu final and binding," ujarnya.

Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sepakat dengan Denny. Dia menambahkan, putusan MK juga bersifat erga omnes atau mengikat bagi semua orang. Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan setingkat undang-undang sehingga harus dijalankan. "Kalau pembentuk UU, DPR dan pemerintah, menolak menjalankan putusan MK, itu sama dengan pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience)," kata Herdiansyah.
Dua putusan yang menjadi polemik itu tak lain adalah hasil uji materi terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf e dan Pasal 40 UU Pilkada. Pasal 7 ayat 2 huruf e mengatur batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun serta calon bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota minimal 25 tahun. Lalu Pasal 40 mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Permohonan uji materi Pasal 7 ayat 2 huruf e diajukan oleh mahasiswa hukum tata negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, A. Fahrur Rozi, dan mahasiswa Universitas Podomoro, Anthony Lee. Mereka mengajukan uji materi karena terdapat dua tafsir soal patokan penentuan batas usia tersebut.
Tafsir pertama berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan usia minimal 30 tahun itu dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara itu, tafsir kedua berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyatakan usia itu dihitung sejak pelantikan. Dalam putusan bernomor 70/PUU-XXII/2024, MK pun memutuskan batas usia itu terhitung sejak penetapan pasangan calon.
Putusan MK itu dianggap bisa membatalkan pencalonan putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Pasalnya, Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada Desember 2024 atau sekitar tiga bulan setelah penetapan pasangan calon kepala daerah.

Sementara itu, dalam uji materi Pasal 40 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, MK menurunkan ambang batas dukungan dari partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Awalnya, partai politik baru bisa mendukung pasangan calon kepala daerah jika memperoleh 20 persen kursi di dewan perwakilan rakyat daerah atau 25 persen suara sah hasil pemilihan umum sebelumnya. Dalam putusan bernomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengubah syarat itu menjadi didukung oleh partai politik dengan perolehan suara 6,5-10 persen dari total suara sah, bergantung pada jumlah warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap daerah tersebut.
Dalam rapat Badan Legislasi pada Rabu, 21 Agustus 2024, DPR memutuskan tidak mematuhi dua putusan MK itu. DPR justru tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam hal batas usia dan menyatakan ambang batas dukungan hanya berlaku untuk partai-partai yang tak memiliki kursi di DPRD. Mereka pun membawa hasil rapat Baleg itu ke rapat paripurna sehari setelahnya, yang kemudian batal karena tidak mencapai kuorum dan ancaman gelombang demonstrasi besar-besaran.
Setelah demonstrasi besar terjadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan RUU Pilkada diam-diam. Ia menegaskan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah pada Selasa pekan depan, 27 Agustus 2024. Kendati begitu, Dasco menyatakan revisi UU Pilkada berpotensi tetap dibahas seusai pilkada 2024. "Karena itu kan ada gugatan parliamentary threshold dari Perludem yang perlu diakomodasi," kata Dasco, Kamis, 22 Agustus 2024.
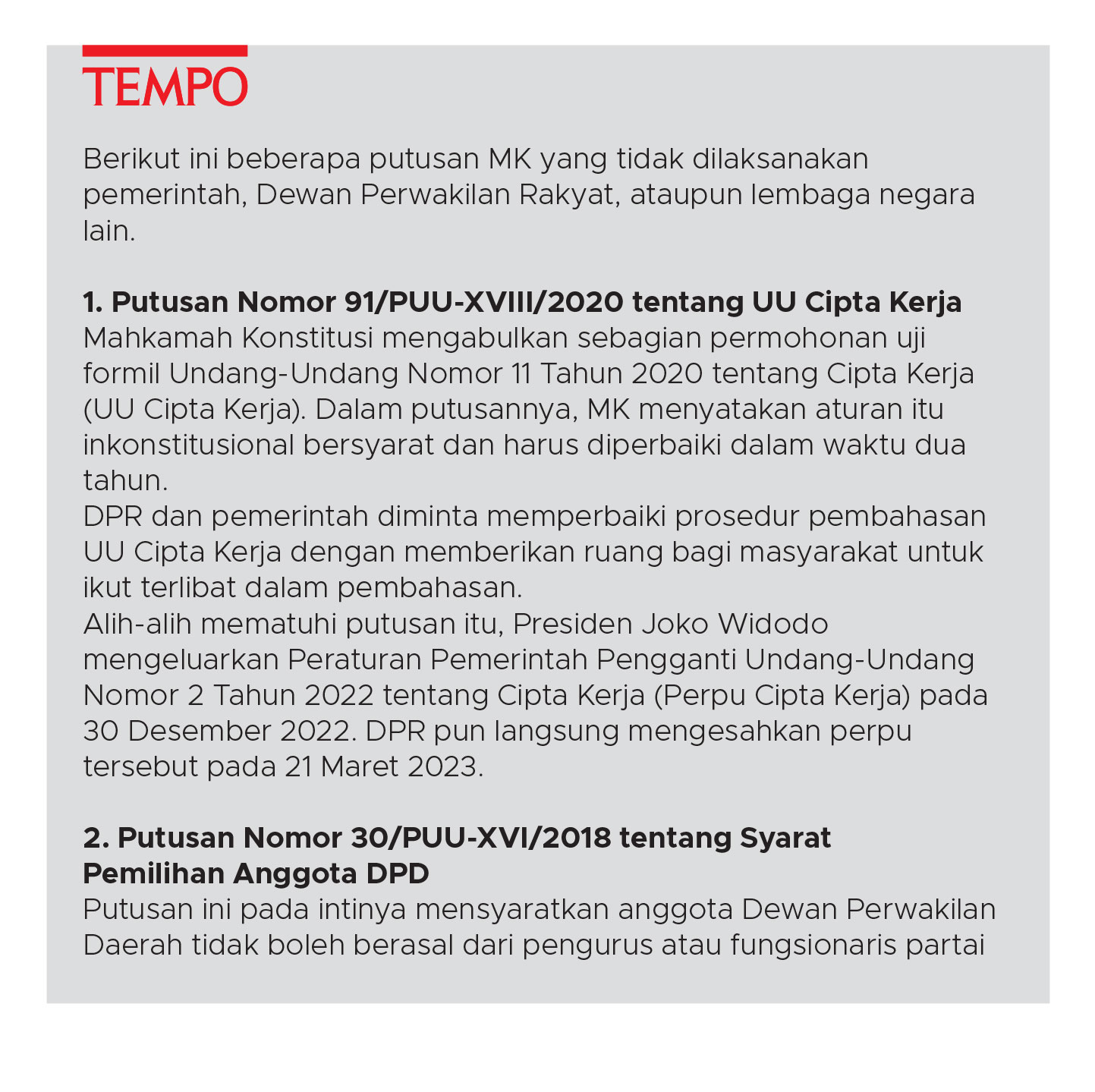
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia Neni Nur Hayati menilai DPR berpotensi terkena sanksi jika tetap mengesahkan RUU Pilkada yang tak sesuai dengan putusan MK. Dia menyatakan anggota yang ikut mengesahkan aturan itu bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena dianggap melanggar konstitusi. Hanya, dia pesimistis Badan Kehormatan DPR akan memproses laporan tersebut. "Tapi, di tengah pesimisme kita saat ini, tetap harus menghadirkan optimisme yang tinggi bahwa Dewan Etik DPR bisa bekerja secara independen dan profesional," kata Neni, kemarin.
Herdiansyah Hamzah pun menilai batalnya rapat paripurna tak menjamin DPR akan mematuhi putusan MK. Menurut dia, terdapat tiga skenario yang patut diwaspadai masyarakat. Pertama, DPR bisa saja menggelar rapat paripurna saat aksi massa melemah. Kedua, DPR dapat menekan KPU saat berkonsultasi tentang perubahan PKPU agar tak mengikuti putusan MK. Ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menjegal putusan MK. "Kartel politik ini akan menggunakan segala cara demi syahwat politiknya, termasuk opsi perpu," ucapnya.
Herdiansyah juga menyebutkan Jokowi bisa dimakzulkan jika mengeluarkan perpu yang isinya tak sesuai dengan putusan MK. Dia menilai hal itu bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi yang merupakan pelanggaran berat. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela serta apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hanya, dia menilai pemakzulan itu tak mudah karena harus melalui DPR, yang berada satu kubu dengan Presiden. “DPR di bawah kendali kartel politik Presiden. Siapa yang akan mengajukan?" ucapnya.
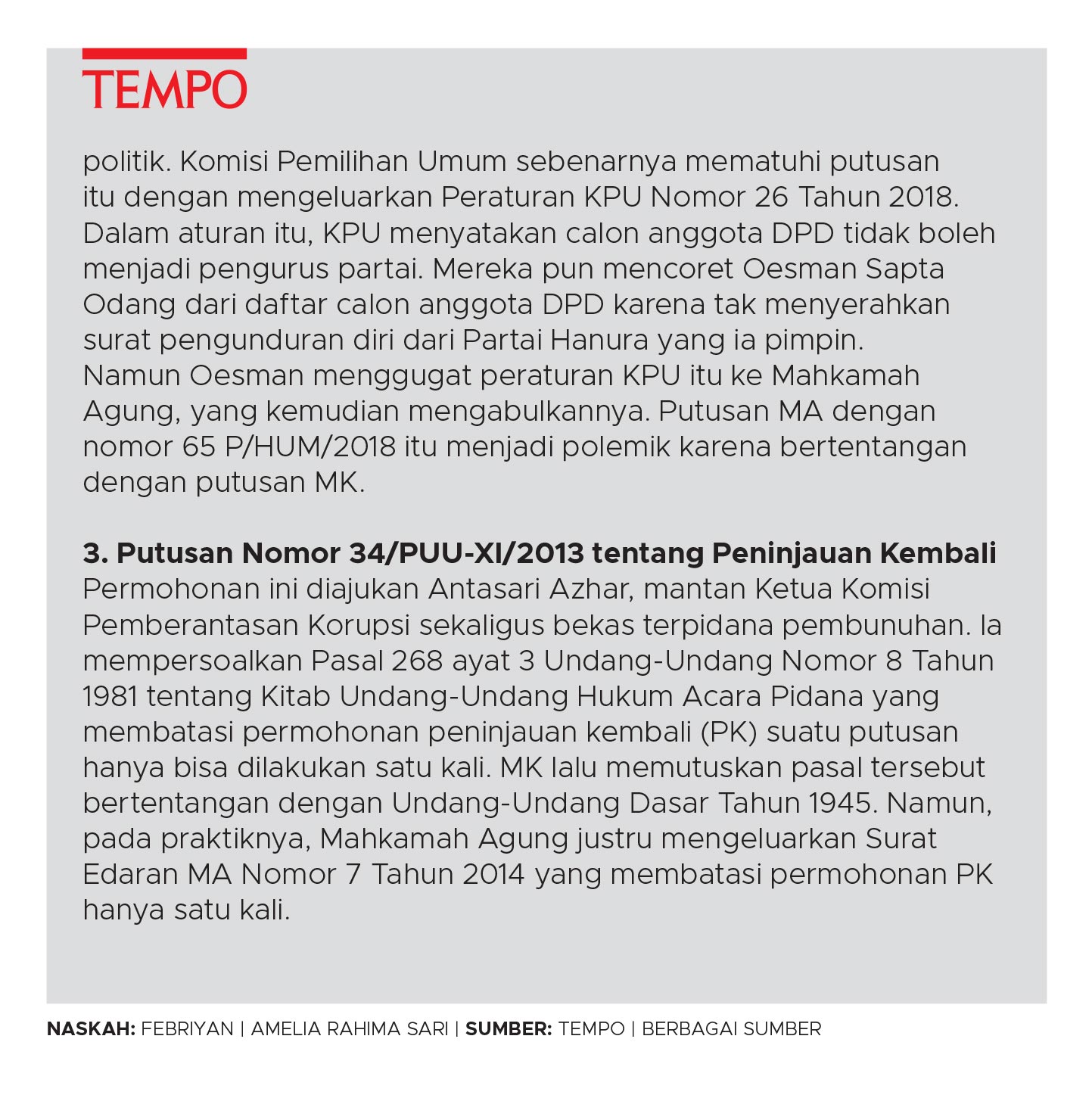
Pesimisme juga diungkapkan dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar. Ia menilai pemakzulan Presiden nyaris mustahil. Sebab, perlu ada peran partai politik. "Kalau partai politik mau impeachment Presiden, rasanya sudah dari dulu. Kan, enggak pernah," tuturnya.
Dosen hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, pun mewanti-wanti Jokowi untuk tak mengambil opsi mengeluarkan perpu. Alasannya, opsi itu akan memiliki konsekuensi yang sangat mahal. "Pasti akan terjadi kekacauan hukum dan ketidakpuasan massa yang meluas," katanya.
Sementara itu, peneliti dari Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Haykal, mewaspadai jika putusan MK tak masuk revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Namun Haykal menilai hal itu justru akan menjadi masalah bagi KPU sendiri. "Ketika KPU tidak mengakomodasi kedua putusan MK ini dalam PKPU yang nantinya dikeluarkan, KPU sangat berpotensi terkena sanksi etik," ucapnya, Jumat, 23 Agustus 2024.
Haykal menyinggung dua sanksi etik yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada KPU pada pemilu lalu. Saat itu KPU menerima sanksi berupa peringatan keras saat tak mengikuti putusan MA soal tata cara penghitungan kuota calon anggota legislatif perempuan. Selain itu, KPU mendapat sanksi peringatan keras terakhir karena mengubah PKPU soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Selain itu, Haykal menilai akan ada potensi gugatan terhadap hasil pilkada jika KPU tak mengakomodasi semua putusan MK.
Untuk sementara waktu, para pakar dan aktivis menyarankan masyarakat terus mengawal dua putusan MK tersebut dipatuhi oleh DPR dan pemerintah. Langkah yang bisa dilakukan adalah tetap bersuara. "Masyarakat tetap harus peduli dan gerakan massa tetap harus menunjukkan soliditasnya," ujar Titi Anggraini.
Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Ramadhan, mengungkapkan hal serupa. Ia mewanti-wanti agar rakyat terus mengawal. "Kejadian revisi UU Pilkada ini hanya sebagian kecil dari kelakuan serampangan pemerintah dan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi," kata Nur. "Masih banyak yang perlu rakyat kawal."
Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Antoni Putra, menilai perlu dibuat sebuah instrumen yang mampu memaksa agar putusan MK dijalankan dengan benar ke depannya. Hal itu, menurut dia, untuk mengantisipasi putusan MK dibelokkan oleh pemerintah, DPR, ataupun pihak lain. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.
Antoni menyarankan dua solusi, yakni menetapkan sanksi pidana dan memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi ke hierarki perundang-undangan. Kendati demikian, dia menyatakan penerapan sanksi pidana mungkin sulit dilakukan. Sebab, dalam sejarah, belum ada negara yang telah menerapkannya sebagai model yang bisa dijadikan acuan. "Solusi yang paling relevan saat ini mungkin memasukkan putusan MK ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dengan menempatkan putusan tersebut di atas undang-undang atau perpu," ujarnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Hendrik Yaputra dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
































