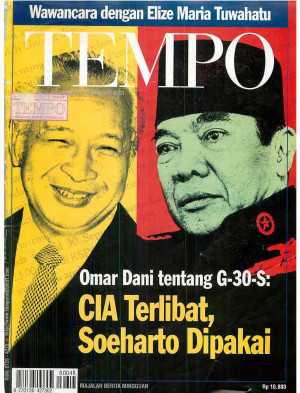SUDAH agak lama sejumlah besar negara berkembang menyaksikan lonjakan gerakan antikorupsi yang dipimpin berbagai kekuatan sosial. Basis sosial gerakan-gerakan ini tak pernah dikaji secara tuntas. Yang ada hanya hipotesis umum bahwa ia merupakan ekspresi lambat dari suatu masyarakat madani (civil society) yang bertujuan memperbaiki pengaturan (governance) perekonomian mereka.
Yang jadi soal adalah munculnya keyakinan bahwa mobilisasi civil society di bawah panji-panji antikorupsi akan secara nyata mengurangi korupsi di negara-negara tersebut.
Istilah civil society berasal dari alam pikiran Barat-liberal, menggambarkan suatu masyarakat yang mapan dalam jaringan hubungan sosial dan ekonomi serta norma kepatutan tertentu. Jaringan itu sudah lama diterima luas di Barat, dan sudah berkesempatan dikembangkan berdasarkan dinamika konsensus bersama, dan kemudian diresmikan dalam sistem hukum. Seperti barang impor lainnya dari Barat, konsep civil society langsung diterima oleh para aktivis di negara berkembang dan dipakai sebagai cap untuk aspirasi yang dibawa oleh gerakan swadaya masyarakat.
Civil society dalam pengertian aslinya hanya akan tumbuh di negara berkembang bila pertumbuhan ekonomi sedemikian lajunya sehingga melahirkan suatu kelas menengah modern di sektor profesi dan jasa. Kelas menengah baru inilah yang membunyikan lonceng pertanda lahirnya era baru yang tak sudi lagi hidup di bawah sistem "bapak-anak buah" (patron-client relations). Ini terjadi di Thailand dan Korea Selatan, tapi tidak terjadi di India, Pakistan, atau Bangladesh.
Siklus korupsi
Di India, Pakistan, dan Bangladesh, pembangunan ekonomi belum mencapai tingkat yang memungkinkan pemerintahnya mampu membiayai program kesejahteraan umum. Penerimaan pajak belum mampu mendukung prasarana dasar umum, apalagi pembagian rezeki secara transparan yang diharapkan menjamin adanya stabilitas politik.
Sementara itu, cekcok dan perpecahan di kalangan elite menjadi-jadi karena keresahan akan lambannya pertumbuhan ekonomi. Struktur dasar "bapak-anak buah" dalam keadaan seperti itu tidak tumbuh ke arah demokrasi sosial yang modern dan transparan. Pertumbuhannya justru mengarah ke jurusan desentralisasi manajemen stabilitas politik yang agak kacau dan dikendalikan oleh pemerintah daerah.
Pada tahun 1980-an dan 1990-an berkali-kali muncul gerakan antikorupsi di India, Pakistan, dan Bangladesh. Gerakan-gerakan ini didukung oleh pelbagai kelompok yang dipimpin oleh orang-orang dari golongan menengah.
Mereka selalu sukses. Pemimpin yang korup diganti. Tapi struktur dan pola sosial tidak berubah. Tak lama setelah pergantian para pemimpin, muncul lagi tuduhan korupsi terhadap rezim baru. Begitulah roda berputar tanpa henti.
Masalah Pokok
Dalam kebanyakan masyarakat negara berkembang, sistem kapitalistis yang baru muncul belum diterima luas dan tidak didukung oleh stabilitas politik. Selain itu, negara tidak cukup kuat untuk memaksakan penegakan ketertiban.
"Dalam keadaan semacam ini jaringan bapak-anak buahlah yang mengatur pembagian rezeki," kata Mushtaq H. Khan dalam The Role of Civil Society and Patron-Client Networks in the Analysis of Corruption, makalah di konferensi tentang korupsi, Paris, 1997. "Stabilitas politik `dibeli' dengan pembagian rezeki hasil korupsi."
Dalam kancah inilah terjun sejumlah LSM yang menuntut diakhirinya korupsi. Sementara itu, perubahan sosial tak kunjung tiba. Apa gerangan akibatnya kalau gelanggang yang sudah begitu padat dengan pemain dimasuki oleh para pemain baru yang menuntut agar permainan dihentikan?
Mungkin mereka akan masuk ke bawah tanah atau menciptakan bentuk-bentuk baru korupsi. Sebab, maling lebih kreatif daripada polisi. Lagipula, sumber rezeki terbatas, yang menagih terlalu banyak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini