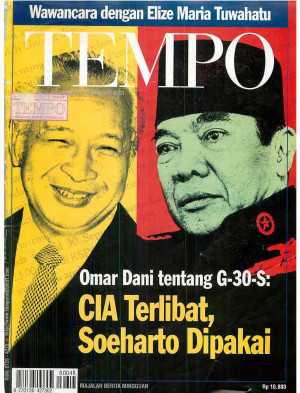Tidak perlu diragukan lagi, saya memimpin langsung pemberantasan korupsi," ujar Presiden Soeharto dalam pidato 17 Agustus 1970 di DPR-GR. Jenderal yang baru dua tahun dikukuhkan sebagai presiden itu menekankan, korupsi tidak dapat dibiarkan. Korupsi merugikan keuangan negara, yang berarti merugikan rakyat, membahayakan pembangunan, bertentangan dengan hukum, berlawanan dengan moral dan rasa keadilan.
Pada 2 Desember 1967, enam bulan setelah diangkat oleh MPRS sebagai penjabat presiden, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) untuk membantu pemerintah memberantas korupsi "secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya". TPK diketuai Jaksa Agung Letjen Soegih Arto.
Media massa, yang pada awal Orde Baru menikmati kebebasan, ramai memberitakan penyelewangan yang diduga melibatkan karyawan ABRI. Adanya "jenderal-jenderal yang kebal hukum" pun sudah diributkan. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD (kini Kopassus), yang ketika itu sangat dekat dengan Soeharto dan mahasiswa, menyarankan kepada Presiden agar empat jenderal ditindak demi menjaga nama baik ABRI. Sarwo Edhie dipindahkan menjadi Panglima Kodam di luar Jawa.
Skandal besar yang melibatkan jenderal-jenderal sahabat Soeharto adalah kasus Coopa (pupuk untuk Bimas) dan Pertamina. Pada Februari 1970 rapat pimpinan ABRI memanggil Direktur Utama Pertamina, Letjen Ibnu Sutowo, untuk memberikan pertanggungjawaban. Kasus Coopa dan Pertamina tak pernah sampai ke pengadilan.
Jaksa Agung Tersinggung
Suatu hari pada bulan Agustus 1970, Jaksa Agung Soegih Arto dengan marah meninggalkan pertemuan dengan kelompok Angkatan Muda yang mau menyampaikan kepadanya Piagam Penghargaan Pahlawan Nasional dan Bintang Emas Penegak Hukum. Ejekan ini disampaikan lantaran Jaksa Agung selaku Ketua TPK "dengan keberanian yang luar biasa berhasil menyeret sembilan pelaku korupsi ke pengadilan".
Sembilan koruptor itu terbukti menggelapkan uang negara Rp 150 hingga Rp 35.000. Padahal, dua bulan sebelumnya Kejaksaan Agung membebaskan Arief Husni, pelaku utama kasus Coopa, yang merugikan program swasembada pangan nasional.
Harian KAMI (26 Agustus 1970) menurunkan editorial berjudul 9 Koruptor, 5 Perkara, dan 2 Sila. "Sebagai respons terhadap gelora antikorupsi," tulisnya, "pendekar-pendekar kita di TPK telah membekuk, menghantam, dan mematikan tidak kurang dari 9 orang koruptor." Lalu para koruptor itu dirinci: Moh. Jusuf, 46 tahun, selama 1967-1968 melakukan korupsi Rp 30.000, sama dengan 60 kilogram beras sebulan untuk dimakan anak-anaknya yang lapar; Alexander Johannes, 67 tahun, mengorupsi Rp 32.000, senilai 21 slof State Express yang merupakan rokok "status" para pembesar kita.
Raden Matheus Sumardi, 31 tahun, melakukan "penggelapan dan penipuan" Rp 150, sama dengan lima bungkus gado-gado di pinggir jalan; Abdulkadir, 41 tahun, melakukan korupsi Rp 1.500, seharga selembar kemeja buat hari lebaran; Sudjadi, 33 tahun, korupsi Rp 700, senilai sembilan bungkus rokok Davros; Djajadi, 36 tahun, korupsi Rp 35.000, seharga dua kaca mata Persol yang biasa dipakai para pembesar kita.
Tiga koruptor lainnya: Sadeli, 31 tahun, korupsi Rp 500, senilai 10 kilogram beras; Raden Harry Suharno, 38 tahun, korupsi Rp 24.000, senilai 12 kaset pita tape recorder Philips untuk mobil sedan anak-anak pembesar yang mau "pacaran" ke Bina Ria dengan iringan musik romantis; Zainal Arifin, 42 tahun, juru ketik yang melakukan korupsi Rp 1.500, senilai 50 liter bensin premium untuk Mercedes-Benz pembesar yang mau ber-weekend di Puncak.
Harian KAMI lalu berpesan kepada para terdakwa: "Kalau Saudara-saudara digantung, bersama Saudara-saudara digantung pula dua sila dari dasar negara ini: Keadilan Sosial dan Perikemanusiaan. Sungguh berat bagi si lemah untuk hidup di negara yang kejam ini."
Undang-undang & operasi
Pada masa Sukarno, kampanye pemberantasan korupsi justru dipelopori oleh Angkatan Darat, yakni pada saat berlakunya keadaan darurat perang. Undang-undang antikorupsi belum ada, kecuali sanksi KUHP yang mengadopsi pasal hukum zaman kolonial.
Gerakan pembasmian korupsi ditetapkan melalui peraturan Kepala Staf AD selaku Penguasa Militer "di daerah kekuasaan Angkatan Darat". Lalu pada 1958 gerakan ini bercakupan nasional melalui peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) No. 013, setelah MKN/KSAD menjadi Penguasa Perang Pusat. Isinya meliputi pengusutan, penuntutan, pemeriksaan pidana korupsi, dan penilikan harta benda.
Baru pada 1960 muncul peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi Undang-Undang No. 24/1960. Sementara itu, militer tetap melancarkan Operasi Budhi, khususnya untuk mengusut karyawan ABRI yang tak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. Operasi Budhi antara lain mengusut Mayor Suhardiman (kini mayjen TNI purn.). Ia bebas dari dakwaan.
Akhir 1967 Soeharto membentuk TPK yang dasar hukumnya masih tetap UU No. 24/1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain. Hasil kerja orang-orang part-timer inilah yang kemudian menyeret sembilan "koruptor" tadi.
Presiden Soeharto membentuk Komisi 4 pada Januari 1971, untuk memberikan "penilaian obyektif" terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan "pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi". Mantan wakil presiden Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi 4. Anggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, I.J. Kasimo, Prof. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Kepala Bakin Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris.
Siswadji dan Budiadji
Di luaran, mahasiswa menggencarkan kampanye antikorupsi dengan berdemontrasi, membentuk Komite Anti-Korupsi (KAK), Mahasiswa Menggugat (MM), serta menggelar pelbagai forum yang mengundang para pembicara tentang korupsi.
Pada awal 1970-an itu Soeharto masih bersedia menerima delegasi mahasiswa dan kelompok masyarakat, baik di Bina Graha maupun di Jalan Cendana. Maret 1971 lahirlah UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK), yang bertahan selama 28 tahun, sampai munculnya UU No. 31/1999 pada masa Habibie.
Pada masa Soeharto, wakil presiden diberi peran pengawasan, sementara presiden sendiri masih dibantu oleh tiga inspektur jenderal pembangunan (irjenbang). Kendati sudah ada lembaga tinggi negara (Badan Pemeriksa Keuangan), pemerintah merasa perlu membentuk BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan (dan Lingkungan Hidup, PPLH).
Meski sudah ada undang-undang dan lembaga penegak hukum yang seharusnya menindak koruptor, pemerintah tetap merasa perlu mengerahkan Kopkamtib dan Laksusda (Pelaksana Khusus Kopkamtib Daerah yaitu kodam) untuk melaksanakan Operasi Tertib memberantas korupsi, manipulasi, dan pungutan liar. Opstib yang dibentuk pada September 1977 itu bergerak dengan jaringan Satgas Intel Kopkamtib. Di setiap provinsi dan inspektorat jenderal departemen ditempatkan inspektur Opstib untuk "mendinamisir" pengawasan.
Khusus untuk penyelundupan dan penggelapan di bea cukai dan perdagangan ekspor-impor, dilancarkan pula Operasi 902 (tahun 1976). Operasi ini di bawah kendali Jaksa Agung. Namun, banyak perkara 902 kandas di pengadilan. Istilah "mafia peradilan" mulai banyak disebut.
Begitupun, selama Orde Baru hanya satu pejabat tinggi yang dipenjarakan karena korupsi, yaitu Deputi Kapolri Letjen (Pol.) Siswadji (1977, divonis delapan tahun). Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kalimantan Timur, Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (grasi Presiden menguranginya menjadi 20 tahun). "Warlord" beras itu menilep uang negara Rp 7,6 miliar?jumlah yang kala itu menggemparkan. Selebihnya, yang dihukum adalah para koruptor lapis kedua dan rendahan.
Pernyataan & Ikrar
Lepas dari kadar prestasi yang dicapai dan lolosnya orang-orang dekat Soeharto, dan kendati Newsweek menulis bahwa pemerintahan Soeharto telah korup sejak hari pertama, bagaimanapun pemerintahan Orde Baru masih ditandai adanya upaya sistematis demi menunjukkan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu khususnya berlangsung selama Kabinet I (1968-1973) sampai IV (1983-1988). Kita masih membaca berita media berisi laporan resmi tentang temuan korupsi dan penanganan perkaranya.
Ada laporan tahunan Kejaksaan Agung, laporan berkala Opstib, serta pengungkapan penertiban ke dalam oleh departemen pemerintah setiap apel bendera tanggal 17. Kantor Wakil Presiden juga membuka Kotak Pos 5000 untuk menampung pengaduan masyarakat.
Mengawali Kabinet Pembangunan III (1978-1983), misalnya, para menteri dan pejabat eselon I pemerintahan harus menyampaikan laporan pajak kekayaan pribadi ke Presiden. Pejabat eselon II harus melaporkan pajak kekayaannya ke menteri. Pada awal periode ke-4 pemerintahannya (1983), Soeharto dalam pidato kenegaraan di DPR menegaskan "tidak akan setengah-setengah dalam membasmi korupsi".
Walau Opstib telah menyelamatkan uang negara Rp 200 miliar dan menindak 6.000 pegawai selama 1977-1981, dan setiap selambatnya tiga bulan melaporkan ke Presiden penertiban di departemen dan jawatan pemerintah, toh Ketua BPK Umar Wirahadikusumah menyatakan bahwa "tidak ada satu pun departemen yang bersih dari korupsi". Sebulan kemudian, November 1981, Wakil Presiden Adam Malik menimpali bahwa "korupsi sudah epidemik".
Dan Ketua DPR RI Daryatmo tidak yakin pemerintah sanggup menumpas tuntas korupsi. "Saya ingin tanya, apa ada satu negara atau pemerintahan di dunia ini yang bisa memberantas korupsi secara tuntas?" tambahnya dengan empatik. "Kalau ada, kepala negara yang bersangkutan akan saya sewa untuk jadi presiden di sini." Itu dikatakannya pada 1979.
Sampai 2001 ini, orang yang ingin disewa Daryatmo tak kunjung kita dapatkan.
(Daud Sinjal)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini