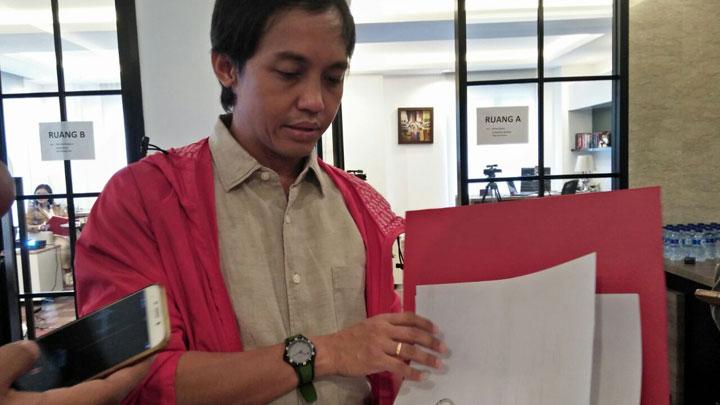Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bandung Mawardi
Kuncen Bilik Literasi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari ini, jutaan orang mendatangi bilik suara. Kita mendingan menanti waktu pencoblosan dengan membuka album pemilihan umum masa lalu. Mari kita mulai membuka album pemilu bertahun 1955. Kita mengutip studi apik Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (1999).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kita disuguhkan penggalan studi yang penting dibaca lagi hari ini. “Pada hari pemungutan suara, muncul suasana yang mencolok. Sebelum tempat-tempat pemungutan suara dibuka, para pemilih sudah datang. Pukul tujuh pagi sudah banyak orang yang berkumpul di setiap tempat pemungutan suara, dan pada pukul delapan semua pemilih telah siap di tempat. Jumlah orang yang berkumpul sungguh mengherankan. Seluruh keluarga datang, termasuk orang-orang tua yang sakit dan anak-anak. Perempuan yang hamil tua juga datang, bahkan ada yang melahirkan di tempat pemungutan suara. Banyak dari penduduk desa yang hadir itu sudah lama meninggalkan kampungnya. Dan semuanya berpakaian bagus.”
Kita mengimajinasikan “pakaian bagus” itu seperti mau datang ke kondangan. Pakaian bagus tak dijelaskan Feith ihwal bahan, motif, dan warna. Kita mengingat saja cara berpakaian masyarakat itu membuktikan bahwa pemilu itu dihormati dan penting bagi nasib Indonesia. Mereka pun belum tentu sudah bisa membaca-menulis. Pada 1955, para pemberi suara adalah orang-orang yang belum direcoki kata dan gambar di media sosial seperti sekarang. Mereka lugu, bijak, dan lugas, meski dicap oleh pemerintah belum mentas dari program kolosal “pemberantasan buta huruf” atas perintah Presiden Sukarno. Isi album dari 1955 itu mengharukan. Kita masih sulit mengulangnya dalam pemilu bertahun 2019.
Kita beralih ke pemilu setelah malapetaka 1965-1966. Pemilu disambut gempita oleh elite politik, kaum mahasiswa, para jelata, dan golongan saudagar yang sempat bermimpi demokrasi kembali terang. Di mata mereka, Soeharto mampu memberi godaan menjadikan Indonesia membangun dan makmur. “Sempat” itu lekas mendapat ralat. Sekian orang malah mulai bersumpah melawan Soeharto setelah istirahat sejenak dari melawan Sukarno.
Album dari 1971 kita ambil dari majalah hiburan bernama Varia. Majalah itu laris dan khas dengan foto-foto perempuan seksi. Kita membuka Varia edisi Juni 1971. Di bawah editorial, pembaca disuguhi foto artis Aida Mustafa. Di samping foto, kita diminta membaca lirik lagu tentang pemilu. Lagu memihak secara mistis dan politis. Lagu berjudul Pohon Beringin itu terasa berlebihan, tapi boleh diingat untuk mengerti kebesaran golongan itu selama rezim Orde Baru.
Album yang paling penting adalah di halaman belakang majalah Varia: “Sajembara Pemilu-Varia”. Majalah itu mengadakan sayembara bagi para pembaca untuk memeriahkan pemilu. Pesta demokrasi itu berhadiah. Pembaca dapat meramalkan: “Partai/golongan manakah, menurut dugaan Anda, akan memperoleh djumlah suara jang terbanjak dalam Pemilihan Umum nanti?”. Jawaban ditulis di formulir untuk dikirimkan ke redaksi majalah.
Hadiah utamanya adalah piknik ke Jakarta sebagai tamu majalah Varia bagi pemenang yang tinggal di kota-kota lain. Pemenang dari Jakarta bisa minta ganti pelesiran ke Bali. Hadiah hiburan adalah duit Rp 5 untuk tiga pemenang. Pemilu pun memberi kegembiraan kepada warga, bukan bertengkar atau saling membenci. Pemilu itu adalah partisipasi dan hadiah.
Pemilu 1977 diikuti tiga peserta: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Kita mengenang ada nalar dominatif di hajatan demokrasi. Pemilu ini sudah tampak ada penciptaan drama demi kemenangan dan kemapanan kekuasaan. Pesta demokrasi diceritakan pemerintah untuk pembuktian kebebasan berpendapat dan bersuara meski ada jebakan dan jeratan. Pemilu itu sudah memiliki tumpukan laporan kecurangan. Demokrasi pun ternoda.
Goenawan Mohamad menulis di rubrik “Catatan Pinggir” Tempo, 19 Maret 1977. Tulisan itu kritis dan sinis. Pembaca mungkin menemukan pula lelucon. Goenawan mengajukan tokoh muda yang bernafsu politik selama dua tahun, 1976 dan 1977. Kita mulai dengan pengakuan seorang pemuda pada 1976: “Sudah sekian tahun saya tak pernah naik bus kota. Tapi pagi itu mobil mogok di tengah jalan dan tak ada taksi. Maka saya cegat bus. Di dalamnya saya ketemu rakyat.”
Tokoh muda itu anggota parlemen, tapi lupa atau emoh bekerja. Pada 1977, ia berkampanye untuk bertahan di parlemen dengan pengakuan aneh di muka orang ramai: “Saudara-saudara, saya adalah murid saudara-saudara. Maafkanlah justa saya. Saya telah bertemu dengan rakyat, dan ternyata ia bukan anak-anak....”
Kita cukupkan dulu membuka album pemilu masa lalu. Pembaca diharapkan tak terlalu menuntut harus ada ribuan kliping dimasukkan ke album. Tuntutan itu mustahil dipenuhi. Pembaca boleh membuat pertimbangan setelah membaca buku berjudul Politik tanpa Dokumen (2018) garapan Muhidin M. Dahlan. Pengarsip partikelir itu membuktikan bahwa politik di Indonesia (sungguh-sungguh) tanpa kerja dokumen(tasi). Pemilu, dari masa ke masa, meninggalkan sesalan terbesar gara-gara ketiadaan arsip lengkap.