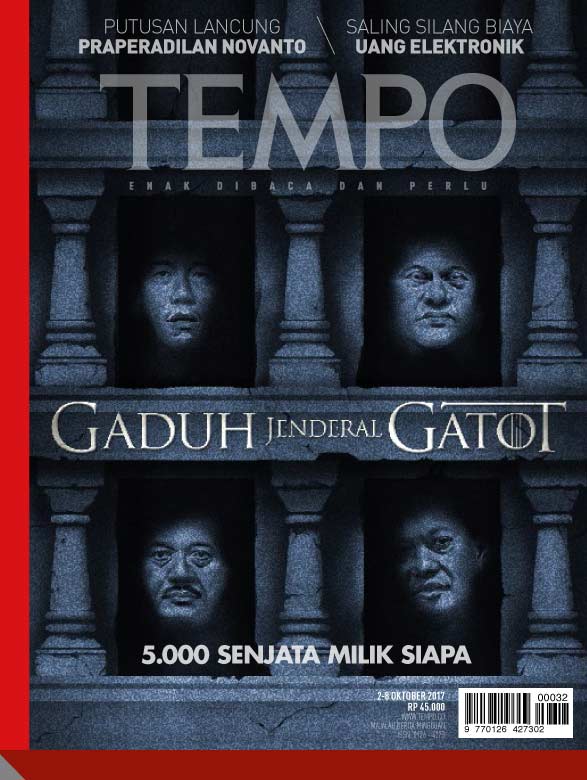Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Masa lalu tak selalu memberi cerita girang. Pada saat Balai Pustaka menjalankan peran menerbitkan buku-buku di naungan pemerintah kolonial Belanda (akhir September 1917), kegandrungan belum memusat ke bahasa Melayu, sebelum menjadi bahasa Indonesia. Penerbit itu memilih menerbitkan buku-buku berbahasa Jawa dan Sunda. Buku untuk memberi bukti gerak "kemadjoean" di tanah jajahan dan membentuk pembakuan bahasa sesuai dengan selera pemerintah.
Pilihan menerbitkan buku-buku berbahasa Jawa dengan aksara Jawa dan Latin mengacu pada peningkatan jumlah pembaca di Jawa. Sekolah-sekolah modern telah memberi keajaiban berupa kemunculan umat pembaca. J.J. Ras (1985) menuduh penerbitan buku-buku sastra Jawa oleh Balai Pustaka mementingkan kandungan moral atau budi pekerti. Penggunaan bahasa Jawa mulai memiliki patokan-patokan untuk ditetapkan dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Sebaran bacaan dari Balai Pustaka memungkinkan tata bahasa Jawa lekas dipahami dan dibakukan. Pada masa lalu, Balai Pustaka tak cuma penerbit buku, tapi memiliki peran dalam pembakuan bahasa.
Kebijakan Balai Pustaka berubah setelah bahasa Melayu dipilih dalam pelbagai terbitan surat kabar. Ketenaran bahasa Melayu dijadikan dalih meningkatkan jumlah penerbitan buku berbahasa Melayu, bersaing dengan buku berbahasa Jawa dan Sunda. Balai Pustaka memiliki sikap mendua dalam penerbitan buku berbahasa Melayu. Keinginan mengembangkan dijejali pamrih kodifikasi. Penguatan pamrih bertanding dengan penerbit-penerbit partikelir. Bahasa telah jadi pilihan dalam perseteruan ideologi, sastra, identitas, dan pendidikan.
Pemerintah melalui Balai Pustaka memastikan ingin membuat perbedaan tingkat penggunaan bahasa Melayu. Edisi resmi terbitan Balai Pustaka mengaku berbahasa Melayu dalam tingkat tinggi ketimbang buku-buku terbitan kalangan peranakan Tionghoa dan bumiputra. Atribut-atribut membedakan tingkatan bahasa Melayu mengakibatkan perlawanan-perlawanan. Balai Pustaka membesarkan peran kolonialistik. Di luar kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, bahasa Melayu bergerak menjadi bahasa Indonesia untuk melawan kuasa Balai Pustaka (Faruk, 2007). Bahasa Indonesia pun ada di sengketa panjang dalam penggunaan di garapan sastra dan buku-buku pendidikan-pengajaran.
Naskah dari para pengarang yang bekerja sebagai guru sering masuk ke Balai Pustaka. Naskah mereka harus mengalami perbaikan yang mengacu ke dalil-dalil kebahasaan penerbit. Jassin (1992) mengingat ada dua tokoh terpenting dalam mendandani dan membentuk bahasa Indonesia di Balai Pustaka: Nur Sutan Iskandar dan Aman Datuk Madjoindo. Penerbitan buku cerita berlatar Jawa, Sunda, Bali, Maluku, dan Sulawesi terasa aneh saat bahasa Indonesia mengalami olahan para redaktur bahasa yang berasal dari Minangkabau. Buku-buku sastra terjemahan pun bercita rasa bahasa yang sesuai dengan selera editor, bukan bahasa Indonesia yang bertumbuh dan bergerak di luar Balai Pustaka.
Balai Pustaka kukuh sebagai penerbit besar sejak 1917 sampai masa Orde Baru. Pada peringatan 70 tahun Balai Pustaka, Sutan Takdir Alisjahbana (STA) memberi kritik bahwa posisi Balai Pustaka terlalu "resmi". Peran Balai Pustaka tampak menuruti kemauan pemerintah ketimbang membuat gerakan-gerakan intelektual dan peradaban. Kritik itu hendak dibandingkan dengan pengalaman STA saat mulai bekerja sebagai redaktur di Balai Pustaka, 1929. Pengarang novel Lajar Terkembang itu mengenang saat mendaftar ke Balai Pustaka: "Kesan saya ketika itu, bahasa saya berbeda dari bahasa Balai Pustaka yang dibawa oleh kebanyakan orang Minangkabau, berdiploma guru, tidak begitu menguasai bahasa Belanda." STA mengaku menulis dengan bahasa Melayu bercita rasa Belanda. Cara dan sikap berbahasa itu mempengaruhi penerimaan bekerja di Balai Pustaka.
Pada masa berbeda, STA memberi saran ke Balai Pustaka agar sering menerbitkan buku terjemahan, bermaksud ke usaha mendewasakan bahasa Indonesia (Tempo, 26 September 1987). Usul STA seperti igauan tak tepat waktu. Buku terjemahan untuk sastra dunia semakin jarang diterbitkan Balai Pustaka. Kita justru mengenal Balai Pustaka sebagai penerbit buku pelajaran ketimbang meraih kehormatan dengan penerbitan buku-buku sastra bermutu. Bahasa Indonesia tak terlalu menjadi urusan terbesar meski Balai Pustaka menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada 1980-an, redaksi kebahasaan di penerbit-penerbit partikelir cenderung menggirangkan ketimbang Balai Pustaka. Nostalgia kebahasaan malah dikerjakan Balai Pustaka melalui cetak ulang novel-novel dari Marah Roesli, Abdoel Moeis, dan STA. Bahasa Indonesia berselera "lama", tak lagi memberi gairah saat Indonesia mau melintasi abad XX. Pada 2017, Balai Pustaka berusia 100 tahun: semakin tua tanpa bergirang bahasa. l
Bandung Mawardi
Pengelola Jagat Abjad Solo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo