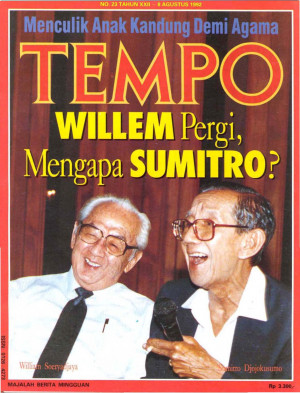BANYAK indikator ekonomi yang amat dikenal masyarakat. Inflasi yang tinggi segera dirasakan oleh masyarakat bisnis hingga ibu-ibu rumah tangga. Untuk kalangan terbatas, perubahan nilai rupiah terhadap dolar menjadi perhatian penting, karena kurs devisa ini mempengaruhi nilai impor bagi perusahaan yang memerlukan barang dari luar negeri. Di pihak lain, bila Pemerintah maupun para ekonom berbicara tentang defisit neraca transaksi berjalan, reaksi masyarakat amat terbatas. Padahal, defisit neraca transaksi berjalan adalah defisit neraca perdagangan dan neraca jasa-jasa faktor produksi dan nonfaktor produksi dalam tahun berjalan. Dana Moneter International (IMF) memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan untuk tahun fiskal 1991-1992 adalah US$ 5 milyar. Ini merupakan lonjakan dari defisit tahun fiskal 1990-1991 yang berjumlah US$ 4,2 milyar. Apa bahayanya defisit neraca transaksi berjalan yang membengkak? Pertama, kita harus mendalami dulu konsep neraca transaksi berjalan dengan membahas komponen-komponen penting yang menjadi unsur dari neraca itu. Satu komponen penting adalah besarnya lonjakan impor, dan tidak tampak tanda-tanda pengurangannya. Dari tahun fiskal 1989-1990 ke 1990-1991, menurut IMF, impor bukan migas melonjak dari US$ 16,5 milyar menjadi US$ 21,6 milyar. Untuk 1991-1992 pun akan terjadi peningkatan impor yang sebagian besar adalah impor barang modal dan bahan baku. Untuk itu, amat perlu mengkaji ulang apa yang dikenal sebagai konsep domestic resource cost. Konsep ini, misalnya, bisa menghitung berapa rupiah biaya (cost) untuk setiap dolar yang dihemat. Ini penting karena pada industri otomotif, misalnya, larangan impor mobil CKD (completely knocked down) dan adanya industri mobil, baik niaga maupun sedan, tidak mengurangi tingginya impor barang modal. Akibatnya, untuk tiap dolar yang di"hemat" lebih dari Rp 8.000 biaya yang dikeluarkan. Ciri tingginya domestic resource cost ini adalah ciri utama industri manufaktur yang dilindungi oleh larangan impor karena orientasinya untuk pasaran domestik. Selama ada pembedaan kebijaksanaan menonjol antara industri untuk ekspor dan industri untuk keperluan domestik, selama itu pula tekanan impor ini akan menghinggapi ekonomi nasional. Hal kedua dari defisit neraca berjalan adalah tingginya komponen pembayaran bunga utang luar negeri. Untuk tahun fiskal 1991-1992 hingga 1993-1994, pembayaran bunga akan terus "menekan" neraca transaksi berjalan, karena makin besarnya komponen pembayaran bunga utang komersial. Sebelum sidang CGI di Paris Juli lalu, total utang Indonesia menurut IMF adalah hampir US$ 77 milyar, dan hampir US$ 27 milyar adalah utang swasta yang tingkat suku bunganya lebih tinggi dari utang Pemerintah. Rasio utang Pemerintah dengan utang swasta meningkat dari 4 : 1 (1987-1988) jadi 1,8 : 1 (1991-1992). Utang swasta bukan saja tercermin pada bunga utang yang menekan defisit neraca berjalan, tetapi juga pada pembayaran cicilan utang (amortization) yang jangka pembayarannya jauh lebih pendek, antara dua hingga empat tahun. Dari pembahasan ini jelas kiranya alasan CGI untuk menyiapkan apa yang disebut fast disbursed loan sebesar US# 1 milyar. Ini sematamata untuk "pengamanan" lebih lanjut atas kemungkinan situasi neraca transaksi berjalan yang memburuk untuk tahun fiskal 1992-1993. Dengan memahami komponen-komponen neraca berjalan yang demikian, jelas bahwa penerimaan bantuan luar negeri US$ 5 milyar bukanlah "garansi obyektif" akan amannya posisi Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia. Harus diingat pula bahwa kewajiban membayar cicilan utang komersial dan utang konsesional juga amat besar. Dalam tahun fiskal 1991-1992 saja pembayaran cicilan utang adalah US$ 4,9 milyar. Untuk 1992-1993 diperkirakan cicilan lebih besar dari itu. Apa arti angkaangka ini bagi stabilitas eksternal ekonomi Indonesia? Tidak lain bahwa masih diperlukan pemasukan modal yang lebih besar lagi dari pos PMA (foreign direct investment) dan pos portfolio investasi (pembelian saham dan obligasi oleh asing). Kedua pos ini kini berhadapan dengan saingan-saingan yang kuat. Untuk menghadapi saingan-saingan kita (baik yang lebih kuat seperti Muangthai, Cina, dan Vietnam), salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan pembenahan kebijaksanaan yang mampu memperbaiki iklim investasi. Pemerintah, antara lain, membuat PP 17/1992 yang memungkinkan PMA 100% untuk investasi US# 50 juta ke atas dan investasi di lokasi-lokasi yang ditetapkan Pemerintah. Selanjutnya deregulasi 7 Juli 1992 memungkinkan penggunaan HGU selama 35 thaun yang bisa diperpanjang 25 tahun serta dapat digunakan sebagai jaminan collateral untuk kredit. Dalam menilai "maju"nya suatu kebijaksanaan, patokan yang dipakai antara lain memperbandingkannya dengan kebijaksanaan di negara lain. Bila HGU di Cina 100 tahun, di Malaysia 99 tahun, jelas itu lebih menarik dari 30 tahun yang bisa (bisa juga tidak) diperpanjang 25 tahun. Selain itu, PMA 100% berlangsung di Vietnam (tanpa ketentuan dan pembatasan) serta Cina. Belum lagi insentif-insentif lainnya seperti tax holiday dan insentif kredit yang diberikan oleh saingan-saingan kita bagi PMA mereka. Saya setuju dengan pendapat bahwa kita tidak perlu serta merta meniru apa yang dilakukan saingan-saingan kita. Untuk bisa berkata demikian, harus ada daya tarik lain di luar kemudahan-kemudahan tersebut. Daya tarik lain itu bisa birokrasi yang tanggap terhadap dunia usaha serta sekaligus bersih dari mental memeras. Juga yang merupakan daya tarik adalah efisiensi sistem ekonomi yang tercermin pada bebasnya pasar barang dan jasa dari distorsi-distorsi, seperti tata niaga, larangan impor dan larangan ekspor, serta berbagai bentuk "pasar SK" yang menghasilkan inefisiensi. Sepanjang di sektor "kebijaksanaan" kita belum bebenah, dan di sektor birokrasi dan efisiensi sistem ekonomi kita belum membaik, selama itu pula kita harus mewaspadai defisit neraca transaksi berjalan secara ekstra hati-hati. Bahaya potensi terguncangnya stabilitas eksternal masih bersama kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini