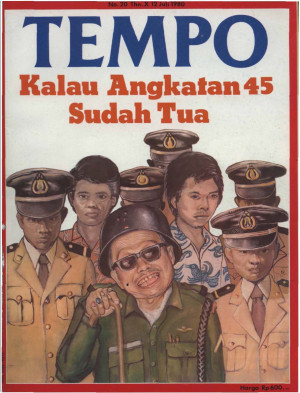LIHATLAH pohon-pohon. Mereka bercerita tentang generasi. Bahkan
Homerus, penyair Yunani Kuno itu, dalam buku ke-VI cerita besar
Iliad beratus-ratus tahun yang silam sudah bisa memetik amsal
dari padanya:
Sebagaimana generasi daun-daun, begitulah generasi manusia suatu
ketika angin mengguncang daunan hingga rontok ke tanah, tapi
kemudian hutan yang rimbun melahirkan, dan musim semi hadir.
Begitulah generasi manusia, yang berganti-ganti datang dan
pergi.
Tapi Homerus hanya melihat daun. Padahal pohon selalu punya dua
cerita-cerita daun dan cerita kulit.
Kita, dari jauh, sering terpesona akan tamasya yang hijau dan
rimbun, yang di negeri empat musim, bisa demikian mengasyikkan
perubahannya. Suatu ketika merah dan kuning menumpuk. Suatu
ketika segalanya runtuh. Suatu saat lain pupus terbit, dan
burung menjemputnya kembali.
Mungkin karena itu kita melupakan kulit, yang dengan kasar
menutupi tubuh pepohonan. Lihatlah dari dekat. Rasanya ada
cerita lain: bukan cerita perubahan, tapi cerita sesuatu yang
menetap. Bahkan sesuatu yang bertimbun bersama waktu--satu jejak
sejarah. Kadang ada tulisan ditorehkan dengan pisau ke sana.
Kita tak selalu tahu apa: tapi yang jelas, itu pun sebuah
percobaan untuk membikin kekal suatu peristiwa, biasanya indah,
tapi sekaligus mungkin tak begitu penting.
Pohon-pohon selalu punya dua cerita, cerita daun dan cerita
kulit. Jika terlalu lama kita simak daun-daun, dan hanya
teringat akan perubahan generasi ke generasi, ada baiknya kita
saksikan kulit yang setidaknya memberikan ilusi tentang sesuatu
yang permanen. Orang tua mati dan orang muda muncul, tapi
barangkali tak segala hal menjadi baru.
Mengapa kita harus tenggelam terus dalam pembedaan dan
dikhotomi "baru" dan "lama" hanya karena sejumlah orang jadi
tua dan meninggal dan sejumlah orang lahir dan jadi dewasa?
CERITA seperti Ramayana dan Mahabarata yang kita kenal bukanlah
cerita tentang suatu generasi baru dan generasi lama sebagai
satuan yang saling terpisah. Bahkan dalam kedua cerita itu,
terutama jika kita kenang kisah Pandawa Lima, yang pokok
hanyalah satu generasi. Pada akhirnya semua anak para Pandawa
gugur dalam perang. Dan sebelumnya tentu kakek mereka sudah pada
almarhum.
Tetapi toh kita berbicara tentang generasi lama dan baru,
seperti Homerus dalam Iliad. Kita berbicara tentang pemuda.
Barangkali karena hidup bukanlah cerita wayang: sesuatu yang
bisa kita selesaikan sebelum siang hari Dengan kata lain,
barangkali karena ternyata kita bukan para Pandawa. Anak kita
tak mati. Justru kita yang berangkat mati.
Dan juga karena peristiwa di tahun 1928, lalu revolusi di tahun
1945, kemudian perubahan besar di tahun 1965, tiba-tiba
menunjukkan bahwa anak-anak itu bisa menutup suatu zaman,
seperti merobek kalender.
Lalu kita pun berbicara tentang generasi, tentang "angkatan".
Yang menarik ialah bahwa pada dasarnya suatu "angkatan"
merupakan suatu antithesis. Kata ini bagaimana pun lebih militan
ketimbang "generasi". Dan jika kita berbicara tentang "angkatan"
dalam sejarah kita, secara tersirat kita sebenarnya berbicara
juga tentang sesuatu yang ditolak, didobrak, dijebol. Mungkin
tak selamanya jelas, namun pasti masih lebih jelas dari apa yang
tidak ditolak dan apa yang diharapkan.
Suka atau tak suka kita kini, dengan demikian kita sebenarnya
membayangkan sejarah kita sehagai berbagai peristiwa
kontradiksi, malahan konflik. Antithesis lebih menojol daripada
thesis. Dan karena "angkatan" kita samakan dengan "generasi",
melalui suatu proses yang tak kita sadari, diam-diam kita pun
membentuk konsep si sejarah yang mirip cerita Oedipus.
Cerita Oedipus itu boleh ditafsirkan sebagaimana ditafsirkan
oleh Freud: pemberontakan, bahkan pembinasaan sang ayah oleh
sang putra. Tapi cerita Oedipus juga bisa diperpanjang, sesuai
dengan naskah pujangganya, Sophocles: Oedipus bukan sebgai
anak, tapi sebagai bapak. Di sana ia ditinggalkan para putranya,
dan dalam keadaan buta mengutuki mereka. Semuanya adalah
tragedi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini